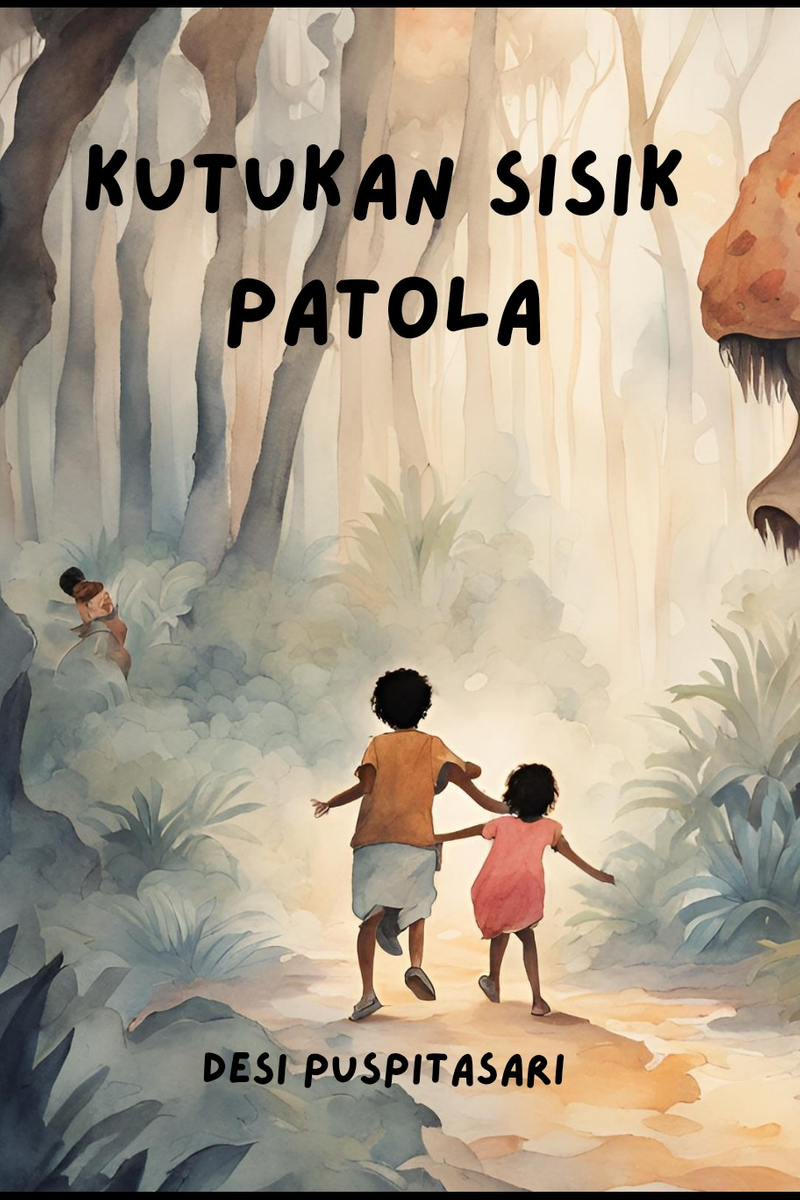Seekor ular sanca berukuran besar melata melintasi jalan. Kendaraan yang dikendarai Bapa terpaksa berhenti. Kemunculannya bukan pertanda buruk, kan, ya?
Seperti biasa, saat akhir pekan Bapa mengajak Mama beserta Simon dan Mauria berburu di hutan. Seekor rusa yang berhasil mereka tangkap bisa untuk persediaan makan seminggu. Bila mendapat dua ekor rusa, yang seekor lainnya bisa mereka jual. Uangnya untuk membeli beras.
Malam belum sepenuhnya beranjak pergi. Langit gelap membentang di angkasa. Jalan raya Merauke sepagi buta itu tampak lengang. Simon duduk terkantuk-kantuk di bak belakang pikap. Tubuh kurusnya mengenakan kaos gombroh dan celana training lusuh. Jaketnya yang kumal dikenakan Mauria, adik perempuannya. Gadis kecil itu memeluk lutut yang dilipat di depan dada.
Pikap reyot yang dikemudikan Bapa berderit-derit. Melintasi perkampungan rumah dari kayu. Pintu-pintu rumahnya tertutup rapat. Suasananya temaram oleh lampu teras yang berwarna kuning dan redup.
“Ko lihat itu, ee?"
Kepala Simon tersentak mendengar suara keras Bapa.
“Anak siluman terkutuk,” lanjut Bapa.
Kaca pembatas ruang kemudi dengan bagian belakang pikap pecah separuh. Noda darah kering melekat pada ujung-ujung yang tajam. Suara Bapa terdengar sampai belakang.
“Anak siluman terkutuk? Anak patola-kah?” Dengan mata mengantuk Simon melongok penasaran. Ia sering mendengar rumor tentang anak patola tapi belum pernah melihat wujudnya dari dekat. Mauria tetap duduk memeluk lutut yang masih terlipat di depan dada.
Pikap reyot itu dikemudikan Bapa pelan-pelan. "He, anak patola!" seru Bapa.
Mama mendesis lirih.
Bocah berusia kira-kira empat tahun, kulitnya hitam legam, duduk di halaman depan rumah. Kepalanya menoleh. Kedua bola matanya hitam legam tanpa putih sedikit pun. Dalam cahaya remang lampu teras, wajahnya terlihat runcing dengan rahang tegas.
“Pih!”
Bapa meludah. Mama memekik lirih. Mulutnya serta-merta merepet minta ampunan pada Tuhan.
Bocah patola itu mengusap ludah di keningnya menggunakan lengan kaosnya yang berlubang.
"Ko tak boleh seperti itu," tegur Mama jeri.
“Untuk anak hasil kawin deng siluman ular tidak apa-apa." Bapa sama sekali tak merasa bersalah.
“Sebaiknya ko berhenti dan minta maaf,” tambah Mama. “Sa takut ada kejadian yang tidak menyenangkan nanti.”
“Ko selalu membantah. Mo sa pukul-kah?” geram Bapa sambil terus mengemudikan kendaraan.
Tak terdengar lagi sahutan Mama.
Tangan Simon meraih kerikil yang terserak di pojok bak belakang pikap.
Pletak!
Kerikil yang dilempar Simon menghantam pelipis anak patola. Bocah itu melengking kesakitan. Lidahnya yang bercabang menjulur-julur keluar.
Simon menoleh cepat ke arah adiknya."Ko lihat itu? Lidahnya bercabang persis ular."
“Seharusnya tak ko ganggu dia,,” kata Mauria takut-takut, meniru perkataan Mama.
Tangis bocah patola pecah. Suara perempuan dewasa terdengar mengomel dari dalam rumah. “Menangis terus! Menangis terus! Sa capai pu anak seperti ko!”
Pikap reyot yang dikendarai Bapa semakin menjauh. Laju mereka tak seberapa kencang, kendaraan itu sudah tua. Simon terus mengawasi anak patola yang terus menangis. Semakin lama sosoknya semakin tak kelihatan.
Bocah patola biasanya berumur tak lama. Entah karena ia anak siluman atau karena keluarganya tak sudi merawatnya dengan baik. Bila mati, konon katanya roh anak patola akan bergentayangan di hutan-hutan di Merauke.
“Anak siluman ular,” kata Simon puas. Ia kembali duduk bersandar. “Sa baru saja melukai anak siluman ular. Menurutmu ia akan mengadu pada bapanya?”
“Siapa bapa si anak patola?” tanya Mauria.
“Bapa dari anak siluman ular tentu saja patola,” kata Simon.
“Seharusnya ko tak melukai anak siluman itu.” Siku Mauria menyenggol lengan kakaknya. Ia menunjukkan memar samar biru pada lengannya. “Nowena bilang muka sa menakutkan. Mirip spok. Ia bilang spok bersaudara deng anak patola."
“Nowena bicara omong kosong,” sergah Simon. “Spok hantu Merauke yang orangtuanya memang hantu. Anak patola hasil siluman ular kawin deng manusia. Ko itu anak manusia. Jadi, ko bukan spok dan tidak bersaudara deng anak patola.”
Mauria mengangguk. “Sa bantah perkataan Nowena. Sa dipukulnya keras.”
“Tak ko adukan pada Ibu Guru?” tanya Simon.
Mauria mencibir tanpa suara. Simon mengerti apa maksudnya. Ibu Guru tak peduli dengan pertengkaran murid-muridnya.
“Seharusnya ko balas pukul dia,” kata Simon.
“Seperti Bapa yang memukul Mama?”
Simon mengangguk. Saat mabuk Bapa memukuli Mama. Mama menangis kesakitan tapi tak berani membalas. Simon membayangkan Mauria balas memukuli Nowena sampai menangis seperti Bapa.
Mauria menggeleng. “Sa tidak berani, Kakak. Tapi, sa su adukan perbuatan Nowena pada Tuhan.”
Simon mendengus. “Ko boleh adukan Nowena pada Tuhan. Tapi, setidaknya ko juga melawan.”
“Kata Bapa tak ada gunanya membalas kejahatan manusia. Serahkan saja semuanya pada Tuhan.”
Simon kembali mendengus. Adiknya memang tak pandai. Terlalu menurut pada Bapa. Tak berani melawan Bapa. Simon juga tidak berani melawan tapi setidaknya ia tahu untuk tidak menelan mentah-mentah perkataan Bapa.
“Jang ko menurut pada semua kata Bapa. Ko pilih-pilih-lah, mana yang baik dan mana yang sebaiknya ko abaikan," gusar Simon.
"Kalau sa adukan pada Bapa, sa juga akan dipukulnya." Kedua mata Mauria berkaca-kaca. “Sa hanya berani mengadu pada ko….”
“Dan, Tuhan….”
“Iyo,” balas Mauria lirih.
Simon terdiam. Ia juga dipukul Bapa saat mengadu ada yang mengganggunya di sekolah. “Ko anak laki-laki cengeng. Urusan sepele begini saja mengadu pada sa. Kepala sa penat mencari uang.”
Sejak saat itu Simon berprinsip, lebih baik ia membalas lalu dipukul temannya daripada mengadu lalu dipukul Bapa.
“Sa memang tak pandai, Kakak. Sa juga tak cantik. Sa menakutkan mirip spok. Bersaudara pula deng anak patola.”
Simon memerhatikan adik perempuannya. Mauria kecil dan tak tinggi. Kakinya hitam kotor. Telapaknya tebal. Gadis kecil itu cekatan berjalan di hutan tanpa alas kaki. Simon dan Mauria hanya mengenakan alas kaki saat bersekolah. Rambut Mauria keriting dan pendek. Entah mengapa rambut keruwil itu tak juga lekas memanjang. Akademis Mauria paling bontot di kelas. Anaknya penakut. Simon juga penakut tapi ia berani membalas bila diganggu.
"Ko tak mirip spok," kata Simon. “Ko dengar itu, Mauria? Ko bukan hantu spok. Ko tidak bersaudara deng anak patola. Jang ko dengarkan teman ko yang bicara melantur.”
“Sa tetap tak berani balas memukul,” katanya tersendat.
"Ko adukan saja pada Tuhan,” balas Simon mengantuk. Bocah laki-laki kelas 6 SD itu menguap lebar. Masih ada waktu untuk tidur sejenak sebelum mereka tiba di hutan--
Ckiitt…
Bapa mendadak menginjak rem. Tubuh Simon dan Mauria tersentak. Anak laki-laki itu bergegas melongok ke depan. “He, ko harus lihat ini, Mauria.”
Seekor ular berukuran besar melintas di tengah jalan. Binatang itu melata perlahan. Sangat pelan. Kulitnya hitam dan licin. Sisiknya mengkilat. Motifnya tak terlihat jelas meski telah disinari lampu pikap yang muram.
"Patola," bisik Mauria. Ia turut melongok di sebelah Simon. “Besar skali. Ular sanca-kah?”
Kakak beradik itu memerhatikan ular besar yang terus melata perlahan. Kini ia masuk ke dalam semak-semak.
Bulu kuduk Simon meremang. Seekor ular besar melintas di tengah jalan, menghalangi perjalanan mereka. Semoga bukan pertanda buruk.
“Ko tadi melukai anak patola, toh?”
Simon menarik adiknya untuk kembali duduk. “Tidak. Tidak ada hubungannya.”
"Patola tadi mencari ko."
Simon mengancam akan memukul Mauria bila tak berhenti menakut-nakutinya.
Bapa melajukan pikap reyotnya kembali. "Hampir saja," katanya. "Masih gelap begini tiba-tiba ia muncul. Kalau tak cekatan, sa bisa melindasnya sampai gepeng."
"Seekor ular melata di tengah jalan. Pertanda buruk-kah?" tanya Mama khawatir.
"Tidak. Tak usah ko percaya takhayul." Bapa menyetir kendaraannya.
“Jangan-jangan karena tadi ko meludahi anak patola--”
"Hanya manusia yang lemah iman yang percaya pada takhayul," potong Bapa keras.
Mauria menengok ke arah Simon.
“Sa mo tidur,” kata Simon. Ia merebahkan tubuhnya. Tak lama kemudian tidurnya telah pulas.
Pikap reyot itu terus melaju berderit-derit.
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰