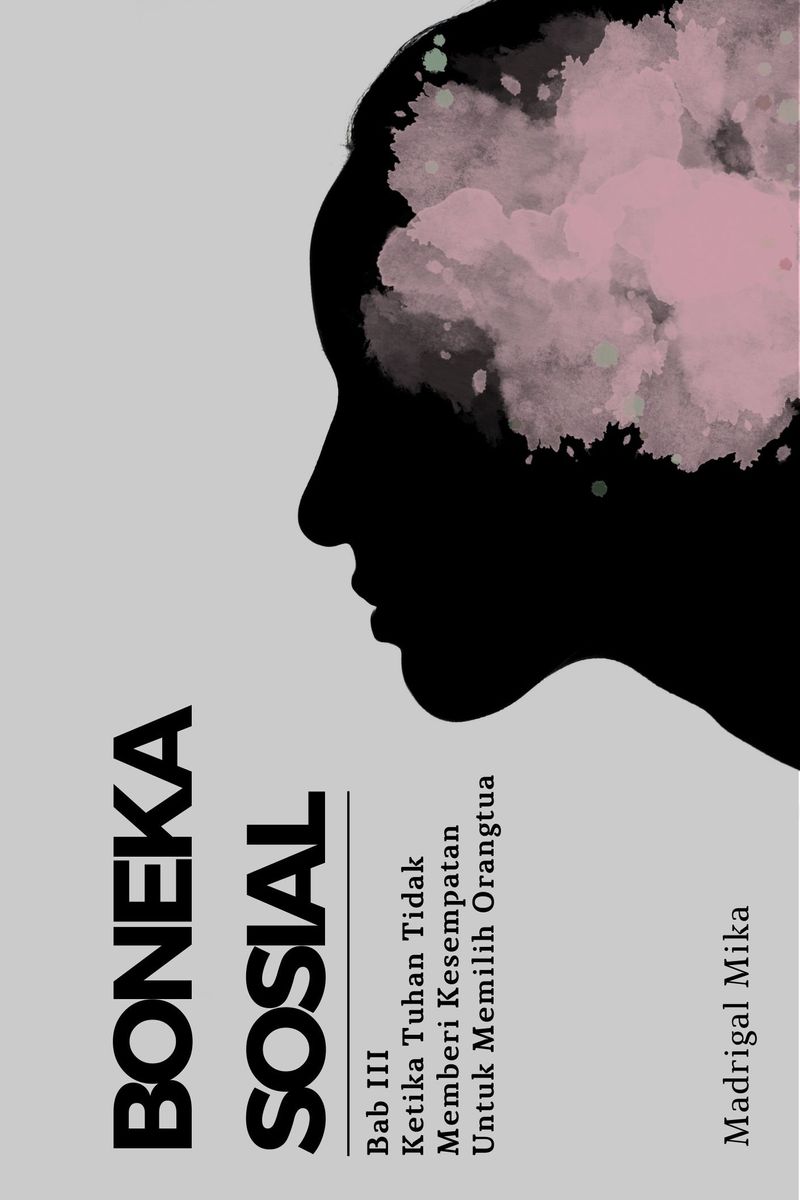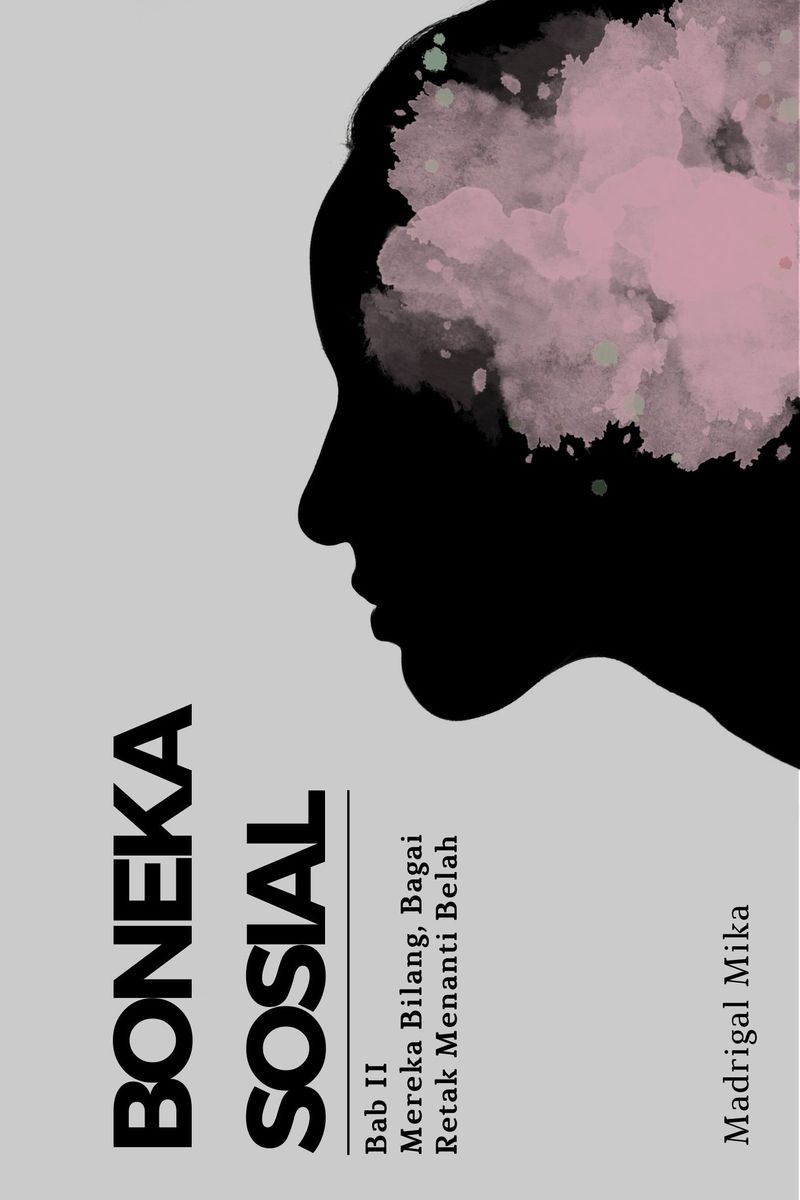
Sebelum ini, tidak pernah ada yang berkata pada ayahnya bahwa memukul ketika marah adalah hal yang salah. Tapi, setelah ia pikir kembali, memangnya, siapa yang bisa mengatakan hal itu pada ayahnya? Toh, setiap kali ayahnya marah dan melontarkan pukulan demi pukulan padanya, tidak pernah ada siapa-siapa di antara mereka. Tidak pernah ada yang melihat mereka.

-
(Hai, aku Mika.
Pertama-tama, makasih ya udah ngelirik seri Boneka Sosial ini. Ehehe.
Kalau kalian mutusin buat mulai baca, ada beberapa hal...
Sejauh ini, Binar berhasil mempelajari satu hal: mana yang benar dan mana yang salah. Dan apa yang selama ini ia alami dari ayahnya adalah hal yang salah.
Bagaimana bisa, kau bertanya?
Maka, jawaban atas pertanyaanmu akan mengantar kita pada ingatan berkabut Binar tentang kerumunan anak –teman sekelasnya di sekolah dasar- yang ia amati dari jarak empat meter jauhnya. Kerumunan itu mendengungkan berbagai macam suara. Sorak-sorak liar yang bersemangat, tawa cemooh, ketakutan, panik, bahkan teriakan-teriakan histeris yang hampir menyerupai teriakannya ketika sang ayah mulai memandangnya sebagai karung tinju yang dapat berjalan dan bernapas.
Ayo, pukul lagi!
Jangan mau kalah!
Pukul terus!
Hei, dia berdarah!
Berhenti!
Tolong, panggil guru-guru kemari!
Aku tidak mau melihat ini!
Aku ingin pulang!
Hei, dia menangis!
Pukul kepalanya!
Tinju wajahnya!
Jangan lemah begitu!
Setiap suara yang datang hanya terasa seperti angin lalu bagi Binar. Ia tidak lagi terpengaruh pada perkelahian seperti itu, mengingat ia sudah merasakannya sendiri, bahkan lebih parah dari itu. Mereka hanyalah dua anak lelaki seumuran yang tenaganya tidak jauh berbeda. Sementara Binar, dalam seminggu ia bisa berulang kali berhadapan dengan amukan lelaki dewasa yang terpaut dua puluh tahun lebih dengannya, yang dengan satu pukulan saja bisa membuatnya terempas sebelum ia dapat merangkak untuk melarikan diri.
Apa yang terjadi di hadapannya itu tidak ada apa-apanya, Binar diam-diam menarik lengan bajunya melewati pergelangan tangannya.
Tapi, entah bagaimana, hal sepele tersebut justru mendapat tanggapan begitu hebat dari satu-satunya orang dewasa di kelas itu, yang dengan terburu-buru menghambur melewati pintu kelas dan melerai dua anak laki-laki tadi.
“Cukup! Berhenti!” orang dewasa yang sudah tiga tahun ia sebut guru itu berusaha menjauhkan mereka yang masih belum puas mencekik satu sama lain. “Kalau kalian marah, selesaikan baik-baik, bicara agar dapat saling memahami, bukan dengan memukul begini!”
Bukan dengan memukul begini, katanya.
Binar, yang kala itu masih berusia sepuluh tahun, memiringkan kepalanya, bingung pada apa yang ia saksikan. Sebelum ini, tidak pernah ada yang berkata pada ayahnya bahwa memukul ketika marah adalah hal yang salah. Tapi, setelah ia pikir kembali, memangnya, siapa yang bisa mengatakan hal itu pada ayahnya? Toh, setiap kali ayahnya marah dan melontarkan pukulan demi pukulan padanya, tidak pernah ada siapa-siapa di antara mereka. Tidak pernah ada yang melihat mereka.
Sejak kejadian itu, Binar terus memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Membandingkan apa yang terjadi pada mereka dengan apa yang terjadi pada dirinya. Alhasil, selain mengamati perkelahian tadi, Binar juga berhasil mengetahui bahwa hanya ia-lah yang memiliki memar dan luka hampir di sekujur tubuhnya. Tidak sulit mengetahui hal itu, sebab ketika pelajaran olahraga tiba, ia dan gadis-gadis kecil lain di kelasnya akan berdesak-desakan mengganti seragam mereka dengan baju olahraga di ruang ganti. Melihat tidak ada tubuh dengan warna-warni muram sepertinya, Binar memutuskan untuk mengganti pakaiannya di salah satu bilik toilet tak jauh dari ruang ganti dengan alasan ia tidak mau berlama-lama menunggu giliran.
Sambil meloloskan diri dari lubang kepala baju olahraganya, pemikirannya yang masih begitu muda menyimpulkan bahwa apa yang ia alami di rumahnya bukanlah sesuatu yang benar, karena banyak dari mereka yang tidak mengalaminya.
Bermula dari kejadian itulah, Binar mulai berpikir bahwa ia tidak mau terus-menerus mengalami apa yang tidak dialami oleh anak-anak lain. Sebab, ia merasa ini tidak adil. Dan dengan penolakan tersebut, semakin hari, perlakuan ayahnya terhadapnya semakin terasa salah baginya, sehingga Binar berniat untuk menghentikan hal tersebut. Tidak dengan menceritakan apa yang terjadi padanya pada orang lain, tentu saja, karena terlalu berisiko baginya. Melainkan dengan berusaha melarikan diri dengan tangan dan kakinya sendiri.
Itulah, yang kemudian membawanya pada lelaki paruh baya berpayung dan berjas hujan yang sedang menyodok-nyodok dedaunan di saluran pembuangan air hari itu.
*
Pria paruh baya itu mendudukkan Binar di sebuah kursi makan dari kayu jati dengan pernis yang menyilaukan. Untuk beberapa menit yang masih terasa menggelisahkan, ia ditinggal sendiri di ruangan itu. Sesekali, matanya tertuju pada arah masuknya tadi dan jendela-jendela yang mengarah langsung pada hujan di luar sana, takut-takut kalau ayahnya memutuskan untuk datang menjemputnya dan mengurungnya kembali di rumah neraka itu.
Kegelisahan tersebut membuat Binar lupa bahwa sekujur tubuhnya basah dan ia gemetaran.
“Kita akan bicara ketika istriku datang. Jadi, untuk sementara, keringkan dulu dirimu dan pakai ini,” si lelaki paruh baya tiba-tiba muncul, membuatnya terperanjat. “Maaf, kau pasti masih ketakutan,” ujarnya selagi meletakkan sehelai handuk tebal yang tampak lembut dan dua potong pakaian di meja yang menjadi set dari kursi yang Binar duduki. Kemudian, lelaki itu menunjuk ke satu arah, “kamar mandinya di sana.”
Binar mengangguk pelan, meraih handuk dan pakaian yang disediakan untuknya dan berjingkat-jingkat menuju kamar mandi lantaran tidak ingin mengotori lantai putih itu dengan kaki kotornya lebih banyak lagi. Membuat kesal sang pemilik rumah dan berakhir diusir bukanlah sesuatu yang ingin ia alami, mengingat ia tidak memiliki tempat lain untuk melarikan diri.
Di kamar mandi yang berukuran cukup besar itu, ia menemukan cermin setinggi orang dewasa di salah satu dinding. Pantulan dirinya terlihat begitu menyedihkan di sana. Kantung mata yang menghitam, hasil dari malam-malam tanpa tidur lantaran menangisi perih di luka baru di tubuhnya. Pipi cekung, hasil dari makanan dalam jumlah kecil yang diterimanya, sebab sang ayah benci memberi makan anak tak berguna sepertinya. Tubuh kurus yang selama ini ia balut dengan baju-baju lengan panjang berukuran satu nomor lebih besar dari ukurannya kini terlihat seperti tulang berbalut kulit ketika pakaian basah itu melekat ketat pada dirinya.
Malu pada pantulannya sendiri, ia segera mengalihkan pandangan dan mulai melepaskan satu demi satu pakaiannya.
*
Setelah dirinya bersih, barulah Binar berani menginjakkan seluruh telapak kakinya di lantai rumah itu. Langkah pelannya tidak sedikitpun menimbulkan suara, hasil dari waktu-waktu penuh teror ketika ia harus berjalan sepelan mungkin agar tidak ketahuan ayahnya saat ia ingin menghindari lelaki itu. Sampai di ruangan tempat ia duduk tadi, hidungnya disambut oleh aroma hangat cokelat yang serta-merta membuat perutnya bergemuruh nyaring, hampir menyerupai gemuruh di langit di luar sana.
“Hei.”
Untuk kesekian kalinya, Binar terperanjat. Hampir saja menjatuhkan gumpalan pakaian kotornya yang telah ia peras hingga tidak mengeluarkan setitik air pun. Itu suara yang berbeda, pikirnya, sembari menoleh dan mendapati seorang perempuan berjalan ke arahnya. Dahi perempuan itu berkerut, sementara mata perempuan itu tertuju padanya.
Nantinya, di masa depan, jauh setelah hari itu, barulah Binar tahu, yang ada di wajah perempuan itu merupakan ekspresi cemas. Tentu saja, ia tidak pernah mengenali raut seperti itu, sebab tidak pernah ada yang mencemaskannya.
“Maaf mengejutkanmu,” suara lembut milik perempuan itu terasa asing di telinga Binar yang sudah terbiasa melahap makian demi makian yang diteriakkan sang ayah padanya setiap waktu, “lelaki yang tadi membawamu kemari itu…, aku istrinya, Malena,” raut sangsi di wajah Binar membuatnya merasa harus memperkenalkan diri.
Masih terperangah, Binar mengangguk sekali. Lalu, mencengkeram gumpalan pakaiannya erat-erat.
“Ini, minum ini,” Malena meletakkan cangkir berukuran sedang di meja yang tadi dihuni oleh Binar, lalu mengulurkan tangannya pada gadis itu, “biar kuurus handuk itu dan pakaianmu.”
Dengan kikuk, Binar memberikan gumpalan pakaiannya pada Malena berikut dengan handuk kotor yang sejak tadi tersampir di pundak kanannya.
Sementara Binar menduduki kembali kursinya, Malena menghilang di balik salah satu pintu yang berada agak jauh di bagian belakang rumah, kemudian muncul kembali. Kali ini, ia memutuskan untuk menemani Binar.
“Kuharap kau tidak keberatan mengenakan pakaian anakku,” ujar Malena selagi ia mendudukkan diri di hadapan Binar.
“Dia… laki-laki?” tanya Binar, menyimpulkan dari gambar yang tercetak di bagian dada baju yang ia kenakan.
“Kau tidak tahu?” Malena mempelajari wajah Binar, memastikan kalau mereka memang bertetangga, meski berjarak beberapa buah rumah.
Binar menggeleng.
Malena mengerutkan dahinya. Semua anak di kompleks perumahan ini tahu, anaknya seorang laki-laki. Oh, mungkin tidak semua, batin Malena ketika matanya menelisik sosok Binar, hampir semua. Lagipula, kalau diingat-ingat, sejak ayahnya pindah ke komplek perumahan kami, kapan terakhir kali aku melihat anak ini berkeliaran dan bermain dengan anak-anak yang lain? Malena memutar belasan ingatan di kepalanya, namun sulit menemukan gadis ini di sana.
“Ke mana saja kau selama ini?” lalu pertanyaan itu tanpa sadar terlontar darinya.
“Maaf,” Binar menjawab dengan suara yang kian memudar, “aku dikurung ayahku.”
Terkejut, Malena memicing, “berarti Argani— maksudku, suamiku, tidak mengada-ada. Hei, mau menceritakannya padaku? Barangkali kami bisa membantu.”
Binar bisa merasakan matanya membesar. Ia tidak tahu betapa ia mengharapkan kata-kata itu diucapkan padanya. Betapa ia menginginkan seseorang untuk membantunya. Diam-diam, air mata memunculkan diri, bergelayut di sudut-sudut matanya. Menceritakan seluruh kisahnya sudah pasti akan membutuhkan waktu lama. Jadi, Binar memutuskan untuk membuatnya menjadi lebih sederhana.
“Ayah membenciku. Setiap kali ia memandang wajahku, ia marah. Setiap kali ia marah, ia memukuliku. Tapi, aku tidak boleh memberitahu orang lain. Aku tidak boleh mengadu. Aku juga tidak boleh keluar dari rumah itu.”
Sedetik, raut di wajah Malena goyah. Namun, segera bisa ia kendalikan dan kembali memakai raut ramah yang menenangkan. “Mengapa ayahmu membencimu?”
“Karena wajahku mirip mantan istrinya. Mantan ibuku.”
Perempuan itu tertawa kecil, tapi tawa itu tidak sampai di matanya. “Kau tahu, mantan istri memang ada. Tapi, tidak ada yang namanya mantan ibu.”
“Mengapa begitu? Bukankah aku dan ayahku sama-sama ditinggal pergi oleh ibuku?”
“Yah, kuharap aku bisa menjawabnya. Tapi, aku sendiri tidak tahu.”
Diam. Hujan di luar sana pun perlahan mereda, seolah ingin berpartisipasi dalam diam tersebut.
“Umm… di mana anak laki-lakimu?”
“Di luar kota. Bersama neneknya.”
“Liburan?” tapi, kemudian, Binar bingung pada pertanyaannya sendiri. Memangnya boleh liburan ke luar kota pada hari sekolah?
Teringat akan sekolah, pertanyaan lain menimpalinya, bagaimana ia akan pergi ke sekolah besok, sementara barang-barangnya masih tertinggal di rumah sang ayah?
“Umm… ya, bisa dibilang ia sedang liburan.”
Mengejutkan. Ternyata, benar-benar ada anak yang beruntung bisa liburan di hari sekolah, batin Binar selagi ia mendengungkan hmm lemah pada Malena. “Tidak sabar menunggu sampai hari libur tiba?” tanya Binar lagi.
Malena terdiam sejenak. Raut wajahnya lagi-lagi berubah. Kali ini, terlihat bimbang dan menimbang-nimbang. Namun, tentu saja, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa Binar sadari.
Lalu, ketika Binar berpikir bahwa Malena telah lelah menjawab pertanyaannya, ia justru mendapat jawaban berupa, “seandainya alasannya memang sesederhana itu,” disusul dengan satu tarikan napas panjang dan raut sedih mencoreng wajahnya, “tapi, sebenarnya, ia mengalami hal yang buruk di rumah ini. Jadi, untuk sementara, ia kutitipkan pada neneknya.”
Binar mengerjap beberapa kali, tidak tahu harus berkomentar seperti apa. Ia berusaha untuk menyingkirkan rasa tidak nyamannya terhadap kata ‘mengalami hal buruk di rumah ini’ mengingat ia baru saja mengalami hal buruk di rumahnya sendiri. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal buruk lain yang terjadi di rumah lain. Terutama di rumah yang sedang menjadi tempat persinggahannya ini.
Jadi, ia hanya menundukkan kepala, tiba-tiba saja tertarik untuk mengamati secangkir cokelat hangat yang sejak tadi berada di tangannya, dan berkata, “begitu,” entah pada siapa.
Jeda kembali terjadi. Kali ini lebih lama dari yang sebelumnya.
“Kau tahu di mana ibumu?”
Dari semua kalimat yang bisa diucapkan, Malena justru memilih hal yang tidak pernah terpikir oleh Binar. Dalam diam yang ia harap bisa ia perpanjang lantaran semua topik mengenai sang ibu merupakan hal yang tabu baginya, ia gelisah. Namun, ketika Binar tidak sengaja mengangkat pandangannya dan bertemu pandang dengan Malena, Binar tahu, tidak peduli seperti apa jawaban yang ia tawarkan pada perempuan itu, ia harus tetap menjawab.
“Tidak, karena Ayah tidak suka membicarakannya.”
“Kalau begitu, ayo kita cari tahu. Barangkali kau bisa hidup dengan ibumu alih-alih bersama ayahmu.”
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰