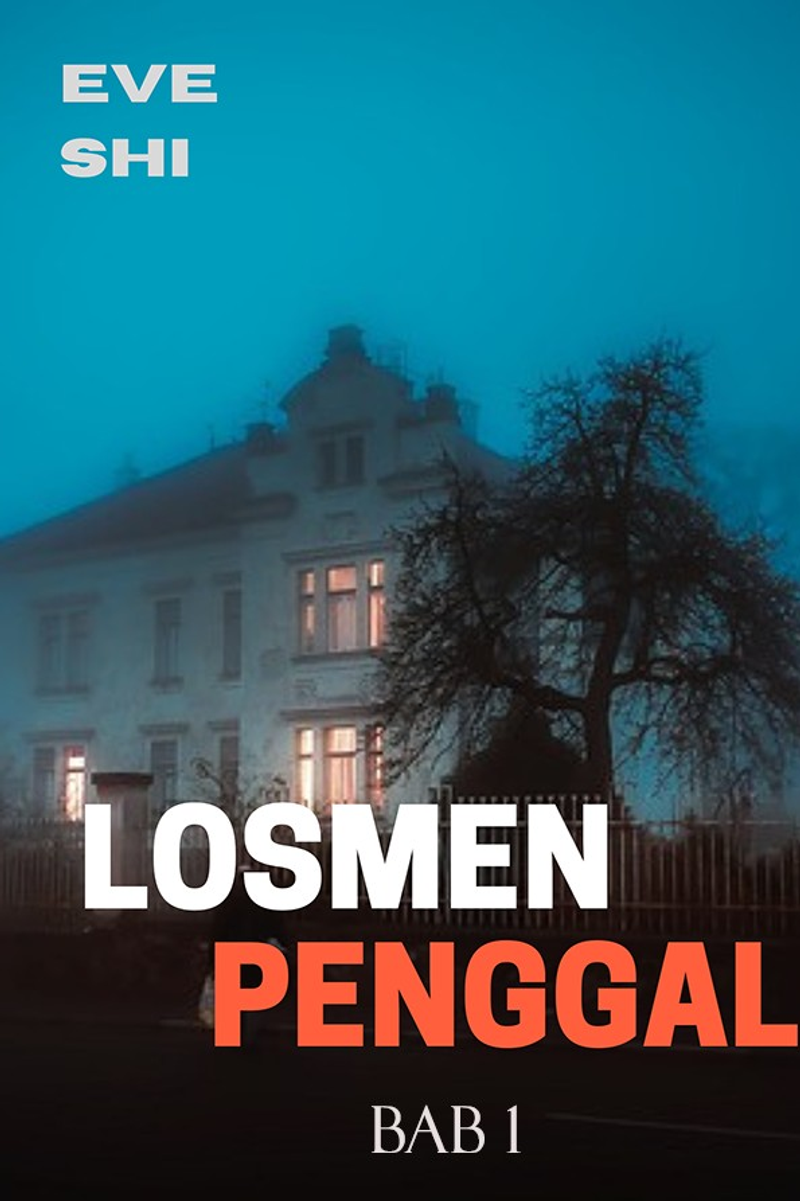
Iza, yang peka atas kehadiran makhluk halus, ditawari pekerjaan di losmen yang terkenal angker.
ongan di Losmen Angker
Di kehidupan nyata, sosok bergelimang darah itu berada di kamarku. Dalam mimpi, dia bangkit dan berjalan terseok-seok. Sambil menuding bajunya yang lengket oleh darah, dia membentak.
Pembunuh! Ini gara-gara kamu! Mati sana, bangsat! Dia menjangkau leherku, dan saat itulah aku tersentak bangun.
Hidungku masih dikepung bau anyir. Ujung lidahku bagai mencecap kentalnya darah. Butuh beberapa menit sebelum aku benar-benar tenang. Aku turun dari tempat tidur sambil mengatur napas.
Tak ada yang berubah di kamar ini. Dipan, lemari pendek, serta meja dan kursi nyaris berjejalan. Jendela dengan panel kaca yang sedikit macet menjadi jalur udara selain pintu. Aku pun seorang diri, tidak ditemani makhluk bukan manusia.
Aku melintasi lantai yang dingin, lalu mendorong kaca jendela. Sejuknya udara malam menerpa wajahku, mengeringkan peluh di pelipis. Derum kendaraan dari jalan raya dan suara tukang tahwa sayup-sayup sampai.
Lambat laun bau amis tak lagi terhidu. Irama napasku kembali normal dan rongga dadaku lapang. Bahkan ubin di bawah telapak kaki tak sedingin tadi. Ingatanku ganti melayang pada hari yang mengawali kedatanganku ke losmen.
***
"Za, kamu masih kebal hantu?"
Aku berhenti melipat celana jeans dan menoleh ke arah Delia. Teman satu prodiku itu, yang sejak tadi menulis pesan WhatsApp, kini memandangiku. Karena perempuan, dia duduk di ambang pintu alih-alih di dalam kamar. Menuruti peraturan rumah kosku yang khusus pria, penghuni wajib membuka pintu kamar bila ada tamu perempuan.
"Kebal kayak gimana dulu?" sahutku. "Lihat sekali-sekali masih bolehlah. Aku tinggal cuekin sampai mereka pergi atau bosan sendiri. Kalau diikuti kuntilanak seharian, malas."
Dia mengangguk dengan maklum. Sifat Delia memang serius, termasuk dalam menyikapi hal supernatural. Ketika teman-teman kami tahu bahwa aku peka pada makhluk halus, umumnya mereka kagum atau meminta aku bercerita. Delia hanya bertanya: Kamunya keganggu? dan aku menjawab: Kadang-kadang. Sifatnya yang lugas dan peduli teman itulah yang mengantarkan dia terpilih jadi ketua prodi angkatan kami.
Delia menaruh ponsel di atas karpet yang setengah gundul. Akibat langit mendung dan hujan tertunda, udara kota Malang sore ini sedikit gerah. Dari dalam tasnya, dia mengeluarkan ikat rambut warna-warni. Seraya mengucir rambutnya yang lurus tebal, dia berbicara.
"Baguslah kalau gitu. Aku punya lowongan kerja buatmu."
Keningku berkerut. Delia jelas tidak sedang bergurau. Sebaliknya, aku sukar membayangkan kerja apa yang menuntut kekebalan atas makhluk halus. Asisten vlogger yang khusus meliput fenomena gaib?
"Kerabatku ada yang punya losmen," lanjut Delia. Suaranya ditimpali lagu girl group Korea bergenre trap dari kamar sebelah. "Namanya Tawang Permai, agak di luar Malang."
"Kayaknya aku pernah dengar. Losmen yang ada lukisan angkernya itu, kan?" Menurut rumor, Tawang Permai memiliki lukisan berusia tujuh puluh tahun. Pada tengah malam, lukisan itu kerap mengeluarkan suara tangis. Seperti umumnya rumor, kisah ini banyak dibubuhi kata orang dan konon.
"Oh, kamu tahu, toh?" sahut Delia. "Iya, lowongan kerjanya di situ. Pekan ini bakal ada pegawai mengundurkan diri."
Aku menggeleng. "Sama lukisan angker aja aku kebal, tapi aku nggak punya pengalaman atau ilmu di industri hospitality."
"Pengalaman nggak diutamakan, kok. Job desc-nya ringan, fresh graduate juga bisa asal mau belajar. Syaratnya, ya, itu—hidup seatap bareng penghuni bukan manusia."
Aku menaruh celana jeans di kasur. Baju-baju lain yang baru diangkat dari jemuran bertumpuk, menunggu dilipat untuk nantinya diseterika. Sembari ganti melipat kaus, aku bertanya, "Gangguannya parah?"
"Iya, lumayan. Pegawai yang keluar ini hampir tiap malam susah tidur—selimutnya terus-terusan ditarik, barang-barangnya kegeser. Tiap pagi dia kerja sambil ngantuk, nggak konsen. Begitu terus, sampai dia nggak tahan dan keluar."
"Aku bisanya lihat makhluk gaib, Del, bukan suruh mereka ini itu. Mereka tetap aja bakal narik selimutku biarpun dilarang."
"Minimal kamu terbiasa dengan mereka, ya kan?" balas Delia. "Nggak gampang kaget. Yang aku dengar, makhluk gaib lebih suka serang orang yang takut daripada yang terbiasa. Betul, nggak, sih? Kalau betul, mestinya kamu—seperti yang kutanya tadi—lebih kebal sama mereka."
"Kebalnya butuh waktu, nggak dari awal. Kerabatmu pernah coba panggil orang pintar?"
Delia mengirapkan kucir agar tengkuknya terpapar angin yang hangat. "Pernah, satu kali. Losmen ditutup sebentar, nggak terima tamu, terus Bu Triya—nama kerabatku itu—minta orang pintar bersihin losmen. Tapi ilmunya kurang ampuh, mungkin. Baru sepekan, gangguannya muncul lagi. Ini pegawai kedua yang keluar gara-gara itu."
Aku hanya menggumam.
"Terima aja, Za," ujar Delia. "Mau, kan? Barusan kamu bilang, makhluk begitu tinggal dicuekin sampai bosan. Ditambah lagi, ini pekerjaan—kamu dapat gaji. Masa kamu tolak?"
Sambil menghela napas, aku melempar kaus ke atas kasur. Berdebat dengan Delia ibarat merambah jalur yang ditumbuhi semak-semak rimbun. Aku begitu sibuk menebasnya dengan parang hingga berisiko tersesat ke arah yang tak kukehendaki.
"Bakal aku kasih referensi ke Bu Triya, deh," imbuh Delia. "Yang diutamakan beliau bukan pengalaman, tapi niat kerja. Atau lamaran kerjamu udah ada yang tembus?"
Aku diam saja. Pengalamanku bekerja hanya sebatas anak magang untuk keperluan tugas akhir. Setamat kerja magang, aku rajin mengirim surel lamaran ke berbagai tempat. Nahasnya, satu pun tak ada yang diterima. Fresh graduate, terlebih lulusan D3 sepertiku, ratusan jumlahnya, dan pengalaman mereka lebih luas.
"Lamaran kerja itu topik sensitif, ya?" lanjut Delia. "Makanya, biar jadi topik bahagia, aku tawari kamu pekerjaan. Gajinya cukup, kamu nggak akan kelaparan. Apalagi kamu—" Ucapannya tiba-tiba terpotong.
Aku mengangkat alis. Selama tiga tahun kami berteman, baru kali ini aku melihat Delia salah tingkah. "Apalagi aku apa?"
Delia mendeham. "Kamu ... sendirian. Nggak punya orang yang harus kamu mintai izin."
"Ah."
Kali ini kami sama-sama membungkam. Delia mengambil ponselnya dan mengetik, menunggu suasana canggung ini mencair. Hawa makin gerah, menerbitkan titik-titik peluh di dahiku. Seraya menyekanya dengan punggung tangan, aku tercenung.
Orang tuaku bercerai selagi aku masih bayi. Papi ditugaskan bekerja di Jerman, dan hingga kini tak ada kabarnya. Ketika usiaku sembilan tahun, Mami menikah lagi. Suami barunya tak ingin dibebani anak dari pernikahan lama, maka aku diserahkan pada Opa, ayah dari Mami. Aku pun tinggal di Malang bersama Opa, dan Mami pindah bersama suaminya ke Semarang.
Setahun sekali Mami berkunjung ke Malang, menengok aku dan Opa. Tahun ini Opa meninggal akibat kanker. Rumahnya dijual dan kini aku tinggal di rumah kos. Semua teman kuliahku tahu tentang situasiku ini.
"Aku cuma pengin bantu kamu," cetus Delia. "Salah rasanya, ada teman sebatang kara dibiarin begitu aja."
"Makasih." Istilah sebatang kara, kendati melodramatis, juga tepat. Semua kakek dan nenekku sudah tiada. Papi dan Mami sama-sama anak tunggal, maka aku tak punya om, tante, maupun sepupu. Kerabat lain tinggal di Sumatera dan Kalimantan, serta jarang berkontak denganku.
Jam digital menunjukkan pukul tujuh. Karena Delia datang kemari begitu kegiatan BEM fakultas bubar tadi sore, dia belum makan malam. Maka dia mengucapkan pamit, dan aku mengantarnya sampai ke halaman rumah kos.
Di depan pagar, kami berhenti sejenak. Wajah Delia tersapu sinar kuning dari lampu pagar. "Jangan kelamaan mikirnya." Dia menegaskan. "Keburu Bu Triya nerima pegawai baru."
Aku mengiakan.
"Tanya-tanya aja ke aku kalau masih bingung. Atau kamu butuh diskusi sama temanmu itu—siapa namanya, Gabrian?"
Mendengar nama itu, aku merasa tertikam. Bayangan jok sepeda motor yang koyak oleh benda tajam terkilas di depan mata. Aku menghirup udara penuh-penuh, lalu menyunggingkan senyum kaku pada Delia.
"Nggak perlu," jawabku.
"Ya, udah. Aku tunggu jawabanmu besok. Pagian dikit, jangan siang-siang!"
"Oke." Sembari aku menjawab, tatapanku menyesar ke bahu Delia.
Di sana menjuntai sepotong lengan: pucat tak berdarah dengan urat biru bertonjolan. Kuku-kukunya retak dan hitam oleh tanah. Delia tak menyadari adanya lengan itu, seperti dia tak menyadari seraut wajah yang mengintip dari belakang kepalanya.
Wajah si pemilik kepala—seorang gadis remaja—sama pucat dengan lengannya. Tadi, begitu aku dan Delia keluar ke halaman, gadis itu kontan menempel di punggung Delia. Dia kerap melakukan hal serupa pada tamu perempuan. Aku tak menyalahkannya; mungkin dia kesepian berada di rumah kos yang hanya dihuni laki-laki.
Selagi aku menatap gadis itu, kedua bola matanya menggeleser dari rongga. Bola mata itu bergulir jatuh, menyisakan jejak lendir di pipinya. Aku kembali mengalihkan tatapan pada Delia.
"Pasti aku kabari," ujarku. "Ngomong langsung ke kamu, kalau perlu. Tapi ketemuannya di kampus, jangan di rumah kosku."
***
"Selamat siang, Bu Triya," kataku. "Saya Izarra, yang tadi kirim pesan WhatsApp ke Ibu."
"Siang, Iza," jawab wanita di layar ponselku itu. Sinyal internet sedang labil, maka gerakan Bu Triya pada video agak terpatah-patah. Delia menawariku pekerjaan di losmen tadi malam, dan pagi ini aku menjawab: Setuju. Minta nomornya Bu Triya. Peluang kerja sekecil apa pun akan kuambil sebelum lolos.
Delia mengirimkan nomor Bu Triya. Hubungi beliau pukul satu siang, ujarnya. Jam segitu beliau selesai makan dan lagi istirahat. Nggak usah takut, orangnya baik, kok. Pada waktu yang ditentukan, aku memperkenalkan diri pada Bu Triya lewat pesan WhatsApp. Dari situ, kami sepakat bicara melalui video call.
"Delia bilang apa saja ke kamu?" tanya Bu Triya. Di balik kacamata berbingkai tanduk, sepasang mata beliau dikelilingi garis-garis halus. Rambutnya yang kelabu disanggul di tengkuk dengan tusuk kundai.
"Katanya Ibu butuh pegawai. Tidak pandang pengalaman dan syaratnya, um, kebal sama makhluk halus."
Diucapkan dengan sebegitu gamblang, syarat pekerjaan ini terasa konyol. Akan tetapi, alih-alih geli, Bu Triya tampak serius. Berarti masalah penghuni gaib di losmennya cukup genting.
"Omong-omong soal pengalaman," ujar Bu Triya, "pengalaman kerja kamu apa?"
Aku terbatuk jengah. "Baru tiga, Bu. Jaga toko milik opa saya, kerja magang di industri minuman ringan, dan katering bareng teman-teman."
Opa pernah mengelola sebuah warung kelontong. Di luar jam sekolah, aku bertugas menjaga warung dan mendata keuangan. Setelah kesehatan Opa menurun, warung itu ditutup. Semasa kuliah, aku dan sejumlah teman pernah berbisnis katering kecil-kecilan. Katering itu bubar sejak kami semua sibuk bekerja magang.
"Baik," kata Bu Triya. "Kapan kamu bisa mulai kerja?"
Aku mengerjap. Tiba-tiba sekali? "Anu, saya nggak perlu bawa CV ke losmen dan diwawancara?"
"Silakan saja. Tapi aku percaya pada Delia. Anak itu pintar menilai orang. Dia pasti mengajukan namamu bukan hanya karena kamu kebal makhluk halus. Kalau dia percaya kemampuanmu, aku juga. Jadi, kapan?"
"Besok hari wisuda," jawabku, masih beradaptasi dengan perkembangan ini. "Saya bisa datang sorenya. Apa sekalian saja saya mulai kerja?"
"Boleh. Bawa sebagian barang-barangmu—kamu pindah kemari dulu, hafalkan tugas, baru mulai kerja. Bagaimana?"
Aku setuju, dan kami menetapkan pukul tiga sore untuk waktu kedatanganku ke losmen.
"Satu hal lagi," kata Bu Triya. "Kamu masih muda, pasti ingin cari banyak pengalaman. Aku cuma minta, kamu kerja di sini minimal enam bulan. Dalam kurun waktu itu, akan kuusahakan losmen bebas dari gangguan. Sesudah enam bulan, terserah kamu, tetap bekerja di sini atau tidak."
"Terima kasih, Bu. Saya bakal kerja keras, nggak bikin kecewa Ibu."
Beliau tersenyum simpul. Dalam bayanganku, senyum itu isyarat bahwa kelak beliau akan menagih janjiku. Kami saling mengucapkan selamat siang, dan video call berakhir. Aku termangu, tanganku tetap memegang ponsel hingga layarnya mati.
Pergantian status menjadi pekerja ini terlalu cepat. Hanya makan waktu seperempat jam saja. Kelak, akankah aku bersyukur telah bekerja di Tawang Permai, atau justru menyesal?
Yah, sudahlah. Kepalang basah, jalani saja. Sejak Opa meninggal, aku makan dan membayar biaya kuliah dari uang penjualan rumah. Bekerja di losmen adalah babak pertama dalam upayaku menjadi manusia mandiri—dan menyingkirkan Gabrian dari hidupku.
***
Aku dan Gabrian seangkatan tapi berbeda prodi. Dulu aku hanya mengenalnya sebagai salah satu mahasiswa yang berasal dari Jakarta. Tipikalnya, anak-anak ini belajar Bahasa Jawa ala kadarnya, serta menyebut diri sendiri dan teman lain dengan lo-gue.
Kala itu pertengahan semester delapan, dan kondisi Opa memburuk. Beliau divonis mengidap kanker limfoma, dan gejalanya makin hari makin akut: gerakan serbalamban, pembengkakan kelenjar, dan selera makan berkurang. Suatu pagi beliau tidak sanggup bangkit dari tempat tidur. Diantar seorang tetangga dengan mobilnya, aku membawa Opa ke rumah sakit.
Esoknya, Opa tak sadarkan diri dan tanda-tanda vitalnya menurun. Aku membolos kuliah demi menunggui beliau. Hasil analisis dokter menjurus pada satu simpulan: usia Opa tinggal menghitung hari.
Opa diopname, tulisku pada pesan WhatsApp untuk Mami. Dokter bilang mungkin nggak akan sembuh lagi. Mami datang ke Malang, dan ganti menjaga Opa sementara aku pergi ke kampus.
Hari itu kuliah usai pukul dua siang. Dari ruang kuliah, aku langsung menuju perpustakaan fakultas. Di sana hanya ada dua mahasiswi yang sedang menggarap tugas. Aku pergi ke pojok paling terpencil, lalu terperenyak di lantai.
Sebelas tahun lamanya aku dan Opa saling menemani, menopang dan mengasihi. Kini beliau menyongsong ajal, akan meninggalkan aku selamanya. Siapkah aku melepas Opa? Melepas orang yang bertahun-tahun membesarkan aku dengan kasih sayang?
Dadaku sesak. Air mataku berlinang, dan kepalaku terkulai. Sebentar lagi aku kembali ke rumah sakit. Di sana aku harus berperan jadi anak dan cucu yang tabah. Sebelum itu, dua atau tiga menit ini akan kugunakan untuk menumpahkan perasaan.
"Diputusin pacar?"
Aku tersentak dan menengadah. Seorang mahasiswa prodi lain tengah berdiri di depanku dengan tatapan ingin tahu. Akibat terkancah emosi, aku tak mendengar langkah kakinya. Buru-buru aku menyusut air mata dan ingus.
"Iza dari Akuntansi, kan?" lanjut mahasiswa itu. "Gue Gabrian, Manajemen. Uh, lagi ada masalah?"
Aku berkata bahwa kakekku diopname, dokter pesimis beliau akan sembuh, dan ibuku tengah mencari alamat rumah duka di Malang.
"Oh." Gabrian menggeser-geser kaki. "Mau gue tinggal atau lo perlu curhat?"
"Terserah. Ini tempat umum, nggak ada yang berhak ngatur kamu mesti gimana."
Gabrian menggaruk dagunya. "Gini. Gue mau ngaku—yang diputusin pacar itu sebenarnya gue. Kami cocoknya cuma sebagai tetangga kos, jadi, yah, dia bilang balik aja lagi jadi cuma tetangga. Gue kemari buat menyepi, ternyata ada lo duluan."
Aku bangkit dari lantai. Tubuhku jangkung, tapi Gabrian bongsor dan berbahu lebar. Dibandingkan dia, aku ibarat tiang listrik. "Silakan di sini, aku mesti jaga Opa lagi."
"Di mana rumah sakitnya? Gimana kalau gue antar? Kondisi kakek lagi genting, pasti lo pengin cepat-cepat sampai."
Kendati aku menampik, Gabrian berkeras ingin mengantarku. Akhirnya aku mengikuti dia ke halaman parkir kampus dan ke mobilnya, sebuah sedan Corolla berdebu. Aku meminta maaf telah merepotkan Gabrian, dan dia menggeleng. "Daripada galauin mantan, mending gue manasin mesin mobil."
Jarak rumah sakit lumayan jauh dari kampus, tapi Gabrian tidak lantas mengajak aku mengobrol. Di iPhone-nya, dia menyetel siniar TED Talks Daily. Aku mengalihkan pikiran dengan menyimak topik episode ini: menghadapi rasa takut alih-alih lari darinya.
Ketika Gabrian menghentikan mobil di gerbang rumah sakit, aku berterima kasih. Dia mengawaikan tangan. "Gue yang makasih, jadi ada kerjaan." Gabrian menginjak pedal gas, dan sedan putih itu berlalu.
Opa meninggal dua hari kemudian. Delia dan teman-teman prodi melayat ke rumah duka. Gabrian ada di antara mereka, satu-satunya anak Manajemen. Dia menjabat tanganku dan bergumam, "Turut berduka cita. Semoga opa lo udah nggak sakit lagi," dan aku hanya mampu menepuk tangannya.
Setelah teman-teman prodiku pulang, Gabrian tetap mendampingi aku. Dia berkisah sedikit tentang dirinya: anak tunggal, lahir dan besar di Jakarta. Orang tua Gabrian sama-sama bekerja sebagai arsitek. Dia sengaja berkuliah di Malang demi belajar hidup jauh dari keluarga. Sebelum pulang, dia menyuruh aku mencatat nomor ponselnya. "Siapa tahu lo butuh."
Berdua dengan Mami, aku mengurus penjualan rumah Opa. Selagi sakit, Opa sudah menyetujui penjualan itu. Pembelinya adalah kenalan beliau, seorang pengusaha rumah kontrakan. Beres menangani penjualan rumah, Mami bertanya tentang rencanaku setelah wisuda.
"Kamu sekarang sudah besar, Iza. Sudah siap mandiri. Tapi kamu tetap anakku. Perlu dibantu cari kerja?"
Aku tersenyum sopan. Setelah sebelas tahun, jarak di antara kami kian renggang. Ikatan kami sekadar hubungan biologis serta kemiripan fisik: wajah oval, mata sipit panjang. Kami berdua asing dengan satu sama lain, dan aku tak akan membuang waktu dengan menyalahkan siapa pun. Lebih baik menabung energiku untuk masa depan.
"Cari sendiri juga bisa. Terima kasih perhatiannya. Selamat pulang ke Semarang, hati-hati di jalan."
Mami meminta aku menghubunginya jika ada apa-apa. Ya, jawabku singkat, tanpa tahu apakah aku akan memenuhi janji itu. Mami meninggalkan Malang, dan kembali raib dari hidupku.

