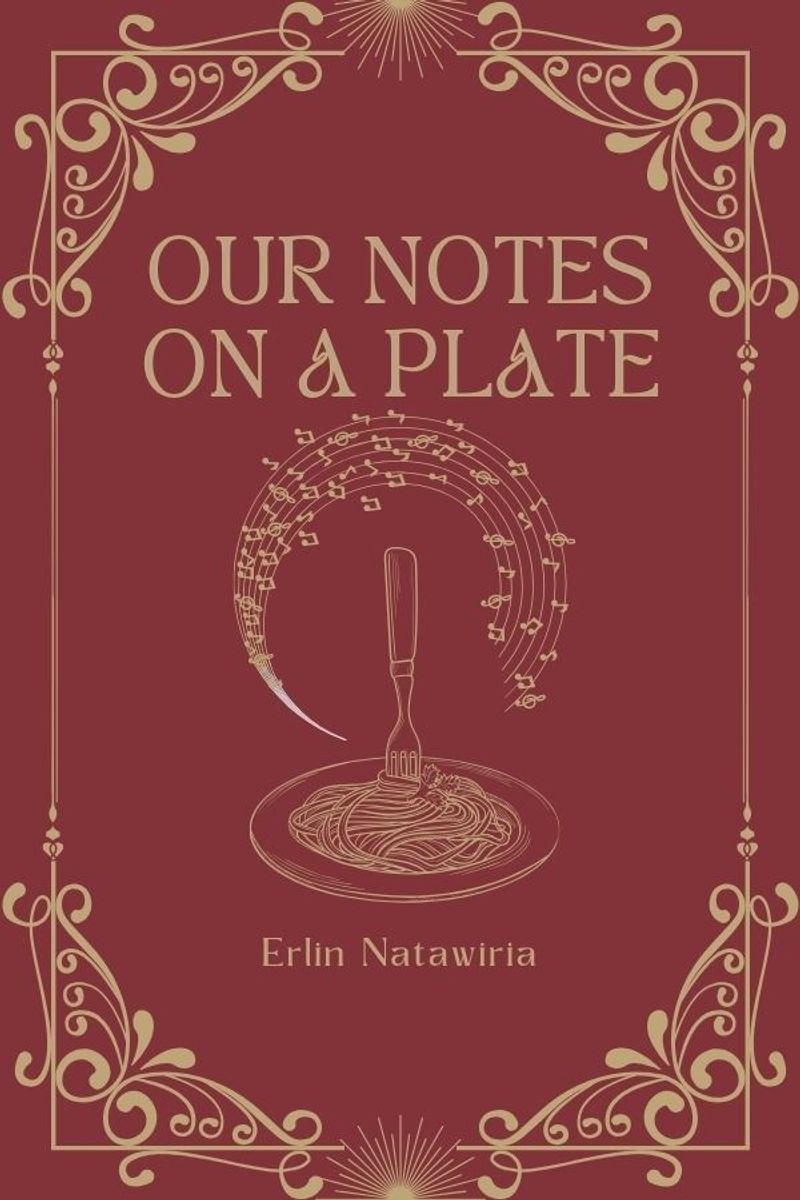
| Kemudian, Ethan mengembuskan napas panjang sebelum meraih tanganku. “Maaf tiba-tiba harus bertemu denganku dalam keadaan seperti ini.”
“It’s fine. Bersyukurlah karena kita udah kenal lama.” Ethan lalu membantuku berdiri. “Kamu enggak mau beli buku atau barang lain sebagai kenang-kenangan?”
Mulutnya mengeluarkan tawa yang terdengar menyedihkan. “Seperti yang kubilang tadi, seandainya bisa, aku ingin mengambil kembali sebagian hidupku yang sudah hilang.”
[ETHAN] Aku lolos TOEFL dan IELTS.
[Winona] Congrats! Rayakan, dong!
[Ethan] Boleh, tempat ramen yang enak di mana, ya?
Setelah menyebutkan kedai ramen autentik baru yang kuliput minggu lalu, aku langsung meluncur meninggalkan No. 46. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Ethan memintaku mampir ke toko buku di BIP. Aku sempat tersesat ke lantai teratas karena jarang masuk. Begitu mengecek peta yang disediakan pihak mal, aku berhasil menemukan toko buku tersebut.
Di atas pintu masuknya, tergantung spanduk berwarna merah bertuliskan Closing Sale. Di bagian luar, terpajang koper, tas, dan ransel dengan diskon sampai 50%. Ada juga buku-buku lama yang dijual dengan harga mulai dari Rp10,000. Kemudian, aku melangkah ke dalam mencari Ethan.
Di tengah lantunan lagu-lagu bertema perpisahan, aku melongkok ke rak-rak yang separuhnya sudah dikosongkan. Ethan, yang posisinya memunggungiku, sedang membaca sebuah buku di rak Fiksi.
“Hei.” Ethan langsung menoleh begitu menyadari kehadiranku. “Untung aku baru sampai perempatan Merdeka pas kamu chat tadi.”
“Kalau bukan temanku yang kasih kabar tentang closing sale ini, aku juga bakal jalan terus ke kedai ramen rekomendasimu.” Sekilas, aku melihat gurat duka dan kekecewaan dari pandangannya. “Dulu waktu menyusun skripsi, aku sering mampir ke sini buat cari buku-buku yang dosbingku referensikan. Toko ini juga memajang buku lebih lama daripada toko buku seberang.”
Pantas Ethan mendadak jadi sentimental. “Closing sale-nya masih lama, kan?”
“Iya, sampai bulan depan, tapi….” Matanya mengamati setiap sudut toko buku. “Bisa lebih cepat. Rak scrapbook di dekat pintu masuk saja sudah dikosongkan.”
Ethan bergeming sejenak, lalu menata buku yang berserakan di sekitar kami. Dia paling gatal melihat buku yang tidak disimpan sesuai dengan genre. Bahkan dia pernah rela memutari seluruh rak demi menaruh satu buku Biologi yang tersesat di sektor Hobi. Aku sempat bilang dia lebih cocok kerja jadi staf toko buku daripada jurnalis dan, yang mengejutkanku, dia mempertimbangkannya.
“Do you need help?” tawarku.
Ethan, yang sedang merapikan baris terbawah, menengadah. Lapisan bening di matanya mengejutkanku. “Seandainya aku punya banyak uang untuk membeli satu toko buku sekarat—”
Kutepuk pundaknya, lalu ikut duduk di lantai. “Aku turut berduka cita meski enggak punya ikatan batin dengan toko buku. Di sisi lain, barangkali ini emang udah saatnya mereka tutup. Persaingan bisnis di mal, seperti tempat-tempat makan yang kusinggahi, semakin ketat. Mereka yang enggak bisa bertahan terpaksa harus mengalah.”
Ethan menaruh buku terakhir di pojok terbawah rak. “Pertama, toko-toko musik yang menjual rilisan fisik. Sekarang toko buku juga mulai menyusul. Aku tidak bisa menolak perkembangan teknologi juga, Wine. Hanya saja menyaksikan tempat-tempat itu hilang seperti mendapati sebagian hidupmu direnggut paksa.”
“Menurutku, secanggih apa pun teknologi, tetap enggak ada yang mampu mengalahkan keterampilan manusia,” kataku, berusaha menghiburnya. “It’s just inevtaible to stop something that must end, Ethan.”
Kemudian, Ethan mengembuskan napas panjang sebelum meraih tanganku. “Maaf tiba-tiba harus bertemu denganku dalam keadaan seperti ini.”
“It’s fine. Bersyukurlah karena kita udah kenal lama.” Ethan lalu membantuku berdiri. “Kamu enggak mau beli buku atau barang lain sebagai kenang-kenangan?”
Mulutnya mengeluarkan tawa yang terdengar menyedihkan. “Seperti yang kubilang tadi, seandainya bisa, aku ingin mengambil kembali sebagian hidupku yang sudah hilang.”
*
Ethan tetap memenuhi janjinya dengan mengajakku makan di kedai ramen autentik yang kurekomendasikan. Sambil menghabiskan kuah tori paitan ramen, aku mengamati lampion-lampion mungil dan gambar barongsai di beberapa sudut. Imlek tinggal menghitung hari. Itu berarti akan ada daftar panjang promo makan di hari raya tersebut.
Dalam arti lain, aku akan kembali sibuk pergi meliput.
Anyway, ramen di tempat ini luar biasa lezat, tapi atmosfernya tidak. Maksudku, dari Ethan, bukan tempat makannya.
Ethan menyandarkan punggung begitu selesai makan. Kupikir mood-nya bakal membaik setelah menyantap makanan enak. Sayang, prediksiku lagi-lagi salah. He’s still gloomy. Firasatku juga mengatakan penyebabnya bukan hanya toko buku favoritnya yang akan tutup.
“I’m all ears, Ethan.” Aku mengaduk-aduk ice matcha green tea yang esnya mulai meleleh. “Apa ada hal lain yang mengganggumu? Beasiswa? Pekerjaan?”
“Kita.” Aku bersyukur sedang tidak meneguk minuman. Hubungan kami. Cepat atau lambat, dia pasti akan mengungkitnya, tapi, bukan sekarang, terutama setelah aku menandaskan seporsi ramen enak.
“Wine, kita akan terus seperti ini, ya?”
“What do you expect? Getting back together?” Aku tidak menyangka bakal sefrontal ini di hadapan Ethan. Sebaiknya aku harus mengendalikan emosi mengingat mood Ethan kurang bagus. “Kita baik-baik saja, kan? Kecuali kamu punya motif lain selama kita ngobrol beberapa minggu terakhir.”
Ethan menegakkan punggung dan menatapku dengan raut wajah serius, seolah-olah aku calon karyawan dengan CV kurang memuaskan. “Rhea bilang kamu pindah.”
Aku menaruh ice matcha green tea di meja. Seharusnya aku ingat Rhea paling lemah berhadapan dengan pria semacam Ethan. “Terus?”
“Perkiraanku salah.” Ethan mengalihkan pandangan ke belakang pundakku. “Awalnya aku berpikir sikapmu yang terus menghindar adalah efek berkabung yang masih tersisa. Tapi dari satu pertemuan ke pertemuan selanjutnya, aku merasa kamu semakin tertutup, Wine.”
“Is that a problem? Kalau aku emang enggak mau terbuka lagi sama kamu, then please respect my decision.”
Kepalanya menggeleng tegas. “Aku—aku juga cemas sikapmu ini tidak hanya berlaku padaku saja. Bagaimana dengan Ghina? Apa kamu menyembunyikan sesuatu darinya?”
“Well, that’s not your business. Jangan bawa-bawa sahabatku dalam masalah kita.” Waiter dan kasir yang berada dua meja dari tempat kami mengamati dari ekor mata. “Apa masalahmu, sih? Tadi kamu gloomy, sekarang cranky.”
“Aku—” Tangannya terkepal. “Aku tahu di mana kamu tinggal sekarang.”
Sekonyong-konyong, otakku menghubungkan potongan-potongan misteri yang nyaris memicu emosiku. Tenang, tenang, jangan terpancing. “Okay, and?”
“Wine, aku cemas. Aku juga takut kamu—oh, lupakan saja.” Tiba-tiba, Ethan yang kekenal lihai merangkai kalimat mendadak kehilangan kemampuannya. “Kamu juga sudah mengambil keputusan.”
“Don’t worry, Aries adalah tuan rumah yang baik. Trims karena kamu juga ternyata masih mencemaskanku, tapi aku bukan masalah yang perlu kamu perbaiki, Ethan. We’re done, remember?”
Biasanya, aku akan merasa sangat bersalah setelah menyampaikan unek-unek kepada Ethan. Ilusi pria sempurna yang menyelimutinya membuatku berpikir dia tak pernah melakukan kesalahan, so I blamed myself instead.
Namun, kali terakhir aku melakukannya, hubungan kami memburuk. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku. Ayahku. Harga diriku. Butuh waktu berbulan-bulan sampai aku bisa bangkit dan menata hidupku lagi. Kini, meski menyakitkan, aku tak mau Ethan membiarkanku jatuh ke lubang yang sama.
“I should go back,” kataku; memecah keheningan seraya beranjak dari kursi.
“Biar kuantar—”
“No, no, aku bisa pulang sendiri,” sergahku cepat sambil meminta waiter membawakan bill. Keterkejutan dari sorot mata Ethan adalah respons yang ingin kulihat. “Satu lagi, jangan menguntit kami. Apa pun alasanmu, that’s creepy.”
“Maafkan tindakanku yang membuat kalian tak nyaman. No more stalking.”
“Kupegang janjimu.” Aku menyelipkan selembar uang seratus ribu pada bill yang disodorkan waiter. “Ingat kataku tadi, kita enggak bisa mencegah sesuatu yang semestinya harus berakhir, Ethan. Just like what happened to us. It’s over.”
***
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰

