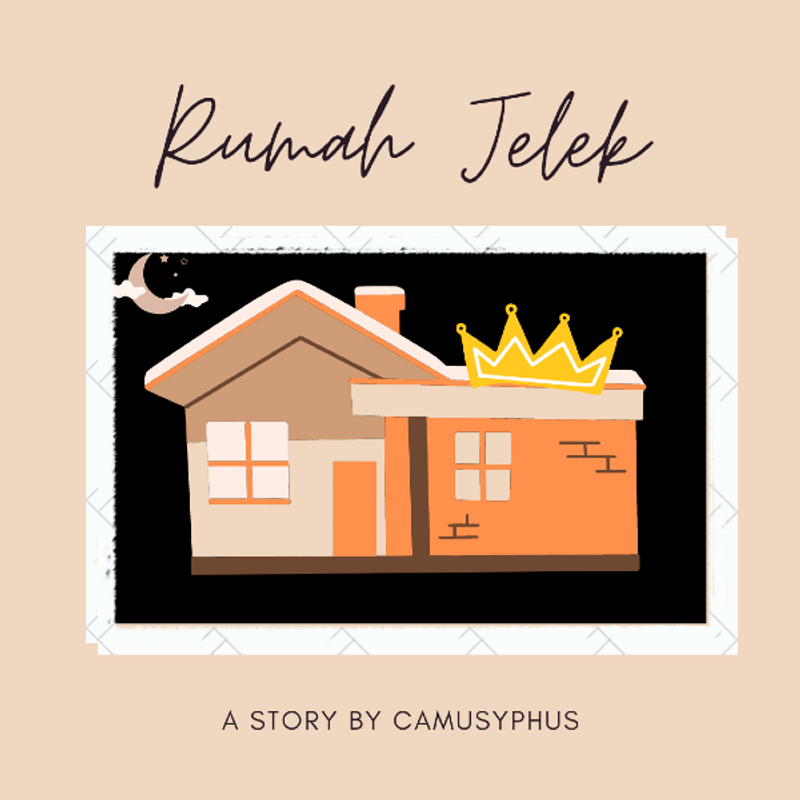
Sari tahu rumah itu tidak jelek.
Tapi ia tidak bisa mengatakan rumah itu bagus.
Setidaknya keluarganya nampak lebih bahagia.
Setidaknya untuk malam ini.
I. Sisa waktu: 25 tahun.
Nggak.
Rumah itu nggak bagus, tapi nggak jelek juga.
Pagar rumahnya terbuat dari besi, pintunya terbuat dari kayu jati. AC sudah terpasang dengan baik. Lantai 2 sudah siap buat jemuran baju. Ada pekarangan kecil di dekat pagar. Rumah itu tidak terlalu buruk untuk keluarga yang dinafkahi seorang karyawan swasta.
Sari juga tahu rumah itu nggak jelek, tapi ia tidak bisa berkata rumah itu bagus juga.
“Jingga norak.”
Begitu pikir Sari yang melihat tembok depan dari depan pagar, sambil menenteng kardus terakhir dari mobil pickup. Rumahnya sudah terlanjur di-cat dengan warna pilihan suaminya, dan dia sudah terlanjur bilang iya. Ya sudah, mau diapakan lagi.
Kakinya kemudian melangkah ke pintu utama, dan kemudian, ke dalam rumah.
Di balik pintu, ruang tamu itu masih kosong. Selain keluarganya, yang menunggu Sari di dalam adalah sebuah sofa coklat yang baru ia beli, puluhan kardus yang baru mereka pindahkan, serta bau cat berkualitas medioker yang tidak akan hilang dalam beberapa hari ke depan.
Ikal, suaminya, duduk selonjoran di lantai sambil meneguk segelas teh manis.
“Ma, kardus isi barang-barangku di mana, ya?” tanya Rofi, anak sulungnya.
“Tuh, yang di belakang sofa.” Sari menjawab.
“Kalau buku-buku pelajaran Lara?”
“Ada di kardus sampingnya. Lihat dulu, dong, yang bener. Baru habis itu nanya.”
“Oh iya, Ma.” Balas Rofi, yang tidak sabar membuka kardus-kardus tersebut.
Sari meletakkan kardus terakhir yang dia bawa di lantai.
“Udah dulu, Fi. Istirahat dulu,” kata Ikal.
“Gapapa, Pa. Nggak sabar aja mau beberes barang-barang dan langsung taro ke kamar masing-masing.” Rofi menjawab, sambil membuka selotip di kardus bertuliskan “BUKU”.
“Ya, boleh. Tapi nanti saja. Papa mau ajak kita semua berdoa, bersyukur sama Tuhan, udah kembali ke rumah ini lagi.”
Lara, anak bungsu Sari, mengrenyitkan dahinya. “Loh, dulu emang kita pernah tinggal di sini?”
Ikal tadinya sudah siap-siap mau berdoa bersama. Tapi berbagai kenangan melintas di kepalanya, dan ada cerita yang bisa ia bagi pada Lara. Ikal selalu senang bercerita, khususnya ke anak bungsunya yang masih SD kelas 3.
“Iya, sebelum kamu lahir. Ini rumah pertama Papa dan Mama. Sebelum kak Rofi lahir, Papa-Mama nabung mati-matian untuk dapat rumah ini. Akhirnya dapet, deh.,” kata Ikal tersenyum.
Senyum di wajah Ikal berbeda 180 derajat dengan ekspresi wajah Sari, yang terlihat seperti sedang berpikir banyak.
“Tapi Mama sekarang nyesel, Pa. Harusnya kita beli di Tangerang aja.,” celetuk Sari.
Ikal menghela nafas. “Ya, gapapa lah. Kan ini lebih deket ke Jakarta. Daerahnya juga lebih berkembang, nggak udik-udik banget. Makanan di sini masih lebih murah. Toko kelontong dekat. Udara di sini masih sejuk.,” balas Ikal.
“Ini berkat Tuhan. Kita terima aja.,” Ikal melanjutkan.
“Aku seneng di sini, Pa, Ma. Lebih bagus dari rumah kita sebelumnya.,” kata Lara. Dengan luas 120m2, rumah ini terasa jauh lebih luas buat Lara. Warnanya masih baru, imut pula seperti permen jeruk kesukaannya, yang berwarna jingga juga.
“Ya iya, lah. Kan baru direnovasi, sayang.,” Sari menjawab.
“Kalau kamu gimana, Fi?,” tanya Sari ke anak sulungnya.
Rofi termenung. Buat Rofi, rumah ini nggak seperti rumah temen-temennya yang orang tuanya kaya, tapi ini nggak sejelek rumah mereka kemarin. Rumah mereka kemarin, yang orangtuanya sewa selama puluhan tahun, nggak punya cat sebersih ini. Tiap malam ada suara tikus di dapur, dan kecoa di tong sampah. Rofi benci tiap kali dia harus berurusan dengan kecoa.
Di sini, tong sampah pun belum ada, apalagi kecoanya.
Tapi rumah lama Rofi dekat sekali dengan rumah teman-temannya.
Sekarang, Rofi akan lebih jarang berkunjung dan main PS ke rumah Ridho, Rama, dan David. Mereka akan berkomunikasi lebih intens lewat hape.
Tapi setidaknya rumahnya lebih layak.
Rofi menghela nafas, seperti bapaknya tadi, lalu menjawab, “Sama. Aku juga senang di sini.”
Ikal senang mendengar jawaban anak-anaknya, khususnya waktu Lara bilang rumah ini lebih bagus. Keputusan pindah lagi ke sini merupakan keputusan yang tepat. Yang lebih tepat lagi, Ikal berhasil membujuk Sari untuk merenovasi rumah ini, dan renovasinya selesai 2 hari lalu dengan lancar.
Mendengar jawaban anak-anaknya, Sari juga lebih legowo. Warna rumah ini mungkin norak, tapi setidaknya anak-anaknya nampaknya akan lebih betah di sini.
“Semoga kalian semua betah di sini, ya. Kalian bakal tumbuh dewasa di sini, lho,” kata Sari.
“Nggak pindah-pindah lagi kita, Ma?” Rofi tanya.
“Harusnya nggak, sih. Gimana, Pa? Pindah nggak?” tanya Sari, dengan nada sedikit bercanda ke suaminya.
“Nggak lah. Papa yakin, ini rumah yang Tuhan kasih buat kita.”
Tidak lama setelah percakapan itu, Ikal sekali lagi mengajak keluarganya berdoa. Sebagai keluarga Nasrani yang taat, tiap anggota keluarga sudah terbiasa berdoa. Dan Ikal selalu mau tiap anggota keluarganya berdoa bergiliran.
Ikal sebagai kepala keluarga terbiasa berdoa dengan kata-kata formal dan suara yang agak berwibawa.
Sari, sebagai istri yang diharuskan taat dan rendah hati oleh Alkitab, selalu berdoa dengan nada tulus dan kata-kata penuh kerendahhatian.
Sementara itu, Rofi sebagai anak sulung selalu mencoba untuk mengikut wibawa papanya dan ketulusan mamanya.
Doa Lara yang masih SD tidak sepanjang doa anggota keluarganya yang lebih tua, tapi doanya polos dan jujur.
Malam itu, dua orang berdoa dengan penuh syukur, sementara dua orang berdoa dengan mencoba ikhlas.
Malam itu, terlepas dari perbedaan cara mereka berdoa, setidaknya mereka masih sama-sama berlutut dan berdoa sebagai keluarga.
That night, they got all the time in the world, and the house was theirs, and theirs alone.
Buat sebuah keluarga yang punya rumah baru dan waktu sebanyak 2.5 dekade, momen seperti ini indah, tapi tidak ada nilainya.
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰

