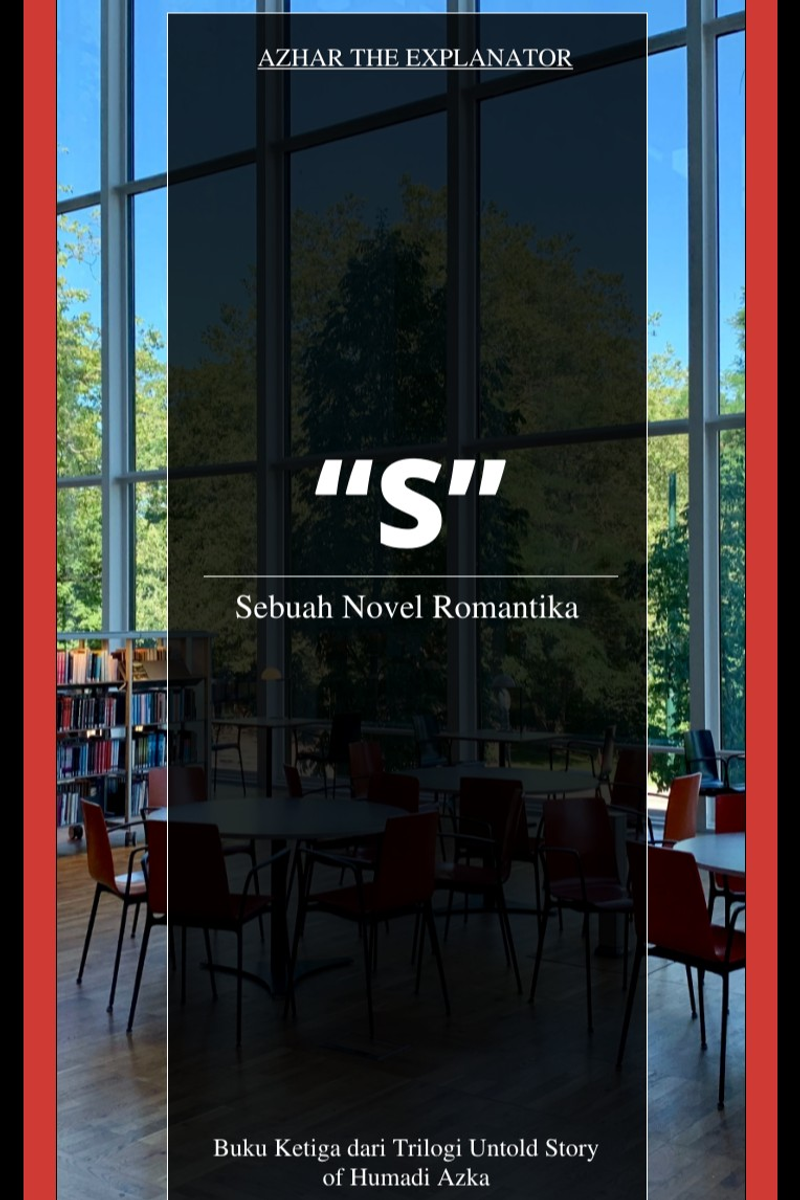Ini adalah semester terakhir di Quart School. Sebuah titik yang sangat spesial bagi Azka, sebab dia dikepung banyak hal. Mulai dari Syifa yang sampai sekarang masih bersarang di hatinya, Dahlia Anggraini dan persahabatannya, Icha Aprilianty yang datang dari masa lalunya, Mawar Alvera dan pesonanya, dan Shiela dengan kejeniusannya. Terdengar rumit, namun tidak.
Di sini, di Quart School, semua tampak begitu memikat. Sekolah terbaik itu sedang ada dalam pergantian suksesor. Seorang guru terbaik,...
Mozaik 1
Ibu Guru Baru
Setelah membaca beratus-ratus catatanku tentang cerita Humadi Azka, aku rasa sudah waktunya aku menuntun kalian melompat beberapa bulan, ke awal semester 5. Kali ini aku ingin bercerita tentang seseorang yang sederhana, namun sempurna. Ah aku berlebihan.
Telah aku sadari bahwa Quart School, bukan hanya soal metode belajarnya yang luar biasa. Bukan saja tentang makanan di kantinnya yang enak. Bukan saja tentang guru-guru berdedikasi tinggi. Quart School adalah tempat berkumpulnya karakter-karakter unik. Sebut saja Aram, Wahid dan Nasri. Berkat kehadiran mereka, Quart School menjadi lebih semarak.
Hari ini, di minggu pertama Semester 5, seorang karakter lagi bergabung ke Quart School. Seorang ibu guru muda. Desas-desus tentang beliau sudah menyebar ke seluruh penjuru mata angin, memudahkanku untuk mengumpulkan informasi. Jadi beginilah kira-kira profil Ibu Guru baru itu. (Perlu kuperingatkan, karena sumbernya adalah desas-desus, tidak semua hal yang ditulis di sini, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.)
Ibu guru baru itu pernah mengajar di salah satu sekolah kejuruan di luar daerah sebelum direkrut oleh Quart School. Perekrutan beliau bukan tanpa alasan, karena beliau adalah seorang guru yang berprestasi. Bayangkan, sekolah kejuruan tempat beliau mengajar dulu, adalah salah satu sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah paling tertinggal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Beliau kemudian masuk dan berusaha memperbaiki keadaan. Dengan sentuhan beliau yang ajaib, dalam waktu cukup singkat, 5 tahun, sekolah kejuruan itu berubah total menjadi sekolah terbaik di kabupaten tersebut. Para alumninya bahkan kini mengisi jabatan-jabatan teknis yang penting di BUMN.
Setelah diangkat sebagai guru terbaik se-kabupaten, dan dianugerahi gelar kehormatan, Quart School mencomotnya. Hei bukankah sekolah kami adalah tempat terbaik untuk kapasitas beliau sebagai guru yang hebat. Kepala sekolah sangat berharap ibu guru muda itu bisa membawa angin segar untuk Quart School. Kami juga demikian.
Dikatakan, beliau adalah tipikal orang yang bukan hanya berwawasan luas, tapi juga memiliki pembawaan yang memikat. Tutur kata beliau lembut dan santun. “para preman” sekolah akan berlaku di hadapan beliau serupa siswa yang memenangkan MTQ tingkat provinsi. Satu kata yang beliau bawakan bisa menembus kalbu siapa saja yang mendengarnya. Luar biasa kawan, luar biasa. Tak sabar rasanya aku bertemu dan bertegur sapa dengan beliau.
“Ah itu hanya desas-desus Az, banyak dilebihkannya.”
Aku mendelik. Yang bersuara barusan adalah Lia. Dia menyela ceritaku yang kusampaikan dengan berapi-api tentang Ibu Guru baru yang akan bergabung di Quart School. “Se-berlebihan apa?” tanyaku, menaikkan alis.
“Misal di bagian, ‘para preman” sekolah akan berlaku di hadapan beliau serupa siswa yang memenangkan MTQ tingkat provinsi. Satu kata yang beliau bawakan bisa menembus kalbu siapa saja yang mendengarnya’. Menurutku itu dilebihkan. Tutur kata melibatkan emosi. Respon emosi yang diterima manusia terkadang berbeda-beda. Bagimu berkesan, boleh jadi bagi Nasri tidak.”
“Aku berusaha untuk tidak mendengar apa-apa,” Nasri menyahut cepat.
Lia menunjuk pria yang duduk di sebelahnya. Kami duduk di depan musholla Quart School. Aku, Lia dan Nasri. Lia menyambung kalimatnya, “tapi jika ada yang bilang beliau guru yang ramah, aku setuju. Menurutku itu tidak berlebihan.”
“Kurasa kau sudah bertemu dengannya,” sahutku.
“Iya.”
“Kurasa bahkan kau sudah tahu siapa nama beliau.”
Lia nyengir. Dasar. “Nama beliau, Qotrun Nada, Ibu Qotrun Nada.”
“Nama yang indah.”
“Bentar lagi kita bakal ketemu beliau kok. Beliau ngajar pelajaran PKN di lokal kita siang ini.”
“Benarkah?” Aku mengerjap mata.
Lokal kami mendadak ramai setelah jam masuk istirahat kedua. Aram dan Wahid yang biasanya uring-uringan di jam siang, malah asyik berdiskusi. Aku menghampiri mereka, heran. “Biasanya kalian tidur siang.”
Aram langsung memasang wajah tersinggung. “Tidak hari ini Az. Aku tidak mau ketinggalan sesi perkenalan dengan Ibu guru yang baru itu. Kau sudah dengar desas-desusnya Az?”
“Sudah.”
“Aku punya update-nya.”
Aku tidak menyahut. Menyilakan Aram untuk bicara. Sebagai pemburu gosip, Aram suka desas-desus. Siapa tahu ada yang belum kudengar.
“Katanya, Ibu guru yang baru itu akan diangkat sebagai wakasek kesiswaan, Az. Bayangkan itu, Ibu Hartini dilengserkan. Astaga,” Aram tidak bisa menyembunyikan gesture senangnya. Jika kawan ingat bagaimana Ibu Hartini selalu mengacaukan empat event besar Quart School, maka kawan akan bisa membayangkan rasanya jadi Aram.
“Ah sepertinya itu dilebih-lebihkan, Ram,” aku meminjam istilah Lia, “tak masuk akal bagiku, guru yang baru masuk bisa langsung duduk di jajaran wakil kepala sekolah.”
“Nah itu Az, yang sedari tadi ingin kujelaskan pada Aram,” Wahid menyahut.
“Bisa saja, kau jangan lupa Hid, beliau adalah guru teladan tingkat kabupaten. Kepala sekolah sendiri yang membujuk dan mengurus kepindahan beliau kemari. Bisa saja, kepindahan beliau memang dimaksudkan untuk mengisi jabatan wakasek kesiswaan.”
Di tengah-tengah semua kalimat Aram yang bersemangat itu, terdengar sebuah salam yang lembut, halus mampir di telinga. Memanggil jiwa untuk membalas dengan salam yang sama.
“Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh,” koor kami semua.
Beliau memakai jilbab kuning lebar, yang nyaris menutupi seluruh badan beliau, dengan rok hitam panjang, yang juga lebar. Beliau memandangi ke seluruh penjuru lokal 4, kemudian berseru.
“Humadi Azka,” panggil beliau. Aku terpelanga, baru sekali beliau masuk, dan beliau sudah memanggil namaku. Ada apa gerangan. Dengan agak takut-takut, aku mengacungkan tangan.
“Tolong dong punguti sampah di bawah meja itu. Terlihat kotor sekali. Kamu jadwal piket hari ini,” ujar beliau lagi. Aku, tanpa disuruh dua kali, langsung mengambil tempat sampah kecil dan memunguti sampah-sampah yang beliau maksudkan.
“Nah begini kan lebih. Apa kata agama kita, an-nazafatu-minal-iman.”
Kemudian beliau duduk di kursi. Aku juga kembali duduk di kursi. Firasatku mulai tidak enak. Sepertinya Lia benar, desas-desus itu terlalu berlebihan. Di luar penampilan Ibu Qotrun Nada (beliau menulis nama beliau di papan tulis), yang cantik dan menawan, beliau mirip seperti Ibu Hartini atau barangkali ibu pengawas jadwal piket kebersihan, menyuruh ini-itu kemudian menyitir dalil untuk membenarkan pendapat beliau.
Aku mulai tidak kerasan. Tapi itu tidak berlangsung lama.
Ibu Qotrun Nada mengajar dengan santai. Sesekali beliau melempar pertanyaan mengenai materi yang beliau ajarkan. Jika salah satu dari kami bisa menjawab, beliau selalu mengacungkan jempol dan senyum manis. Hei, itu membuat kami, entah bagaimana caranya, menjadi lebih bersemangat.
Saat aku berhasil menjawab salah satu pertanyaan beliau, begini kata beliau padaku. “Bagus sekali Azka, ternyata selain rajin, kamu pintar juga. Mantap. Teruskan.”
Oh astaga, aku senang sekali disebut demikian.
Mozaik 2
Event Besar Pertama: Funclass
Ternyata desas-desus itu tidak hanya desas-desus. Terutama perkataan Aram.
Tepat satu hari setelah Ibu Qotrun Nada masuk di kelas kami, suara di pengeras suara, memanggil kami ke lapangan. Aram yang mendengar hal itu, seperti trauma. “Semoga bukan pengumuman yang mengesalkan hatiku,” ujarnya.
Di depan podium upacara, Pak Kepala Sekolah yang gempal itu sudah berdiri gagah memegangi mik, menatap kami semua yang kalang kabut berkumpul. Di samping Pak Kepala Sekolah, berdiri seseorang, mimpi buruk Aram, Bu Hartini.
“Astaga,” beberapa siswa yang melihat Bu Hartini sampai tepuk jidat. Ketika yakin semua murid sudah berkumpul, Pak Kepsek mulai berbicara.
“Anak-anak, murid Quart School semuanya, hari ini Bapak akan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan, sekaligus menyedihkan, tergantung dari mana kalian menyikapinya. Hari ini, akan diadakan perombakan struktur di sekolah kita. Dimana hal ini, nyaris tidak pernah kita lakukan selama sekolah ini berdiri. Jadi Bapak rasa, hari ini akan menjadi hari yang bersejarah…
(Mengenai “hal ini nyaris tidak pernah kita lakukan” itu masih harus diperdebatkan secara seksama),
“Hari ini, setelah menimbang, setelah melewati tahapan rapat yang panjang, Bapak, sebagai Kepala Sekolah memutuskan untuk melakukan pergantian Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Sebagaimana yang kita semua tahu, Bu Hartini telah menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan sepanjang sejarah sekolah ini berdiri, hari ini beliau meletakkan jabatan, dan digantikan oleh Ibu Guru baru, yang muda dan enerjik, dan pasti memiliki program-program tak kalah hebat dari Bu Hartini. Kita sambut, Ibu Qotrun Nada.”
Kalimat kepala sekolah kami sambut dengan gegap gempita, bertepuk tangan. Hanya beberapa orang saja, yang menyadari kalau mik telah berpindah tangan. Bu Hartini berbicara.
“Perlu ibu jelaskan, perlu ibu sampaikan, perlu ibu utarakan, bahwa pergantian ini bukan karena kinerja Ibu yang jelek, bukan karena desakan pihak tertentu, bukan pula karena Ibu dipindah tugaskan. Akan tetapi semata-mata karena keinginan ibu sendiri, ibu ingin menikmati masa-masa menjelang pensiun dengan menjadi guru biasa, tidak mengurusi tetek bengek hal rumit, dan sudah seharusnya ada generasi penerus yang melanjutkan perjuangan Ibu di Quart School ini.”
Mik sudah berpindah lagi ke tangan kepala sekolah.
“Seperti yang murid-murid ketahui, dalam hitungan hari, Quart School akan melaksanakan event besar pertama, Funclass. Mari kita dengar, bagaimana rencana Ibu Qotrun Nada dalam kesempatan yang baik ini.”
Mik kembali berpindah tangan. Kali ini ke tangan Ibu Qotrun Nada. Aku menyimak takzim. Rasanya menyenangkan bisa mendengar suara beliau.
“Bismillah, murid-murid Quart School yang berbahagia. Perkenalkan, nama Ibu, Qotrun Nada. Mungkin ada beberapa kelas yang sudah mengenal ibu saat masuk ke kelas mereka. Yang belum, insya Allah kita akan bersua. Hari ini sebagaimana yang dikatakan Pak Kepsek, Ibu akan memberitahu beberapa rencana yang ada di kepala Ibu untuk merancang Funclass.
Sebelumnya, harus ibu katakan bahwa Ibu sangat terkejut sekaligus bangga bisa terlibat langsung ke dalam event-event besar di Quart School. Ini adalah acara yang hebat dan tidak mungkin bisa ditemukan di sekolah lain di dunia. Mungkin.
Ibu sudah mendengar dan mencari tahu bagaimana Funclass dalam beberapa tahun terakhir. Semoga itu mencukupi untuk Ibu bisa menjalankan acara ini. Tahun ini, Ibu hanya bisa menjanjikan ada tiga lomba yang diselenggarakan. Yaitu baca pidato, futsal dan tarik tambang (ini nantinya lewat lidah panitia, ditetapkan hanya untuk peserta putri). Ketiga-tiganya akan mendapatkan piala. Jadi lekaslah daftar kelas kalian masing-masing kepada panitia. Apabila ada pertanyaan, kalian juga bisa bertanya pada panitia, yang insya Allah setiap kelas nanti ada perwakilan panitianya.”
Mik kembali ke tangan kepala sekolah. Kami bertepuk tangan lagi. Meski hanya tiga lomba, itu jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun lalu. Bubar dari lapangan, kami masuk lokal, siap melakukan rapat informal. Aram segera duduk di meja guru, mengklaim posisi.
“Tarik tambang khusus putri ya,” dia memegangi dagu, seolah berpikir. Kami menatapnya penuh minat. “Mawar, kau siapkan tim untuk tarik tambang. Pilih cewek-cewek berbadan besar. Melihat ukuran tubuh, seharusnya kita bisa menang.”
Mawar mengangguk.
“Kita ke masalah yang sebenarnya sekarang. Tim futsal. Kita tidak punya tim yang cukup tangguh. Aku jujur saja, aku sendiri tidak yakin bisa bermain bola. Ada pendapat?”
Wahid mengangkat tangan. “Silakan Wahid.”
“Kita bisa menggabungkan kekuatan dengan lokal 5. Mereka punya kemampuan yang bagus, aku sering sparing dengan Paderi. Sayang sekali tim mereka tidak cukup orang, karena cuma berempat. Kalau kita bergabung, kita mungkin bisa berbicara banyak dalam kompetisi.”
“Bagus sekali,” Aram sumringah, “tapi bagaimana dengan panitia. Apakah mereka membolehkan penggabungan lokal semacam itu?”
“Aku akan urus panitianya,” sahut Mei. Dia sudah mendapatkan satu kursi di kepanitiaan.
“Bagus sekali. Kalau begitu bereslah rapat kita ini.”
“Hei tunggu sebentar,” Lia mengangkat tangan, “kita belum membahas soal perwakilan lomba pidato.”
“Astaga, itu tidak perlu dipikirkan,” Aram mengangkat bahu, “siapa kemarin yang memenangkan piala juara kedua pidato saat Hari Suka Raya? Azka bukan? Biarkan dia ikut lagi di lomba kali ini, biarkan dia membalaskan kekalahannya.” Lalu Aram berlalu, aku memasang wajah masam, aku ditunjuk tanpa persetujuanku.
Funclass kali ini berbeda dan spesial. Karena penunjukan Ibu Qotrun Nada sebagai Wakasek, dimana di tangan pemangku jabatan itulah semua kendali event besar digelar.
Ibu Qotrun (aku akan mulai memanggil beliau begitu) berhasil mencari solusi dari kritikan Ibu Hartini yang menganggap Funclass itu membuang-buang waktu. Jalan keluar yang beliau tawarkan adalah fifty-fifty, setengah hari belajar, setengah harinya lagi untuk Funclass. Toh semua lomba dilaksanakan di dalam ruang aula yang luas dan nyaman. Berkat keputusan ini, tidak ada minggu-minggu yang tersia-siakan, Funclass tahun ini bisa digelar maraton selama 14 hari.
Aram bersorak gembira setiap menonton pertandingan yang melibatkan lokal 4, baik futsal ataupun tarik tambang. Di luar dugaan siapapun, lokal 4 Quart School bisa melaju sampai ke final dua kejuaraan tersebut.
Di tim tarik tambang, tim para wanita, Mawar berhasil melaksanakan perintah Aram dengan sebaik-baiknya. Mawar memilih anggota tim tarik tambang dengan postur badan yang besar-besar, sehingga tidak ada satupun tim lain yang bisa menandingi tenaga tim lokal kami.
Di tim futsal, tim para lelaki, kolaborasi antar lokal 4 dan 5 sebagaimana yang diusulkan Wahid moncer tak terbendung. Wahid dan Paderi berduet jadi striker mematikan. Meskipun aku geram dengan Paderi Tamtama itu, tapi harus kuakui lokal 4 berhutang padanya.
Tim tarik tambang kami berhasil menyabet juara satu, menggondol piala. Aku, Nasri dan Aram hadir menonton bagaimana para gadis itu menarik tali dengan sangat bersemangat.
Sementara tim futsal kami kalah tragis di final. Lawan kami adalah lokal 2, orang-orang yang sudah terbiasa main futsal dan bahkan sudah punya tim futsal sendiri walau cuma amatiran. Demi menghibur Wahid, Aram mentraktir kawannya itu makan sepuasnya di Kedai kopi Paman Pirates.
Lalu bagaimana dengan lomba pidato? Yang satu ini kawan, juga berakhir dengan dramatis. Aku yang mengangkat tema “pacaran dan narkoba, candu terbesar” dinyatakan memenangkan lomba sebagai juara 1. Itu terhitung mengejutkan karena aku tidak terlalu excited untuk lomba ini.
Tak apalah, aku persembahkan kemenangan ini untuk kamu yang di sana.
Mozaik 3
Rohis Sekolah
Aku sudah membaca buku “Sejarah Sekolah Kebanggaan” yang terpajang di perpustakaan Quart School. Semakin aku cermati, semakin aku membaca, aku tahu bahwa sekolah ini bukan sekolah agama. Ini bukan sekolah berbasis agama macam Madrasah Aliyah. Ditambah dengan “horor” cara mengajar Bu Hartini, menjadikan pelajaran agama menjadi sesuatu yang agak tabu untuk dibicarakan.
Bisakah kawan membayangkan, dalam situasi seperti itu, sesulit apa eskul berbau keagamaan bisa muncul?
Hampir mustahil.
Dulu sewaktu aku masih semester 1, Pak Mubarak, guru Ta’limul Qur’an (mata pelajaran seperti ini punya kelasnya tersendiri di Quart School), sempat membuka eskul keagamaan. Peminat awalnya banyak, tapi seiring waktu, eskul tersebut terpaksa dihapus, karena ditinggal peminatnya.
Waktu berputar, semester 1 telah tertinggal jauh di belakang. Hal yang gagal dilakukan dua tahun lalu belum tentu gagal lagi sekarang. Semester 5 aku bersekolah, cikal bakal eskul keagamaan baru mulai terlihat lagi, sosok sentral di belakangnya, Ibu Qotrun Nada.
Hei, ternyata desas-desus mengenai kehebatan Ibu Qotrun Nada tidak sepenuhnya berlebihan. Kemarin aku melihat sendiri, Ibu Qotrun duduk bersama siswa-siswa lokal 2, bercengkrama, nampaknya beberapa murid di sana sedang bercerita dan meminta solusi, beliau menanggapi, sesekali tertawa.
Hebat. Padahal Bu Hartini saja ogah-ogahan masuk ke lokal 2 karena perangai siswanya macam penyamun.
Landscape lokal 4 yang santai menjelang istirahat pertama. Aku dan Wahid bermain catur untuk mengusir bosan gara-gara Bapak Dahri Ariyanto, kelas khusus kewirausahaan, tidak masuk. Tiba-tiba saja Aram datang, terlihat santai, dengan wajah dan rambut depan yang agak basah.
“Barusan dari mana Ram?” aku bertanya.
“Habis dari musholla, shalat Dhuha.”
Wahid mendelik. Aku ikutan. Aram shalat Dhuha?
“Astaga, aku tidak seburuk itu kawan, apa salahnya aku shalat Dhuha. Toh aku ini muslim juga.”
“Hanya di luar kebiasaanmu, Ram.” Wahid berkomentar pendek, fokusnya ke papan catur terbagi.
“Kalau nanti kau shalat Dhuha lagi, bilang padaku Ram.” Nasri ikut berkomentar.
“Eh?”
“Ya biar aku bisa ikut juga.”
Mengingat bagaimana keutamaan shalat Dhuha sebagaimana yang disampaikan Pak Mubarak kemarin, aku jadi tertarik ikut-ikutan. “Ajak aku juga Ram.”
“Wah menarik nih, banyak yang mau ikutan. Ya sudah besok kita shalat Dhuha ramai-ramai.”
Kawan, itulah cikal bakal eskul keagamaan baru itu. Dari kenyentrikan Aram yang baru aja bangkit. Keesokan harinya aku, Nasri dan Aram sendiri pergi ke musholla. Kami bertemu dengan dua orang lagi yang menunggu di sana.
“Ini Fadel, dan ini Nova. Kurasa kalian sudah sering bertemu cuma tidak kenal nama,” kata Aram memperkenalkan dua orang itu. Sepertinya dia temannya.
“Kau Azka yang kemarin menang pidato itu ya?” tanya orang bernama Fadel. Aku mengangguk. Agak kikuk bertemu teman baru.
“Wah selamat bung, lain kali aku ingin belajar pidato darimu.”
“Ayo mulai Ram,” Nasri berucap. Aram memasang wajah santai, “kita menunggu seseorang.”
Sepertinya Aram sudah beberapa kali melakukan kegiatan ini dan berhasil mempengaruhi beberapa orang untuk bergabung, tapi itu tidak masalah, toh ini kebaikan.
“Wah ternyata kalian sudah ngumpul, maaf ya, Ibu agak lama.”
Sebuah suara lembut hinggap di daun pintu. Aku berbalik, genap menatap beliau. Ibu Qotrun Nada. Aram buru-buru mendatangi beliau. Mengisyaratkan angka dua dengan jarinya sambil menunjuk-nunjuk aku dan Nasri.
“Kita bisa membicarakan itu setelah selesai shalat, Aram.”
Aku menerka-nerka apa yang direncanakan Aram dengan Ibu Qotrun Nada. Itu membuat angkatan takbirku terasa tidak sempurna. Setelah selesai shalat, urusan itu menjadi lebih jelas. Ibu Qotrun menjelaskan apa rencana beliau, menciptakan rohis sekolah. Beliau mengajak aku dan Nasri bergabung. Aram, Nova dan Fadel rupanya sudah sepakat. Aku bilang ke hadapan beliau, aku pikir-pikir dulu.
Ini bukan berarti aku malas melakukan kebaikan. Tapi aku sering berat hati bergabung dengan organisasi. Itu membuat orang dengan pikiran bebas macam aku merasa terkekang.
Sampai ke kelas, Aram masih mencoba membujukku. Aku lagi-lagi bilang “pikir-pikir dulu Ram, belum ada alasan kuat bagiku untuk bergabung dengan rohis.”
Aram menepuk dahi, “Ibu Qotrun Nada itu juga masih belum bisa dikatakan sebagai alasan yang kuat Az?”
“Biar Tuhan yang memberiku alasan yang lebih tepat Ram.” Aku menyahut dramatis. Esok lusa, alasan kuat itu benar-benar muncul.
Mozaik 4
Kamu Ternyata Ikut….
“Ayolah Az, kalau kau memang tidak berminat ikut rohis, setidaknya kau masih bisa ikut dalam shalat Dhuha. Ini ibadah lho Az, astaga kau ini.” Aram menarik tanganku ke musholla. Sebelumnya, dalam dua hari, aku menolak ajakannya, shalat Dhuha. Aku tidak punya jawaban jika nanti ditanya Ibu Qotrun. Tapi hari ini aku luluh, baiklah mungkin Aram benar, ini adalah kebaikan. Aku mengekor langkahnya ke musholla.
“Kali ini kau pasti akan bergabung dengan rohis Az, aku jamin.” Aram berseru-seru ringan sepanjang jalan. Aku curiga dia telah menyiapkan strategi baru untuk menjebakku, mungkin saja itu strategi busuk.
Sampai di musholla, Ibu Qotrun Nada sudah menungguku. Alamak. Kulihat gesture Aram semakin senang saat berhadapan dengan beliau. Tak salah lagi, mereka pasti bersekongkol.
“Nah ini dia, anak murid Ibu yang menghilang. Kemana kamu, Azka?”
“Sibuk Bu, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan di lokal,” aku berkelit. Ibu Qotrun tersenyum takzim, Aram di sampingku siap bersungut-sungut, tapi Ibu lebih dulu mencegahnya.
“Sudah, kalian shalat Dhuha dulu. Nanti sehabis shalat, kita bicarakan lagi hal ini.”
Aku mengangguk, membungkuk berjalan melewati Ibu Qotrun, menuju pancuran wudhu. Menghela nafas, sulit mencari alasan logis untuk menangkis tawaran Ibu Qotrun. “Tuhan, jika kegiatan rohis itu baik untukku, tolong beri aku alasan yang benar-benar kuat.”
Doaku itu tidak menunggu lama. Tuhan maha mendengar.
Hari ini musholla tidak terlalu ramai. Tidak ada si Fadel dan Nova. Yang ada malah dua orang gadis bermukena yang sibuk membaca Al-Qur’an disimak Ibu Qotrun. Ketika aku coba mengenali mereka, Ibu Qotrun menatapku dengan isyarat, agar aku cepat shalat saja, dan tidak macam-macam. Urusan baru benar-benar runyam ketika aku selesai salam.
Aram mengajakku mendekati Ibu Qotrun. Sekali aku mendongak ke arah dua gadis itu, tiba-tiba aku limbung. Kaki-kakiku terasa kehilangan kontrol. Rasanya melayang mendekati Ibu Qotrun. Oh Tuhan, aku mengenal salah satu dari gadis bermukena ini. Dia adalah Syifa.
“Duduk Az,” ujar Aram, “Ibu, Aram izin pergi ya, titip si Azka ini.”
“Eh kamu mau kemana?” Itu suara Ibu Qotrun, aku sudah genap kehilangan pita suara sewaktu mengenali Syifa tadi.
“Mau ke kantin Bu, lapar. Pokoknya pastikan Azka ikut rohis Bu. Dia adalah murid paling potensial yang kita butuhkan.”
Melihat Aram lari bergegas ke luar, seperti dikejar malaikat maut, Ibu Qotrun Nada tertawa. Urusan Aram ini tidak terlalu kuperhatikan, aku sedang mencoba melirik-lirik nakal ke arah Syifa. Aku tahu ini tidak etis dilakukan di musholla, tapi ayolah kawan, sudah hampir enam bulan aku stagnan mendekati dia karena takut keciyean, hari ini Syifa ada, tak sampai satu meter dari aku.
“Bagaimana Azka, organisasi ini memang masih berupa embrio, belum dilahirkan secara sempurna. Tapi cikal bakalnya ada. Lihat, ada Fadel, Nova, Aram dan dua gadis ini yang berniat bergabung. Semakin banyak orangnya, semakin baik. Dan seperti yang dikatakan Aram, kamu juga orang yang potensial untuk menjadi anggota. Rohis membutuhkanmu Azka, Ibu tahu, Azka adalah salah satu murid teladan di Quart School ini.”
Aku terdiam. Tidak kuasa berkata-kata. Lepas sedetik lalu, mataku bertemu dengan mata Syifa, dia melempar senyum. Manis sekali.
“Bagaimana Azka?”
“I… iya… Iya bu, Azka akan ikut. Insya Allah Azka bisa membantu Ibu membangun rohis ini.”
Demi mendengar kalimatku (yang terbata-bata itu), Ibu Qotrun mengusap wajah dengan tangan. “Alhamdulillah,” ujar beliau, “sore ini hadir ya Azka, kita ada diskusi ringan sehabis shalat Ashar.”
“Baik bu.”
Astaga. Siapa sangka Syifa juga ikut kegiatan rohis ini. Hatiku tertawar. Mungkin saja rohis bisa menjadi jembatan bagiku untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan gadis bermata cemerlang itu.
Mozaik 5
Jangan Lagi, Astaga
Aku turut hadir dalam peresmian berdirinya Rohis di ruangan kepala sekolah bersama Aram, Fadl, dan Ibu Qotrun Nada. Sebelum peresmian ini, rohis sebenarnya sudah berjalan selama dua minggu.
Dalam dua minggu ini cukup banyak kejadian berwarna terjadi. Aku menikmati rasa deg-degan setiap mampir shalat Dhuha, karena di sana ada Syifa. Terkadang kami berbarengan sampai di pancuran wudhu. Hanya berdua saja. Aku menyilakan dia duluan, dia mengelak, “kamu aja dulu Az.”
Ah kawan, empat kalimatnya itu sungguh luar biasa.
Aku juga deg-degan setiap akan shalat Ashar. Sebagai anggota rohis, kami pulang lebih akhir dibanding siswa lain. Shalat Ashar di mushola adalah satu hal yang diwajibkan Aram sebagai perancang program. Terkadang dia menyuruhku memimpin takbir, menjadi imam. Aku mengangguk, karena itu dengan kata lain, aku juga memimpin Syifa. Dia jadi makmumku. Membayangkan hal-hal menggelikan seperti itu membuatku senang.
Belum lagi menghitung aku dan Syifa bisa pulang bareng, jika situasinya cocok.
Sejujurnya kawan, di luar keberadaan Syifa, aku cukup senang berada di Rohis. Kawan-kawan di sini menyenangkan dan berkarakter kuat. Ada Fadl, Nova dan Aram yang duduk sebagai pengurus inti.
Fadl (ternyata begitu namanya ditulis), adalah pemuda berwajah ke-arab-an. Dia ditunjuk oleh Ibu Qotrun Nada sebagai ketua Rohis. Usut punya usut dialah sebenarnya yang menjadi dalang dari semua kegiatan shalat Dhuha kami, termasuk dia juga yang mengajak Aram. Fadl adalah sosok yang kecanduan majelis ta’lim sejak masih muda. Namanya memang begitu adanya, tapi karena kami sulit mengejanya, terpaksa nama itu kami plesetkan jadi “Fadel”. Dia tidak keberatan, selama Fadel itu diucapkan dengan “e elang” bukan “e ekor.” Dia akan marah jika ada yang memanggilnya Fadil.
Aram duduk sebagai wakil ketua. Aku tidak perlu lagi menjelaskan tentang temanku yang satu ini.
Nova, adalah siswa lokal 5. Dia termasuk circle pertemanan Paderi. Wajahnya mirip Napoleon Bonaparte yang terkenal itu. Dalam rohis dia berperan sebagai pembantu umum, membantu Aram dan Fadl melaksanakan tugas sehari-hari. Nova agak nyentrik. Dia mengaku ingin “hijrah”, hidup sebagai anak baik-baik, dan lurus. Tapi di sisi lain, dia tidak melepas pacarnya yang amat cantik. Bahkan pacarnya itu dia suruh masuk rohis, agar mereka tidak berpisah. Canggih bukan.
Di tengah-tengah kami, duduk Ibu Qotrun. Rutin mengajak kami berdiskusi tentang materi-materi yang tidak kami dapat di kelas agama. Setiap Rabu sore.
“Jadi Az, apa yang membuat Islam tidak menjadi agama mayoritas di Eropa?”
Itu adalah pertanyaan Aram. Hari ini sesi diskusi Rohis yang ketiga. Topik hari ini adalah penyebaran agama Islam. Pertanyaan Aram terlontar ke arahku, karena sepanjang diskusi hari ini, aku tampil sangat vokal.
“Jadi begini,” aku mulai menjelaskan, “kita harus tahu terlebih dahulu bahwa penyebaran Islam sangat cepat. Seratus tahun sejak lahir di Kota Mekkah, Arab Saudi, Islam sudah sampai di Spanyol. Kecepatan itu beriringan dengan perluasan wilayah kekhalifahan Islam itu sendiri. Perwakilan kekhalifahan Islam di Spanyol di abad ke-9 telah mengambil ancang-ancang untuk menyebarkan Islam ke Prancis. Penyerbuan dan peperangan segera pecah di wilayah Prancis, sampai di titik dimana setengah wilayah Prancis jatuh ke tangan kekhalifahan Islam. Hal itu tentu saja mengganggu Paus dan para raja Kristen di Eropa. Mereka mencoba menyatukan kekuatan untuk menghalau kekhalifahan Islam sekali dan selamanya. Pasukan besar terbentuk di bawah pimpinan Raja Syarla Martell. Pasukan Islam dan Pasukan Kristen bertemu di Kota Poitiers, Prancis dalam pertempuran yang disebut Balathus Syuhada. Di pertempuran itu, pasukan Islam mengalami kekalahan, bahkan jenderal pasukan Islam mati Syahid dalam pertempuran itu. Sejak saat itu, kekuasaan Kekhalifahan terhenti di Spanyol dan lama kelamaan semakin terdesak hingga Islam terusir dari Eropa pada akhir abad ke-15.”
Tepuk tangan mengiringi penjelasanku.
“Ibu tak tahu kamu menguasai pelajaran tentang sejarah Azka, luar biasa.”
Di seberangku, Syifa duduk. Dia tersenyum. Tak sia-sia aku mengeluarkan semua kemampuanku. Aku tahu, senyumnya barusan adalah untukku.
Di saat yang sama kawan, aku perlu berhati-hati sekali dalam mendekati Syifa kali ini. Salah gerak sedikit, keciyean yang sangat dibenci Syifa, bisa memenuhi Rohis. Tak terbayang apa yang harus kulakukan jika itu terjadi.
Tapi seperti yang dikatakan pepatah, bangkai gajah tidak bisa ditutupi dengan nyiru. Perasaanku terhadap Syifa terlanjur terlalu besar untuk disembunyikan. Akhirnya ketahuan juga.
Kejadiannya begini, saat itu aku, Aram dan Nova duduk bersama Ibu Qotrun di teras musholla. Kami sudah siap-siap pulang. Tahu-tahu angin darimana, Aram tiba-tiba menunjuk pada Nova.
“Nova ini bu, keterlaluan sekali orangnya. Biar sudah ikut rohis, dia belum hijrah sepenuhnya. Masih intim dengan pacarnya. Playboy cap paku-pakuan.”
“Oh ya, Nova, kau seperti itu?” Ibu Qotrun memandangi Nova lekat, mencoba mengorek informasi.
“Iya bu, malah pacarnya itu diajaknya ikut Rohis. Biar tetap dekat-dekatan dengan dia. Astaga bu, Aram takut Rohis kena kutuk kalau Nova terus begitu.”
“Bongkar terus Ram,” aku menyela. Padahal niatku, hanya numpang lewat, sekedar peramai suasana. Ternyata itu adalah awal dari serangan balik ke arahku. Nova menengok ke arahku. Menatap nakal.
“Nah Bu. Ibu harus tahu, sekeras apapun aku membujuk, pacarku itu tidak mau ikut rohis. Sebrengseknya saya Bu, kami berdua masih terpisah di Rohis ini. Ada yang lebih parah dari Nova bu. Dia dan pacarnya sudah ikut rohis sejak hari pertama, tapi Ibu tidak tahu.”
Aku meneguk air liur. Firasatku memburuk.
Ibu Qotrun bertanya, “oh ya, siapa?”
“Azka bu. Dia pacaran dengan Syifa.”
Ibu Qotrun terperangah. Aku juga. Menepuk dahi. Setengah dari hatiku bersorak, ternyata aku adalah “pacar Syifa”. Itu adalah hal yang menarik. Kukira Ibu Qotrun akan melabrakku dan memberi wejangan tentang “larangan pacaran” atau “pacaran itu haram” atau yang lain. Tapi tidak. Ibu malah tertawa.
“Tak ibu sangka, selera Azka sangat tinggi. Pantas saja semangat ikut Rohis, ada cintanya di sini. Ya sudah, jangan melakukan hal yang aneh ya Azka. Aram dan Nova, ayo kita pulang. Hari sudah sore.”
Mozaik 6
Ibu Angkat
Satu hari setelah semuanya terbongkar di hadapan Ibu Qotrun…
Aku, Aram dan Nova berbarengan datang ke pancuran wudhu, shalat dhuha hari ini. Tidak lama kemudian, Ibu Qotrun menyusul datang. Namun yang paling mengejutkanku justru yang berjalan mengikuti beliau. Syifa.
Aram dan Nova berbisik-bisik, berkonspirasi.
“Syif, yuk cepat. Kamu jadi makmumku.”
Kalimat Aram membuat telingaku berdiri. Sabar, mereka sengaja melakukan ini, jangan terpancing, aku mewanti-wanti hatiku sendiri. Nova yang berdiri tidak jauh dari Aram, segera memahami situasi.
“Hush, jangan bicara begitu, Ram. Satu-satunya yang boleh mengimami Syifa, adalah Azka.”
Diam-diam aku mengamati wajah Syifa. Ekspresinya berubah seiring mendengar kalimat-kalimat bersulam indah yang dilancarkan Aram dan Nova, mendung. Sepertinya aku harus menyelamatkan keadaan, buru-buru menyelesaikan wudhu.
“Az, mau kemana astaga,” Aram mencekal lenganku saat aku ingin melangkah cepat ke mushola. Adegan selanjutnya mirip sinetron Indonesia. “Nih Syif, Azkanya sudah siap menjadi imammu. Aihh tampan kali kau Az,” ucap Aram lagi. Aku tersenyum geli.
“Sudahlah, cepat kita ke mushola.” Kucoba menetralkan suasana, walau kupikir kalimatku terucap patah-patah.
“Astaga Az, lihat makmum kau itu belum selesai wudhu lagi, oh ya Az, kamu harus lihat bagaimana wajah Syifa setelah berwudhu, pasti cantik sekali.” Nova memberi serangan lanjutan, menancapkan.
Tidak ada pilihan lain lagi, aku ambil langkah seribu. Lari ke mushola. Bisa kudengar yang paling ngakak adalah Ibu Qotrun Nada.
Kejadian di pancuran wudhu itu adalah sebuah kejadian domino yang menggerakkan kejadian-kejadian besar berikutnya. Sekitar 3 hari setelah kejadian itu, kejadian pertama terjadi. Mengejutkan.
Syifa keluar dari rohis. Itu diproklamasikannya dengan cara keluar dari grub whatsapp rohis.
Aram, Nova dan Fadl tidak terlalu terkejut dengan hal tersebut. Mereka angkat bahu saja, tidaklah penting. Fadl dan Aram sedang sibuk merumuskan cara melancarkan ekspansi rohis kepada adik-adik kelas. Itu lebih berpotensi bagi mereka.
Akan tetapi bagiku itu adalah kejadian sangat besar. Ini pasti gara-gara semua momen di pancuran wudhu kemarin. Hatiku berdecak, tapi aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Aku diam saja. Aku diam saja waktu Ibu Qotrun Nada mengumumkan pengunduran diri Syifa di hadapan semua anggota rohis. Aku diam saja waktu Aram dan Nova mencoba menggodaku. Belum waktunya.
Tetapi, kegiatan rohisku menjadi menurun. Aku menjadi pendiam. Tidak aktif lagi saat diskusi keagamaan setiap rabu sore. Lebih banyak menghindar saat Aram mengusulkan aku jadi imam, bahkan aku lebih sering menghindar dari mushola. Mungkin sebentar lagi, aku juga akan keluar dari rohis.
Ibu Qotrun Nada membaca situasi dan perubahan yang terjadi pada diriku, beliau berkali-kali menyemangatiku. Mengundangku mengobrol jika aku butuh tempat untuk bercerita. Beliau jelas tidak akan membiarkan dua anggota rohis keluar secara hampir bersamaan. Aku juga merasa tertarik. Mungkin sudah waktunya aku bercerita pada Ibu Qotrun Nada. Guru yang konon bisa meluluhkan hati siapa saja yang mendengar suara beliau.
Habis Ashar hari kamis.
“Jadi apa yang hendak kamu ceritakan, Azka?”
Serba salah aku hendak memulai cerita darimana. Beruntungnya Ibu Qotrun cepat membaca semua situasi.
“Ini tentang Syifa-kan Az? Kelihatan banget lho Azka, dia adalah roh rohis bagi kamu. Dialah yang membuat kamu bersemangat. Sekarang dia pergi, dengan alasan-alasan yang kuat. Ibu sudah tanya kepada dia, dan Ibu kira ini adalah keputusan terbaik untuknya.”
“Syifa keluar karena semua ke-ciye-an yang dilakukan Aram dan Nova-kan Bu?”
“Belum tentu begitu Azka. Namun, mungkin sekali itu alasan terbesarnya. Hei memangnya apa yang menjadi masalah kalian?”
“Syifa membenci semua ke-ciye-an itu Bu.”
“Oh seperti itu, bisa Ibu pahami. Tapi hei, serius sampai sekarang, Ibu masih tidak menyangka ada hubungan istimewa antara Azka dengan Syifa.”
“Tidak ada hubungan istimewa Bu, hanya hubungan yang dilebih-lebihkan.” Aku menggeleng. “Azka dan Syifa hanya teman,” aku menegaskan, meski setengah hatiku meneriakiku agar tidak berbohong.
“Tapi perasaan kamu tidak seperti itu-kan Az, sejak kapan kamu mulai suka dengan Syifa, seberapa jauh hubungan kalian? Astaga maaf Ibu menjadi kepo begini. Sepertinya Ibu ketinggalan banyak sekali cerita.”
“Azka menyukainya sejak awal semester 3, pertemuan pertama dengannya di Perpustakaan. Secara bertahap, Azka mendapat nomornya, memulai pendekatan, melayangkan chat-chat, membantunya, mengajarinya matematika, membantunya mengerjakan makalah. Mungkin semua itu yang menjadi bumbu cinta Bu. Bayangan duduk semeja dengan Syifa, masih lekat di ingatan Azka.”
“So sweet,” sahut Ibu Qotrun. Lupakan, itu hanya reflek orang Indonesia.
“Kami sekali bertengkar, eh bukan, Azka cemburu karena melihat dia jalan dengan orang lain, dengan Paderi.”
“Sebentar, Paderi lokal 5 itu?” Ibu Qotrun memotong.
“Iya bu, semenjak kejadian itu, Azka merasa kalah dan menghindar, dan menghindar.
Tapi setelah itu kami berbaikan lagi. Mendekat lagi. Kali ini cukup dekat sampai Syifa meminta saran dan pertimbangan Azka, atas apa-apa yang hendak dia lakukan. Di puncak kedekatan kami, Azka mengungkapkan perasaannya.”
“Kamu menembaknya?”
“Hanya sekedar, “aku suka kamu Syif,” begitu saja Bu.”
“Bagaimana tanggapan dia Az?”
“Azka akan selalu ingat bagaimana jawaban Syifa, Bu. Dia bilang, “iya aku hargai kok.” Begitu saja Bu. Setelah kejadian itu, sebenarnya hubungan Azka dan Syifa baik-baik saja. Sampai orang bernama Paderi itu muncul lagi. Dia menyebar ke-ciye-an, Syifa sangat tidak suka dengan hal semacam itu, jadi Azka mau tidak mau harus menghindar lagi dari bertemu Syifa. Begitu akhirnya Bu, walau harus Azka akui, perasaan Azka pada Syifa belum berakhir.”
Ibu Qotrun menutup mulutnya, menahan diri agar tidak tertawa lebar. Hei ceritaku selucu itu? Bagiku, cerita itu menyedihkan. “Bisa ibu pahami Az,” komentar Ibu setelah tawa beliau reda, “mengapa kamu dan Syifa seperti tidak saling kenal di rohis. Ternyata begitu toh.”
“Azka minta saran Ibu,” ucapku pelan.
“Baiklah,” Ibu Qotrun memperbaiki duduknya, “pertama-tama, hal paling dasar, cinta adalah fitrah. Cinta itu suci, datang dari Tuhan. Camkan itu baik-baik Az, tapi Tuhan punya aturan main yang harus ditaati agar cinta bisa dijalankan dengan baik. Cinta tidak mungkin menyakiti, kecuali dimainkan dengan aturan main yang salah. Siapa yang membuat aturan main yang salah itu? Manusia. Celakanya, pikiran manusia terkadang sangat cerdas untuk membuat aturan main baru, yang sulit dideteksi benar atau salah. Saran ibu, kamu renungkan dulu, bagaimana aturan main yang kamu jalankan dalam kisah cinta kamu dengan Syifa ini.”
Mozaik 7
Event Besar Khusus: Hari Administrator
Geliat program pendidikan yang ada di Quart School berubah cukup signifikan sejak Ibu Qotrun menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan. Setelah membentuk rohis sekolah sebagai pionir segala kegiatan keagamaan sehari-hari di sekolah ini, Ibu Qotrun menyiapkan banyak strategi lainnya.
Diantaranya beliau menyederhanakan dan merapikan sistem absensi di Quart School. Kini jelas siswa ingin masuk di mata pelajaran apa, dan hanya itu yang dihitung sebagai absen. Siswa diperbolehkan hadir di mata pelajaran lain, tapi dihitung sebagai nilai plus, di luar absen. Dengan cara-cara itu, Quart School berubah menjadi semacam universitas mini.
Selain kelas wajib, ada berbagai kelas pilihan yang dikembangkan oleh Ibu Qotrun Nada, bekerja sama dengan Bapak Wakasek Kurikulum yang terhormat. Kelas khusus mengetik, kelas khusus kewirausahaan, dan kelas khusus instalasi komputer, kemudian disusul oleh kelas khusus desain grafis, kelas khusus kaligrafi, hingga kelas khusus instalasi listrik. Semua tersedia di Quart School, kawan. Sekali lagi, para siswa dibebaskan untuk memilih keahlian apa yang hendak dia geluti.
Selain mengembangkan kegiatan-kegiatan lama, Ibu Qotrun sekarang bahkan mengambil ancang-ancang untuk merombak empat event besar yang ada di Quart School, tepatnya ingin menambahnya. Kami para murid bersorak senang. Pidato beliau, pada Senin siang.
“Anak-anak, siswa Quart School yang berbahagia. Mohon maaf sebelumnya jika Ibu memanggil kalian di saat yang kurang tepat seperti ini. Ibu punya kabar gembira yang harus diketahui siswa semua. Setelah melewati rapat, diskusi dan pertimbangan yang matang dari dewan guru semua, Ibu mendapat restu untuk meluncurkan event besar baru tahun ini. Harap event ini tidak dianggap sebagai event besar kelima, ini bukan seperti itu. Ibu tidak akan merusak tradisi Quart School yang hanya punya 4 event besar. Ini adalah event besar khusus. Namanya adalah Hari Administrator. Event ini bertujuan untuk menyiapkan kalian agar bisa bersaing dalam dunia kerja, mengajari kalian bagaimana jadi seorang administrator yang handal dan baik. Kita semua bisa belajar di sana. Akan tetapi, karena ini event baru, maka Ibu harus membatasi pesertanya, tidak boleh semua orang. Yang berkesempatan ikut adalah 50 orang saja, 50 orang yang beruntung bisa merasakan menjadi administrator kantor dalam satu hari penuh. Sisanya boleh mengikuti seminar Administrator. Nah silakan daftarkan diri kalian, siapa tahu tertarik. Oh ya, supaya adil, setiap lokal wajib mengirim 3 orang sebagai perwakilan. 5 orang sisanya bebas siapa saja.”
Belum genap lagi Ibu Qotrun menyelesaikan kalimat, riuh tepuk tangan menghujani beliau. Aku menepuk dahi. Maaf Bu, Azka tidak tertarik untuk ikut lomba seperti itu.
Sehabis pengumuman di lapangan, lokal 4 segera menggelar rapat, sebagaimana biasanya, Aram menjadi pemimpin informal.
“Ini event yang tidak boleh kita lewatkan.” Aram membuka rapat dengan wajah semringah. Jika aku mengingat bagaimana biasanya Aram membuka rapat dengan memukul papan tulis, rapat hari ini ibarat antitesis.
“Siapa yang akan kita kirim sebagai wakil kita?” Itu Mawar yang melempar tanya. Dari gesture tubuhnya, kentara betul bahwa dia ingin dipilih sebagai salah satu perwakilan itu.
“Terserah kalian. Adakah yang mau mengajukan diri, kalau tidak ada yang bersedia, maka aku akan menutupinya,” ujar Aram demokratis. Tidak jelas apa yang dia maksud “menutupi” itu.
“Aku deh, aku mau coba.” Mawar, malu-malu menawarkan diri. Sekali lagi, itu hanya gesture. “Nah satu sudah, dua lagi.”
“Aku juga ikut,” ucap Wahid antusias. Semua peserta rapat menatap ke arahnya. Wahid lebih ahli menendang bola ketimbang jadi administrator. Tapi bagi aku, yang mengetahui bagaimana hubungan antara Wahid dan Mawar di balik layar, tidak heran. Aram menyeringai, “baiklah, sudah dua. Siapa lagi?”
Peserta rapat hening.
“Ayolah,” Aram berucap lagi.
Peserta rapat masih hening.
Aku bersiap-siap mengambil langkah seribu. Pokoknya apapun alasannya, aku tidak mau terlibat dalam hal seperti ini. Aram bersiap-siap mengeluarkan suara. Sial aku terlambat melarikan diri. Aram pasti menunjukku.
“Kalau tidak ada yang bersedia, aku saja yang jadi…”
“Tidak. Biar aku saja.”
Semua orang kembali terperangah. Yang baru saja bersuara, adalah Nasri.
“Kau yakin Nas?”
Nasri tidak menjawab, mengacungkan tangan. Membentuk jempol. Dia benar-benar yakin. Serius sekali.
Mozaik 8
Syifa, Lomba dan Karier
“Hei, apa yang membuatmu mengajukan diri, Nas?”
Iseng, saat pulang sekolah kutanya Nasri. Maksudku jelas, apa yang membuat Nasri tiba-tiba tertarik pada event merepotkan itu.
“Aku tidak bisa membiarkan Aram mengajukan diri, itu akan memalukan bagi lokal kita.” Dia menutup kalimat sambil tersenyum lucu (walau tidak lucu).
Aku hanya terkekeh. “Aku serius,” ujar Nasri lagi, “kau sendiri, kenapa tidak tertarik Az?”
“Kau tahu Nas, mencari baju seragam, mengikuti event sehari penuh, itu mengganggu dan merepotkan.”
“Kau benar juga. Tapi tidak masalah, tidak ada masalah aku mencoba.”
Heran sekali aku melihat kelakuan Nasri hari ini.
“Azka, tunggu.” Suara seseorang menginterupsi percakapanku dengan Nasri. Aku mengenali suara itu, dan karena namaku yang dipanggil, aku berhenti, menengok ke belakang.
“Ada apa, Mawar?”
“Kenapa kamu tidak ikut Az? Astaga padahal kamu adalah saingan utamaku di kelas khusus mengetik. Sayang banget tidak ikut event khusus ini.”
“Dia malas,” Nasri yang menyahut.
“Oh ya Az, ini Syifa ada nitip pertanyaan.”
Aku tercekat. Apa katanya, Syifa. “Apa katanya?” Kuusahakan untuk bertanya tanpa mencolok.
“Ya itu, dia bertanya-tanya kenapa kamu tidak ikut. Dia amat menyayangkan hal itu. Karena dia sendiri ikut. Dia berharap tadinya kamu bisa sedikit mengajari dia.”
Aku tercekat lagi. Astaga. Kenapa aku tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Ah sial, aku membuang satu kesempatan berdekatan dengan Syifa. Karena sudah sia-sia untuk menarik kalimat, aku menyembunyikan semuanya lewat kalimat pendek. “Tidak perlu memancingku begitu, Mawar.”
“Ya sudahlah Az, kamu dibilangin juga tidak percaya. Oh ya, satu lagi. Dan ini super serius. Syifa minta dibawakan laptop buat Hari Administrator nanti.”
“Kenapa laptopku?”
“Mana aku tahu. Ini permintaan Syifa. Demi Tuhan, aku tidak berdusta Az.”
Kemudian Mawar berlalu. Aku harus mempercayainya, mau tidak mau. Secara pohon keluarga, dia dan Syifa memang masih memiliki hubungan darah. Aku anggukkan saja.
Nasri kemudian mengajakku bicara soal parlemen Prusia. Soal Syifa terpinggirkan sementara.
Hari ini, Hari Administrator telah tiba. Sesuai arahan Ibu Qotrun, kami yang tidak mengikuti event khusus, akan mengikuti sesi seminar. Untuk menambah stamina, aku duduk santai di kedai kopi Paman Pirates, meminum kopi karibia.
Kejutan itu benar-benar datang.
Seseorang (katakanlah mbak sekretaris) datang menghampiriku. Ketika kukenali lagi, astaga dia Syifa. Dia berdiri di depanku, tersenyum manis. “Maaf Az, kukira Mawar sudah menyampaikan pesanku padamu.”
“Eh iya Syif. Ada kok kubawakan. Tenang saja.”
“Makasih Az. Maaf merepotkan kamu.”
“Memangnya apa istimewanya laptopku Syif, hehe.”
“Hehe, tidak ada apa Az. Enak makai laptop kamu ini.”
“Macam makanan aja Syif.”
Kemudian kami tertawa berbarengan. Aku mengeluarkan laptopku yang berat itu dari dalam tas. Syifa hendak mengambilnya, tapi kucegah. “Biar kubawakan, Syif.”
“Makasih Az.” Dia masih menghamburkan senyum.
Kami membelah kerumunan. Menuju ruang aula tempat perhelatan Hari Administrator. Beberapa adik kelas yang melihat aku jalan bersama Syifa, terperangah. Sebenarnya aku juga terperangah kawan, ini di luar skenario. Tak kubayangkan hari ini aku berjalan beriringan dengan Syifa, sekali lagi.
“Kenapa tidak ikut?”
“Eh?” Aku balik bertanya, tidak paham. Sedetik kemudian, mataku dan matanya bertemu. Membuat detik-detik alam semesta melambat. Oh Tuhan, hari ini sungguh dia cantik sekali.
“Kenapa kamu tidak ikut Az?”
“Sedang malas saja Syif, hehe. Lagipula aku mewakilkan diriku kok,”
“Eh gimana tuh Az?”
“Nih,” aku menunjuk laptop, “aku mewakilkan kehadiranku dengan laptop ini.”
“Hehe Azka deh. Aku akan berusaha memenangkan lomba ini Az, aku tidak akan mengecewakan laptop itu.”
Aku terkekeh, sejenak kemudian mengangkat alis, “ini lomba?”
“Iya Az, ini lomba. Siapa yang penampilan terbaik, dia yang menang.”
Kami tiba di pintu aula. Aku serahkan laptop itu ke tangannya seraya berkata, “Ya pasti Syifa-lah yang menang. Semangat ya.”
“Makasih Az.”
Sebenarnya aku ingin memasukkan sedikit kalimat pujian pada penampilannya yang membuatku pangling hari ini. Ketika memakai pakaian sekolah biasa saja, dia sudah cantik, apalagi sekarang. Astaga. Sayang sekali, lidahku tertahan.
“Senang dah nih Azka, kulihat tadi sepanjang jalan, barengan dengan Syifa.” Nova muncul dari balik pintu. Aku meletakkan telunjuk di depan bibir, kemudian cepat-cepat angkat kaki. Ternyata konspirasi itu masih terjadi. Siasat perang si Paderi masih berjalan. Aku harus hati-hati. Baiklah, tujuan berikutnya, ruang seminar administrator. Aram pasti sudah menungguku di sana.
Mozaik 9
Kanvas Cinta
Episode Hari Administrator itu menjadi semacam selingan yang amat menyenangkan. Siapa sangka aku dan Syifa bisa berdekatan seperti itu sejak aku mengungkapkan perasaan padanya. Menurut hematku sendiri kawan, Syifa kemarin itu adalah Syifa sebagaimana yang kujumpai pertama kali.
Namun, sebagaimana sebuah selingan, selepas itu berlalu, semuanya kembali seperti semula. Mungkin kejadian di bawah ini adalah pemicunya.
Ini Selasa yang gerah, kalau menurutkan perasaan, sudah dari tadi aku kabur dari lokal, menuju kantin. Berleha di kedai kopi Paman Pirates, minum kopi es. Tapi tidak seorangpun berniat pergi dari kelas, termasuk Aram. Tentu saja, karena ini adalah jam pelajaran Ekonomi. Kawan akan mafhum segera jika kukatakan Aram terobsesi berlebihan terhadap Bu Jannah.
Bu Jannah hari ini datang membawa setumpuk buku ke lokal 4. Sebaris kalimat beliau segera mengonfirmasi. “Tolong bantu Ibu memeriksa tugas kawan-kawan kalian di lokal 5. Seseorang tolong segera bagikan buku ini.”
Telingaku berdiri. Apa yang dikatakan Bu Jannah, Lokal 5? Itu berarti lokalnya Syifa. Itu berarti buku Syifa ada di tumpukan buku-buku itu. Sial bagiku, hari ini yang berinisiatif membagikan buku adalah Wahid. Tidak sulit bagi Wahid untuk meletakkan buku Syifa di mejaku.
Sebenarnya itu juga yang kuharapkan. Senang rasanya bisa memegang buku Syifa. Rasa senang yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sedang jatuh cinta. Hanya saja, Aram yang duduk di sebelahku, segera berkomentar ringan, “waduh, buku Syifa tuh Az. Emang jodoh ya kalian.”
Sungguh komentarnya itu adalah pertanda buruk pertama hari ini.
Aku berusaha tidak menghiraukan apapun yang keluar dari mulut Aram (terkecuali itu wasiat dan Aram mendadak sakaratul maut), dan fokus mengoreksi jawaban Syifa dengan jawaban yang diucapkan Bu Jannah. Hei lihat kawan, tulisannya yang berbaris rapi dan indah. Ditulis oleh paras-paras kuku dan jemari Syifa yang halus. Astaga, aku jatuh cinta hanya karena menatap tulisannya.
Habis soal yang dikoreksi, Bu Jannah berucap, “Tolong tulis nama pemeriksanya, lalu sebutkan berapa nilainya. Langsung Ibu masukkan ke nilai.”
Sungguh itu adalah pertanda buruk kedua hari ini.
Aku menulis nama pemeriksa, (yakni namaku sendiri) dengan baik, dengan kesan bahwa aku bertanggung jawab penuh terhadap hasil koreksi itu. “NP: Humadi Azka” itulah tulisannya. Aram menengok. Jelas sekali dia memulai ide iseng.
“Salah itu Az, sini aku tambahkan.”
“Eh.”
Lalu sebelum aku sempat bereaksi, buku pindah ke tangan Aram. Dia bekerja cepat, menulis sesuatu, menahanku mengganggunya, sekaligus berbuat sesenyap mungkin agar tidak memancing keributan.
“Nah begini baru bagus Az,” Aram dengan bangga menunjukkan hasil kerjanya.
Aku terbelalak. Di bawah tulisanku yang bertanggung jawab tadi, Aram menambahkan tulisan yang amat menarik, “Bebeb kamu, Syifa”. Astaga, tak bisa kubayangkan, apa yang dipikirkan Syifa begitu dia membaca tulisan ini. Lekas-lekas kusambar buku itu dari tangan Aram. “Kembalikan Ram.”
Tapi gagal.
“Eits, jangan Az. Nanti kau hapus. Hid, nih bawa ke belakang, tambahkan bunga dan bumbu-bumbu.”
Buku sekejap kemudian berpindah ke tangan Wahid. Dia membawanya ke belakang. Jika aku bersikeras merebut buku itu dari tangannya, kejadian siang ini bisa berujung pada kejar-kejaran ala anak TK. Terpaksa aku mengalah. Menghela napas, duduk mendongkol di kursi.
“Tenang Az, kami ini mau bantu kau,” Aram menepuk bahuku. Aku mendesis.
Bu Jannah mulai membacakan daftar nama kawan-kawan di lokal 5. Menjelang abjad N, kulihat kawan-kawanku mulai berbisik. Nah apa pula maksud mereka kali ini.
Sungguh itu pertanda buruk ketiga hari ini.
“Nur Syifa Muliyana,” ujar Bu Jannah.
“Sembilan puluh empat, Bu,” ujarku.
“Ciyeee,” koor seluruh kelas. Wajahku memerah. Seketika salah tingkah. Bu Jannah mendengar itu semua, tersenyum misterius. “Ada apa ini nih,” ujar beliau. Aku menepuk dahi, hancur reputasiku.
“Paderi Tamtama,” ujar Bu Jannah.
“enam puluh lima, Bu.”
Mozaik 10
Episode Kelas Bersama
“Lia,”
“Iya Az?”
“Gimana ya respon Syifa kalau melihat coretan-coretan di bukunya itu.”
“Ya paling dia tersenyum, terheran-heran melihat semua itu.”
“Astaga, kau tidak membayangkan sebagaimana kemungkinan terbesarnya. Bagaimana kalau saat Syifa buka buku itu, dia berkomentar, ‘astaga, Azka kurang ajar sekali, aku benci’. Bagaimana kalau begitu yang terjadi?”
“Kamu berlebihan sekali Az.”
“Kau tidak tahu bagaimana Syifa membenci semua keciyean itu.”
“Azka, apa kata Syifa soal perasaan kamu dulu? Dia menghargaimu bukan? Sekarang pun demikian.”
Gara-gara buku Syifa yang dicoret-coret oleh Aram, aku sampai rusuh meributkan akibat apa yang akan ditimbulkan olehnya, pada Lia, tempatku mengadu. Kurasa dia sampai habis kesabaran meladeni keluh kesah dan ketakutanku.
“Lalu bagaimana aku bisa menghadapi kelas bersama, Kamis depan?”
“Ya kamu hadir, duduk santai saja, ngobrol dengan Nasri, catat sana-sini. Seperti Azka biasanya.”
“Tapi, gosip itu sudah menyebar sampai ke seluruh kelas.”
Oke ada beberapa poin yang perlu kujelaskan dari percakapanku dengan Lia di atas. Pertama, Kelas Bersama itu adalah prakarsa Bu Jannah sebelum beliau meninggalkan kelas tadi siang. Beliau ingin menggabungkan dua lokal dalam satu jam pelajaran. Kamis siang, sudah disepakati, untuk lokal 4 dan lokal 5.
Poin kedua, dengan kejadian “ciye” siang tadi, efektif, hubunganku dan Syifa sudah tersebar ke seluruh isi kelas. Tidak lagi di lingkar Aram dan Wahid saja, tidak juga di lingkar Paderi dan geng-nya. Bagaimana bisa aku memasuki kelas bersama kalau seisi kelas tahu. Bisa mati kena ciye seluruh kelas aku. Dan Syifa juga pasti benci sekali dengan hal itu.
“Sudah Az, begini saja. Kau pura-pura cuek saja. Urusan Syifa marah atau tidak, itu biar aku yang tangani. Bagaimana?”
Aku menghela napas. Itu opsi terbaik yang bisa diberikan.
Kelas Bersama adalah sesuatu hal yang baru di Quart School. Bu Jannah berhasil menginisiasi hal baru ini, dan kami menelannya mentah-mentah. “Biar tidak ribet dan Ibu juga tidak berulang-ulang mengajarnya. Sistem baru ini direstui oleh Bapak Wakasek Kurikulum.”
Aku menghela nafas lagi, apanya yang tidak ribet, malah kelas bersama itu menyusahkan bagi siswa. Panas, sesak dan sumpek.
Tapi jaminan yang diberikan Lia, hanya bisa terucap di mulut. Susah menangkis gelombang gosip ini. Baru saja, rombongan lokal 5 berdatangan ke lokal kami, Aram sudah berdiri, posisi meja kami yang dekat dengan pintu, membuat aku dan Aram bisa melihat siapa saja yang masuk ke kelas.
Begitu melihat Syifa masuk, Aram mendekat. “Eh Syif, mau duduk di samping bebeb Azka-kah?”
Syifa tidak hirau. Dia melewati Aram dengan dingin, juga termasuk melewatiku, tak sedikitpun hirau. Seolah aku tidak melakukan apapun dalam hidupnya. Dia berjalan menuju Lia dan Mawar.
“Tak mau disapakah Az, astaga. Tawari lagi, apakah dia mau duduk di sampingmu. Ini momen yang tidak terjadi setiap hari.”
Aku menyuruh dia diam. Tidak lama kemudian Bu Jannah masuk.
Di sela-sela materi yang disampaikan Bu Jannah, aku sempatkan melirik ke arah Syifa. Seorang pria duduk di belakangnya, sesekali berbicara dengan Syifa (yang itu artinya Syifa harus menoleh ke belakang). Aku mengenali pria itu.
Paderi Tamtama.
Astaga lengkap sudah hari ini.
Mozaik 11
Ini tentang Aku yang Tidak Bisa Bergerak
Hari-hari sehabis buku Syifa dicoret-coret, hari-hari sehabis kelas bersama, adalah hari yang berat bagiku.
Hari ini misalnya, aku, Wahid dan Aram pergi ke kedai kopi Paman Pirates, sekali lagi. (Aku sebenarnya heran bagaimana bisa aku tetap mengakrabi mereka berdua saat mereka terus-terusan menciyekan aku).
Rombonganku dan rombongan Syifa berpapasan tepat di depan pintu masuk kantin. Dia memasang raut wajah tak hirau. Aku juga demikian.
“Wah kenapa tidak disapa Az? Bebeb lewat dibiarkan saja,” Wahid memancing.
“Kami tidak dalam hubungan spesial apapun Hid, astaga. Berhentilah mendramatisir.”
“Tidak mungkin tidak ada hubungan Az. Kemarin-kemarin Syifa menyapamu, melempar senyum, melambai-lambai. Apa arti semua itu?”
“Mana aku tahu.”
Aram menyeringai. Hari ini dia tidak perlu berkomentar untuk ikut memojokkanku.
Di hari lainnya. Aku ke kantin sendirian. Tidak mengajak Wahid ataupun Aram. Kukira dengan begini, hidupku akan lebih mudah, tapi ternyata aku salah. Lagi-lagi salah.
Aku kembali berpapasan dengan rombongan Syifa di depan pintu masuk kantin. Kukira sekarang adalah waktu yang aman untuk melempar senyuman. Syifa, menerima senyumku, dengan wajah tak hirau. Teman-temannya berbisik.
“Azka senyum tuh Syif. Gak mau disapakah?”
Aku menepuk dahi begitu mereka serombongan berlalu. Tak kusangka, teman-temannya juga tahu. Kini aku harus semakin berhati-hati.
Hari lainnya lagi, cerita lain juga. Tempatnya saja yang sama.
Aku, Aram dan Wahid kembali lagi ke kantin. Hanya saja sekarang ini sudah pulang sekolah. Tadi kami bertiga tidak sempat minum kopi di jam istirahat kedua, lantaran Pak Hadi menjelaskan terlalu bersemangat, tidak sadar telah memotong jam belajar murid-muridnya. Sehabis Pak Hadi keluar, yang masuk malah Bu Hartini. Selesai sudah.
“Pesan Kopi Karibia, dengan cangkir besar, Paman.”
Aram berteriak sesampainya di kantin, sudah sepi. Paman Pirates mengacungkan tangan. Aku dan Wahid meniru menu pesanan Aram. Duduk tertib.
“Kasihan betul nasib Manchester United belakangan ini Az, kipernya sering blunder, bek-nya tidak kuat, tambahkan mental pemainnya yang lemah. Astaga, kalau begitu, dalam 10 tahun ke depan, MU bisa terdegradasi.”
Di akhir analisis “cemerlang”-nya, Wahid menyeringai. Dia jelas sedang mencoba menyerangku secara verbal. Aku dan Wahid memang suka mengobrolkan soal berita-berita sepak bola terbaru. Kami punya klub idola masing-masing, aku pegang MU, Wahid pegang Chelsea. Sialnya, dalam lima tahun belakangan, Chelsea lebih berprestasi dari MU. Jadilah Wahid selalu jumawa tiap membahas sepak bola.
“Jangan lupa Hid, MU biar begini-begini, pernah dilatih Mourinho. Mourinho jadi salah satu keping puzzle performa MU belakangan ini. Mengejek MU adalah mengejek Mourinho, mengejek Mourinho sama halnya mengejek legenda Chelsea.”
“Mana bisa begitu,” Wahid menyergah kencang. Aku terkekeh. Biarlah begitu. Aku lebih suka Wahid yang seperti ini, daripada Wahid yang menciye-ciyekan aku di depan Syifa seperti kemarin. Semoga kali ini tidak terjadi. Aku menghela nafas, untung kami ke kantin sepulang sekolah, tidak berprospek bertemu Syifa.
Namun aku salah.
Tahu-tahu dari ujung kantin, Syifa dan rombongan kawannya muncul. Menuju ke sini pula. Kukira kawan-kawan di rombongannya berkonspirasi. Baiklah aku sebaiknya bergegas. Aku segera bayar, menghabiskan kopi, dan terlambat…
Wahid sudah mencekal lenganku.
“Ayolah Az, jangan pergi kemana-mana dulu.”
Syifa dan rombongannya masuk ke kedai kopi, memesan, kemudian mengambil tempat duduk. Kentara betul, kalau teman-temannya (sekali lagi) berkonspirasi. Memaksa Syifa, duduk di seberangku.
Astaga, sebelum kejadian ini berakhir memalukan, aku harus angkat kaki. Aram di sebelahku tidak kalah gesit, bergegas merangkul bahuku. Bilang dengan keras, “kenapa buru-buru Az, duduk dulu, ngobrol. Mumpung ada Syifa di sini. Benarkan Syif?”
Yang ditanya malah tersenyum. Astaga, dia cari mati.
“Ciye, ceweknya senang nih,” koor teman-temannya. Paman Pirates bertepuk tangan.
Satu lagi, di tempat berbeda.
Saat itu, aku sedang bersiap-siap menunggu Ibu Qotrun untuk shalat Ashar di Mushola. Tahu-tahu Mawar menghampiri. Berbicara dengan suara rendah dan misterius, “Az, mau kubantu berbaikan dengan Syifa kah?”
“Eh, apa-apaan maksudmu,” aku tersentak.
“Iya Az, gampang kok sebenarnya berbaikan itu. Hanya perlu ngobrol. Nah itu Syifa, aku panggilkan ya?”
“Eh jangan,” aku gelagapan.
Terlambat. Mawar sudah berteriak, “SYIFAAAAA!!” sambil melambai-lambai. Syifa melihat, dan mendatanginya. Aku berdecak sebal. Buru-buru mengambil sandal, melarikan diri ke arah pancuran.
“Azka, tunggu. Astaga ini sudah kupanggilkan, tinggal ngomong aja.”
Aku berusaha untuk tidak mendengar lagi.
Mozaik 12
Event Besar Dua: Festival Togut
Satu hari menjelang Festival Togut.
Ibu Qotrun Nada berujar di depan kami semua, “Besok sekali lagi adalah pengalaman pertama yang ibu hadapi dalam menyelenggarakan sebuah event besar di Quart School ini. Festival Togut. Ibu sudah bicara dengan beberapa guru, meminta pendapat, mencari tahu sebanyak-banyaknya tentang acara ini. Ibu mencari tahu bagaimana caranya menjadi “Togut” sebaik-baiknya.
Besok, silahkan kalian datang Quart School dengan pakaian Togut, putih bersih. Kantin akan dibuka seluas-luasnya. Ibu juga sudah bicara dengan beberapa pedagang makanan di luar yang menyediakan makanan-makanan khas Nusantara agar bergabung di Festival ini. Pelajaran dan kelas ditiadakan. Kalian boleh makan sepuas-puasnya. Tapi selalu ingat esensi Festival ini, sebanyak apapun makanan yang kalian makan, pakaian kalian tidak boleh kotor. Kalian harus tetap “Togut” sepanjang Festival.”
Aku manggut-manggut, rupanya begitu esensi dari Festival ini. Bu Hartini mana pernah membicarakan hal semacam ini. Beberapa tangan mengacung, bertanya, apakah jika pakaian putih mereka kotor, mereka diusir dari Festival?
Ibu Qotrun tertawa kecil. “Bukan Quart School namanya jika membatasi siswanya dengan peraturan konyol. Tentu saja kalian masih boleh makan. Tapi di akhir acara, menjelang pulang, akan ada pemilihan siswa paling “Togut” di Quart School tahun ini. Kalau kalian tidak hati-hati, penghargaan ini bisa kalian lewatkan.”
Sehabis pengumuman, sebagian besar siswa bubar, sebagian lainnya ke kantin. Termasuk aku, Aram dan Wahid. Tidak ada rapat informal kali ini. “Festival Togut tahun ini akan menjadi sangat menyenangkan. Berbeda dengan Festival di tahun-tahun sebelumnya, mari kita bersenang-senang.” Aram selaku pemimpin rapat informal berujar.
Kami sampai di kantin. Di sana sudah ada Syifa bersama rombongannya. Kalian sudah bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Aku bergegas menyingkir, nyaris baku hantam dengan Wahid.
“Bisa kutebak.”
Saat aku masuk kelas, yang pertama kuterima adalah semprotan kata-kata ikhlas dari Nasri. Aku menghempaskan diri ke kursi, memejamkan mata, menghela nafas. Merasa tidak digubris, Nasri rupanya bicara lagi.
“Hei Azka, apa yang sebenarnya terjadi? Maksudku seburuk apa?”
Aku mendelik. Kenapa Nasri tiba-tiba bertanya seperti itu. Biasanya Nasri tidak terlalu suka urusan orang lain. Apalagi melihat mood-nya yang belakangan lebih sering diam. Tak apalah, kuceritakan saja, semua keciyean yang memenuhi kantin.
“Aku lelah Nas, menghadapi semua ini. Padahal aku ingin sekali berbaikan dengan Syifa.”
“Bisa kulihat,” sahutnya, gaya bahasanya berubah, “kau menderita gejala kesaltingan yang harus segera diatasi.”
Aku mengangguk malu-malu. Aku memang masih salting setiap bertemu dengan Syifa. Entah kenapa, setiap melihat dia, aku serupa melihat dia untuk pertama kalinya.
“Lalu aku harus bagaimana?”
“Ya kau harus hadapi dengan biasa saja. Toh Syifa juga mengetahui bagaimana perasaan kau terhadap dia, santai saja Az. Sikapmu itu membuat hidupmu terlihat buruk.”
“Kau tidak mengerti Nas, para pemburu gosip itu,” aku menyela dengan sengit.
“Kau mau bagaimanapun, mereka akan tetap ada. Sekarang kau hanya punya dua pilihan, mendekatinya lalu berbaikan, atau menjauh dan membiarkan dia pergi. Menurut hematku, berdasarkan ceritamu juga, waktumu tidak banyak.”
Kalimat Nasri seketika merasuk ke dalam pikiranku. Membuat Festival Togut-ku besok, rasanya tidak karuan.
Pagi hari Festival. Ibu Qotrun benar, kantin dibuka seluas-luasnya, bahkan ada beberapa wajah pedagang baru yang kulihat di sana, khusus menjajakan makanan tradisional Nusantara. Meski suasananya benar-benar semarak, sepagi ini aku sudah mengantuk.
Tadi malam aku tidak bisa tidur. Nasihat yang diberikan Nasri benar-benar ampuh. Aku memikirkannya dengan seksama. Hei ini adalah perjalanan satu arah. Di ujung sana, di akhir semester 6 nanti, Syifa akan pindah, pergi selamanya. Apakah aku akan membiarkan dia pergi begitu saja tanpa kenang-kenangan yang berkesan?
Demi mendapatkan pencerahan, aku (dengan pakaian Togut berwarna putih) naik ke kantor dewan guru, menuju ruang Wakasek Kesiswaan, menemui Ibu Qotrun Nada. Di hari Togut, mungkin beliau memiliki sedikit waktu senggang, untuk mendengarkan curhatanku.
Panjang kali lebar.
“Semua akan baik-baik saja,” ujar beliau, suara beliau lembut sekali. “Kamu tidak perlu menyikapi ini berlebihan begitu. Jangan panik, jangan lari dan yang terpenting, jangan salting. Cukup diam, jangan tanggapi semua keciyean itu. Ibu yakin, nanti mereka semua akan bosan dan berhenti menggoda kamu.”
Dalam cerita ini, dilarang keras meragukan dan membantah Ibu Qotrun Nada. Jadi seusai aku meresapi nasehat beliau, aku memutuskan pergi ke kantin. Melaksanakan ritual Togut. Tentu saja dimulai dari kedai kopi Paman Pirates. Tiga kabar baik segera menantiku di sana.
Kabar baik pertama, Aram dan Wahid belum ada di tempat.
Kabar baik kedua, Paman Pirates punya menu kopi baru.
Kabar baik ketiga, tentu saja, gadis bermata cemerlang yang tengah duduk di salah satu sudut kursi. Nur Syifa Muliyana. Dengan balutan pakaian Togut berwarna putih, dia terlihat bercahaya.
“Syif, apa kabar?” aku mendekati dia malu-malu. Hari ini dia juga sendirian. Ini adalah kesempatan emas.
“Aku baik Az,” sahutnya, diiringi sebuah senyum tanggung.
Tiba-tiba Paman Pirates memotong sesi pembicaraanku yang asyik itu dengan promosi kopi terbaru buatannya.
“Ini kopi yang telah dicampur dengan bahan herbal dan rempah-rempah. Sehingga aromanya sangat khas Az. Mau kubuatkan satu?”
“Buat saja Paman,” sahutku, agak sebal.
“Untuk gadismu itu bagaimana?”
Astaga. Apa kata Nasri dan Ibu Qotrun tadi? Ya jangan salting. Tolong jangan salting, aku mewanti-wanti hatiku. Pelan-pelan kutanya Syifa, “mau kopi juga Syif?”
“Eh tidak paman, saya tidak terbiasa minum kopi.”
Kudengar Paman Pirates bersenandung, semacam senandung cinta mungkin. Tapi sekali lagi kucoba untuk tak hirau. Duduk saja menunggu, dengan tetap berhadapan dengan Syifa.
Saat itulah Aram dan Wahid masuk ke kedai.
“Astaga Azka, kucari kemana-mana rupanya dia di sini, janjian makan-makan dengan cintanya. Kurang ajar betul,” Wahid berujar. Aku kembali mewanti-wanti hatiku. Ingat, jangan salting. Jadilah aku diam saja.
Aram dan Wahid memesan kopi yang sama, setelah menerima promosi panjang lebar dari Paman Pirates, kemudian duduk di sebelahku, menghadap Syifa. Tidak lama kemudian, giliran rombongan kawan-kawan Syifa yang datang, bisa kulihat mereka berbisik-bisik. Tapi sekali lagi aku mewanti-wanti agar diriku jangan salting.
“Kok diam-diaman saja Az?” Aram bertanya.
“Sudah ngobrol kok tadi,” aku sahuti sedikit, mulai salting, jadi kututup mulut lagi.
“Pacar Azka nih makin cantik saja Hid, kalau kau mau tahu. Lama-lama aku yang suka.” Lalu dengan simultan, Aram mencoba meraih lengan Syifa. Teman-temannya di sana, reflek membela, seseorang bahkan menyiram Aram dengan air mineral (untung cuma air mineral), “jangan pegang sembarangan, Ram!”
Demikian kejadian di kantin berakhir dengan hambar dan basah.
Sebagai penutup Festival Togut hari itu, Ibu Qotrun mengumpulkan kami semua, menyuruh beberapa siswa pilihan untuk memeriksa pakaian Togut kami. Akhirnya ditemukan pemenang. Dia adalah Nasri. Tak setetes pun noda ditemukan di pakaian putihnya. Aku tertawa tertahan. Tentu saja, karena Nasri sendiri tidak kemana-mana. Dia tidak merayakan festival makan gratis ini. Esok lusa, Ibu Qotrun akan merevisi peraturan terkait hal ini.
Mozaik 13
Perhatian Sentimentil
Aku memang berhasil menahan para pemburu gosip itu (untuk sementara), tapi aku masih belum menemukan cara berbaikan dengan Syifa. Membuka blok-nya itu saja bingung tujuh keliling. Di sisi lain, waktu terus berjalan.
Kerap kali di keheningan malam, aku membayangkan. Suatu saat nanti, Syifa akan benar-benar pergi, selamanya, dan mungkin saat bertemu lagi denganku, dia sudah memiliki suami.
Bayangan-bayangan semua itu, membuat aku senewen dan akhirnya jatuh sakit. Bukan sakit yang terlalu parah, tapi karena fisikku memang agak lemah, dan pengaruh psikis yang amat kuat, membuatku terkapar selama satu minggu.
Singkat cerita, di malam ketujuh, aku harus menerima pilihan, kedatangan malaikat penolong atau malaikan maut. (Itu cukup gila untuk sebuah cerita novel yang belum tentu best seller). Tidak aku bercanda, Lia datang ke duniaku, lewat chat. Perhatikan chat-chatnya yang bercetak miring.
“Az, kamu sakit apa sebenarnya?”
“Biasa saja. Radang di lambung, cuma penyakit kecil-kecilan.”
“Sudah satu minggu lho kamu tidak masuk sekolah. Seharusnya kamu memperhatikan kesehatanmu Az.”
“Iya, aku sudah melakukannya, tapi takdir berkata lain. Aku makan teratur kok.”
“Tidak begadang?”
“Tidak.”
“Tidak makan mie instan?”
“Juga tidak.”
“Ada sesuatu yang kamu pikirkan?”
“Kalau yang itu iya. Aku punya banyak beban pikiran.”
“Masih soal Syifa?”
“Iya.”
“Kamu tahu Az, cukup riskan kamu menggantungkan kebahagiaan hanya pada satu orang seperti itu. Kamu cukup pintar untuk menyadari bahwa kebahagiaan terbaik selalu datang dari diri sendiri bukan?”
(Kawan, kuberitahu jika sedang dalam angin yang tepat, Lia bisa menjadi sangat bijak, melebihi karakter lain di novel-novel best seller)
“Aku tahu itu. Tapi mau bagaimana lagi, keberadaan dia memang menjadi pusat dari kebahagiaan terbesarku.”
“Ah masa sih. Dulu sewaktu ditinggal Syifa mudik ke Pontianak, kamu malah kalap menembak aku.” Chatnya diakhiri dengan emot senyum mengejek. Aku meringis membacanya.
“Itu kejadian lewat. Dan terbukti setelah kejadian itupun, aku masih menyukai Syifa.”
“Az, aku ingin kamu kembali jadi Azka yang hebat seperti awal-awal masuk Quart School. Azka yang bersemangat, dan cerdas bukan buatan. Jangan bermuram durja sampai sakit satu minggu begini hanya gara-gara wanita.”
“Apa kamu bisa mengembalikan aku ke sana?”
“Kita lihat saja. Akan kucoba. Awas ya nanti kalau kamu nembak aku lagi.”
Aku terkekeh. Percakapan dengan Lia cukup menghibur.
“Kamu sudah makan Az?”
“Sudah tadi.”
“Banyak-kah sedikit?”
“Macam tak tahu bagaimana orang sakit makan.”
“Ya kamu kan yang sakit itu sebenarnya hati, bukan fisik. Esok di-banyak-in ya Az. Biar cepat sehat.”
“Insya Allah.”
“Nanti kalau kamu sehat, akan ada kejutan menantimu di Quart School.”
“Entah apa kejutan itu, tapi sepertinya kamu yang berada di belakang semua itu.”
Percakapan terus mengalir seperti sungai sampai tengah malam.
“Sudah waktunya tidur Az.”
“Iya, nih sudah di tempat tidur. Dari awal chat kamu tadi malah.”
“Hehehe iya juga. Jangan lupa baca doa tidur. Jangan malah memikirkan yang aneh-aneh.”
Oh Tuhan, entah kenapa itu menjadi kalimat yang indah.
Mozaik 14
Aku Benar-benar Menembaknya
Tentu saja kawan bertanya-tanya, kapan aku pernah menembak Lia. Kejadian itu sebenarnya sudah lewat beberapa puluh ribu kata, tak pernah kumasukkan dalam cerita sebelumnya, karena aku tidak pernah menemukan ruang yang tepat. Sekarang mungkin aku sudah menemukan ruang yang tepat tersebut.
Jadi, begini ceritanya:
Semua bermula di malam dimana Derby Manchester dilaksanakan. Kenapa harus dari sana, kawan sebaiknya engkau tidak usah bertanya seperti itu. Aku menonton pertandingan ini karena ini penting untuk menegakkan eksistensiku dalam debat kusir bola bersama Wahid nanti.
Itu adalah masa-masa mudik Syifa ke kampung halamannya Seusai aku mengungkapkan rasa, sesudah dia melarangku untuk memikirkannya. Aku syok, aku merasa kosong, aku merasa kehilangan rutinitas. Di saat-saat seperti ini, (aku menuruti saran Guru Olahragaku yang dulu) aku harus mencari rutinitas baru. Saran beliau itulah yang membawaku pada Lia.
Sebenarnya komunikasiku dengan Lia sudah intens sejak awal. Aku hampir tidak pernah melewatkan malam tanpa men-chat-nya. Tapi pembicaraan kami lebih sering absurd ketimbang serius. Apalagi yang bertopik romantik. Amat sangat jarang. Sampai Derby Manchester itu datang.
“Az, kamu tidak siap-siap tidur? Sudah pukul 11 malam ini.”
“Belum, aku sedang asyik menonton Derby Manchester.”
“Apa itu?”
“Eh, pertandingan sepak bola maksudku.”
“Ngapain nonton begituan Az, tidak ada seru-serunya. Cuma bola yang diperebutkan 11 orang laki-laki.”
“22 orang kalau dihitung dua tim,” balasku, mengoreksi.
“Nah apalagi. Kenapa tidak belikan saja mereka masing-masing satu bola. Tidak rebutan lagi.”
“Lia, itulah esensi sepakbola. Saling memperebutkan bola itu. Yang bulat-bulat macam bola itu saja 22 orang yang memperebutkan, apalagi kamu. Tak bisa kubayangkan.”
Tak bisa kupercaya, di chat panjang itu, aku pertama kali belajar merayu Lia. Dia membalas, “Hehe. Kalau memang harus diperebutkan, aku ingin jatuh di tangan orang yang tepat saja, di tangan Humadi Azka.”
“Hehehe,” aku membalas hanya begitu saja. Tak tahu lagi harus bagaimana.
“Sudah Az, mending tidur. Gimana kalau nanti kamu sakit. Jangan begadang, begadang itu tidak baik, lebih baik kamu belajar merayuku. Itu jauh lebih menyenangkan.”
Chat-nya itu ditutup dengan emot senyum menggelikan. Sejak malam itu, hubungan aku dan Lia, meluas hingga ke batas-batas alam semesta. Mungkin efek panas karena tidak berhasil mendapatkan Syifa, membuat aku mengirimi pembuka chat yang begini pada Lia.
“Bebeb Lia.”
(Kawan, aku masih sering tersenyum geli setiap mengingat momen itu. Kutulis di sini agar kawan juga bisa tersenyum geli. Bukankah membagikan hal-hal menggelikan semacam ini adalah ibadah?)
Lia menanggapi dengan tidak kalah menggelikan, “Iya beb. Kamu kangen dengan aku-kah? Astaga belum satu hari kutinggal, kamu ini.”
Dari hal-hal semacam inilah, cinta kemudian tumbuh.
Di masa-masa itu, seringkali di tengah kegelapan malam, aku merenung sendiri semua hal yang terjadi. Termasuk soal Lia. Sering kulukis wajahnya di atas bintang-bintang. Wajahnya yang syahdu dan imut menggemaskan itu.
Apalagi pada beberapa hari berikutnya Lia menghilang dari peredaran. Bukan main gemas aku waktu itu. Aku bertanya-tanya kemana dia, dan saat dia menghubungiku lagi, aku bukan main senangnya.
Aku tahu kawan, kisah ini terlalu singkat untuk diceritakan dalam satu chapter, tapi kalian juga pasti menebak bukan, ini bukan kisah tentang Lia. Setidaknya bukan kisah aku dan Lia. Tidak seperti itu. Jadi aku langsung ke intinya saja, setelah semua chat berbau mesra, aku memutuskan untuk menembaknya. Dengan kalimat seperti ini.
“Lia, seandainya aku suka denganmu, apa yang akan kamu katakan?”
Sebagian hatiku berkomentar: “Ayolah Az, kau bertanya dengan kata ‘seandainya’ lewat chat pula, dan kau sebut itu menembak cewek? Sungguh miris. Ironis.”
Lia menjawab begini, “ditahan-tahan ya Az. Soalnya aku takut bakal menyakiti kamu. Aku sudah menganggapmu sebagai sahabatku yang paling akrab. Sulit bagiku untuk mencari sisi mana yang harus kucinta darimu.”
Sungguh kawan, jawaban dari Lia itu sanggup membuatku tersuruk di akhir semester 4.
Oh ya, mengenai Derby Manchester itu, aku berhasil memenangkan debat kusir dengan Wahid selama satu minggu penuh, karena MU, tim kebanggaanku, menang 2-0.
Mozaik 15
Persahabatan Paling Absurd di Dunia
Aku tidak sedang bercanda kawan. Persahabatanku dengan Lia, memang yang paling absurd di dunia. Hari ini absurd, esok-esok jauh lebih absurd lagi.
Aku sedang duduk-duduk santai di Mushola seusai shalat dhuha. Malas rasanya kembali ke kelas, karena sehabis ini adalah pelajaran Bahasa Inggris. Aku tidak mencantumkan pelajaran satu ini dalam daftar favoritku. Hanya karena gurunya cukup menarik saja, aku sering masuk kelas. Mr. Zee, itulah nama beliau, jika kamu mau tahu, kawan.
Tiba-tiba dari arah kantin, Lia muncul, menyapaku, tersenyum. Aku melambaikan tangan. Ternyata Lia malah mendatangiku.
“Lagi apa Az? Melamun?”
“Hehe,” aku terkekeh, sedikit salting, “bukan melamun. Melainkan mencari inspirasi.”
“Kamu masih menulis cerita Az?” tanyanya. (Aku sudah mulai terkenal di kelas sebagai seorang penulis aktif).
“Masih dong. Ini juga sedang memikirkan lanjutan ceritanya.”
Lia mengambil tempat duduk di sebelahku. “Ceritanya masih tentang Syifa?”
“Iya dong, aku ingin semua orang di dunia ini tahu tentang dia.”
“Kamu ini Az,” Lia geleng-geleng kepala, “kamu benar-benar serius tentang dia?”
“Astaga, tentu saja.”
“Baiklah, ayo masuk Az. Sudah bel masuk. Sebentar lagi Mr. Zee akan masuk ke lokal kita.”
Aku menggeleng. “Aku nanti saja. Silakan duluan. Masih asyik di sini, dan juga aku malas mengikuti kelasnya Mr. Zee. Tidak cocok dengan diriku.”
“Azka Mr. Matematika sih,” Lia terkekeh lagi.
Kemudian kami mengobrol lebih panjang lagi tentang matematika dan soal-soal Pak Farhan. Tak terasa setengah jam sudah. Sadar tidak sadar, Lia juga ikut-ikutan membolos bersamaku.
“Kamu tidak berniat masuk ke kelas, Lia?”
“Eh,” dia menepuk dahi, ekspresi kelupaan, “astaga, mengobrol denganmu, membuatku lupa waktu. Ya sudah, sekalian saja aku bolos. Menemanimu di sini, mencari inspirasi.”
“Kamu ada-ada saja.”
Hari itu, kami menghabiskan satu jam pelajaran penuh untuk mengobrol panjang lebar. Banyak sekali topik yang kami bahas. Melihat dia tertawa, melucu, hatiku terasa hangat. Oh Tuhan, apakah ini cobaan dari engkau.
Entah dimana Syifa sekarang.
Berpindah latar ke hari libur Quart School. Hari yang sibuk. Aku menghabiskan setengah hari, dari pukul 8 pagi sampai 2 siang untuk mengetik skrip novel. Setiap beberapa paragraf, diselingi oleh chat dari Lia.
“Az, sesekali pandangi ke jendela. Jangan natap layar terus.”
“Iya. Ini kulakukan. Ada kok jendela yang besar dekat meja kerjaku.”
“Baguslah kalau begitu.”
“Mungkin kalau bisa memandangimu, itu jauh lebih baik untuk mataku. Hehe.”
“Azka, kamu lupa apa yang kita bicarakan di malam kamu terbaring sakit itu?”
“Apa?”
Lia mengirimiku salinan chat.
“Kamu sudah janji Az,” (tulisnya di bawah), “untuk tidak terbawa lagi ke aku. Ingat-kan?”
Aku menghela nafas. Lia mengungkit soal itu lagi. Iya, aku sudah berjanji, kami bersahabat, bukan hubungan spesial. Tapi dengan segala sensasi yang diciptakannya, hei, mana bisa kutahan. Sedikit banyak, aku mulai menyukainya. Karena tidak bisa membahas soal ini dengan dia, aku berpanjang mulut dengan Nasri saja. Kuceritakan panjang lebar soal kegundahanku, soal perasaanku yang tiba-tiba bercabang dua, satu pada Syifa, satu pada Lia.
“Jadi orientasimu berubah Az?”
“Tidak juga Nas. Aku bahkan bingung bagaimana harus mengatakannya.”
“Kalau menurutku, tidak ada salahnya kau menyukai gadis itu. Lia adalah gadis yang sangat menarik. Tapi aku berani bertaruh, kau memerlukan upaya yang tidak kecil untuk menaklukkan dia.”
“Sepertinya begitu.”
“Kau sudah mendengar bagaimana masa lalunya?”
“Kau tahu?” aku bertanya, menyernit kening.
“Iya tentu saja.”
“Bagaimana bisa?” aku menyernit kening lagi. Aku sudah sering mencoba mengorek masa lalu Lia. Tidak pernah berhasil, bagaimana bisa Nasri mengetahuinya.
“Aku bertanya. Dia bercerita.”
Aku manggut-manggut, urusan ini tidak akan pernah sederhana.
Mozaik 16
Jalan-jalan ke Perpustakaan
“Az, kamu pernah ke perpustakaan daerah?” Lia bertanya pada suatu malam. Lewat chat.
“Pernah, sering malah. Seminggu sekali.”
“Banyak-kah buku di sana Az?”
“Ya tentu dong, namanya juga perpustakaan daerah.”
“Asyik sepertinya. Sesekali, boleh dong ajak aku ke sana.”
Sekedar info untukmu kawan, Perpustakaan Daerah Bumi Melayu adalah perpustakaan terbesar di provinsiku. Di dalamnya ada ribuan buku, mencakupi ruang baca dan ruang referensi. Itu adalah surga bagi para kutu buku seperti aku.
“Ayo, mau kapan?”
“Apakah hari Sabtu, perpustakaan tersebut buka?”
“Sepertinya iya, tapi tidak seharian.”
“Boleh deh Sabtu depan. Penasaran aku bagaimana isi dari perpustakaan besar itu. Jemput ya Az.”
Aku langsung deg-degan. Apakah ini artinya Lia mengajakku jalan-jalan? Berdua saja? Dan itu artinya dia akan duduk di boncengan sepeda motorku? Seperti orang yang sedang kasmaran? Astaga kawan. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu.
Oh Tuhan, izinkan aku melakukan itu.
Hari sabtu itu akhirnya tiba. Tak sabar aku menantikannya. Aku memacu sepeda motor ke rumah Lia, di salah satu kompleks perumahan di Jalan besar Bumi Melayu. Pelan-pelan kuketuk pintu rumahnya, langkah-langkahku hari ini benar-benar penuh dengan keberuntungan. Lia keluar dengan fashion sebagaimana yang telah kubayangkan. Tanpa tedeng aling-aling dia segera duduk di belakangku. Dia siap dibonceng.
“Ayo kita berangkat Az.”
“Let’s go” soraiku dalam hati.
Bagaimana rasanya pertama kali membonceng seorang gadis, kawan? Ah bagi kau yang mungkin berpengalaman di bidang asmara, membonceng gadis bukan sesuatu yang istimewa. Tapi bagiku, yang seumur hidup baru kali ini jalanjalan dengan seorang gadis, astaga, hatiku melambung sampai ke angkasa.
Setelah membelok ke jalan raya, perlahan tapi pasti, kutingkatkan kecepatan dan akselerasi sepeda motorku. Lia yang duduk di belakang kontan berteriak. “Hati-hati Az. Jangan ngebut.”
Aku terkekeh. Manis kawan. Manis sekali. Apalagi merasakan tangannya yang berpegangan kuat di jaketku. Semua hal tak bermutu itu kudapat dari Faddil Al-Aram.
Sesampainya di perpustakaan, kalimat pertama yang kuterima dari Lia adalah, “kalau tahu begini Az, setiap hari kamu kuingatkan agar tidak ngebut.”
“Sungguh aku bersedia diingatkan setiap hari begitu,” sahutku tanpa sungkan. Toh yang di depanku, sahabatku. “Ish, kamu ini Az.” Lalu Lia tertawa. Sampai senyumnya yang manis itu, terburai kemana-mana. Nasri benar, Lia adalah gadis yang menarik. Kenapa tidak sedari dulu aku memikirkan tentang ini?
Resepsionis perpustakaan mengenali aku, karena saking seringnya aku mampir di sini. Tapi kali ini dia terbelalak, mungkin karena aku tidak datang sendiri. Segera kuisyaratkan bahwa yang bersamaku itu, adalah kekasihku. Resepsionis mengangguk-angguk.
Aku mengajak Lia masuk ke ruang baca perpustakaan daerah. Sebuah ruangan besar dengan lebih dari 30 rak buku berbagai macam jenis, dan kursi-kursi empuk nan nyaman. Tambahkan suasana yang senyap dan suhu udara yang adem, mantap sekali suasananya.
Lia menuju ke salah satu rak. Aku menemaninya, pura-pura mencari buku juga, padahal maksud hati tidak ingin jauh-jauh dari dia. Agak penasaran juga buku apa yang akan dipilih oleh Lia. Apakah cara perkembangbiakan kambing gunung, buku tentang tata cara beternak lele, atau malah Lia adalah penggemar buku-buku konspirasi. Bisa saja, karena banyak sekali yang minat buku konspirasi semacam itu.
Ternyata yang dipungutnya adalah buku kecil yang berisi kata-kata puitis nan gombal. Aku terkekeh. Pas juga dengan suasananya.
Kami kemudian mencari kursi. Sengaja pula aku mencarikan kursi agar kami duduk berhadapan. Secara sengaja pula aku memungut salah satu buku tebal milik Sigmund Freud. Kenapa aku memilih buku tersebut? Adalah, tiada lain, agar aku bisa secara diam-diam melirik ke arah Lia. Apa hubungannya buku Freud dengan lirikan semacam itu? Usah bertanya kawan, bukankah hal-hal paling ganjil di dunia ini, memang berawal dari cinta?
Mozaik 17
Lomba Nasional Bumi Melayu
Sobat bola dimanapun kalian berada, tadi malam, terjadi big match yang sangat seru di ajang Copa Italia, laga bertajuk Derby Della Mole. Pertandingan ini tidak hanya panas karena memperebutkan tiket semifinal, tapi juga karena riwayat persaingan dua klub sekota.
Pertandingan berlangsung sangat sengit. Tim tamu yang datang ke kandang juara bertahan, tidak bermain pandang bulu. Mereka seperti singa terluka. Beruntung, meski berjibaku keras, Tuan rumah tetap berhasil mengamankan kemenangan dengan skor…
SEKILAS INFO
Pemirsa, maaf telah menyela acara kesukaan anda, tapi saya di sini punya berita yang amat sangat penting untuk anda simak….
Aku yang menonton TV sambil makan, nyaris tersedak. Bisa-bisanya acara sekilas info macam begitu, menyusup di tengah-tengah acara lain. Tanpa permisi pula. “Ayolah berita tidak penting, aku ingin melihat hasil Copa Italia tadi malam, hasil Derby Della Mole, antara Juventus vs Torino.” Hatiku masih bersungut, saat pembawa acara meneruskan kalimatnya.
Berita gembira untuk kita semua. Mungkin juga berita ini adalah berita yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa menengah atas. Lomba Nasional Tingkat Menengah Atas akan diselenggarakan di Bumi Melayu tahun ini.
Keputusan ini baru saja diumumkan di kantor Kemendikbud oleh Bapak Menteri sendiri. Tentu saja, hal ini akan menjadi momen paling membanggakan bagi Bumi Melayu, sekaligus momen yang sama sekali tidak boleh dilewatkan. Jarang-jarang kebijakan Lomba Nasional mengambil lokasi di luar pulau Jawa.
Terima kasih sudah mendengarkan Sekilas Info, nantikan info-info ter-update lainnya, satu jam ke depan.
Aku nyaris ngomel, protes dan tidak terima atas siaran ini lagi. Tapi informasi yang tadi mereka bawakan, memang benar-benar tidak boleh dilewatkan. Lomba Nasional akan diselenggarakan di Bumi Melayu? Astaga. Setiap mendengar kata Lomba Nasional, aku pasti terbayang lagi, betapa tragisnya perjuangan kami tahun lalu.
Pengumuman berikutnya menanti di sekolah.
Pagi-pagi sekali, Bapak Kepala sekolah sudah berdiri dengan semangat di podium upacara. Sepanjang aku sekolah di sini, tak pernah sekalipun kulihat beliau seantusias itu. Senyumnya tidak putus-putus. Pasti ini ada kaitannya dengan Lomba Nasional di Bumi Melayu itu. Setelah bel tanda masuk berbunyi, beliau meminta kami berkumpul di lapangan. Siap menerima pengumuman dari beliau.
“Siswa-siswaku yang semoga berbahagia sebagaimana Bapak pagi ini berbahagia. Mungkin kalian sudah mendengar, mungkin sudah membaca, atau sudah mengetahui informasi tentang Lomba Nasional tahun ini,”
Beberapa orang berbisik-bisik. Sebagian tahu, dan sebagian lainnya mencari tahu.
“Akan bapak sampaikan terlebih dahulu, bahwa Lomba Nasional tahun ini akan dihelat di Bumi Melayu. SMK Negeri 1 Bumi Melayu mendapat kehormatan untuk menjadi penyelenggara. Mungkin sebagian dari kalian juga mengetahui bahwa, tuan rumah penyelenggara memegang satu golden ticket untuk langsung menuju tahap seleksi nasional.”
Beberapa siswa kembali berbisik-bisik, mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan.
“Nah perihal golden ticket inilah yang ingin Bapak bicarakan hari ini. Jadi tadi pagi juga, Bapak menerima telepon langsung dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bumi Melayu. Bapak Kadisdik mengatakan bahwa di momen yang amat langka ini, Bumi Melayu harus bisa meraih Juara satu dalam duel Cerdas Cermat di Lomba Nasional. Itu target yang ambisius.
Bapak Kadisdik juga sudah berkoordinasi dengan Kepala sekolah tempat Lomba diadakan, dan menurut Bapak Kadisdik, SMK Negeri 1 Bumi Melayu tidak siap menerima golden ticket itu. Sekolah mereka hanya dipilih lantaran dekat dengan pusat kota, dan fasilitasnya unggul. Setelah melakukan koordinasi tiga arah, sebelum pukul 7 tadi pagi, Bapak Kadisdik, memutuskan untuk menyerahkan golden ticket kepada sekolah terbaik di Bumi Melayu. Kepada Quart School. Jadi sekarang beban berat terbeban di pundak kita.”
Bapak kepsek menarik nafas. Menyiratkan bahwa beban yang kami bawa, memang betul-betul berat.
“Kita punya kewajiban memenangkan Lomba Nasional itu. Tentu saja dengan cara-cara yang terang dan terhormat. Tadi pagi juga, Bapak bersama beberapa dewan guru untuk mencari cara terbaik menemukan wakil sekolah untuk mewakili Quart School. Mengambil golden ticket.
Baiklah, tanpa basa-basi yang lebih panjang lagi. Setelah pengumuman ini, harap setiap juara 1, 2 dan 3 dari tiap lokal menghadap Bapak di ruangan Wakasek Kurikulum. Kita akan melakukan seleksi tingkat sekolah. Sementara siswa lain, sementara persiapan, sampai lomba digelar, demi meningkatkan konsentrasi peserta seleksi,” Bapak Kepsek menarik nafas lagi, “kalian semua diliburkan.”
Lalu bak gegap gempita perang, semua orang bersorak-sorai gembira.
Aku sebenarnya kecele ketika kembali ke lokal dan mengambil tas. Ingin sekali rasanya ikut bersaing mewakili Quart School dalam Lomba Nasional seperti tahun lalu. Tapi aku tidak memenuhi standar seleksi. Ranking terakhirku di semester 4, hanya berangka 4 juga. Yang mewakili lokalku (lokal 4, hei kenapa banyak sekali angka 4 di sini. Aku curiga, alih-alih diletakkan di rak buku novel best seller, cerita ini malah akan diletakkan di rak kumpulan buku konspirasi) adalah Nasri, Mei dan satu orang perempuan lainnya.
Aram memahami perasaanku. Demi menghiburku dia mengajak kami bertiga, dengan Wahid ke kantin. Ke kedai kopi Paman Pirates. Jadilah, di saat semua orang melewati gerbang pulang, kami menyelinap ke kantin.
Di lorong, kami sempat berpapasan dengan salah seorang dewan guru, beliau melotot ke arah Aram yang berjalan santai. Maksud tatapan beliau mungkin seperti ini, “hei, kenapa kalian tidak pulang, melanggar perintah?”
Aram mengangkat bahu. Ini Quart School. Jika guru tidak boleh memaksa muridnya masuk di salah satu kelasnya, maka guru juga tidak bisa memaksa muridnya untuk pulang.
Tiga kopi Hindi segera terhidang di meja. Aram yang pertama kali buka mulut, menggerutu. “Astaga, seharusnya aku dipilih mewakili Quart School ini.”
“Kenapa begitu, Ram?” aku bertanya.
“Aku punya keberuntungan yang sangat kuat. Quart School bisa menang mengandalkan keberuntunganku itu.”
“Dua alasan Ram,” Wahid menyahut, tangannya membuat gestur dua, “satu, seleksi memakai sistem ranking, dan kau ranking 15. Dua, keberuntunganmu itu hanya bualan, kalau kau memang beruntung, takkan-lah kau sampai jatuh ke ranking 15.”
Aram menyeringai seram. “Menurutmu siapa yang akan memenangi golden ticket itu Az?” tanyanya.
“Aku bertaruh pada Nasri.”
“Menurutku tidak,” sahut Wahid sengit, “orang yang paling cocok mewakili Quart School dalam event semacam ini, adalah Shiela Camalia. Tidak ada yang lebih baik dibanding dia. Selama 4 semester berturut-turut, dia selalu mendapat bintang pelajar. Itu artinya, selama dia sekolah di sini, tidak ada yang bisa menyaingi nilanya. Tidak juga Nasri.”
Aku manggut-manggut. Prediksi Wahid itu ada benarnya.
Mozaik 18
Untukmu Shiela
Tiga hari sudah seleksi berjalan. Hari ini, aku, Aram dan Wahid menyelinap lagi ke Quart School. Kami bersekongkol lewat grub WA untuk menelikung peraturan sekolah, hanya untuk menyesap cangkir kopi di Kedai Paman Pirates.
“Saat ini, seleksi sudah hampir selesai. Sekolah sudah nyaris meresmikan tiga wakil Quart School untuk Lomba Nasional. Mendapat golden ticket.” Wahid berapi-api bicara. Aku tahu kenapa dia begitu semangat, pasti ada kaitannya dengan Shiela.
Aku dan Aram sibuk mengunyah bakwan edisi seribu perak. Tidak peduli.
“Kalian mau dengar bagaimana jalannya seleksi?”
Aku dan Aram mengangkat bahu. Silakan saja. Wahid mulai bercerita. “Pertama-tama, ada 45 orang juara dari tiap lokal yang berkumpul untuk seleksi. 45 orang ini, segera diberi soal dengan jenis-jenis yang sama dengan soal-soal cerdas cermat tahun-tahun sebelumnya. 30 orang segera gugur. Hanya tersisa 15 orang untuk melanjutkan seleksi.
Tahap berikutnya adalah simulasi, dimana 15 orang yang tersisa dihadapkan dengan simulasi lomba sebagaimana adanya. Siapa yang tidak bisa menjawab dengan tepat dan dengan analisis yang matang, akan gugur. Sekolah hanya mencari 5 orang terbaik dari sesi ini.
5 orang terakhir ini, akan melewati sesi pengayaan materi, mendapatkan materi-materi baru. Untuk kemudian diuji lagi dengan soal-soal dan simulasi. Hanya tiga orang terbaik yang akan lolos, dan menjadi perwakilan Quart School.”
“Dan mereka adalah?” tanya Aram menggantung.
“Salah satunya Shiela dong. Dua lainnya adik kelas.”
“Lho Nasri tidak masuk?” aku menyerobot bertanya.
“Kau tahu sendirilah mood sahabatmu itu Az. Dia mau semau dia saja. Kalau dia mau ya dia lakukan, kalau dia tidak mau, sekeras apapun orang lain memaksa, dia tidak akan mau. Nampaknya ketiadaan kau, membuatnya tidak bersemangat.”
Di hari Lomba Nasional, berduyun-duyun orang, ratusan jumlahnya mengantar utusan Quart School ke SMK Negeri 1 Bumi Melayu. Sebagian bangga terhadap kesempatan Quart School, sebagian lainnya (sebagian besar) hanya ingin melihat Shiela beraksi.
Sepasukan polisi patroli kembali berjaga di lapangan Bumi Melayu. Mengulangi deja vu setahun yang lalu, tapi kali ini mereka tidak berdaya. Tidak peduli siapa yang sebenarnya menyuruh mereka, polisi itu tidak sanggup menahan semua pengiring Shiela Camalia.
Aku turut hadir di antara rombongan pengantar itu.
Banyak sekali, orang yang merubung Shiela sebelum dia masuk ke ruang lomba. Modus ingin dekat-dekat dengan cewek nomor satu di Quart School, walau cuma mengucapkan “selamat berjuang, Shiela. Semangat.” Saking banyaknya orang di sekelilingnya, Shiela sampai risih.
Aku tidak ikut merubungnya seperti mereka-mereka. Aku menunggu sampai semua orang di sekeliling Shiela menjauh, bosan karena Shiela sama sekali tidak merespon perlakuan mereka. Nah baru di saat itulah aku muncul, di hadapannya. Berdua saja.
“Hai Shie.”
“Eh ada kamu juga Azk.” Dia sedikit terkejut melihat diriku tiba-tiba.
“Iya dong, aku harus datang untuk memberimu semangat. Aku yakin sekali kamu akan memenangkan pertandingan besar hari ini.”
Shiela blushing on mendengar kata-kataku. Dia tersipu, “Makasih Azk. Kamu harus tahu, sedari tadi aku bosan sama sekali mendengar semua kata-kata support dari mereka semua. Tapi ucapan darimu ini, baru yang benar-benar membuat aku terkesan.”
Suara dari pengeras suara memanggil peserta lomba. Aku mempersilahkan Shiela segera masuk ke ruangan lomba, dia tersenyum. Dan percayalah kawan, senyumnya itu benar-benar manis. “Aku akan janji Azk. Aku akan melakukan yang terbaik, untuk Quart School, untuk Bumi Melayu dan untukmu.”
Cih, Shiela membalas. Giliran aku yang tersipu malu.
Sore itu juga, sebelum dewan juri resmi bersidang menentukan pemenang dari lomba cerdas cermat, berita itu sudah menyebar. Shiela telah meraih panen besar, dia membungkam seluruh perwakilan sekolah seluruh Indonesia. Aku tidak hirau, toh nanti akan ada pengumuman resminya.
Dan jika-pun Shiela menang, bukankah memang seperti itu sewajarnya?
Mozaik 19
Hari Suka Raya Dadakan
Satu minggu setelah pengumuman “sekilas info”.
Bapak Kepala sekolah hari ini sekali lagi berdiri, tersenyum-senyum di dekat podium. Aku, demi melihat fenomena itu, ikut senang, semoga itu adalah kabar baik dari dewan juri Lomba Nasional.
Kali ini, tidak lagi menunggu dipanggil lewat pengeras suara, para siswa berinisiatif untuk langsung memadati lapangan. Bertanya-tanya, kira-kira apa kabar terbaik yang akan diberikan kepala sekolah.
Tepat pukul 8 pagi, Pak Kepala Sekolah menyalakan mic-nya.
“Siswa-siswaku sekalian, hari ini bapak ingin menyampaikan sebuah kabar gembira yang bapak terima dari panitia Lomba Nasional. Semoga bapak bisa menyelesaikan pengumuman ini tanpa gemetar. Jujur, ini adalah pengumuman terbesar dan terbaik yang pernah Bapak katakan sepanjang sejarah Bapak menjabat kepala sekolah di sini.”
Bapak kepala sekolah menghela nafas sejenak.
“Bapak sebagai warga Quart School sangat bangga, sangat senang, sangat gembira, atas pencapaian yang dicapai tim ananda Shiela Camalia. Karena mereka telah menjuarai Lomba Nasional Cerdas Cermat dan keluar sebagai juara pertama. Bapak memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan pencapaian kalian semua. Kita telah menyenangkan Kadisdik, kita tidak membuang kesempatan, dan yang kita telah membuktikan kepada negeri ini, sekolah mana yang terbaik, terbaik di atas yang terbaik.”
Bapak kepala sekolah menghela nafas lagi.
“Demi menghargai pencapaian dan prestasi kawan kita semua, Shiela Camalia. Hari ini, sebagai pemegang wewenang tertinggi di Quart School, bapak meresmikan Hari Suka Raya dadakan. Silakan, silakan semua merayakannya, demi kawan kita yang berprestasi.”
Inilah kehebatan Bapak Kepala Sekolah. Tahu betul bagaimana membuat seluruh siswanya benar-benar larut dalam euforia. Kantin-kantin segera diserbu para siswa. Shiela sendiri, sebagai sang pemenang, juga diarak ke kantin, mereka, para penggemarnya memutuskan untuk merayakan bersamanya. Tidak peduli Shiela sebenarnya risih diperlukan begitu.
“Shiela, The winner, Shiela si nomor satu, The Champion, Shiela juara.”
Sepanjang kantin, yel-yel itu terus terdengar. Aram dan Wahid sepertinya tertarik untuk ikut ke kantin. Mereka menarik tanganku. “Ayo Az, kita ke kantin. Ini adalah kesempatan besar untuk bisa dekat-dekat dengan Shiela.”
Aku menepis, sama sekali tidak tertarik bergabung dengan kerumunan gila itu.
“Ah Azka, mentang-mentang kau bisa dekat-dekat dengan Shiela kapan saja,” Aram menyeringai nakal. “Ya sudah Hid, ayo kita ke kantin. Kalau beruntung, kita bisa mengamankan satu kursi di dekat Shiela.”
Lepas dari lapangan, aku dan dua kawanku berpisah jalan. Aku menuju kelas, sedangkan mereka bergabung dengan kerumunan. Di lokal, sudah ada Nasri menunggu.
“Kukira kau ikut merayakan hari ini,” ujarnya sebagai kata sambutan.
Aku menggeleng pelan, “kerumunan sebesar itu tidak cocok untukku.”
“Yahh kau benar. Ini adalah hari yang sangat luar biasa.”
Setelah itu, Nasri tenggelam dalam pemikirannya, sementara aku membuka laptop, iseng menulis beberapa cerita, melanjutkan proyek-proyek. Setelah satu jam berlalu, saat Aram dan Wahid sudah kembali ke lokal, barulah aku diam-diam ke kantin. Hei ini adalah Hari Suka Raya dadakan. Makanan gratis tersedia di kantin.
Quart School perlahan menyepi. Kerumunan yang satu jam lalu memadati kantin sudah hilang seluruhnya. Sebagian pulang, sebagian lainnya tidak tahu kemana. Mungkin tidur siang sejenak di lokal. Jam menunjukkan pukul 12 siang.
Di lorong kantin yang senyap itu, seakan sudah dirancang oleh semesta, aku bertemu jalan dengan Shiela. Kami berdua kagok. Aku segera berusaha untuk menguasai keadaan.
“Hai Shie, selamat atas kemenangannya.”
“Makasih Azk. Kuharap itu bisa membuatmu terkesan.”
“Hei aku sudah terkesan sejak kita pertama bertemu. Kamu sangat cerdas Shie, kemenangan ini sudah sepantasnya untukmu.”
“Itu semua berkat kamu Azk.”
“Eh, aku?”
“Kamu lupa, semua kalimat-kalimat yang kamu berikan padaku di awal semester 5 kemarin?”
Aku dengan cepat mengingat-ngingat. Mengais-ngais memori otakku, dan segera tersenyum. “Maukah kamu minum bersamaku dan mengenang lagi hari itu Shie.”
“Oh tentu saja. Dari tadi aku merasa tersiksa karena dikerumuni banyak sekali orang. Ngobrol cerdas dengan Markus Antonius-ku pasti menjadi penawar hari ini.”
Jadi kawan, sekitar awal semester 5, Shiela sempat drop. Aku bisa melihat itu, ketika bersitatap wajah dengannya, pembawaannya tidak biasa. Ketika kunekatkan diriku untuk men-chat-nya, akhirnya Shiela bercerita panjang lebar.
“Astaga, waktu itu aku benar-benar drop Azk. Nilaiku menurun, melewati standar tinggi yang telah ditetapkan untukku. Aku merasa ini bukan diriku. Aku merasa telah melakukan sesuatu hal yang nista, dan membuat semua orang tidak menghargaiku lagi.”
“Sekarang masih?”
“Alhamdulilah. Tidak lagi Azk. Kalimat-kalimatmu hari itu, benar-benar membekas di benakku. Jadi kurasa, terima kasih Azk.”
Dia menutup kalimat dengan senyumnya yang amat menawan. Aku skakmat saat itu juga.
Mozaik 20
Tiga Watak Berbeda
Ini kisah aku, Lia dan Nasri.
Aku sudah mendeskripsikan tentang banyak hal. Aku sudah cerita tentang Quart School, aku sudah cerita tentang Aram dan Wahid, soal Ibu Qotrun, soal Syifa, banyak lainnya. Alangkah keterlaluannya aku jika tidak mencoba menceritakan diriku sendiri.
Namaku Humadi Azka.
Menurut hematku, sekaligus untuk memudahkan jika sekiranya nanti cerita ini dikutip untuk jadi soal Bahasa Indonesia, aku deskripsikan watakku sebagai orang baik, ambisius, sombong sekaligus pesimistis. Bagaimana bisa begitu, aku tidak terlalu mengerti kawan. Tapi aku bisa merasakan bahwa beberapa sifatku itu saling bergantian mengambil alih diriku. Aku merasa berkepribadian ganda.
Hei katakan padaku, penulis novel mana lagi yang berkepribadian ganda, dan mengaku dia berkepribadian ganda. Jika kamu temukan kawan, nanti kuajak engkau minum di Kedai Kopi Paman Pirates.
Sudahlah kawan, lupakan.
Aku pernah bertanya pada Lia, tentang bagaimana penilaiannya padaku, sejujur-jujurnya. Dan begini katanya.
“Kamu itu cerdas, ramah, baik hati, penyabar, asyik dan setia.”
Tidak setitik pun dia menceritakan keburukanku. Aku salut dengan Lia.
“Oh ya, setia?”
“Iya Az. Lihat kamu sekarang. Tetap bersikeras bertahan walau telah disakiti berkali-kali. Walau tidak ada kepastian akan mendapatkan orang itu.”
Aku berdecak.
Lain aku, lain lagi Lia. Sahabatku itu sangat ekspresif dan periang. Lia juga sangat easy going saat diajak ngobrol, sering melontarkan kalimat lucu nan absurd. Ke-absurd-an yang sama, yang mengikat persahabatan kami.
Lia akrab dengan beberapa cowok. Selain aku, masih ada Nasri. Di semester 4, Nasri sempat dekat dengan Mei, sedangkan aku masih menyukai Syifa. Saat-saat itulah kami menikmati asyiknya segitiga persahabatan paling kocak sekaligus paling kuat yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.
Kau tahu kawan, ya Nasri menyukai Mei. Mereka berdua sempat berhubungan sangat dekat, tapi aku tidak menyorot mereka dalam ceritaku. Dalam cerita mereka, Lia adalah wasit yang menengahi hubungan antar insan itu.
Nasri sendiri memiliki watak yang keras, keras kepala sekali dia itu. Juga teramat misterius. Tidak ada yang pernah tahu, apa isi kepalanya yang sebenarnya. Hubungannya dengan Mei, itu adalah satu keajaiban yang kukira tidak pernah hinggap di kehidupan sang profesor. Nasri ternyata bisa jatuh cinta.
Suatu hari, Nasri sempat bertanya padaku.
“Az, bagaimana cara membuatmu marah?”
Aku menyernit kening, itu bukan suatu pertanyaan yang kubayangkan bisa keluar dari mulut Nasri. Tapi kujawab juga.
“Sakiti aku secara sentimentil.” Sejatinya tidak ada yang tahu bagaimana definisi sentimentil itu, bahkan aku sendiri. Nasri manggut-manggut.
Kawan, mungkin saat ini engkau belum mengerti apa yang sedang kuceritakan. Tapi cukup bagi engkau untuk mengingat kepribadian gandaku, sifat Lia yang periang dan ramah pada sahabat-sahabatnya, serta Nasri yang misterius dan tidak bisa ditebak.
Ketiga watak itu akan berkelindan di suatu masa yang akan datang.
Mozaik 21
Ini Antara Azka, Lia dan Nasri
Hari ini, Bu Jannah membagi kami dalam beberapa kelompok, alasan klasik beliau, memudahkan beliau mengajar. Kalau aku boleh melakukan pembelaan, kerja kelompok semacam ini, adalah solusi baik satu arah. Enak bagi guru, tapi membawa akibat tidak menyenangkan bagi para murid.
Tapi aku tidak hirau dengan pembelaanku sendiri. Karena setelah undian kelompok ditentukan, sesuatu yang sejak lama kuimpikan akhirnya tercapai. Aku satu kelompok dengan Lia.
Walau tidak eksklusif. Nasri masuk kelompok yang sama. Beberapa orang kulihat merinding. Azka dan Nasri masuk kelompok yang sama, itu ibarat Ronaldo dan Messi bermain dalam satu tim.
Sengaja benar, aku menyisakan satu kursi kosong, khusus untuk Lia. Kursi itu menghadap padaku (kami duduk membundar). Hei, momen satu kelompok dengan Lia, itu spesial kawan.
Eh tahu-tahunya dia malah menarik satu kursi dan duduk di sebelah Nasri. Aku berdecak. Satu, aku tidak tahu kenapa aku begitu kesal melihat mereka duduk berduaan, dua, kelas ini panas. Ekonomi bukan pelajaran kesukaanku, dan sudah terlalu terlambat untuk kabur sekarang.
Pernah juga, satu kelas ramai gara-gara terjebak di kelas matematika. Jadi saat itu, hujan mendera Quart School, hujan yang betul-betul deras. Seluruh siswa terjebak di dalam kelas, tidak bisa kemana-mana, tanpa resiko basah. Di dalam jadwal, mantap tertulis, ini jam kelas matematika. Pak Farhan adalah pengajarnya.
“Mungkin beliau juga tidak akan masuk,” ujar Aram, menenangkan kerisauan hatinya.
“Pasti, hujan sangat deras, beliau tidak akan bisa menerobos. Kecuali benar-benar nekat.” Wahid turut menyumbangkan analisisnya. Sayang sekali, dia lupa, Pak Farhan adalah salah satu dari 30 orang paling nekat di dunia saat ini. 29 lainnya adalah kami-kami yang nekat masuk kelas matematika ini.
“Assalamualaikum. Maaf semua, kalau bapak membawa basah kemari.”
Tiba-tiba saja, tidak ada yang tahu bagaimana caranya, Pak Farhan sudah muncul di depan kelas kami, meletakkan payung, mengibas-ngibas sandal jepitnya. Beliau menerobos hujan.
“Astaga, hujannya deras sekali. Untung saja, ada jalur rahasia yang bisa diperhitungkan untuk menuju ke mari.”
Kami memperhatikan beliau lekat-lekat. Pak Farhan dengan santai mengelap wajah dan rambutnya yang basah. Beliau bahkan melepas sandal dan memilih bertelanjang kaki. Benar-benar guru yang nyentrik.
“Murid-murid sekalian. Bapak tidak akan repot-repot menerobos hujan, jika bapak tidak memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibagi pada kalian. Ini soal matematika yang sangat fresh untuk kalian. Baiklah, akan segera bapak tulis.”
Aram dan Wahid menegak liur. Adalah sesuatu yang sangat langka, dimana mereka terjebak dalam kelas Pak Farhan. Guru nan nyentrik itu selesai menulis soal. Kemudian beliau berbalik. “Di sini ada dua soal, nah bapak akan mencontohkan satu soal, lalu kalian kerjakan satunya. Sepakat?”
Seisi kelas hening.
Pak Farhan tidak terlalu peduli, beliau fokus mengerjakan soal. Dengan rangkaian yang sangat rumit, melibatkan aljabar, logaritma, matriks dan istilah-istilah pertanian. Kawan-kawanku yang tidak biasa terjebak di kelas matematika, seketika terkesima dengan cara-cara yang ditunjukkan Pak Farhan. Seolah-olah angka-angka itu muncul begitu saja dari teknik-teknik beliau.
“Sekarang giliran kalian,” ujar beliau tersenyum. Kemudian berlalu. Semua orang di kelas sudah terjebak dan tertantang untuk mengeluarkan kemampuannya menjawab soal itu. Sebagian lainnya, sudah mulai berteriak, “AZKA!! Bantu kami mengerjakan soal ini.”
Aku tersenyum simpul. Saatnya master matematika bekerja.
Aku mengajari hampir setiap orang. Sebutan hampir itu berubah menjadi ironi karena orang yang tidak kuajari hari itu, justru adalah orang yang paling kuharapkan. Dahlia Anggraini. Tak sekalipun dia mampir ke mejaku untuk bertanya. Pelan-pelan, saat pulang kutanya dia. Secara terselubung tentu saja.
“Oh tadi, aku minta diajari Nasri. Kamu kelihatan sibuk sekali Az. Aku tak tega memotong penjelasanmu pada mereka,” jawab Lia tanpa dosa.
Aku berdecak sebal dalam hati. Nasri?
Keesokan harinya, aku berangkat sekolah pagi-pagi sekali. Maksud hati ingin duduk santai di lokal 4, mencari inspirasi untuk menulis cerita. Siapa sangka Lia sudah duduk di sana, sarapan. Ingat ya, niatku dari rumah itu tulus ingin mencari inspirasi. Perkara duduk di sebelah Lia itu, bukan urusanku. Itu adalah urusan Tuhan.
“Apa itu Az?” tanya Lia saat aku mendekat, membawa lembaran helai kertas F4.
“Rancangan novelku. Aku ingin kamu memberikan review sebelum aku tulis.”
“Sini, coba lihat.” Lia menghentikan sendoknya sementara, fokus pada kertasku.
Aku diam, mengamati wajahnya yang tengah membaca penuh kekhusyukan. Detik-detik alam semesta melambat.
“URANG-URANG BANJAR,” Lia membaca judul novelku dengan suara agak keras, “sepertinya ini novel budaya ya Az?”
“Iya, novel ini akan menggambarkan kehidupan masyarakat Banjar yang unik dan berbeda dengan masyarakat lainnya. Genrenya bercampur antara sosial dengan komedi.”
“Unik ya, unik apa nih?”
Baru saja aku hendak membuka mulut, saat kemudian Nasri muncul. Wajahnya agak murung. Aku tidak heran, angin menjelang bulan Desember agak dingin, alam terasa kelabu. Mungkin itu mengusik mood sang profesor.
Dia mendekati kami yang tengah duduk bersebelahan. Melambaikan tangan padaku, salam penghormatan. “Hai Li, sepertinya itu sarapan yang enak.”
“Eh iya Nas.”
“Seperti orang Jepang.”
“Memangnya orang Jepang makan seperti ini?”
Nasri terkekeh. Sikapnya aneh sekali.
Lama-lama Lia dan Nasri asyik mengobrol soal Jepang. Aku yang pertama datang, tersingkirkan.
Kejadian itu mengirim semacam pukulan telak ke otakku. Pasca kejadian hari itu, aku demam.
Tentu saja kawan, tentu saja Lia kembali memperhatikan aku begitu tahu aku jatuh sakit. Dia ingatkan aku untuk makan, untuk minum obat, dan segala tetek bengek lainnya yang apabila kutulis, akan terasa betul perhatiannya.
“Apa yang terjadi di sekolah? Apakah ada tugas?” aku bertanya padanya.
“Tidak ada Az. Hari ini Bu Jannah menyuruhku me-fotocopy-kan bukunya yang tebal itu, untuk kawan-kawan sekelas.” (Lia mempunyai bisnis fotocopy di rumah kakaknya).
“Oh ya, lalu bagaimana kamu membawa buku-buku sebanyak itu nanti?”
“Nah itu makanya aku juga bingung Az. Padahal seandainya kamu ada, aku bisa minta dijemput.”
“Aku bisa kok menjemput kamu.”
“Kamu sedang sakit Az. Jangan dipaksakan. Biar nanti aku cari bantuan lain. Mungkin Nasri bisa membantu.”
Entah kenapa kepalaku makin panas.
Mozaik 22
Trik-trik Ibu Qotrun Nada
Kemarin-kemarin itu, aku sakit gara-gara terlalu banyak memikirkan Syifa, dan Lia datang membawakan obatnya, kali ini situasi terbalik. Aku sakit karena terlalu banyak memikirkan Lia, dan (seharusnya) Syifa adalah obat terbaiknya. Itu logika matematika sederhana.
Masalahnya mendatangkan Syifa ke hidupku sekarang, tidak sesederhana mencari tahu asal alam semesta.
Kecuali Tuhan mencampurkan tangan ke dalam urusan ini.
Ibu Qotrun Nada juga memperhatikan siklus kesehatan anak muridnya ini. Itu tidak mengherankan, karena jika aku absen, maka rohis kurang satu orang. Pembahasan kajian tidak akan seramai jika aku bergabung. Jadi malam ini, beliau mengirimiku chat.
“Anak didik kebanggaan ibu sakit apa?”
Astaga, aku menghela nafas. Sebaris chat dari Ibu Qotrun itu saja sudah membawa keriangan tersendiri di dalam jiwa. Beliau membanggakan aku? Jangan bercanda, Ibu.
“Azka cuma kelelahan Bu. Sudah biasa ini.”
“Lho lelah kenapa nih, apa karena rohis pulang telat terus?”
“Tidak bu, ada banyak hal lain yang Azka kerjakan, terlalu memforsir tenaga sepertinya.”
“Ah masa sih. Apa jangan-jangan batinnya yang lelah karena tidak ketemu-ketemu dengan kekasihnya.”
Aku berdecak sebal. Ibu Qotrun Nada sengaja menggodaku. Katakan padaku kawan, di belahan dunia mana lagi, ada guru macam beliau ini.
“Mungkin juga Bu.” Aku membenarkan. Hatiku tidak bisa berdusta.
“Ya sudah. Tidak seru kalau Azka sakit-sakitan begini. Nanti Ibu bantu supaya kamu bisa ketemu dan ngobrol dengan Syifa. Jadi cepat sembuh ya.”
Sungguh Tuhan telah ikut campur dalam urusan ini. Penyembuhanku berlangsung sangat cepat.
Hari pertama setelah kesembuhanku adalah hari kelas bersama Bu Jannah. Kelas bersama yang panas dan sumpek. Aku berusaha duduk tenang. Syifa berada di pojokan yang berbeda denganku. Aram tidak tertarik bergosip, dia melotot memandangi Bu Jannah. Hanya Wahid yang berkomentar ringan, “Az, itu bebeb Syifa. Tidak mau disapakah?”
“Tidak deh.” Aku menggeleng rendah, lalu diam.
Bu Jannah langsung menerangkan teori-teori ekonomi yang paling beliau kuasai. Aram membuka buku catatannya, menggambar. Aku sesekali menelungkupkan kepala. Fisikku rasanya masih lemah hari ini. Apalagi setelah menyimak pelajaran sejak pagi hari tadi.
Adalah suara Pak Hadi yang menyela suasana kelas. Beliau datang sambil membawa catatan kecil. Setelah meminta izin secara takzim pada Bu Jannah, Pak Hadi menyampaikan maksudnya.
“Humadi Azka, dan Nur Syifa Muliyana dipanggil ke ruangan Ibu Qotrun Nada.”
Beberapa siswa, terutama yang tidak tahu menahu tentang urusan ini, menyangka aku dan Syifa terkena masalah berat. Ibu Qotrun Nada sekarang adalah Wakasek Kesiswaan, dan tidak ada yang masuk ke ruangan Wakasek Kesiswaan kecuali masalahnya benar-benar besar.
Bu Jannah tersenyum simpul, “silahkan kepada Azka dan Syifa untuk memenuhi panggilan itu. Sepertinya penting.”
Aku berdecak. Sebagian hatiku senang. Ini adalah trik-trik yang dijalankan Ibu Qotrun sebagaimana yang beliau janjikan. Adapun mengapa Pak Hadi terlibat dalam urusan ini, adalah bagian dari karakter Ibu Qotrun Nada yang dramatis.
“Azka, Syifa, maaf sebelumnya memanggil kalian secara mendadak. Apakah kalian sibuk?”
“Eh kami tadi sedang ada kelas Bu.” Itu Syifa yang menyahut. Ibu Qotrun memasang wajah bersalah.
“Ya sudah. Duduk dulu. Ada yang ingin Ibu sampaikan. Ini terkait mata pelajaran PKN yang ibu pegang.”
Alhasil, aku dan Syifa duduk bersebelahan menghadap Ibu Qotrun Nada. Cukup dekat, untuk parfum Syifa, mampir di hidungku.
“Ibu tidak yakin bisa masuk atau tidak di sisa semester. Ternyata tugas Wakasek benar-benar banyak dan membuat Ibu kesulitan memanajemen waktu. Pantas saja, dulu Bu Hartini lebih sering memberi tugas. Nah Ibu sepertinya terpaksa mengikuti jejak beliau, setidaknya sampai sisa semester ini. Mungkin nanti di semester 6 akan ada guru pengganti.”
“Jadi apa tugasnya Bu?” Syifa bertanya. Nampaknya dia tidak terbiasa meninggalkan kelas di jam pelajaran.
“Ini bahannya,” Ibu Qotrun menunjuk setumpuk kertas, “kalian bagikan ke teman-teman. Sudah ada instruksinya kok di situ. Kalau ada kesulitan, nanti teman-teman bisa lapor pada kalian, dan kalian bisa lapor pada Ibu. Oke?”
“Siap Bu. Terima kasih.” Syifa segera mengambil kertas-kertas bagiannya. “Kami izin kembali ke kelas ya Bu.”
“Iya Syif silahkan.”
Aku menarik nafas. Andai saja, momen ini bisa lebih panjang.
Sebelum aku genap keluar dari ruangan beliau, Ibu Qotrun sempat berbisik. “Selamat ya Az, senang gak, duduk bersebelahan dengan Syifa?”
Aku mengangguk.
“Tuh cepat dikejar Syifanya. Mungkin kalian masih bisa ngobrol satu atau kata di lorong.”
Aku segera tersadar oleh teguran dari Ibu Qotrun Nada. Ada sepanjangan lorong menuju lokal 4, kesempatan aku mengobrol dengan Syifa. Tak boleh kusia-siakan. Lalu tanpa mengingat betapa aku salting biasanya di depan dia, aku mengejar Syifa.
Bisa kudengar Ibu Qotrun tertawa terpingkal-pingkal.
“Syif,” akhirnya aku bisa menyapanya. Menyejajarkan langkahku dengan dia. Kami berjalan di lorong.
“Iya Az,” dia menjawab pendek.
“Apa kabar Syif?”
Susah payah aku mengarang topik dalam keadaan serba cepat, tapi gagal. Akhirnya yang keluar malah kalimat yang klise.
“Kabarku baik Az. Kamu sendiri bagaimana?”
“Sudah lumayan baik Syif.”
“Oh iya, kudengar, kemarin-kemarin kamu sakit ya?”
Alamak, dia memperhatikan aku.
“Eh iya Syif. Tapi sekarang sudah sembuh sih.”
“Jaga dirimu Az. Sebentar lagi Uji Test Semester 5 lho.”
Aku lagi-lagi hanya bisa terkekeh. Setiap ucapanku, tersekat di tenggorokan. Tapi tidak apa-apa. Sepanjang lorong ini telah bersaksi, dalam beberapa menit yang krusia, Syifa kembali menjadi Syifa yang kukenal. Syifa yang hangat dan menyenangkan.
Mozaik 23
Taktik Promosi Paman Pirates
Tiga hari lamanya, aku harus menghindari kopi demi larangan dari dokter. Sekarang di hari keempat, etis kiranya jika aku menghindari larangan dokter demi secangkir kopi. Kopi Hindi dari kedai Paman Pirates.
Paman Pirates menyapaku dengan aksen senang. Aku memesan kopi Hindi satu cangkir, dan mencomot bakwan edisi 1000 peraknya. Paman Pirates dengan gesit meraup kopi dari toples, kemudian mengguyur sesuatu dari ceret yang senantiasa mengepul, cangkir terisi setengahnya, lalu setengah lagi, ditambah air dalam termos.
Jadilah, kopi Hindi versi Jumbo. Cangkir besar. Heran aku. Jelas aku tidak keberatan dengan porsinya, tapi keberatan dengan harganya. Satu gelas Kopi Hindi biasa, dibanderol Paman Pirates 2 ribu rupiah, sedangkan yang versi Jumbo 3 ribu rupiah. Sedikit penambahan yang berbahaya bagi uang sakuku.
“Tidak apa-apa Az, versi jumbo harga biasa. Sesekali aku bagi promosi untuk pelanggan paling potensialku ini.”
“Pelanggan potensial, Paman?” aku menyernit dahi. Kata-kata “potensial” selalu berakibat panjang ke belakang.
“Iya, kalau ada kau, biasanya kedaiku lebih ramai.”
“Mana ada begitu Paman.” aku tertawa kecil.
“Ada-lah Az. Hanya kamu satu-satunya orang di sekolah ini yang punya akses ke bintang iklan Quart School.”
Paman Pirates pasti bicara melantur. Asap dari rempah-rempah pasti membuatnya berhalusinasi. “Jangan aneh-aneh, Paman.”
“Astaga Az, kau kira aku mengada-ngada. Baik, begini saja. Kau masih berteman dengan Shiela Camalia bukan?”
Aku manggut-manggut. Seketika urusan menjadi terang. Bintang iklan itu tentu saja Shiela.
“Nah, kau bebas memesan apa saja gratis dari kedaiku ini, selama kau bisa membawa Shiela bersamamu.”
Aku mengulum senyum. Segera menjabat tangan Paman Pirates. Tanda kesepakatan kami. Kau tahu kawan, pada titik-titik tertentu, makan gratis di warung kopi bisa sama berbahayanya dengan kasus korupsi.
Lihat saja Paman, aku akan mengajak Shiela datang ke kedai Paman.
Malam itu, aku pantau WA Shiela. Informasi yang kudapat dari terakhir kali dilihat-nya, dia tidak aktif selama berhari-hari. Sejak dua minggu yang lalu. Ragu-ragu kukirimi dia chat. “Shie.”
Semenit kemudian langsung berbalas. “Punii.”
Hei dia aktif kok.
Shiela segera memberi alasan saat kutanya perihal “terakhir kali dilihat”-nya tadi. “Aku hanya aktif jika itu penting Azk.”
“Jadi aku ini penting?”
“Biasanya apa yang datang dari kamu penting.”
“Aku mau bercerita Shie. Ada sedikit beban yang harus kubagi denganmu.”
“Oh boleh Azk. Silahkan saja, mau lewat chat, telepon atau video call?”
“Tidak Shie. Aku mau bicara secara langsung.”
“Oh boleh juga Azk. Tentukan saja tempatnya.”
“Sepulang sekolah, di kedai kopi Paman Pirates.”
“Sepakat.”
Jika caranya benar kawan, tidak sulit membujuk Shiela untuk sekedar bertemu, atau bahkan mengobrol asyik. Aku bersorak dalam hati, besok aku akan dapat Kopi Hindi gratis.
Paman Pirates muram ketika melihat aku datang berjalan beriringan dengan Shiela ke kedainya saat pulang sekolah. Kuterjemahkan sinyal-sinyal di raut wajahnya itu sebagai astaga Azka, iya sih kau bawa dia kemari. Tapi kenapa di saat hendak pulang sekolah begini.
Aku kirimkan balik sinyal dari raut-raut wajah yang artinya kurang lebih begini, sudah paman, namanya juga dia introvert. Mana tahan kalau orang ramai.
Setengah tidak ikhlas Paman Pirates menghidangkan kopi untuk kami berdua. Aku mempersilahkan Shiela menyesap dari cangkirnya lebih dulu. Seteguk dia minum, yang aku tahu satu teguk itu sudah membawanya ke alam kewangian rempah-rempah.
“Bagaimana rasanya Shie?”
“Enak Azk. Rasa rempah-rempahnya sangat menonjol, beda dengan kopi yang sebelumnya pernah kuminum di sini.”
“Itu kopi Karibia. Ini namanya kopi Hindi.”
“Nama-nama yang menarik. Paman Pirates nampaknya sangat kreatif dalam memilih nama-nama.”
Paman Pirates yang tadi bermuka masam, agak tertawar mendengar puji-pujian dari Shiela.
“Jadi apa yang hendak kamu ceritakan Azk?”
Baru saja aku ingin membuka mulut, saat tiba-tiba telepon Shiela berdering. Dengan posisi teleponnya yang terbuka di atas meja, aku bisa lihat itu, telepon dari OSIS.
“Astaga, kenapa tiba-tiba mereka menelepon,” Shiela berdecak.
“Angkat saja, Shie.”
Shiela berbicara di telepon. Sepertinya serius. Setelah selesai, dia memandangi aku dengan tatapan menyesal. “Maafkan aku Azk, tapi ada panggilan yang mengharuskan aku meninggalkanmu di sini. Kamu keberatan jika pembicaraan kita ditunda?”
Mozaik 24
Misi untuk Shiela
Usahaku mengajak Shiela ke kantin kemarin, tidak hanya berlandaskan kopi gratis Paman Pirates, aku sebenarnya memang menyimpan sesuatu yang ingin kusampaikan pada Shiela, sebuah permintaan, sebuah misi.
Hanya saja, aku terpaksa kecele, karena Shiela keburu dipanggil oleh pejabat OSIS. Terpaksalah, pembicaraan kami ditunda. Aku seggera mengatur janji temu baru, di tempat baru, Kafe Sahajaku.
Aku memilih tempat duduk agak di belakang, tapi aku mengarahkan pandangan ke pintu depan. Dengan begitu, aku bisa memantau siapa saja yang keluar masuk dari kafe ini.
Ketika Shiela masuk, aku melambaikan tangan. Menandakan kehadiranku. Dia mengangguk, lalu berjalan menghampiriku. Kawan, biar kuberitahu, melihat gadis secantik Shiela datang menghampirimu, sensasinya sangat ganjil.
“Kuharap kamu tidak menunggu terlalu lama, Azk.”
“Tentu tidak. Aku berharap aku tidak mengganggumu hari ini, Shie.”
“Tidak apa-apa Azk, anggap saja ini ganti hari kemarin yang tertunda. Jadi ada apa sebenarnya Azk?”
Astaga, Shiela langsung menusuk ke topik. Tidak bisakah kita mengobrol sebentar tentang basa-basi Shie. “Aku ingin minta tolong,” ucapku.
“Oh boleh saja Azk. Selama itu bukan pertolongan membongkar makam Tutankhamun, atau sejenisnya, kukira aku bisa membantumu.”
Aku menggeleng lucu. Shiela selalu mengeluarkan joke yang anti-mainstream.
Perlahan-lahan kuceritakan apa yang sebenarnya terjadi padaku, Lia dan Nasri. Kenapa bisa-bisanya aku merasa cemburu pada mereka berdua, dan kenapa Nasri seperti ingin menelikungku dari belakang. Shiela mengangguk. Dia menyimak.
“Baiklah Azk,” katanya sambil mengusap wajah setelah aku selesai bercerita, “ini masalah yang cukup rumit. Memiliki masalah dengan sahabat dekat, itu adalah mimpi buruk. Apalagi kalau sudah menyangkut cinta. Astaga, cinta. Kau tidak boleh sampai membenci Nasri Azk, dia sahabatmu.”
“Aku rasa aku mulai membencinya.”
“Baiklah, apa yang kamu ingin aku lakukan terkait masalah kamu ini?”
“Aku ingin kamu temui Nasri, tanya pada dia baik-baik. Apa yang sebenarnya menjadi masalah dia, sehingga dia seolah-olah mengusik kebahagiaan Azka.”
“Astaga Azk, itu misi yang sulit. Aku bukan siapa-siapa di kehidupan Nasri. Apa yang bisa kulakukan?”
“Kau bisa melakukan ini Shie. Dulu kudengar kamu pernah makan semeja dengan Nasri.”
“Baiklah Azk. Untung saja kita berteman dekat. Beri aku waktu 4 hari untuk mencoba menyelesaikan misi ini.”
Pertemuan di Sahajaku berakhir begitu saja.
Aku menunggu sambil harap-harap cemas. Tiga hari penuh aku berkutat dengan rasa penasaran. Hari ini Shiela akhirnya mengirimiku pesan. “Aku ingin bertemu di perpustakaan daerah, membicarakan misi yang kamu berikan.”
Akhirnya Shiela.
“Jadi bagaimana Shie?”
Aku langsung mendesak begitu aku melihat dia duduk di salah satu kursi di pojokan. Shiela tersenyum tipis. “Sabar Azk. Duduk dulu,” ucapnya sambil memperbaiki posisi kerudungnya. Bagiku itu membuat Shiela bertambah anggun.
“Pertama Azk,” ujar Shiela, “aku tidak berhasil menemui Nasri.”
Kalimat pertamanya itu, langsung membuatku terpukul. “Bagaimana bisa Shie?”
“Maaf Azk. Kamu mungkin tahu, seberapa sulitnya sahabatmu itu diajak bertemu. Dia selalu menghindar. Ada saja alasannya. Entah malas atau sibuk.”
“Berarti misi ini gagal Shie.”
“Maafkan aku Azk. Tapi aku ada sedikit saran untukmu, supaya hati kamu jadi lebih tenang.”
Aku mengangguk.
“Kendalikan perasaanmu Azk, Lia itu cuma batu sandungan, atau malah pelampiasan perasaanmu. Aku memang belum tahu, siapa sebenarnya cinta yang menetap di hatimu, tapi aku rasa itu bukan Lia. Nah jangan kamu gadaikan cinta main-mainmu ini untuk persahabatan kalian yang kokoh.”
“Tapi ini bukan cinta main-main, Shie.” Bagaimana pula rasa berdebar-debar setiap dekat dengan Lia itu hanya main-main.
“Aku tidak merasa demikian Azk. Menurut hematku, jika kamu tidak menyelesaikan perasaanmu ini segera, akan ada sesuatu yang besar terjadi di masa depan.”
Aku berdecak sebal. Dasar Shiela. Pelajaran moral yang bisa kutarik dari hal ini, adalah, jangan coba-coba minta saran pada orang cerdas. Karena seringkali saran dari mereka tidak simpatik, dan lebih buruk, bisa benar-benar terjadi.
Mozaik 25
Event Besar Tiga: Party Class
Aku sudah bersepakat dengan diriku sendiri, agar tidak usah bercerita tentang Uji Test semester 5, melainkan hanya Party Class saja. Party Class pertama di bawah kendali Ibu Qotrun Nada. Seperti yang seharusnya terjadi, beliau berpidato di atas podium.
“Ibu sudah baca bagaimana sejarah event ini,” buka beliau, sambil senyum ke seluruh siswa pendengarnya, “sungguh event yang mulia. Baik, karena hari sangat panas, Ibu sebagai koordinator penyelenggara, akan memaparkan skema Party Class, seminggu dari sekarang. Mengapa dari jauh-jauh hari, karena Ibu ingin kalian bersiap-siap menghadapinya.”
Jakun Aram naik turun mendengar frasa “bersiap-siap” itu. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda dan merepotkan di Party Class kali ini. Apakah itu artinya Bu Hartini sukses ikut campur kali ini?
“Ibu punya terobosan baru dalam event ini, namanya Party Class Show. Jadi nanti, akan didirikan panggung di tengah-tengah lapangan sana, panggung untuk pentas pertunjukan kalian. Setiap lokal dituntut untuk menunjukkan show terbaik dan terheboh yang bisa dilakukan. Nanti ada piala dan hadiah untuk Show terbaik dari yang terbaik. Ini semacam kontes.”
Kami riuh bertepuk tangan. Nah yang seperti ini baru menarik.
Segera setelah Ibu Qotrun selesai menyampaikan pengumuman dan ide beliau, kami lokal 4, langsung menggelar rapat informal. Beragam usul berlompatan. Aram menjabat sebagai moderator dan pemimpin rapat yang semau dia sendiri.
“Kita tampilkan nasyid.”
Kena blacklist Aram.
“Kita tampilkan kemampuan tarik suara kita.”
Kena blacklist juga.
“Kita pakai pidato saja.”
Aku panas dingin mendengar usul itu. Beruntung Aram mengibas tangan. Usul itu terlalu remeh baginya.
“Kita gelar pertandingan catur, menang jadi Tuhan.”
Segera kutampar mulut tak tahu diuntung itu. Terlalu cepat menuju ke situ.
“Lalu apa Ram, yang harus kita tampilkan. Kau sendiri punya usulan?” Wahid bertanya, setelah tiga usulannya dipatahkan Aram. Si pemimpin rapat itu tersenyum. “Kita harus menampilkan sesuatu yang beda, sesuatu yang menghebohkan, sesuatu yang mampu membuat mulut siapa saja, menganga.”
“Apa itu?”
“Kuncinya adalah diriku. Silatku. Hanya itu yang cukup pantas mewakili lokal 4.”
Apa kataku, Aram semau dia saja.
Tapi yang dikatakan Aram benar juga. Silat merpati cocok untuk Party Class Show itu. Silat itu menakjubkan, membuat sang pesilat terlihat seperti orang sakti. Sekarang, di seantero sekolah, kurasa cuma Aram yang masih konsisten memegang sabuknya. Tak sabar aku melihat Aram memecahkan beton dengan kepala.
Satu minggu berlalu dengan lambat. Aram dan yang lainnya sibuk mempersiapkan detail-detail kecil menjelang tampil. Aram bahkan sudah mengangkut beberapa keping besi, keping baja, dan beton sepanjang 1 meter ke lokal 4. Persiapannya sempurna.
Hari Party Class tiba. Seisi sekolah bersuka cita. Hawa pesta pora memang lekat dengan event ini. Sudah beberapa lokal menampilkan show terbaiknya. Wahid yang mengklaim diri sebagai manajer bagi Aram, sibuk memantau di bawah panggung. Matanya terpana ketika ada salah satu adik tingkat kami yang juga menampilkan silat. Meski cuma menampilkan teknik, bukan unjuk kebolehan macam Aram nantinya.
“Ah itu biasa,” ujar Aram santai. Dia naik ke panggung begitu dipanggil. Timnya, yaitu aku, Wahid dan beberapa lainnya membantu Aram mengangkat perkakasnya ke panggung, melakukan penataan.
Wahid sekarang merangkap sebagai host. “Ya kawan-kawan, kita akan segera menyaksikan ahli silat dari Lokal 4 Quart School, yaitu Faddil Al-Aram beraksi. Dia akan mematahkan batangan besi ini, kawan-kawan. Astaga, batangan besi ini keras sekali.”
TENGGG TENGGG
Wahid memukul dua batangan besi. Mendemonstrasikan betapa kerasnya benda itu. kemudian dia segera memasangnya di tiang penyangga. Aram yang sudah berganti pakaian, mendekat, “pakai apa?” isyarat Wahid. Aram mengangkat tangannya. Itu artinya dia akan mematahkan besi itu dengan tangannya. “Hanya memakai tangan kawan-kawan semua. Beri tepukan yang luar biasa untuk pesilat kita ini.”
Tepukan tangan dari adik-adik lokal kami riuh terdengar. Mereka yang baru masuk Quart School memang telat melihat penampilan sehebat ini.
BATANGAN BESI ITU TERPOTONG DUA DENGAN SEMPURNA, HANYA DENGAN SEKALI PERCOBAAN KIBASAN TANGAN ARAM, KAWAN-KAWAN!!
Tepukan tangan mulai membahana. Aram menerima aplaus dengan senyum mengembang. Wahid menarik nafas, “Kawan-kawan, luar biasa. Sepertinya batangan besi ini tidak ada apa-apanya bagi pesilat kita yang tangguh. Sekarang dia akan coba memotong batangan baja ini. Apakah dia bisa? Batangan baja ini 5 kali lebih kuat daripada besi sebelumnya. Bisakah Aram memotongnya.”
Batangan baja segera dipancang di atas tiang penyangga. Aram menunjuk sikunya. Wahid segera paham, “kawan-kawan, pesilat kita akan menggunakan sikunya untuk mematahkan batangan baja ini. Luar biasa kawan-kawan. Mungkin dia bukan pesilat saja, dia adalah pendekar dari kuil China.”
Aram mengambil posisi, menarik nafas, dan menghujamkan sikunya tanpa ampun ke batangan baja itu. LUAR BIASA. Batangan baja itu terbelah dengan cantik. Serupa potongan gabus saja.
Penonton semakin riuh bertepuk tangan.
“Luar biasa penonton sekalian,” Wahid sebagai host makin berkoar-koar, “batangan baja nan keras itu terpotong dengan sangat mudah di tangan pendekar kita. Tantangan berikutnya haruslah lebih menantang lagi. Apakah kawan-kawan penasaran benda apa yang berikutnya dipatahkan pendekar kita?”
Penonton menunjuk-nunjuk potongan beton sepanjang satu meter yang segera diambil Wahid. “Ini?” Wahid bertanya. Kemudian dia sendiri menggeleng suram, “ini tidak lebih keras daripada batangan baja barusan penonton sekalian.”
Aram mendekati Wahid, berbisik-bisik. Menunjuk tiang penyangga, dan menunjuk dahi. Aku berfirasat, ini adalah penampilan penutup Aram hari ini. Wahid mengangguk. Pelan-pelan dia memasang 4 lapis potongan beton itu di tiang pancang. “Ya penonton, 4 lapis barulah menantang bagi pendekar kita yang perkasa.”
Penonton semakin antusias ketika Wahid menyiram suatu cairan ke atas 4 lapis beton itu. Lalu menyulut api ke atasnya. Beton-beton itu kini menyala berkobar. Wahid tersenyum simpul ke arah penonton.
“Inilah aksi terbaik yang bisa diberikan pendekar kita. Luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama.”
Aku tidak sempat melihat kelanjutan aksi Aram hari itu, karena mendadak ada seseorang yang mendekatiku, kemudian memanggil namaku lembut, “Az.”
Aku menoleh. Dan alamak, Syifa telah berdiri di sana. Aku tergagap. “Ada apa Syif?”
“Ibu Qotrun memanggilmu, kamu diminta datang ke ruangan beliau.”
“Oh iyakah, baik. Aku segera ke sana, terima kasih Syif.”
Aku masih memasang wajah cengengesan pada Syifa sepanjang jalan. Memang ada-ada saja strategi yang dipikirkan Ibu Qotrun Nada.
Beliau menunggu di ruangan, dengan tawa tergelak.
“Ibu membuat dia terlihat malu.”
“Astaga Az, Ibu hanya ingin membantumu agar bisa ketemu dan berbaikan dengan Syifa. Jadinya gimana tadi? Apakah sudah berbaikan?”
“Belum Bu. Ngobrol saja Azka tidak bisa.”
“Sabar ya Azka, semuanya akan ada waktunya. Oh ya, sekali lagi Ibu ingatkan, kamu jangan cepat salting di depan dia. Itu tidak baik.”
Aku meninggalkan ruangan Ibu Qotrun dan menutup hari Party Class dengan satu kesimpulan sederhana: Ternyata Aram bukan hanya pesilat, pendekar dari pedalaman China, tapi dia juga pemadam kebakaran.
Mozaik 26
Kisah Pedalaman Hati Wahid
Beranjak dari Party Class, kita kembalikan kisah ke Kedai Kopi Paman Pirates. Hari ini, aku, Wahid dan Aram duduk bertiga, takzim di depan Kopi Hindi masing-masing. Versi jumbo.
“Entah sudah berapa gelas kopi yang kita habiskan di sini ya Az,” Aram bertanya, teroris. (Ah salah, maksudku retoris, tolong diharap maklum, mengetik sejauh ini kadang melelahkan bagi mata).
“Banyak sekali Ram. Apalagi bagi kau yang sudah nongkrong di sini sejak semester 1. Aku yang gabung sejak semester 3 saja, menaksir 300 cangkir lebih sampai hari ini.” Aku menjawab panjang lebar, sedang bersemangat menganalisis.
“Padahal minum ini rutin, tidak baik untuk kita,” ujar Wahid. Dia menyahut dengan tenang. Amat berbeda dengan Wahid yang tampil di panggung tempo hari.
“Apa boleh buat,” Aram menegak kopi lagi dari cangkirnya, “cairan ini sangat ampuh untuk mengembalikan mood dan mencegahku mengantuk.” Aku manggut-manggut mendengar ucapan Aram.
“Tetap saja, kopi itu sama dengan rokok. Karsinogenik, bikin ketagihan.”
Paman Pirates langsung nimbrung, tak terima produk olahannya disamakan dengan bahan berbahaya, “jangan salah, kopi Hindiku ini diracik dengan campuran rempah-rempah, kopi ini adalah ramuan herbal, baik untuk kesehatan paru-paru dan jantung, meski mungkin berdampak negatif pada kehamilan dan janin.”
Ah kawan, sebaiknya engkau tidak usah memperhatikan apa yang diucapkan Paman Pirates. Promosi semacam itu, tidak bermutu.
“Lupakan semua efek itu Az. Bagi kita orang Melayu, kopi bukan sekedar minuman. Tapi gaya hidup. Kopi adalah media silaturahmi. Di depan segelas kopi kita bertemu, ngobrol, berdebat dan bergosip.”
Wajah Aram meyakinkan sekali. Seolah kemarin Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru mampir ke rumahnya.
“Terlepas dari tradisi atau semacamnya, aku sebenarnya kurang cocok dengan minuman semacam ini. Seharusnya sebentar lagi, ada yang menegurku.”
Tak paham aku mengapa Wahid berucap demikian. Agak aneh. Aram rupanya mengerti arah pembicaraan Wahid. Dia berbisik ke arahku.
“Az, kamu mau dengar gosip terbaru?”
“Apa?” aku menyorongkan kepala.
“Teman kita ini,” ujar Aram menunjuk Wahid, “telah menemukan cintanya.”
“Sungguh?” aku bertanya tanggung, Wahid yang dikenal pemburu cewek cantik, bukan berita besar kalau tiba-tiba dia dapat cinta, “Mawar Alvera?” sambungku lagi, sambil mengingat-ngingat kisah cinta Wahid dengan Mawar.
“Bukan,” sahut Aram keras-keras, yang digosipkan tersenyum-senyum saja. Demi dramatisnya cerita, aku bertanya lagi pada Aram, “lalu siapa?”
“Icha Aprilianty”
Aku ternganga. April? Dia kawan sekelasku. Gadis bukan yang biasa-biasa saja. Aku pernah menjalin cerita juga dengan cewek itu, pernah mati-matian mengejar cintanya. Ah nanti, kapan-kapan aku cerita soal itu.
“Iya Az, April, mantanmu dulu itu.”
“Aku dan April tidak pernah pacaran,” koreksiku, setiap kali ada yang menyebut aku dan gadis bernama April itu pacaran.
“Baiklah Az, Wahid menaruh hati dengan gadis yang pernah kau taksir itu. Bagaimana menurutmu Az?”
Aku tersenyum tawar. “Bagaimana bisa Hid? Bagaimana bisa kau malah memilih gadis itu dari semua pilihanmu.”
“Cinta itu tidak mengenal pilihan Az. Dia jatuh suka-suka. Kemanapun bisa,” Aram menyahut lagi.
Aku lagi-lagi geleng kepala. Aku mengenal Wahid ketika dia jatuh bangun berusaha memikat Mawar Alvera, bunga sekolah paling mekar, dan kini dia jatuh suka pada April? Terlalu dramatis.
“Azka sepertinya cemburu nih,” sulut Aram.
Aku langsung memasang senyum tawar, “jangan mengada-ngada. Cintaku hanya satu.”
“Ah masa sih? Bebeb Syifa nih berarti?”
“Ram!”
Aram terkekeh, puas melihat ekspresiku yang terpancing kalimatnya. “Baiklah Az, sebaiknya kau berikan tips untuk Wahid biar bisa bersatu dengan April. Kau punya banyak pengalaman bukan?”
“Astaga, aku tidak tahu apa-apa.”
Wahid akhirnya buka suara, panjang. “Ayolah, doakan saja aku kali ini berhasil. Kali ini aku serius, tidak sekedar cari sensasi. April berhak dapat yang terbaik dari Muhammad Wahidurrahman.”
Mozaik 27
Gonjang-ganjing Sana-sini
Aku terhenti di hari ini, sebuah Rabu di Bulan Januari yang panas. Itu agak anomali sebenarnya, di musim hujan seperti ini.
Hidupku sampai di sini tenang-tenang saja. Gejolak-gejolak kerinduanku dengan Syifa, cuma berkobar di dalam hatiku. Hampir tidak ada lagi gosip-gosip miring bertebaran. Sampai kemudian terjadi insiden kecil di kantin.
“Aduh.”
“Eh maaf.”
Karena asyik melamun sambil melihat kerumunan di kantin, aku menabrak seorang cewek. Jilbabnya berkelabat tertiup angin, barang bawaannya, botol mineral dan roti di kantong plastik terjatuh ke tanah. Aku reflek memunguti barang-barangnya.
Semua itu berlangsung sangat cepat, sampai aku tidak sempat menyadari siapa cewek yang aku tabrak. Ketika aku mendongak, barulah aku tertegun. Dia Syifa. Wajahnya pun tidak kalah kaget saat melihat wajahku.
“Maaf Syif. Aku tidak melihat, tadi melamun.”
“Iya Az, tidak apa-apa. Makasih sudah membantuku memungutinya kembali.”
Percakapan kami berakhir di sana. Syifa bergegas menuju lokalnya. Aku meneruskan jalan ke kantin. Bergabung dengan Aram dan Wahid yang sudah lebih dulu meramaikan kedai Paman Pirates.
“Kok lama Az? Kukira tadi tidak jadi,” sambut Aram. Aku langsung menuju ke meja pesanan, segelas Kopi Hindi adalah penawar yang baik untuk siang ini. Aram dan Wahid segera asyik membicarakan langkah-langkah PDKT Wahid pada April yang menurut hemat Aram, kuno sekali.
Aku menyumbangkan beberapa lelucon.
Tak lama kemudian, datang dua orang teman sekelasku yang lain. Hamed (laki-laki) dan Intan (perempuan), bergabung. Dan itu menjadi permulaan angin gosip berbalik lagi padaku. Rupanya kedua orang ini, melihat momen aku bertabrakan dengan Syifa tadi.
“Azka tadi bertabrakan jalan dengan Syifa lho,” ujar Intan, menyulut api. Aram, begitu mendengar kata “Syifa” langsung berpaling ke arahku.
Benar yang dia katakan itu Az, astaga so sweet sekali.
Aku menggeleng kuat-kuat. “Tidak ada yang istimewa dari itu Ram. Astaga. Kami hanya bertabrakan, tidak sengaja pula.”
“Ah Azka,” Wahid menyahut, “sudah lama tidak saling sapa dengan Syifa, sekalinya menyapa, ada-ada saja caranya.”
“Ini pasti gara-gara kau Hid,” semprot Aram.
“Eh kenapa aku?”
“Gara-gara kau mendekati April, makanya Azka panas.”
Mereka tergelak bersama. Intan yang masih berdiri di sana, menyahut lagi. “Memangnya Azka ada hubungan apa dengan April?”
“Astaga kau tidak tahu?” Hamed nimbrung, “Azka pernah dekat dengan April, pacaran malah.”
Hamed dulu sempat bersinggungan jalan denganku.
“Kami tidak pernah pacaran,” potongku tajam. Mengoreksi kalimat Hamed.
“Astaga Azka, aku baru tahu soal hubunganmu dengan April itu.”
Wajar saja kau bukan lingkaran pergaulanku, sungutku pada Intan.
“Jangan lupakan kisah kedekatan Azka dengan Shiela,” ungkit Aram.
Aku menepuk dahi, semakin lama aku diam di sini, semakin ramai jadinya. Herannya, aku tidak beranjak. Seolah menikmati semua hal privasiku diungkit-ungkit seenaknya.
“Kau juga dekat dengan cewek tercantik di Quart School itu Az?”
“Kau tidak tahu soal ini Ntan? Astaga, kisah Azka dan Shiela sudah melegenda di Quart School ini.”
Intan geleng-geleng kepala. “Tak kusangka, Azka yang begini-begini, ternyata gebetannya banyak.”
“Hush, hati-hati kalau begitu kau,” ujar Aram sambil mengibaskan tangannya pada Intan, “kau jangan sampai jatuh hati juga dengan Azka.” Semua orang di sana tahu bahwa Aram jatuh hati pada Intan Larasati.
Tapi cerita hari ini tidak berakhir di situ saja. Lepas jam makan siang, ada sebuah chat masuk ke inbox-ku. Atas nama Ibu Qotrun Nada. “Az, habis jam makan siang ini, bisa ke ruangan ibu sebentar? Penting.”
Aku langsung bertanya-tanya. Apa lagi yang direncanakan Ibu Qotrun Nada. Biasanya kalau beliau menyuruhku ke ruangannya, itu berarti ada kejutan. Bisa saja ada Syifa di sana. Aku harus bersiap-siap, agar tidak salting.
Begitu aku membuka ruangan beliau, dengan jantung berdebar tidak karuan, ternyata tidak ada Syifa di sana. Hanya Ibu Qotrun, yang menumpukan kepala beliau di meja, ekspresi beliau seperti kelelahan.
“Azka, Ibu harap Ibu tidak mengganggumu,”
“Tidak bu,” sahutku, “ada yang bisa Azka bantu? Ibu kenapa?”
“Ibu tidak apa-apa,” sahut beliau lagi, memaksakan diri terkekeh, “cuma sakit kepala. Ibu mau minta tolong, bisakah kamu mengantarkan buku-buku ini ke lokal 2. Sampaikan bahwa Ibu tidak bisa mengajar, dan Ibu sudah memberi tugas lewat pesan Whatsapp. Maaf ya jadi merepotkan kamu Az, ketua kelas lokal 2 tidak ada respon sedikitpun.”
“Tidak masalah Bu,” dengan enteng aku ambil tumpukan buku yang ada di atas meja. Siap menuju lokal 2.
Aku tidak punya banyak referensi mengenai lokal 2 ini. Pergaulanku tidak luas, jadi aku tidak punya banyak kenalan. Untung ada satu orang yang berdiri di depan lokal itu, yang langsung kukenali, namanya Munir Al-Hambra. Teman SMP-ku dulu.
Camkan namanya kawan, dia itu unik.
“Apa itu Az?” sapanya, dengan suara khas.
“Buku-buku kalian, aku diminta Ibu Qotrun Nada menyerahkan ini kepada ketua kelas. Sekalian ada pesan dari beliau.”
“Oh iya, masuk saja Az, ketua kelas ada di dalam.”
Aku mengangguk, sejenak memandangi lokal 2 ini. Baru tersadar satu fakta, ketika melihat struktur organisasi lokal ini.
KETUA KELAS: SHIELA CAMALIA
Astaga, rupanya dia yang jadi ketua kelas di sini. Shiela duduk di depan, pojok kanan. Menyendiri dari kerumunan lokalnya yang kebanyakan laki-laki, dengan buku di tangannya. Aku bergegas menghampirinya.
“Eh Azk, kejutan yang menyenangkan. Kenapa tiba-tiba kamu ke sini,” sapanya begitu mendongak kepala.
“Ada pesan dari Ibu Qotrun Nada. Kata beliau, beliau tidak bisa masuk hari ini, dan sebagai gantinya, beliau sudah memberi tugas lewat pesan Whatsapp.”
Aku bicara lancar sekali.
“Oh terima kasih kalau begitu Azk. Aku terlalu asyik dengan novel ini, sehingga lupa menengok handphone.”
Tak kusadari bahwa semua pasang mata laki-laki di sana nanar menatapku. Jenis tatapan serigala yang siap menerkam. Aku buru-buru angkat kaki.
Mozaik 28
Kelas Mr. Zee
Aku tahu, seharusnya aku menceritakan lebih banyak tentang kegiatan pembelajaran di Quart School. Namun, entah kenapa aku kesulitan mencari ruangan untuk menempatkan cerita semacam itu.
Kali ini, kupaksakan memasukkan cerita bertema semacam itu. Ini tentang kisah Mr. Zee, pemilik Kelas Bahasa Inggris.
Aku pernah curhat dengan Shiela, mengenai ketidaksukaanku ini. Aku merasa bodoh sekali tidak menguasai mata pelajaran yang penting semacam Bahasa Inggris. Shiela menjawab, “Azk, kamu harus mengubah imej-mu yang buruk.”
“Bagaimana caranya Shie, aku tidak bisa. Tiap masuk jam pelajaran Bahasa Inggris, tidak satupun kalimat ‘aneh-aneh’ itu masuk ke kepalaku.”
“Baiklah, mungkin Mata pelajaran ini memang bukan bakatmu. Namun, kamu harus ingat Azk, belajar Bahasa Inggris itu penting untuk masa depan.”
“Perkataanmu membuat aku semakin takut, Shie.”
“Baiklah Azk. Menurutku, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mudah menerima pelajaran. Ada yang memang karena pelajaran itu cocok denganmu, ada pula yang berfaktor pada pengajarnya. Pengajar yang baik, terkadang membuat kita bisa menikmati pelajaran tersebut, sesulit apapun itu.”
Aku mengangguk membenarkan, Ibu Qotrun Nada adalah contoh yang baik untuk itu.
“Nah Azk, Kelas Bahasa Inggris-pun memiliki peluang yang sama untukmu.”
“Tapi aku tidak suka dengan Mr. Zee, Shie, gaya bicara beliau yang bercampur-campur Inggris itu, terdengar seperti kaset rusak di telingaku.”
“Maka ubahlah imej-mu itu Azk. Itu pilihanmu, kamu bisa mengendalikan penilaianmu. Mungkin kamu bisa menganggap kalau Mr. Zee sebenarnya bermaksud baik, sebenarnya lewat dialog-dialog beliau itu, beliau ingin membuatmu lebih familiar dengan Bahasa Inggris. Kamu bisa mulai dari jalur-jalur ini Azk. Aku yakin berhasil.”
Aku mencoba tersenyum, tidak ingin mengecewakan Shiela yang sudah repot-repot memberiku saran.
Kau tahu kawan, Mr. Zee memang begitu adanya. Saat pertama kali masuk kelas, beliau akan bercerita sebentar tentang sarapannya, tentang buku yang dibacanya, dan hal-hal kecil lainnya, dalam bahasa yang menurutku seperti kaset rusak, Bahasa Inggris langsung dari penutur aslinya. Aku curiga, sebenarnya beliau pernah tinggal di pedalam Sussex dan pernah pula menyelam di selat Inggris.
Nama panggilan beliau saja, nyentrik begitu, Mr. Zee.
Sialnya lagi, Shiela benar. Hari dimana aku menikmati kelas Mr. Zee, akhirnya tiba.
Pertama-tama masuk, beliau langsung mengucap salam, memberi sapaan good afternoon students, dan melambai-lambai ke arah kami. Lalu keluarlah basa-basi yang mirip kaset rusak itu saat beliau duduk di kursi beliau.
“Today I tried to drive the car to school. Unfortunately, I was stuck in traffic, it was long, more than 2 kilometers. Even worse, I never realized that when I was riding a motorcycle.” (Mohon maaf jika ini agak berantakan. Ini bukan versi asli ucapan beliau, tentu saja aku tidak sanggup mentranskripsikan apa yang beliau katakan. Jadi aku minta Nasri menyadurnya, setidaknya kau mengerti maksudku kawan).
“Oke students, mengingat ini sudah semester 6, dan Ujian Akhir kalian sudah dekat, saya memutuskan untuk meringkas gaya belajar kita agar kalian bisa menjawab soal-soal Ujian akhir kelak, dan masih bisa mendapatkan pengetahuan seputar Bahasa Inggris.”
Kami menanti-nanti apa yang akan dilakukan beliau.
“Cara terbaik yang saya pikirkan adalah membentuk kelompok untuk belajar bersama. Saya punya banyak lembar-lembar soal bahasa Inggris dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita bisa menjawab soal-soal itu bersama-sama. Berkelompok. Kalian setuju?”
Aram langsung angkat tanga.
“Iya Aram?”
“Kelompok ini apakah ditentukan atau memilih sendiri, Sir?”
“Untuk kelompok, akan saya tentukan. Sebentar lagi saya sampaikan. Ada pertanyaan lain?”
Aram menggeleng. Duduk mengelus dada, cemas. Dalam situasi berkelompok semacam ini, posisi Nasri selalu yang paling strategis. Bagaimana tidak, dia adalah Master Bahasa Inggris. Bahkan Mr. Zee mengakui hal itu.
“Oke baiklah,” ucap Mr. Zee (beliau menjentikkan jari) “akan saya sebutkan. Dimulai dari ketua kelompok. Ketua kelompok saya pilih berdasarkan orang yang saya anggap kompeten, sehingga nanti ketua kelompok bisa membantu anggotanya. Ada lima ketua kelompok yang sudah saya tentukan, Nasri Abdillah, Humadi Azka, Faddil Al-Aram, Dahlia Anggraini dan Mei. Cukup jelas?”
Aku berdecak sebal. Tidak bisa-kah aku sekelompok dengan Lia?
Mr. Zee mulai membacakan anggota-anggota kelompok, nama-nama yang tidak benar-benar penting ada di kelompokku. Hanya satu nama terakhir yang mampu membuat telingaku tegak berdiri. “Mawar Alvera”. Aku akan sekelompok dengan cewek paling semlohai di Quart School?
Luar biasa.
Apalagi tanpa tedeng aling-aling Mawar langsung mengambil posisi duduk di sebelahku saat kami duduk melingkar. Dia berbisik sumringah, “untunglah sekelompok denganmu Az. Kurasa kamu bisa membantuku bukan?”
Mr. Zee mulai menjalankan kegiatan belajar mengajar. Aku tidak benar-benar bisa fokus. Ayolah kawan, jika cewek paling cantik di Quart School duduk di sebelahmu, siapa juga yang bisa fokus. Kadang aku perhatikan telapak tangannya, putih bersih, kadang kulihat jemarinya, lentik-lentik. Sekali coba kulirik wajahnya, astaga. Pantas saja Wahid mati-matian mengejar gadis ini.
“Ya Azka, Mawar. Tolong bacakan soal nomor 17, itu bentuknya conversation. Baca bergantian, sampai ke jawabannya.”
Aku mengangguk. Mawar juga, aku membaca teks bercetak miring.
“I heard that Rani is going to celebrate her birthday next Saturday at 8 p.m. “
“I got the information from Shinta. Will you come to the party with me?”
“Sure, it will be more interesting to come there with you. I’ll pick up at 7.”
“I’ll be waiting for you, then.”
Habis membaca, kami tiba-tiba dihujani koor ciye. Apa maksudnya ini, aku tidak mengerti. Mawar yang tampak Bahasa Inggrisnya lebih baik dari aku, memerah wajahnya. Saat-saat itulah dia tampak semakin cantik saja.
Mozaik 29
Hikayat Mawar Alvera
Sejak hari itu, hidupku kembali tidak tenang. Kemanapun aku pergi, koor ciye menghujani. Koor ciye yang mendoakan kedekatan Azka dengan Mawar Alvera. Aku geleng-geleng kepala, ada-ada saja cara mereka untuk membuat kehebohan.
Lama-lama aku mulai gerah dan terganggu dan jelas penasaran. Apa sebenarnya maksud dari percakapan yang kulangsungkan dengan Mawar itu? Karena aku tidak paham sepenuhnya, akhirnya kuputuskan untuk bertanya pada Nasri.
“Secara garis besar, lewat percakapan itu, kau mengajak Mawar untuk datang ke pesta, dan kau akan menjemputnya.”
Aku manggut-manggut. Pantas saja, pantas saja semua koor ciye itu menerpaku.
Mungkin kawan tertarik untuk mengenal Mawar Alvera lebih jauh. Mengenali seorang gadis yang dijuluki sebagai yang tercantik di Quart School. Baiklah, akan segera kubacakan hikayatnya
***
Mawar pertama kali datang ke Quart School pada semester 2. Dia adalah murid baru, di pertengahan semester. Entah bagaimana dia melangkahi segala prosedur penerimaan siswa yang rumit di Quart School, mungkin kekuatan uang berkata di sini. Ya Mawar adalah anak orang kaya.
Lucunya kawan, saat pertama kali masuk ke Quart School, Mawar tidak lebih dari sekedar murid baru. Euforia sesaat, pembicaraan sambil lewat, selebihnya tidak penting. Bahkan Aram dan Wahid, (yang satu seniman asmara, dan satunya pemburu cewek cantik) tidak terlalu memperdulikan Mawar. Anak baru itu bahkan terlihat aneh dengan baju warna-warni yang mencolok. Mawar terkesan kolot. Akan tetapi, hanya butuh waktu kurang dari 6 bulan untuk menjungkir balikkan semua itu. Kini Mawar adalah primadona.
Mengenai porsi tubuhnya, kuperkirakan Mawar pasti bertinggi tak kurang dari 160 cm. Wajahnya cemerlang, senyumnya manis dengan deretan gigi rapi setiap dia senyum, kulitnya kuning langsat, blasteran China, matanya jernih, ditambah kacamata yang membuat dia kian memesona. Tak pelak, Mawar bisa membuat siapa saja pria, bertekuk lutut di hadapan body proporsionalnya. Tak perlu kusinggung-singgung soal buah dada.
Segera setelah Mawar bertransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu, dia menjadi incaran remaja-remaja tanggung kebelet pacaran. Beda dengan Shiela, untuk hitungan cewek yang sangat cantik, Mawar terbuka dan apa adanya. Dia berkali-kali berganti partner asmara.
Dari kalangan kami, tidak ada yang lebih keukeuh mengejar Mawar, selain Wahid.
Bagi temanku itu, Mawar adalah resolusi sempurna hidupnya. Wahid berjanji dengan sungguh-sungguh jika bisa mendapatkan Mawar Alvera, dia tidak akan mengincar wanita lain seumur hidupnya. Berulang kali Wahid berkirim salam, mencoba menyapa Mawar setiap bertemu, mengucapkan selamat pagi, mengajak jalan ke kantin, membelikan makanan dan lainnya. Namun sepertinya takdir tidak berpihak pada dia.
Ada orang-orang tertentu yang sukses mencuri hati Mawar, bahkan sampai membuat adegan close up paling romantis di Quart School. Di tengah lapangan, duduk bersama, berpegangan tangan. Siapapun yang melihat pasti gigit jari. Apalagi lapangannya panas waktu itu.
Saking cantiknya, Mawar Avera bahkan bisa main seleweng belakang, alias berselingkuh. Aku pernah memergoki dia dan teman sebangkunya (cewek) saat lokal kosong di jam istirahat pertama.
Mawar tertawa-tawa sendiri sambil memandang layar handphone. Telinganya sepertinya sudah terhubung dengan earphone, tertutup jilbabnya.
Karena Mawar terlalu cekikikan sampai mengganggu aku yang sedang mengerjakan tugaas, kutanyalah pada temannya. “Kenapa dengan dia?”
“Ah jangan terlalu dipikirkan Az, asyik Mawar video call dengan selingkuhan dari Jakarta.”
Aku ternganga. Selingkuhan? Jakarta?
“Eh ganteng ini orangnya,” sahut Mawar, masih tertawa-tawa senyumnya terburai-burai, “iyakan sayang?”
Aku tepuk dahi.
Bisa kukatakan, jika ada orang yang berniat membuat semacam daftar cewek-cewek paling cantik di Quart School, maka Mawar akan ada di urutan teratas, bahkan dia unggul atas Shiela Camalia, dengan segala pesona dan keramahannya itu.
Mozaik 30
Taktik Asmara
Aku tidak pernah berpikir untuk menjadikan Mawar sebagai target. Juga tidak pernah berharap bisa dekat-dekat dengan gadis itu. Bagiku tidak ada juga untungnya.
Seperti yang kukira, koor ciye yang kemarin-kemarin terdengar, atas nama aku dan Mawar itu, lama kelamaan, menghilang, ditelan waktu. Dilebur panas, dibawa angin, pergi ke suatu tempat lain. Terlupakan. Aku juga diam saja, bagiku itu tidak istimewa.
Hanya saja, ada satu orang yang keras kepala, yang entah kenapa, terus mempertahankan isu kedekatanku dengan Mawar. Astaga, menulisnya saja aku merasa geli sendiri. Aku dekat dengan Mawar? Utopia sekali hal itu.
Satu hari setelah Kelas Mr. Zee, Wahid mengajak aku main catur. Kami memang punya catur di dalam kelas, yang dibeli atas inisiatif Aram, aku rasa aku sudah pernah menceritakan hal ini padamu kawan. Aku manggut saja, menyanggupi. Wahid adalah lawan yang menantang. Dalam permainan papan hitam putih itu, dia cerdas sekali.
Kami saling berjual beli serangan. Saling makan bidak satu sama lain, dengan cepat Wahid menguasai permainan ini. Dia mengurung bidak-bidakku serupa tentara Xerxes dalam pertempuran Thermopyle. Aku berada dalam posisi nyaris skakmat. Saat itulah Mei datang, tidak tahu apa motifnya. Yang jelas, dia langsung menyorong pertanyaan.
“Sudah jadian belum, Hid?”
“Jadian apanya?” Wahid menyahut, limbung.
“Jadian dengan April-lah.”
“Oh sebentar lagi, sebentar lagi.”
Percakapan itu cukup memecah konsentrasi Wahid, aku menemukan celah untuk kembali bergerak.
“Dan Azka,” Mei menatap balik ke arahku, “apa langkah yang akan kamu ambil. Mantan gebetanmu akan dicaplok oleh Wahid lho. Apakah Azka akan menembak Syifa, Shiela atau malah seseorang yang ada di kelas ini?”
Sialan. Aku berdecak sebal dalam hati. Mei sengaja cari penyakit. Jelas sekali konotasi kalimatnya itu, mengarah pada Lia. Wahid mendengar semua itu, lalu menyahut, bertanya.
“Eh siapa lagi yang dekat denganmu di kelas ini Az? Astaga banyak sekali targetmu.”
“Tidak ada Hid. Mei berhentilah mendramatisir, dan jangan merusak konsentrasiku.” Aku setengah membentak. Mei berlalu dengan wajah masam.
“Kalau aku menang dalam pertandingan ini, kau harus mengaku Az, aku harus tahu siapa yang dimaksud Mei itu. Kita taruhan. Sepakat.” Wahid bersepakat secara sepihak.
Aku merinding memikirkan kemungkinan itu. Astaga, mana mungkin aku mengarang-ngarang cerita tentang siapa yang sekarang dekat denganku. Beruntung, hari itu rahasia perasaanku pada Lia, tidak terbongkar. Aku berhasil memenangkan pertandingan (walau itu semacam keajaiban karena Wahid bermain mati-matian). Sungguh Tuhan tidak suka orang-orang yang bertaruh.
“Aku hanya bisa memikirkan satu kemungkinan Az,” ujar Wahid, mengusap wajah saat pertandingan berakhir, “Mawar Alvera.”
Astaga, kenapa nama itu dimunculkan lagi.
“Hid, kau mendramatisir terlalu jauh.”
“Ah sudah Az, kau tak usah membantah. Sini aku panggilkan Mawar. MAWAR!!”
Wahid berteriak serupa tidak ada hari esok. Mawar dengan wajah malas, mendatangi kami berdua. “Ada apa Hid?”
“Gimana malam minggu, Mawar?” (sungguh kawan, itu adalah pertanyaan yang tidak bermutu).
“Biasa saja. Di rumah saja. Kenapa? Kamu mau ajakin aku jalan-jalan?”
“Eh tidak,” sahut Wahid diplomatis, “tapi mungkin Azka mau.”
“Tuan Azka yang cerdas ini?” Mawar beralih menatapku dengan jenis tatapan yang susah untuk kujelaskan, “oh boleh dicoba tuh.”
“Nah Az, bagaimana, kalian tinggal atur jadwal.”
“Astaga Hid, berhentilah mendramatisir.”
“Ciye-ciye, lihat Mawar, Azka mulai salah tingkah.”
Buru-buru kutinggalkan mereka ke toilet.
Esok harinya di kedai Kopi Paman Pirates. Aku duduk bersama Aram, minum kopi Hindi. Tanpa Wahid, karena Wahid sedang asyik PDKT dengan April. Obrolanku dengan Aram tidak pernah jauh dari isu-isu terbaru. Aku mengeluh-kesahkan kelakukan Wahid yang berusaha mencocokkan aku dengan Mawar. Aram tersenyum simpul.
“Mungkin dia sedang mencoba membuat kau sibuk Az. Agar kau tidak terpikirkan sedikitpun tentang kedekatannya dengan Icha Aprilianti.”
Hei, itu masuk akal.
Mozaik 31
Kisah Kedekatan Azka dan Mawar Alvera
Mr. Zee rutin masuk seminggu sekali. Jadwal beliau hari Selasa. Itu artinya seminggu sekali pula, kami belajar sesuai kelompok yang dibagi Mr. Zee. Itu artinya pula, seminggu sekali, aku harus duduk berdekatan dengan Mawar Alvera. Dan itu terjadi karena dia sengaja mendempet-dempet duduk dengan aku.
“Supaya ketularan pintarnya kamu, Az.”
Ah kawan, bayangkan dia mengucapkan kalimat pujian itu dari jarak tak sampai sejengkal. Untuk ukuran cewek secantik Mawar, pujian semacam itu adalah hal memabukkan. Lama kelamaan, aku benar-benar mabuk dengan pujian itu. Lambat laun, aku mulai suka dekat-dekat dengan Mawar, aku mulai menyenangi kelompok ini, dan itu artinya aku mulai suka dengan Bahasa Inggris.
Hari ini misalnya, aku tidak langsung menarik bangku saat kelompok usai dan menyambut jam istirahat. Mawar bertanya padaku tentang opsi kuliah yang mungkin aku pilih.
“Aku tertarik untuk masuk UGM,” sahutku optimis.
“Luar biasa Az, itu kampus terhormat, salah satu yang terbaik di seluruh Indonesia.”
“Hehe iya. Walau masih mengambang di alam mimpi sih bisa kuliah ke sana,” aku cengengesan.
“Ah untuk Azka yang cerdas, kuliah ke sana adalah opsi yang sangat masuk akal.”
“Aamiin.”
“Aku sambil makan ya Az, mari.” Mawar mengeluarkan kotak makan siang dari tasnya, kemudian menyantapnya. Aku masih duduk di hadapan dia. Mawar menawariku, nyaris aku terima, tapi aku teringat bahwa mungkin kelak cerita ini akan dipajang di rak-rak novel best seller, jadi kurasa itu adalah momen yang tak bermutu.
“Oh ya Az, boleh tidak sesekali aku minta diajari matematika, secara privat olehmu. Astaga aku ingin sekali bisa menjawab soal seperti yang kau sering lakukan itu Az.”
“Tidak masalah. Itu bisa kita atur.”
Dalam rangkaian jadwal kelas Mr. Zee ke pertemuan selanjutnya, aku juga sempat terlibat obrolan lewat room chat dengan Mawar Alvera. Bahkan aku yang men-chat-nya duluan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tak pernah terbayangkan olehku.
“Mawar.”
“Eh, Azka? Ada apa Az?”
“Mau tanya sedikit. Maaf karena ini akibat rasa penasaranku.”
“Tanya saja Az.”
“Sepanjang sore ini, kamu kemana saja?”
“Eh aku, aku di rumah saja Az, mulai dari pulang sekolah, sampai sekarang.”
“Oh baiklah, mungkin aku salah lihat.”
“Ada apa? Kamu melihat aku di suatu tempat.”
“Iya tadi saat jalan-jalan ke pasar malam. Kukira itu kamu, untung saja tidak kusapa.”
(Mengenai hal ini benar adanya kawan, aku memang melihat orang yang mirip Mawar saat mengantar ibuku berbelanja ke pasar malam. Mengenai seberapa mirip, itu bolehlah kulebih-lebihkan sedikit).
“Wah nyaris saja kalau begitu Az. Hehe.”
“Eh tapi kamu tahu tidak?” aku membuat pertanyaan mengambang.
Jeda 5 menit.
“Iya Az? Beritahu aku.”
“Setiap orang memiliki setidaknya 7 kembaran di dunia ini.”
Jeda 15 menit.
“Oh ya Az, aku baru dengar tentang itu. Makasih Az, astaga men-chat kamu begini saja aku dapat banyak pengetahuan.”
“Sama-sama. Kamu sedang apa? Apakah kamu sedang sibuk?” Kucoba membuat chat itu tidak terlihat klise.
Jeda 30 menit.
“Ah tidak kok Az.”
Apa yang dikirimnya jelas ambigu dengan perbuatannya. Chat-chat balasan darinya terus tersendat-sendat dalam waktu yang lama. Mungkin dia sedang asyik membalas chat dari pujaan hatinya, dan aku bukan prioritas dalam antriannya itu. Ah kawan, klise sekali hal itu.
“Baiklah.”
Akhirnya kukirim “pemati chat”.
“Eh Az, bagaimana caranya ya agar lukisanku terlihat bagus?” Mawar malah mengirimiku chat balik.
Aku memang mengenal Mawar sebagai ahli lukis.
“Taruh lukisanmu di baliho. Biar semua orang melihat. Makin orang melihat, makin bagus terlihatnya.”
“Kamu ada-ada saja, Az.”
Kelas berikutnya dengan Mr. Zee, aku dan Mawar, sekali lagi duduk bersebelahan. Hari ini kami mengikuti dengan takzim bagaimana Mr. Zee menjelaskan. Aku lebih menyimak karena Mawar benar-benar terlihat serius. Malulah aku jika main-main di hadapan gadis cantik nan semlohai ini.
Di tengah-tengah pelajaran, tiba-tiba handphone Mawar menyala. Dia mungkin sudah menyetel handphone itu agar silent tapi tentu saja tetap menyala jika ada panggilan masuk. Karena Mawar meletakkan hape itu di antara aku dan dia, jadi aku bisa melihat siapa yang menelepon itu. “Mama”, itulah tulisannya.
“Gimana nih Az?”
“Keluar saja dulu, angkat telepon itu. Siapa tahu penting,” ujarku, berbisik-bisik.
“Tapi aku tidak tahu bagaimana cara minta izin dengan Mr. Zee, beliau pasti minta aku berbahasa Inggris.”
Aku mengangguk menenangkan. Melempar isyarat padanya, tenang saja, serahkan ini padaku. Aku mengacungkan tangan, melambai pada Mr. Zee, kemudian berbicara lugas, “Sir, my friend has an important call, can she take it outside of class?”
Aku sendiri ternganga, bagaimana bisa aku mengeluarkan kalimat sebaik itu. Masih misterius kawan.
Mr. Zee mengangguk mengiyakan. Mawar bergegas bangkit ke luar kelas. Menelepon ibunya.
“Makasih Az, aku bisa mengandalkanmu,” ucapnya saat kembali duduk. Hidungku rasanya mekar.
Mozaik 32
Hari Ketika Wahid Mengaku jadi Tuhan
Ketika Semester 6 ini, Aram dan Wahid berinisiatif untuk menghidupkan kembali permainan catur yang sempat vakum. Seperti yang kawan ingat, di ujung semester 3 kemarin, kami membeli catur.
Adapun kevakuman itu disebabkan oleh teguran Bapak Dahri Ariyanto. “Permainan catur ini haram, membuang-buang waktu, lalai dari ibadah shalat,” ujar beliau. Diiringi tatapan mengancam. Aram dan Wahid jeri. Baru semester 6 ini, permainan ini dimulai lagi. “Kita hampir lulus, jangan sampai kita tidak menikmati hidup kita di sekolah ini.” Aram percaya diri menyusun kembali bidak-bidak. Menantang siapa saja untuk melawannya.
Tidak lama kemudian, terjadi pertandingan eksebisi antar murid lokal 4. Aku, Aram dan Wahid. Belakangan, Nasri ikut nimbrung. Kami bahkan membuat semacam kejuaraan catur mini.
“Aku sebenarnya tidak terlalu lihai main catur,” ujar Nasri ketika melakukan pertandingan percobaan melawanku, “tapi ini terlihat sangat menarik.”
“Permainan ini memang menarik Nas.”
“Tolong koreksi jika aku salah Az. Aku masih dalam tahap menghafal langkah-langkah bidak ini.”
Aku mengangguk. Nasri sering mengajakku main jika sudah pulang sekolah. Saat-saat sunyi. Kukira itu adalah selingan yang menarik untuk pikiran sang profesor.
Empat kali bertanding dengan dia, aku selalu menang mudah. Agak heran juga bagaimana bisa Nasri yang pemikirannya yang cerdas, selalu kalah dalam pertandingan catur. Trik-trik yang kumainkan padahal tidak terlalu rumit.
Satu minggu setelah kami saling menjajal kemampuan masing-masing, Aram mengeluarkan ide yang luar biasa. “Kita akan buat kejuaraan. Buat pertandingan 3 ronde, sistem semifinal. 4 orang sudah cukup, aku, Azka, Wahid dan Nasri. Pasti sangat mantap.”
Tak menunggu tempo, aku, Nasri dan Wahid mengangguk mengiyakan.
Undian dibagi oleh Aram. Sistem semifinal memungkinkan kami bertemu satu sama lain, sebelum saling sodok di final. Wahid bersorak karena undian mempertemukan dia dengan Nasri. Sedangkan aku menghadapi Aram. Sungguh lawan yang sulit.
“Kita mulai bertanding esok Az, jam istirahat pertama. Astaga aku sudah tidak sabar melawan kau lagi,” ujar Aram, wajahnya serius, seolah-olah kami tidak pernah bertanding satu sama lain. Sementara itu aku stress. Karena Aram menamai ini sebagai kejuaraan, nafsu kemenanganku langsung terpancing.
Gengsi sekali kalau harus kalah dalam kejuaraan.
Dalam beberapa kali tanding percobaan melawan Aram, kami berimbang. Aku memenangkan 4 kali pertandingan, 4 kali dia menang, dan 2 kali imbang. Imbang dalam catur, dalam posisi aku sedang terdesak.
Aram adalah calon yang tangguh.
Akhirnya, Kamis yang cerah di awal bulan Maret menjadi hari yang amat penting. Hari kejuaraan catur lokal 4. Memang tidak terpampang di kalender resmi Quart School, pun tidak diakui sebagai event resmi, tapi bagi kami para peserta, kejuaraan mini ini, benar-benar spesial.
Pagi harinya, lebih dulu tersaji pertandingan antara Wahid melawan Nasri. Nasri sebenarnya ingin pertandingan setelah pulang sekolah, karena dia menyukai ketenangan. Tapi Wahid bersikeras, ingin menghadapi Nasri dalam kondisi otak paling segar di pagi hari. Logikanya, Nasri belum banyak berpikir, sehingga otaknya masih prima. Melayu sekali pemikiran Wahid itu.
Pertandingan pertama, Wahid vs Nasri
Ronde pertama
Wahid membuka jalan, menyusun formasi. Pion-pionnya menyebar tak tentu arah. Tapi jangan salah kawan, kalau lawannya lengah, pion-pion itu bisa berubah tiba-tiba jadi Queen.
Nasri sebaliknya, melakukan langkah-langkah antisipasi. Tiap pergerakan bidaknya adalah bertahan dari serbuan Wahid. Nasri memang perlu waktu untuk belajar menyusun taktik menyerang. Tapi aku yakin di pertandingan kali ini, dia bisa beradaptasi. Wahid menyunggingkan senyum. Papan ini telah dia kuasai.
Siapa sangka Nasri kemudian menemukan momentum. Tiba-tiba saja, pion-pion Wahid kena gulung serangan Queen yang digerakkan Nasri. Dalam sekejap, Raja milik Wahid nyungsep ke bawah. Nasri memenangkan ronde pertama.
“Aku hanya kurang waspada saja, tunggu, akan kubalas di ronde berikutnya,” ujarnya, beralasan.
“Jaga mulut kau Wahid, jangan besar-besar gertak kau, kena gulung lagi di ronde dua tahu rasa kau kehebatan Nasri.” Aram tergelak.
Sayangnya, yang Wahid lakukan bukan gertak-gertak besar. Dia benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dua ronde berikutnya, Nasri harus bertekuk lutut. Bahkan sekali dengan jalan ringkas, 4 kali jalan saja.
“Ya, mau bagaimana lagi. Tapi tadi adalah pertandingan yang cukup menarik,” kata Nasri sambil mengangkat bahu.
Pertandingan kedua, Aram vs Azka
Ronde pertama
Begitu lonceng dan bel berbunyi. Aram langsung dengan sukacita mengeluarkan papan catur dari laci mejanya. Aku curiga, sebenarnya Aram tidak memperhatikan pelajaran. Pikirannya sibuk merancang strategi untuk mengalahkan aku.
Enak saja, aku tidak kalah dengan mudah.
Begitu pertandingan dimulai, tensi langsung naik. Aku dan Aram jual beli serangan tanpa ragu-ragu. Jika tadi Nasri menghadapi Wahid dengan strategi defensif, maka aku dan Aram saling terkam. Dia caplok pion-ku, aku caplok kuda miliknya, dia serang benteng-ku, aku serang Queen miliknya. Serangan terakhir itu, membuat dia sedikit terperanjat.
“Tak apalah, aku masih bisa menang tanpa Queen,” ujarnya, ragu-ragu terkesan jelas sekali dalam suaranya.
Tanpa prajurit andalannya itu, Aram kehilangan kesaktian. Ronde pertama kugasak dengan mudah. 1-0 untuk Azka.
Ronde kedua berjalan lebih seru lagi. Aku dan Aram kembali jual beli serangan. Tapi kali ini, Aram seperti mengerahkan kesaktian lainnya. Tahu-tahu, perwira-perwira penting milikku, lenyap.
“Coba kita lihat Az, apakah kamu bisa menang hanya dengan menggunakan Queen,” sesumbarnya. Aku berdecak sebal. Mencoba mengontrol diri. Emosi hanya akan merusak pertandingan. Di ujung ronde dua, aku kalah. Skor imbang 1-1.
“Ha, aku akan mengalahkanmu di Final Hid. Tunggu saja.”
Aku mengusap wajah. Saatnya serius. Saatnya membungkam mulut sesumbar Aram itu. Aku mengerahkan kemampuan terbaik, jual beli serangan lagi. Aku mengandalkan dua ekor kuda yang bergerak dinamis. Target terkunci, Queen milik Aram. Sebab kalau tidak dibereskan, bidak satu itu benar-benar merepotkan.
Akhir dari rode ketiga, Aram membalik papan, frustasi. Aku dinyatakan menang. Berhak beradu di final melawan Wahid. Pertandingan akan dilakukan sepulang sekolah.
Pertandingan final, Azka vs Wahid.
“Aku beri kesempatan untuk menenangkan diri dulu Az. Jangan sampai nanti kau frustasi macam Aram tadi.” Wahid mencemeeh. Ternyata di atas papan catur, sifat seseorang bisa berubah drastis.
Aku diam saja.
Ronde pertama.
Berkaca dari permainan Wahid dengan Nasri, aku bisa kalah jika aku terus-terus bertahan. Jadi kucoba untuk melakukan serangan seintensif mungkin. Seluruh bidak kukerahkan. Wahid tenang-tenang saja. Dia malah defensi dengan mematikan gerakan bidak-bidakku menggunakan pion. Aku terus menyerang sampai tidak ada lagi celah. Jalan buntu. Wahid tersenyum.
“Giliranku Az.”
Tahu-tahu kemudian, bidak-bidak Wahid menyerang serupa bangkit dari kubur. Serangannya dahsyat. Ditambah pertahananku yang terbuka karena asyik menyerang. Ronde pertama, raja-ku terpancung di tempat.
Ronde dua.
Berkaca dari ronde pertama, aku memutuskan untuk bermain lebih santai. Tidak terprovokasi dan lebih terencana. Ronde ini lebih balance. Jual beli serangan terjadi, tapi tidak intens. Kami sama menjaga jarak. Nampaknya pertandingan kedua ini akan panjang.
“Skakmat,” sekonyong-konyong, Wahid menepuk papan sambil tergelak. Aku ternganga. Di sana, lagi-lagi rajaku terpancung. Aku kalah telak. “Tidak perlu ronde ketiga ya Az. Kau sudah kalah.” Wahid tergelak. “Aku benar-benar yang terhebat di kelas ini.
“Tutup mulut kau Hid, aku akan melawanmu,” Aram terprovokasi.
“Tak usahlah Ram. Kau bukan tandinganku. Cukup. Aku sudah resmi jadi Tuhan catur di sini.”
Kami ternganga. Tak percaya dengan apa yang kami dengar.
“Az, karena kau jadi runner-up, kau akan segera kuberkati menjadi Nabi-ku,” ujar Wahid lagi. Aku mundur perlahan, menjauh. Aram pelan-pelan bertanya pada Nasri, apakah dia bisa menelepon rumah sakit jiwa.
Mozaik 33
Event Besar Empat: Hari Suka Raya
Hari terus berganti. Matahari terus bergerak. Tak terasa sudah tanggal 19 Maret. Itu hanya berarti satu hal, besok adalah Hari Suka Raya. Ibu Qotrun Nada segera mengumpulkan kami di lapangan.
“Ibu sudah membaca,” ujar beliau memulai pengumuman, aku tahu Ibu Qotrun adalah orang yang suka mencari tahu, “perbedaan utama antara Hari Suka Raya dengan tiga event sebelumnya, adalah esensi di belakangnya. Ketiga event sebelumnya memiliki tujuan akhir, sedangkan Hari Suka Raya tidak. Hari Suka Raya mengambil elemen-elemen yang terpenting dari ketiga event tadi menjadi satu. Ibu berjanji dengan kalian, Hari Suka Raya besok akan terasa spesial. Kita punya lomba, kita punya pesta, dan tentu saja kita punya makanan gratis. Silakan dibayangkan, pasti meriah sekali. Ada pertanyaan?”
Beberapa orang mengacungkan tangan, bertanya. Lomba seperti apa yang akan diadakan besok.
“Ada catur,” jawab Ibu Qotrun Nada dengan tenang. Aku yang berdiri tidak jauh dari situ, menyernit. Ibu serius ingin mempertandingkan catur kali ini? Apa kata Bapak Dahri Ariyanto nantinya. Ibu Qotrun sepertinya bisa membaca pikiranku, lalu menjelaskan dengan lembut.
“Sebenarnya Ibu ingin menyelenggarakan lomba cerdas cermat. tapi mengingat keberadaan Shiela bisa membuat beberapa orang kalah mental sebelum bertanding, sepertinya catur lebih adil. Pertandingan penuh strategi. Silahkan dirundingkan siapa yang akan bertanding mewakili lokal kalian masing-masing. Jangan lupa bergembira di Hari Suka Raya.”
Kami bergegas menggelar rapat terbatas untuk membahas siapa perwakilan kelas yang akan mengikuti lomba catur yang strategis itu. Rapat informal kali kacau, karena Aram masih menjadi pemimpin rapat yang sekehendak hatinya, sedangkan Wahid masih bersikeras bahwa dia adalah Tuhan catur.
Sesat sekali pemikiran dia itu.
“Baiklah, biarkan saja Wahid bertanding. Aku kehabisan kata-kata. Lama-lama aku juga ikut gila,” ujar Aram emosional menutup rapat terbatas itu.
Musik berdentang kencang. Seisi Quart School bergetar oleh musik keras itu. Empat pengeras suara yang besar dipasang di empat pojok sekolah. Ibu Qotrun benar, suasananya semarak.
Kantin ramai. Hari Suka Raya tidak memiliki mekanisme pencegahan nafsu semacam Festival Togut dengan pakaian putihnya. Namun ada ruangan lain yang lebih ramai daripada kantin. Yaitu aula, tempat pertandingan catur digelar. Wahid menunjuk aku sebagai manajernya.
“Ayolah Az, kemarin kau sudah kuangkat menjadi Nabi.”
Aku menepuk dahi. Seharusnya aku mengikuti jejak Aram, kabur dan seolah menghilang dari dunia. Dia tidak ingin terlibat sedikitpun dalam urusan ini.
Berderet meja panjang telah disusun di dalam aula. Catur-catur yang entah darimana panitia mendapatkan semua itu, juga telah tersusun rapi di atas meja. Wahid dan aku terpesona oleh pemandangan semacam itu.
Di dinding, telah tertampil mekanisme pertandingan yang melibatkan seluruh perwakilan lomba catur dari tiap lokal. Wahid segera mengamati papan mekanisme itu. Lawan pertamanya adalah Zain, perwakilan lokal 2.
“Pertandingan ini akan berlalu sangat mudah,” ujar Wahid menjentikkan jari.
Dia segera mencari meja tempat dia bertanding. Tidak lama kemudian, lawannya, Zain, juga tiba. Pertandingan catur ini segera dimulai. Jika Wahid membawa aku, sebagai manajer, Zain membawa sekelompok siswa lokal 2, teman-temannya sebagai suporter. Jumlahnya belasan. Aku mengamati wajah Wahid, ekspresinya berubah.
“Kau masih bisa bertanding-kan, Hid?” Aku memastikan.
“Tentu saja, sekali libas.”
Jual beli serangan segera terjadi. Pertandingan bisa dibilang balance. Bahkan Zain terlihat lebih defensif. Dia membiarkan Wahid memunguti 4 butir pion tanpa perlawanan. Senyum percaya diri Wahid langsung terkembang. Dia semakin gencar menyerang. Zain semakin bertahan.
Tapi anehnya, lawan Wahid itu sama sekali tidak terlihat terdesak.
Pelan-pelan, ketika Wahid sudah memasuki wilayah kekuasaannya, jaring-jaring Zain mulai merapat. Perwira-perwira Wahid berjatuhan. Tuhan catur itu masuk ke dalam perangkap lawannya. Melihat gerakan Zain yang anggun, suporter mulai beringas. Berteriak.
“ZAIN!! ZAIN!! GO!! GO GO!! KALAHKAN DIA!!”
Seketika aku melihat dahi Wahid berkeringat. Sepertinya dia tertekan oleh yel-yel. Pikirannya tidak lagi jernih. Ujung-ujungnya, raja Wahid terpancung di hadapan dia sendiri. Ironis, ironis sekali.
Ronde dua dimulai. Para suporter Zain langsung berteriak. Menggetarkan langit-langit. “ZAIN!! ZAIN!! GO!! GO GO!! KALAHKAN DIA!!” Bisa ditebak, Wahid kembali kelimpungan. Dia tidak bisa berpikir jernih. Di ronde kedua ini, Wahid kalah tragis. Sulit dipercaya.
Ujung hari ini, Wahid ke kantin. Aku masih mendampinginya sebagai manajer. Manajer dengan klien yang sedang terpuruk. Aram ada di sana. Sedang minum kopi. Wahid memesan, kopi pahit, sepahit-pahitnya. Aram tertawa-tawa. “Jadi sekarang kau sudah lengser jadi Tuhan catur Hid?”
“Tutup mulut kau, Ram. Setidaknya aku masih lebih hebat dari kau.” Aku yang duduk di sana, harap-harap cemas. Mana siapa tahu jika sekali lagi Wahid mengaku jadi Tuhan, kantin ini terbelah macam Laut Merah?
Mozaik 34
Cerita Munir di Tengah Hari
Hari itu, Jum’at. Musim kemarau sedang menerjang Bumi Melayu. Hampir tidak ada angin, seisi rumah pengap. Selepas pulang dari masjid, aku berleha-leha di teras rumah, mencari angin sepoi-sepoi. Seketika ada suara tawa menggelegar dari arah barat daya.
Itu Munir Al-Hambra. Temanku yang unik, yang jago tertawa di setiap keadaan. Ada apa gerangan dia mencariku siang bolong begini. Pasti urusan penting. Segera kuajak dia duduk di teras, dengan minuman dingin sebagai sambutan tamu.
“Ada apa gerangan, Nir?”
“Aku datang untuk mengklarifikasi beberapa hal, Az.”
Kaget aku. Sejak kapan pembawaan Munir jadi mirip pegawai bank.
“Katakan Nir. Apa itu?”
“Wahid sudah menceritakan semua tentang petualangan asmaramu Az. Sungguh berwarna sekali hidup kau setelah lulus dari SMP.”
Aku semakin kaget. Apa saja kira-kira yang dibicarakan Wahid tentang aku. Aku harus tahu lebih jauh.
“Mulai dari Syifa, Mawar hingga Shiela. Bukan main Az, cantik-cantik semua pacar kau.”
“Wahid berlebihan. Aku tidak berpacaran dengan mereka,” aku mengusap wajah.
“Ah sudah Az, aku kenal kau sejak SMP. Tak usah berkelit macam begitu. Tapi terus terang Az, aku tidak tertarik dengan Syifa ataupun Mawar, tapi Shiela, aku harus tahu lebih detail di bagian ini.”
“Apa yang kau mau.”
“Ceritakan bagaimana hubungan kalian.”
“Biasa saja. Kami berteman, sering ngobrol di kantin jika waktunya pas, dan aku beberapa kali men-chat-nya jika ada sesuatu hal yang penting.”
“Itu benar-benar cerita yang tidak bermutu Az.”
“Astaga, lalu aku harus bercerita seperti apa,” aku berdecak sebal.
“Mari aku contohkan,” Munir bersila. Mulai bercerita.
***
Kisah pertama ini tentang Risky Ramdhan. Begawan cinta level dewa dari lokal 2. Dia sesumbar punya lebih dari 250 mantan pacar dan telah putus dengan mantannya yang ke-251. Dia bilang akan segera mencari pengganti, dan target diarahkan pada Shiela. Kemarin dia mulai bergerak, mendekati Shiela yang sedang duduk tenang di kursinya, di pojok. Sebagaimana kebiasaan Shiela.
“Hai, Shiela.” Risky Ramdhan mulai membuka percakapan, menarik kursi dan duduk di depan Shiela.
Shiela diam saja.
“Shiela, kok kamu bisa jadi pintar sekali sih, bagi-bagi tipsnya dong,” kata Risky lagi.
Shiela diam.
“Boleh aku mengenalmu lebih jauh Shiela?” Risky masih tidak menyerah.
Shiela tetap diam.
Risky pura-pura mati.
***
Benar-benar cerita yang luar biasa. Dengan gaya bahasanya yang khas, dan tawanya di sana-sini, Munir sukses membuatku terpingkal.
“Bukan itu saja Az,” kata Munir setelah semua tawa reda.
“Ada lagi?”
Munir mengangguk. “Paderi juga sempat coba mendekati Shiela. Mungkin tertantang dengan Risky Ramdhan.”
“Ceritakan padaku.
***
Siang hari menjelang jam istirahat makan siang, Lokal 2 sudah sepi karena sebagian besar penghuninya ke kantin. Saat itulah, Paderi datang kepada Shiela. Secara teknis, mereka rekan se-organisasi, OSIS.
“Hai Shiela,” Paderi menyapa. Shiela mendongak, balas menyapa, “Ada apa Pad?”
“Ke kantin yuk, bahas rapat OSIS.”
“Eh ada rencana rapat-kah? Seingatku tidak ada.”
“Kalau begitu lupakan kita lupakan rapatnya dan kita ke kantin saja.”
“Kalau begitu kamu ke kantin saja dan tidak perlu mengajakku.”
Paderi tersenyum hambar.
***
Lagi-lagi pembawaan Munir membuat cerita itu menjadi semakin lucu. Aku terpingkal-pingkal membayangkan kegagalan Paderi. Menyaksikan rival asmara kalah tragis seperti itu, sungguh menyenangkan, kawan.
“Baiklah, semua ceritamu ini sangat lucu Nir. Tapi aku tahu kau tidak datang ke sini hanya untuk berbagi cerita. Jadi sudah waktunya kau katakan apa maksudmu yang sebenarnya,” aku memandangnya selidik.
“Nah itu Az, setelah kejadian Risky Ramdhan mendekati Shiela kemarin, lokal kami berubah seakan menjadi arena perburuan. Targetnya jelas, Shiela Camalia. Sebenarnya aku juga ingin ikut berburu. Mana tahu aku bisa dapat pacar secantik itu, jadi aku minta tips padamu.”
“Tips?”
“Iya Az, kau adalah satu-satunya cowok di Quart School yang bisa duduk berjam-jam, ngobrol dan berdekatan dengan Shiela Camalia.”
“Astaga Nir, aku tidak punya tips semacam itu.”
Munir siap memasang sikap menyembah-nyembah.
Mozaik 35
Observasi Azka
Aku jelas tertarik dengan cerita Munir. Perburuan Shiela telah dimulai, katanya. Hei itu istilah yang menarik. Aku jadi tertarik, setidaknya untuk mengamati jalannya perburuan itu, apalagi ada Paderi yang tak tahu diuntung ikut di sana.
Hari Senin, tiga hari setelah Munir bercerita, saat aku lewat di depan lokal 2, samar-samar aku mendengar percakapan. Rasanya itu suara Risky Ramdhan, begawan cinta yang sudah terkenal di seluruh sekolah. Kemungkinan dia bercakap-cakap dengan Shiela. Segera, dengan gerakan terselubung, aku bersandar di dinding, mencuri dengar.
“Apa kabar Shiela?”
Tidak ada jawaban, kurasa Shiela sedang mengangguk atau diam.
“Mau ke kantin Shiela?”
Tidak ada jawaban, kurasa Shiela sedang menggeleng atau diam.
“Astaga ngomong dong Shiela, tidak seru kalau cuma diam-diaman seperti ini.”
“Iya,” nah kali ini kudengar Shiela bicara, walau pelan saja. Kudengar pula Risky berdecak.
“Bisa tidak Shiela bicara lebih panjang lagi?” nada suara Risky sudah mulai gusar.
“Kenapa kau terlihat begitu marah, apakah itu karena ini bulan-bulan terakhir Persephone ada di bumi?”
Bisa kudengar Risky bersorak. Mungkin dia senang sekali bisa membuat Shiela bicara lebih dari lima kata. Tapi suaranya kemudian terdengar bingung, “siapa itu Persephone?” kata Risky, kentara betul dia tidak pernah menyebut kata itu seumur hidupnya.
“Anak dari Ceres, suami dari Pluto.”
“Ah sudah, aku mau ke kantin saja,” sergah Risky gusar. Aku susah payah menahan tawa. Jelas sekali, PDKT ini gagal karena percakapan jenius.
Di lain waktu dan lain kesempatan, aku memergoki momen lainnya di kantin. Shiela sedang makan nasi goreng, ketika seorang pria mendekatinya. Pria itu, aku tidak kenal siapa, yang jelas dia segera menyapa Shiela. “Hai.”
“Hai juga.”
“Apa kabarmu, Shiela?”
“Kabar baik.”
“Sepertinya itu nasi goreng yang enak.”
“Iya.”
Pria itu kemudian memesan nasi goreng yang sama. Ketika pesanannya datang, Shiela sudah selesai makan. Dia segera berdiri. Pria tadi buru-buru mencegah. “Mau kemana Shiela?”
“Perpustakaan.”
“Eh temani dulu aku makan.”
“Tidak, terima kasih.”
Aku kembali susah payah menahan tawa. Sekaligus tersenyum geli. Munir benar, jika saja aku yang duduk di sana, mungkin Shiela tidak buru-buru pergi. Mungkin dia akan mengajakku ngobrol, panjang lebar dengan senang hati. Ah, aku mulai tertarik dengan perburuan ini.
Malamnya, aku mencoba men-chat Shiela. Bar statusnya menunjukkan terakhir kali dilihat yang lama sekali. Mungkin itu adalah saat aku dulu men-chat-nya juga. Hal-hal seperti ini kutegaskan untuk menunjukkan seberapa spesialnya aku bagi Shiela Camalia.
“Shie.”
“Puniii, Azk.”
“Apa kabarmu Shie?”
“Aku selalu baik Azk. Aku berusaha untuk selalu baik. Kalau kamu?”
“Tidak terlalu Shie.”
“Kenapa ya Azk, aku merasa kamu menghubungiku pas setiap galau terus. Apakah itu kebetulan?”
Astaga, aku salah strategi. Terpaksa kujawab dengan kalimat klise, “aku cuma tidak ingin mengganggu hidupmu yang sibuk itu terlalu sering Shie.”
“Aku tidak pernah keberatan Azk. Pembicaraan kita selalu bisa menjadi selingan yang menyenangkan.”
“Bagaimana kalau kita makan-makan Shie?”
“Boleh Azk, tapi jangan ada misi lagi.”
Aku tertawa, “iya Shie, bisakah kamu rekomendasikan tempat lain, aku bosan dengan Sahajaku.”
“Oh boleh, kita ke 3 Warna saja. Di sana, makanannya lebih enak. Walau lebih ramai.”
“Kamu punya masalah dengan keramaian itu?”
“Tidak masalah Azk.”
“Kalau begitu kita sepakat.”
Mozaik 36
Hanya Pura-pura Kok...
Shiela benar. Kafe yang dipilihnya lebih ramai daripada Sahajaku. Agak kesulitan aku menemukan dimana dia duduk. Celingukan kepalaku. Untunglah kemudian, Shiela melambaikan tangan. Aku segera mendatanginya.
“Kamu benar Shie, tempat ini lebih ramai,” itulah kalimat sapaanku, aku menarik kursi, duduk.
“Kamu mau makan apa Azk?”
“Apapun yang kamu pesan, aku ngikut saja. Pilihan orang cerdas biasanya menarik.”
“Kayak kamu tidak cerdas saja Azk.” Shiela melambaikan tangan pada seorang “mas pramusaji”. Orang itu mendatangi meja kami dengan ekspresi senang. Shiela segera membacakan pesanannya, sejenis makanan yang namanya sulit kueja. “Aku pesan apapun yang dia pesan,” sahutku cepat saat mas pramusaji melihat ke arahku.
Tiba-tiba Mas pramusaji itu bersuara. “Saya akan beri mbak ekstra kentang tumbuk kalau mbak mau memberi nomor telepon.”
“Tanya sama dia,” Shiela menunjukku santai, “dia cowokku.”
“Eh tidak mbak,” Mas pramusaji itu gelagapan, “baik saya tidak akan mengganggu. Pesanan akan segera siap. Tolong lupakan apa yang tadi saya bilang Mas,” katanya padaku, seperti mengiba-ngiba. Semua kejadian itu berlangsung sangat cepat.
Aku dan Shiela susah payah menahan tawa melihat ekspresi pramusaji barusan. Dia macam kalah perang, dari ekspresinya dia sama sekali tidak meragukan aku sebagai kekasih Shiela Camalia.
Bukankah itu lucu, kawan?
Makanan-pun sampai, mas pramusaji yang tadi agak gemetar menyerahkan pesanan ke hadapanku dan Shiela.
“Astaga Shie, menurutku kalimatmu tadi sedikit berlebihan.”
“Habisnya Azk,” Shiela menghela nafas, mengambil sendok, “aku terkadang risih dengan cowok-cowok semacam itu. Entah kenapa dalam beberapa hari terakhir, mereka menggila. Hampir setiap cowok yang kutemui, pasti berbasa-basi membosankan denganku, dan ujung-ujungnya merayu. Tidak di kelas, di kantin, di room chat, sampai ke sini-pun masih sama.”
“Habisnya kamu memang pantas menerima semua itu, Shie.”
“Eh maksudmu?”
“Bukan negatif, maksudku adalah, kamu memang memiliki kualifikasi untuk jadi seorang primadona Shie. Aku sudah pernah mengatakannya bukan?”
“Huft, tapi tidak harus seperti juga Azk. Lama-lama aku merasa ingin menyamar saja. Memakai kacamata, masker dan mengubah aksen suara.”
“Hei segitunya kamu ingin menghindar?”
“Kalau bisa lebih dari itu akan kulakukan.”
“Tapi kenapa kau menutup diri dari mereka, dan malah membuka diri padaku?” tak tahu dorongan dari mana, yang membuat aku bertanya seperti itu.
“Kamu bisa mengimbangi pembicaraan denganku Azk, sehingga mengobrol denganmu bisa jadi sesuatu yang nyambung, mengasyikkan. Mereka tidak.”
Aku teringat ekspresi Risky Ramdhan kemarin.
“Aku sudah dengar dari sumber terpercaya Shie, siswa Quart School memang sedang berlomba mendapatkan hatimu. Mereka membuat semacam perburuan.”
“Astaga Azk, sungguh mengerikan. Sepertinya aku harus memikirkan cara menghentikan mereka. Kamu ada saran?”
“Mereka tidak akan berhenti sampai ada yang berhasil mendapatkan hatimu. Biasanya begitu. Serupa padang rumput di Utah, tidak akan berhenti diperebutkan, sampai ada yang bertani di atasnya.”
Tiba-tiba Shiela tersenyum. Aku kira itu senyum senang karena aku baru saja mengaitkan dirinya dengan Utah. Shiela suka percakapan sejenis itu. Ternyata tidak, bola matanya berbinar-binar, dia mendapat inspirasi!
“Aku tahu Azk,” serunya bersemangat, “aku tahu bagaimana membersihkan semua orang itu, serupa Hitler membersihkan kota Danzig.”
“Apa itu?”
“Berjanjilah untuk dua hal, kamu tidak tertawa dan kamu bersedia membantuku.”
“Baiklah, aku berjanji,” sahutku cepat. Aku penasaran.
“Kamu benar Azk, ada satu cara ekstrem untuk menghentikan mereka, yaitu menerima seseorang jadi kekasihku. Walau aku tidak tertarik untuk pacaran, aku masih bisa berpura-pura.”
“Kamu mau pura-pura menerima salah satu dari mereka? Sepertinya itu bukan pilihan yang baik.”
“Nah makanya itu,” suaranya makin pelan, “aku membutuhkanmu Azk. Maukah kamu… ehm… pura-pura jadi kekasihku, sampai gelombang pemburu ini berhenti.”
Shiela susah payah menyelesaikan kalimatnya. Pipinya bersemu merah. Aku terpaku di tempat. Oh Tuhan, ampuni aku. Tawaran Shiela ini terlalu menggiurkan untuk ditolak.
Aku mengangguk malu-malu. Shiela tersenyum senang. Hari itu, secara teknis, aku resmi jadi kekasih Shiela Camalia.
Mozaik 37
Babak Mabuk Cinta Azka-Shiela
Jam pelajaran kelas khusus kewirausahaan akhirnya usai. Itu berarti jam istirahat pertama telah tiba. Teman-teman sekelasku banyak yang bergegas ke kantin, karena di jam inilah paling enak menghabiskan uang. Jam istirahat makan siang nanti, mereka tinggal tidur saja.
Aram dan Wahid lain lagi. Begitu Bapak Dahri Ariyanto menghilang dari pintu, mereka bergegas menuju ke kursi belakang, mengeluarkan papan catur legendaris. Sejak kekalahan Wahid di Hari Suka Raya, dua seteru itu terus bertanding untuk mengukur kemampuan masing-masing. Aku tidak tertarik untuk ikut, rencanaku saat jam istirahat pertama ini, aku ingin menulis novel. Adapun Nasri, duduk di depanku, merenung saja.
Saat itulah, masuk chat ini. “Kamu sibuk? Boleh temani aku ke kantin, Azk. Eh salah… ehm, beb.”
Itu chat Shiela. Membaca chat darinya aku seolah mendengar dia mendehem nakal di ujung kalimat. Aku mengaduk kepala. Perlu waktu bagiku untuk terbiasa menerima chat semacam itu. Baiklah. Aku memasukkan kembali laptop. Tindakan yang membuat Nasri heran.
“Tidak jadi mengerjakan proyek Az?”
“Tidak Nas.” Aku berdiri, siap meluncur ke kantin. Sebaiknya aku cepat, aku tidak boleh membiarkan Shiela menunggu.
Aku menjemputnya ke lokal 2. Agak gugup juga masuk ke sana, karena jika mengingat cerita Munir, aku ibarat masuk ke sarang singa. Kuhela nafas sejenak. Shiela ada di sana, duduk tenang, membaca buku.
“Maaf ya Azk, aku jadi merepotkanmu begini,” katanya meletakkan buku, begitu aku sampai.
“Tidak masalah Shie.”
“Deduksiku mengatakan sebenarnya kamu tidak ingin ke kantin.”
“Tepatnya tidak terbiasa,” aku memotong, “tapi aku siap menemanimu. Ayo berangkat.”
Bisa kurasakan ada singa-singa yang menatap nanar ke arahku. Astaga, belum juga kupegang tangannya.
Saat sampai ke kantin, kutanya Shiela, dimana dia hendak makan. Dia nyengir, katanya ikut saja dimanapun bebeb-nya makan. Serius kawan, mendengar dia mengucap hal-hal demikian, merinding aku.
Karena mengingat janji manis dan promosi Paman Pirates tempo hari, aku memutuskan singgah ke kedainya. Seakan dirancang semesta, entah bagaimana, hari ini Paman Pirates menyediakan Nasi Pecel. Klop
Kau bisa membuatku bangkrut Az. Demikian kira-kira maksud Paman Pirates saat menyambut kedatanganku dan Shiela.
Kami segera mencari tempat duduk yang nyaman. Duduk bersebelahan. Berdempetan. “Aku tak tahu sebenarnya darimana kamu mendapatkan ide gila ini Shie.” Aku membisikinya. Shiela terkekeh.
“Tenang saja. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Hehe. Kamu terlihat tampan kok, Azk, eh salah, beb.”
Aku mengusap wajah lagi.
“Aku tidak tahu Shiela bisa jadi secentil ini.”
“Ayolah Azk, dunia ini memang unik. Pria paling santun di Barat adalah seorang pembunuh, sedangkan gelandangan paling menjijikan di Persia justru seorang raja. Penampilan bisa mengecoh. Lagipula aku harus melakukan ini, agar kita tidak terlihat sedang bermain peran.”
Aku hanya ingin minta kamu tidak membuatku serangan jantung, Shie.
“Terima kasih sudah menemaniku hari ini Azk. Kuharap besok kita bisa menghabiskan waktu seperti ini lagi.”
Aku tersedak. Shiela mengetahui hal itu.
“Maaf jika ini merepotkanmu Azk. Aku janji ini tidak akan lebih dari seminggu.”
Aku menghela nafas. Aku tidak keberatan Shie. Aku tidak pernah keberatan. Siapapun tidak akan keberatan. Tapi aku harus membiasakan diri. Lama-lama mungkin aku tidak hanya bersedia untuk jadi kekasih pura-puranya, aku ingin jadi kekasihnya selamanya.
Selama satu minggu, Shiela mengajakku berkeliling kantin. Tujuannya tentu saja memamerkan aku sebagai kekasihnya. Agar tidak ada lagi orang yang berani mengganggu dia. Tapi itu juga membawa pisau bermata dua bagi aku. Aku telah berani membuka permusuhan dengan para pemburu. Aku sudah memprediksikan hal ini, jadi aku tahu resikonya. Aku harus siap menerima konsekuensinya. Termasuk saat ada yang menarik tubuhku ke belakang sekolah.
Aku mengenali orang itu. PADERI TAMTAMA!!
Paderi mondar-mandir di hadapanku. Dari gerakannya, aku tahu dia akan marah besar. Aku mencoba tetap tenang, selain itu aku juga berusaha mengingat jurus-jurus Silat merpati yang dulu pernah kupelajari. Siapa tahu, Paderi ingin adu tinju.
“Kau sungguh tidak pantas Az!” Paderi mulai menyalak.
“Maaf, aku tidak paham konteks kalimatmu,” aku menyahut tenang.
“Kenapa kau selalu ikut campur dalam setiap urusan asmaraku, dari Syifa, sekarang Shiela. Tak tahu diuntung!”
“Maaf, tapi aku tahu aku pantas melakukan itu. Mereka adalah perempuan-perempuan bebas.”
“Jangan bercanda. Shiela terlalu hebat untuk orang sepertimu. Dia terlalu cantik dan jenius untuk jatuh cinta dengan orang sepertimu.”
“Maaf, tapi aku benar mendapatkan dia. Jadi aku kira aku pantas untuknya.”
“Pantas katamu,” Paderi menyalak lagi, “aku hanya melihat ada dua faktor. Satu, kamu terlalu beruntung, dua, kau hanya dimanfaatkannya. Manapun itu, kau hanya akan sakit pada akhirnya.”
“Maaf, tapi sebagai pemiliknya, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi.”
Paderi tertawa keras. “Percaya diri sekali kau Az. Ingat baik-baik kata-kataku. Hubungan ini akan berakhir dengan cepat. Bahkan lebih cepat dari yang bisa kau sangka.”
“Maaf, saat ini aku adalah kekasihnya, aku berhak melakukan apapun untuk mempertahankan dia, dan aku akan berusaha keras untuk itu.” Aku menyahut tegas. Paderi hendak meninjuku, tapi lekas kutangkis. Dia makin murka, tapi sadar tidak bisa berbuat apa-apa.
Mozaik 38
Hanya Saja Aku Tidak Sedang Berpura-pura
Sabtu. Adalah hari yang kusepakati dengan Shiela, bahwa ini adalah hari terakhir kontrak kami sebagai sepasang kekasih. Shiela sendiri bercerita padaku bahwa jumlah orang yang meliriknya kian berkurang. Aku urung bercerita bahwa orang yang ingin menjotosku setiap hari kian bertambah.
“Azk, hari ini kamu mau menemaniku ke perpustakaan tidak?” Shiela mengirimiku chat.
“Tentu saja.”
“Baik, sampai jumpa esok, beb.”
Aku mengaduk rambutku. Tiga huruf yang dikirim di akhir kalimatnya itu sukses membuatku panas dingin. Hei, bagaimana tidak kawan, pesan itu dikirim oleh gadis secantik Shiela Camalia. Sila kawan sebut definisi cantik, semua itu ada pada Shiela. Aku tak bisa menggambarkannya dengan kata-kata.
Esok, aku tiba di perpustakaan Quart School. Hari Jum’at sore sehabis shalat Jum’at. Shiela sudah menungguku di sana.
“Makasih ya Azk, sudah mau repot-repot berpura-pura jadi kekasihku. Astaga, sejujurnya aku menikmati momen-momen itu Azk. Menarik sekali. Pantas saja, banyak orang kecanduan pacaran.”
Aku tersenyum meringis. Terlalu dekat dengan Shiela bisa membuyarkan akal sehat. Aku alihkan pandangan pada buku-buku yang ditumpuknya di hadapan dia. “Apa ini bahan bacaan terbarumu Shie?”
Beberapa buku di sana bisa kukenali. Buku-buku biografi. Alexander The Great, Jengis Khan, Napoleon dan Hitler. Menarik sekali.
“Aku sedang tertarik mengumpulkan data-data tentang para pemimpin hebat yang tidak sempat menikmati kekuasaannya sendiri.”
“Kamu sudah baca semua ini?” aku bertanya lagi.
“Hanya sekilas-sekilas saja. Aku tertarik sekali mencari kesamaan antara mereka berempat. Itu menggangguku Azk. Bahkan aku kabur dari kelas hanya untuk ini.”
“Kamu di sini sepanjang hari?”
“Iya Azk. Jika saja kamu bisa menunjukkan kesamaan dari mereka berempat, aku sangat berterima kasih.”
Oke kawan, mulai dari sini, bacaan ini akan sedikit intelektual.
“Mereka sama-sama menguasai daerah yang sangat luas.”
“Benar,” sahut Shiela cepat. Kurasa dia sudah tahu itu.
“Mereka sama-sama meninggal dengan cara yang tragis.”
“Benar,” sahut Shiela, lagi-lagi dia sudah tahu tentang itu.
“Mereka memiliki hamparan kekuasaan yang mencakupi suku bangsa dan budaya yang sangat berbeda.”
“Eh kurasa itu benar.” Shiela mulai ragu. Bisa kulihat sinar kecerdasannya memancar.
“Selain Alexander, semuanya menemui kegagalan dan kecelakaan besar dengan menyerbu Rusia.”
“Astaga Azk,” Shiela berseru, “aku belum terpikir mengenai itu, terima kasih Azk.” Shiela memasang ekspresi yang benar-benar senang. Kurasa jika saja tidak ada norma kesopanan di Quart School, dia bisa saja memelukku.
“Hei, bagaimana kalau kita mencari makan setelah ini Azk. Aku puas sekali dengan jawabanmu tadi.”
Aku mengangguk.
Setibanya di parkiran, aku heran dengan tingkah Shiela yang terus mengekor langkahku.
“Aku tadi ke sekolah diantar. Jadi ini pengen nebeng kamu saja. Kamu tidak keberatan-kan Azk,”
Lagi-lagi aku hanya bisa mengangguk. Cewek primadona Quart School itu sekarang duduk di boncenganku. Manis kawan, rasanya manis sekali.
“Sahajaku atau 3 Warna?”
“Sahajaku saja deh Azk. Di sana lebih nyaman. Lagipula aku ingin makan Nasi Goreng Sahaja.”
Kami meluncur ke Sahajaku. Sepanjang jalan, landscape terasa sinetron Indonesia. Kejadian paling sinetron justru saat kami duduk semeja. Saat itu Shiela nekat menyingkirkan piring nasi gorengnya dan menyendok dari piringku. Heran sekali aku.
“Itu Azk, ada cowok yang dari tadi menatap nanar ke arahku. Aku takut. Kita makan sepiring berdua ya.”
Aku mau bilang apa lagi, tak sabar saja ingin menelan sendok yang sempat singgah di bibir indah Shiela.
Oh Tuhan, perasaan ini benar-benar indah. Aku tak bisa berbohong bahwa aku tidak sedih dengan berakhirnya pacaran pura-pura ini. Aku masih sangat-sangat ingin berdekatan dengan Shiela. Hatiku berbisik nakal. Aku berusaha menenangkan “teman kecil”-ku itu dengan mendebatnya.
“Sudah tembak saja, mumpung dekat begini.”
Kalau dia tolak bagaimana?
“70% bakal diterima.”
Bagaimana kau bisa seyakin itu?
“Ayolah, Shiela sebenarnya cuma cari alasan agar bisa berdekatan denganmu. Dia aslinya memang suka denganmu. Kalau tak, takkan-lah dia repot-repot mau pacaran pura-pura. Masih banyak cara lain yang bisa dia pakai.”
Pada akhirnya hatiku menang. Aku ambil handphone, untuk melakukan tindakan yang gila, menembak Shiela Camalia.
“Shie, aku ingin bicara serius.”
Pesan itu langsung bercentang dua, tidak lama kemudian membiru, dan kemudian muncul tulisan hijau menggoda itu. Dalam waktu yang cukup lama. Butuh 5 menit lebih bagi Shiela untuk mengetik. Apa yang ingin dia katakan? Ketika pesannya masuk, tahulah aku bahwa dia sudah mendeduksi.
Sila kawan baca baik-baik
“Maaf sebelumnya jika aku langsung menduga-duga Azk. Ketika kamu memakai kata “serius” dalam chat di atas, aku langsung menduga arahnya, pasti soal perasaan. Ya sebenarnya itulah taruhan dari status “pura-pura” yang kutawarkan. Aku tahu kalau kemungkinan kamu benar-benar suka padaku pasti muncul. Kukira cinta di dalam hatimu, cukup untuk mencegahmu menyukaiku. Ternyata tidak rupanya. Baiklah Azk, aku minta maaf, aku tidak bermaksud membuatmu menyukaiku, dan jelas aku tidak bisa menerima perasaanmu itu, karena aku berdiri di atas komitmen (yang mungkin kau sendiri juga tahu). Aku benar-benar minta maaf, tapi aku menghargai perasaanmu itu kok Azk. Kutawarkan minum di Sahajaku sebagai permintaan maaf.”
Aku balas pesannya dengan singkat dan padat, “maaf Shie, aku juga merepotkanmu. Kurasa tidak perlu minum-minum lagi, ini sudah cukup hebat.”
Kawan, diantara kita saja, sebenarnya aku tidak terlalu kaget Shiela menolak dan menyebut-nyebut soal komitmen. Yang membuatku terguncang adalah kata “menghargai” itu. Kata yang mengingatkan aku pada satu kejadian di masa yang silam.
Mozaik 39
Pidato Singkat Kepala Sekolah
Hari demi hari terus berjalan. Tak terasa, kami telah sampai di ujung perjalanan studi kami di Quart School. Ini bulan April. Bagi semester 6, bulan ini adalah bulan-bulan ujian yang super sibuk. Untuk menyambut bulan ini, kepala sekolah mengumpulkan kami di lapangan. Beliau terlihat bersemangat.
“Anak-anakku, siswa Quart School yang berbahagia. Tadi pagi Bapak bangun, dan mendengar kabar dari matahari, bahwa bulan April telah datang,” buka beliau dramatis. Kami menunggu beliau melanjutkan kalimatnya.
“Bulan April selalu spesial. Terutama sekali bagi siswa yang kini duduk di semester 6. Di depan mata kalian telah menanti ujian-ujian penting sebagai tahap terakhir studi kalian di sekolah yang megah ini. Hari ini akan saya kabarkan lagi, ujian apa saja yang akan kalian hadapi. Jangan khawatir, jangan takut, ujian ini jangan dipandang sebagai momok, ujian ini adalah tantangan, batu loncatan yang harus kalian taklukkan.”
Heroik sekali pak kepala sekolah hari ini.
“Ada tiga macam ujian. Yang pertama, bersifat praktek, meliputi tiga mata pelajaran, yang memang memerlukan praktek. Kewirausahaan, Seni Budaya, dan Olahraga. Ujian kedua adalah ujian akhir sekolah, meliputi semua mata pelajaran formal Quart School, dan terakhir, Ujian Nasional.”
Aku menarik nafas.
“Kalian harus serius dalam ketiga ujian itu. Karena nilai-nilainya akan terpampang di ijazah kalian nanti. Bapak akan memberikan kabar ekstra gembira jika kalian berjanji akan serius dalam ujian kali ini. Kalian bersedia berjanji?”
“KAMI BERJANJI!!” Koor suara memenuhi lapangan.
“Ada dua macam reward yang menanti kalian di akhir ujian. Yang pertama, Piala Quart School Champion, bagi siapapun yang mengemas nilai tertinggi di Ujian Akhir sekolah, dan dana beasiswa untuk yang bisa mencapai nilai Ujian Nasional tertinggi se-kabupaten. Piala Quart School Champion hanya untuk satu orang, tapi beasiswa ada untuk 3 orang, jadi bersemangatlah belajar. Berikan yang terbaik, perlu saya sebut nama di sini? Shiela Camalia? Nasri Abdillah?”
Darahku menggelegak. Entah kenapa aku diam-diam bertekad belajar sungguh-sungguh, untuk mendapatkan salah satu reward itu. Walau aku sendiri belum tahu bagaimana caranya mengungguli dua bintang sekolah paling cemerlang itu.
Mozaik 40
Ujian Praktek Kewirausahaan
Sebelumnya tak kusangka kawan, bahwa kelas khusus kewirausahaan, yang tidak memegang status sebagai mata pelajaran utama di Quart School, akan memiliki ujian prakteknya sendiri. Ujian praktek yang membikin aku merinding memikirkannya.
Bayangkan, dari namanya saja, sudah terasa arah ujian praktek ini. Pasti berhubungan dengan “kewirausahaan”. Sepertinya itu akan merepotkan, bagaimanapun bentuknya.
Hari ini Bapak Dahri Ariyanto, menerangkan seperti apa ujian praktek kewirausahaan itu.
“Sebagaimana pidato kepala sekolah kemarin, dan sebagaimana prosedur sekolah kita, hari ini bapak ingin menerangkan bagaimana pelaksanaan ujian praktek kewirausahaan.”
Bapak Dahri Ariyanto menarik nafas sejenak, mengedarkan pandangan pada kami. Kemudian beliau melanjutkan.
“Mungkin kalian masih ingat, tahun lalu, kakak-kakak kelas kalian menjual snack makanan ringan ke kelas-kelas. Sebenarnya itu salah, mereka mengakali instruksi dari Bapak. Yang bapak suruh adalah mereka melakukan kegiatan kewirausahaan yang bermanfaat, misal menjual alat tulis, buku tulis, snack mungkin boleh, tapi tidak harus semuanya. Mungkin kesalahan Bapak juga memberi instruksi yang kurang jelas tahun lalu. Maka tahun ini…”
Aku sudah punya firasat pasti kami menjadi pelampiasan kegagalan sistem. Selalu kami.
“Bapak akan memberikan tugas yang spesifik pada kalian. Kalian harus membuat dan menjual jajanan tradisional Melayu yang khas. Misalnya wadai untuk-untuk, wadai gagatas, wadai bingka tapai dan yang sejenis dengan itu, tradisional Melayu. Agar menarik, Bapak akan menilai kalian dengan sistem poin. Kalian harus buat 20 buah kue atau jajanan, satu kue dinilai 5. Yang bisa menjual semuanya, dapat nilai sempurna 100. Jangan coba-coba main curang, Bapak akan mengawasi kalian. Oh ya, kalian harus bikin video dokumentasi saat pembuatan kue itu. Ada pertanyaan?”
Kelas hening saja. Bapak Dahri Ariyanto tersenyum puas. Beliau menyebutkan tanggal main ujian ini, satu minggu dari hari Kamis sekarang.
“Tugas ini dibuat berkelompok, satu kelompok terdiri atas 6 orang.” Itulah instruksi terakhir Bapak Dahri Ariyanto sebelum meninggalkan kelas.
Aku memahami apa yang dipikirkan oleh teman-teman sekelasku. Faktanya mereka adalah remaja tanggung Bumi Melayu yang sama sekali tidak pandai membuat jajanan tradisional. Jangankan membuat, memakannya saja mereka amat jarang. Bagaimana caranya mengerjakan ujian praktek ini kalau demikian?
Saat itulah Azka punya solusinya.
Sebut aku beruntung kawan. Bukan saja karena aku terlahir sebagai anak kampung yang terperosok nun jauh di pelosok, tapi juga karena ibuku adalah pembuat jajanan tradisional Melayu yang amat terampil. Jika aku mengungkapkan fakta itu pada kawan sekelasku, bayangkan apa reaksi mereka. Tentu saja mereka akan rebutan ingin masuk kelompokku.
Makanya aku memendam saja, informasi berharga ini. Aku akan diam-diam membentuk kelompokku sendiri, dari orang-orang yang dekat denganku saja. Yang pertama-tama kutawari, adalah Lia. Sayangnya gadis pemilik senyum manis itu menggeleng. “Maaf ya Az, aku sudah janji ikut kelompok April.”
Huft, aku menghela nafas kecewa. Gagal lagi sekelompok denga Lia.
Aku urung mengajak Nasri, karena dia pasti sudah sekongkol dengan Lia dan Mei. Maka dari itu, aku memutuskan mengajak Aram dan Wahid saja. Pertimbangannya di sini, adalah promosi. Aram dan Wahid memiliki mulut berbusa-busa yang bisa diandalkan untuk menjual kue itu nanti.
Saat kutawari masuk kelompokku, keduanya bersorak, memelukku macam tak ada hari esok. “Terima kasih Az, kau menyelamatkan nilaiku,” ujar Aram dramatis. Dengan aku dihitung, sudah 3 orang dalam kelompokku ini. Tinggal mencari 3 lagi.
“Boleh aku ajak Intan Az?” tawar Aram.
“Kenapa harus dia?”
“Kasihan dia Az, tidak punya kelompok.”
Walau aku tahu apa motif sebenarnya Aram menawarkan Intan, akhirnya aku setuju. Tapi jangan pikir aku tidak tahu trik asmaramu itu Ram, tidak bermutu. Aram kembali memelukku macam tak ada hari esok. Dengan bergabungnya Intan, tinggal dua orang lagi yang harus kucari.
Siang itu, Intan menemuiku di kantin. Dia berkata dengan pelan, “Az, kudengar Aram mengusulkan aku ikut kelompokmu?”
“Iya.”
“Boleh tampung Hamed tidak Az? Sekalian. Kasihan dia tidak punya kelompok.”
Apa? Hamed? Aku menggeleng keras. Aku tidak suka Hamed ada di kelompokku. Masih kentara di benakku bagaimana dia berseteru jalan denganku dan tak pernah menyapaku selama dua tahun.
Tak, aku tidak akan menerima Hamed.
Kugelengkan kepala di hadapan Intan. Dia memasang wajah kecewa. Aram ada di sana, dia membisikkan surah Al-Lahab ke telingaku. Aku mengangguk takzim. Seketika aku menyetujui Hamed ada di kelompokku. Entah kenapa. Itu berarti, kelompokku tinggal kurang satu orang.
Satu orang pelengkap itu, adalah orang mendatangiku di parkiran saat pulang sekolah. Dia mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba merayuku. Dia adalah Mawar Alvera.
“Ayolah Az, aku ditinggal di kelompoknya Mei. Bingung aku mencari kelompok mana lagi. Kudengar dari Hamed, kelompokmu masih kurang satu orang.”
“Iya tapi…” aku berusaha menunjukkan ekspresi bahwa aku sedang menimbang-nimbang.
“Kumohon Az. Aku butuh bantuanmu. Aku yakin, Azka selain cerdas, juga baik hati. Boleh ya Az?”
Aku menarik nafas. Hatiku tertawar. Siapa pula yang tidak tertawar jika dibujuk oleh gadis tercantik di Quart School?
Kelompokku genap 6 orang.
Mozaik 41
Membuat Kue di Rumah Azka
Setelah formasi kelompok dibentuk, aku mulai melakukan konsolidasi. Bapak Dahri Ariyanto mengajarkan tentang hal itu.
Aku mulai bicara dengan ibuku tentang pembuatan kue tradisional apa yang menarik dan bisa cepat laku terjual. Ibuku menyebut bahwa papare dan gagatas adalah dua jajanan tradisional yang amat diminati.
“Tengok sana ke kedai kopi Paman Asad, kue apa yang paling cepat laris,” tantang ibuku. Jadilah aku riset ke kedai kopi Paman Asad, kedai paling ramai di kampungku. Selama dua hari penuh pemantauan di hari libur, aku mengambil kesimpulan, yang paling cepat habis adalah gelas kopi, karena yang minum kopi di sana ramai sekali
Aku mufakat mengambil dua jenis jajanan yang telah disebutkan ibu. Hanya saja ada satu masalah dalam konsolidasiku dengan Ibu. Kata ibuku, jajanan kue itu dibuat di waktu subuh, dan dijual di waktu pagi. Tidak mungkin dibuat di waktu sore (ini rencana awalku dengan kelompokku), karena adonannya tidak akan enak lagi. Tapi aku-pun sadar, tidak mungkin kelompokku datang ke rumahku di waktu subuh, demi membuat video dokumentasi, sebab rumahku gelap.
Akhirnya hasil konsolidasi dengan Ibu, kubawa ke kelompok. Aram langsung menyarankan rapat sangat terbatas. Kini kami yang harus berkonsolidasi. Ah kawan, semakin banyak kata konsolidasi itu, heroik sekali rasanya. Kami bertemu di kedai kopi Paman Pirates sepulang sekolah.
“Kita harus mencari solusi untuk ini,” kataku, mengakhiri penjelasan panjang lebarku yang berbau keluh kesah itu.
“Astaga kenapa jadi susah begini,” Hamed menimpali. Dia memang senang berkeluh kesah.
“Kita tidak boleh mengeluh. Kita harus bergerak mencari solusi,” Mawar menengahi. Diam-diam kulihat Wahid tidak berkedip memandangi Mawar bicara. Dasar. Baiklah, bukan saatnya membicarakan hal itu.
“Sudah, kalian tenang saja. Aku punya solusi yang jitu.” Aram berujar dengan tenang. Dia memasang wajah kekar gagah perkasa. “Apa itu Ram?” aku bertanya.
“Bapak Dahri Ariyanto menginginkan kita membuat video dokumentasi. Bapak Dahri Ariyanto ingin kita membuat kue jajanan tradisional. Bapak Dahri Ariyanto ingin kita menjualnya. Harap ketiganya itu dipandang sebagai tiga masalah yang berbeda.”
Kami terperangah. Aram terdengar sangat pintar.
Dia melanjutkan, “karena ketiganya adalah tiga masalah yang berbeda, kita bisa mengerjakannya secara terpisah. Tak ada masalah kalau sore ini kita mengerjakan video dokumentasi itu, dan membuat kuenya esok pagi. Tidak ada masalah dengan itu.”
“Kau tidak mengerti, Ram. Kata ibuku, adonannya itu harus segera dibuat jadi kue. Tidak bisa disimpan sampai pagi.” Aku menyela sengit.
“Itu jika kau berpikir adonan yang kita buat saat video dokumentasi, adalah adonan yang dibuat kue. Bagaimana kalau itu adalah dua adonan yang berbeda? Kita buat adonan untuk dokumentasi saja, habis itu kita makan-makan. Habis satu masalah.”
“Lalu adonan kue untuk dijual?”
“Tergantung kebaikan hati ibumu untuk membantu Az.”
“Maksudmu, ibuku yang harus membuat adonannya?”
“Tentu saja.”
“Tega sekali kau, Ram.”
“Apa boleh buat,” Aram menyela dengan sengit, “ini adalah solusi yang bisa kupikirkan. Jika ada solusi lain, silakan kemukakan.”
Aku garuk-garuk kepala. Yang lain juga. Kami tidak punya solusi yang lebih jitu daripada Aram tadi. Akhirnya aku mengangguk mufakat. Tinggal memikirkan bagaimana membujuk ibuku untuk membuat adonan kue itu. “Nanti kami bantu Az, tenang saja. Kita punya Mawar sebagai tukang rayu terbaik di sekolah,” Wahid terkekeh nakal.
“Iya Az, tenang saja. Aku akan membujuk ibumu. Pasti diizinkan.”
“Jadi kapan kita mau membuat adonan dokumentasi itu?”
“Bagaimana kalau hari ini?”
“Itu ide gila,” semburku ikhlas.
“Baiklah, besok kalau begitu. Makin cepat, makin baik.”
Lagi-lagi aku harus tunduk pada forum.
Sejak Bapak Dahri Ariyanto keluar dari ruangan kemarin, lokal kami ramai dengan pembicaraan dan rencana-rencana pembuatan kue. Kelompok ini akan membuat ini, kelompok itu akan membuat itu dan seterusnya.
Hari ini, Aram dan kawanan kelompokku terlihat begitu senang karena hari ini mereka akan ke rumahku. Entahlah kawan, aku sebenarnya tidak terlalu mengerti juga, bagaimana bisa perjalanan ke rumahku bisa sedemikian menyenangkan bagi mereka. Serupa perjalanan ke Baitullah saja. Aram sampai bersorak-sorak, “hore akhirnya ke rumah Azka.”
Ah jangankan teman sekelasku, kawan saja, yang sudah mengikuti ceritaku sampai sejauh ini, belum pernah ke rumahku. Rumahku itu terletak nun jauh di pelosok. Di sebuah kampung yang tidak terlihat di peta, kecuali peta kecamatan yang ada di kantor desa. Konon, pak kepala desa saja tidak paham bagaimana membaca peta itu.
“Ibumu sudah setuju Az?” Mawar bertanya, mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motorku. Aku mengangguk, mereka tidak perlu tahu bagaimana alotnya aku dan ibu berkonsolidasi tadi malam.
Kau dengar itu kawan, Konsolidasi!
“Ingat, jangan sampai kalian tertinggal di belakangku, dan jangan sampai pula kalian menyalipku. Ribet nanti kalau kita terpisah.” Aku memperingati mereka sungguh-sungguh sebelum berangkat.
Aram dan Wahid mengangguk. Pelan-pelan kujalankan sepeda motor ke rumahku. Kami sekali berhenti untuk membeli bahan baku adonan, dan satu kali lagi karena Mawar hilang di belokan. Untung tidak jauh.
Ibuku sudah menunggu di rumah. Kami segera membagi tugas, mengumpulkan alat-alat. Seseorang lainnya memasang kamera, mencari sudut yang tepat, kami siap membuat video dokumentasi.
Ketika aku ingin menuliskan tentang proses pembuatan kue gagatas dan papare itu, ibu melarangku untuk melakukannya. Katanya biarlah proses itu menjadi rahasia dibalik layar. Yang jelas, aku geli-geli jijik melihat Aram mengaduk adonan dengan tangannya sendiri. Kita sama tahu kawan, entah bekas apa tangan Aram itu.
Mozaik 42
Mengawal Tamu yang Spesial
“Jadi sejauh ini Az, jarak yang kamu tempuh setiap hari untuk sekolah?”
“Tentu saja,” aku menyahut. Karena kue sudah masuk di penggorengan, aku memutuskan untuk duduk di samping Mawar, di teras rumah.
“Selama tiga tahun?”
“Iya.”
“Jauh sekali Az. Pasti kamu termasuk orang yang rajin.”
Aku tersenyum kecut. Mawar pasti tidak pernah membaca cerita soal orang yang mengayuh sepeda dari subuh untuk bisa sekolah, mengayuh sejauh 40 kilometer. Itu baru orang rajin. Kau akan menemukan cerita tentang itu di novel best seller.
“Tidak terasa jauh kalau kamu terbiasa,” sahutku.
Percakapan itu bisa berlanjut andai Aram tidak berteriak-teriak memanggilku. “Hoy tuan rumah, ini kuenya sudah matang. Ayo kita cicipi bersama. Jangan pacaran terus. Kau dengar aku, tuan rumah.”
Aram berteriak semacam itu di depan ibuku. Heroik, itulah deskripsi yang tepat untuknya.
Lupakan itu, kami menghabiskan sore dengan berkonsolidasi bagaimana kami menjual kue itu nanti. Konsolidasi kami makin menyenangkan dengan tersajinya kue-kue tradisional asli bikinan tangan Aram. Konsolidasi baru selesai menjelang maghrib.
“Kalian ingat jalan pulang, Ram?”
Aku berdiri tidak jauh dari stang sepeda motor Aram. Dia berboncengan dengan Intan. Temanku itu mengangguk-angguk.
“Tenang saja Az, rumahmu bukan banyak belokan juga. Mudah saja bagi ingatan fotografis Aram ini,” ujarnya tertawa. Kata “ingatan” itu secara misterius mengingatkan aku pada nilai Aram yang mentok di 75 kemarin.
Berturut-turut mereka memutar gas kemudi, Aram dengan Intan, Wahid dan Hamed. Tertinggal satu orang, Mawar Alvera yang masih ngobrol dengan ibuku. Kudekati mereka. Mawar mengangkat jempol. “Seperti janjiku, aku membujuk ibumu Az.”
Aku terkekeh. “Kamu ingat jalan pulang, Mawar?”
“Eh yang lain sudah duluan?” katanya berseru, memandangi tempat Aram tadi menempatkan sepeda motor. Yang kemudian keluar dari mulutnya adalah decakan sebal.
Saat itulah, aku tahu saatnya aku tampil sebagai pahlawan.
“Tak apa, biar aku antar.”
“Kamu serius Az?”
“Iya, ayo keluarkan sepeda motormu.”
Aku gesit mengambil jaket dan helm, mengiringi sepeda motor Mawar menelusuri jalanan kampungku yang sudah gelap. Sepanjang jalan aku merinding. Bukan saja karena jalanan kampungku itu angker (karena memang angker), juga karena Mawar terus-terusan bilang “terima kasih” dengan diiringi senyumnya yang luar biasa.
Kami sampai di gerbang komplek perumahan Mawar. Komplek perumahan yang sangat megah.
“Kurasa cukup sampai di sini, kamu tidak akan tersesat lagi.”
Mawar bergegas mencegah aku yang hendak putar balik. “Mampirlah ke rumahku sebentar Az. Aku tidak ikhlas kalau kamu langsung pulang.”
Oh Tuhan, apa boleh buat, dengan senang hati aku mampir ke rumahnya.
Tanpa malu-malu Mawar memegang pergelangan tanganku, menarikku ke rumahnya. Di sana sudah Ibunya berdiri di ruang tamu.
“Ma, ini teman aku. Sekelompok tugas membuat kue.” Mawar memperkenalkan diriku. Aku tersenyum canggung.
“Siapa namanya Ar?”
Aku segera mengetahui kalau nama panggilan Mawar adalah “Ar”.
“Azka Ma, Humadi Azka.”
Seketika raut wajah Ibunya Mawar berubah. “Azka Quart School yang cerdas bukan buatan itu-kah?”
“Iya Ma, yang sering diceritakan Syifa.”
Aku berdiri di sana, salah tingkah. Satu karena dipuji oleh ibunya Mawar, dua karena nama Syifa disebut.
“Buatkan minum untuk tamu kita Ar. Jangan pulang dulu Nak Azka. Sudah lama tante ingin mengobrol dengan orang cerdas.”
Kami terlibat obrolan yang terus-terusan membuat aku salting. Bagaimana tidak, sesekali Mawar tertawa, memamerkan senyumnya yang menawan itu. Sesekali dia malah menyenggol-nyenggol hubunganku dengan Syifa. Bahkan di satu kondisi, Ibu Mawar membandingkan aku dengan pacar-pacar yang pernah dimiliki Mawar, dan menyebut aku lebih baik dari mereka semua, aku nyaris terbang.
Saat aku hendak berpamitan pulang, Mawar sempat berkata lirih padaku. Kalimatnya serius. “Az, kamu harus tahu, mamaku adalah kakak kandung Tante Shimala, mama Syifa. Artinya aku bersepupu dengan Syifa.”
Aku mengangguk.
“Aku bersumpah, akan membantumu memperbaiki hubunganmu dengan Syifa. Kamu bisa pegang kata-kataku.”
Entahlah kawan, entah kenapa aku merasa lebih baik jika Mawar cuma bercanda saja dengan kata-katanya itu.
Mozaik 43
Aku Benar-benar Tidak Suka
Sebagai pelaksana penjualan, Aram telah merumuskan strategi pemasaran yang jitu sekali. Dia memberikan titah dengan praktis di grup Whatsapp.
“Kawan-kawan, kita harus bisa membawa kue-kue itu ke Quart School pagi-pagi sekali. Bahkan harus yang paling pagi dibanding kelompok lainnya.”
“Kenapa begitu, Ram?”
“Karena makanan pertama yang mereka lihat, adalah makanan pertama yang mereka beli. Kita tidak bisa menjual kepada orang yang sudah membeli produk kelompok lain. Tak akan sudi mereka beli dua kali.”
Kami mengangguk-angguk. Aram benar juga.
“Usahakan bawa kue itu di dalam wadah plastik berlapis daun Az.”
“Kenapa begitu, Ram?”
“Karena dengan begitu kesan tradisionalnya lebih nampak.”
Sekali lagi kami mengangguk-angguk. Aram benar lagi.
“Dan sebelum kita bawa ke sekolah, bawa kue itu ke rumah Wahid dulu. Kita akan bertemu di sana.”
“Kenapa begitu Ram?”
Kali ini Aram tidak menjawab. Apapun alasannya, misterius.
Hari penjualan telah tiba. Kue bikinan Ibuku mengkilap besar-besar. Sengaja beliau buat demikian agar cepat laku. Di rumah Wahid, Aram kembali membagikan instruksi.
“Kita akan menjajakan ke kelas-kelas. Hamed dan Wahid membawa wadahnya, aku dan Mawar bagian promosinya, Intan bagian dokumentasi, dan Azka pegang uangnya. Sepakat?”
Sungguh hebat kalau Aram serius jadi pemimpin.
Kami mulai dengan menapaki lokal 1, tempat paling mula-mula di Quart School. Para penghuninya bersorak ketika Mawar melambai-lambai masuk ke kelas mereka. Sebagian mengajak foto bersama. Mawar menawari mereka kue yang kami jual, 3 orang di antara mereka tertarik membeli.
Tiba di lokal 3, giliran Aram yang pamer wajah. Dia melambai-lambai pada cewek-cewek yang menatapnya tak putus-putus. Aram mengatakan, siapapun yang membeli kue, boleh berfoto dengannya. Luar biasa kawan, antusiasme adalah kuncinya.
Kami meninggalkan lokal 3, dengan dua kue terjual. Itu berarti masih 15 lagi yang harus dijual. Aram mulai pusing. Ternyata menjual kue tradisional di zaman modern, memang profesi yang riskan.
“Kita menuju kantor dewan guru. Ada satu target potensial di sana.”
Aku tahu, siapa yang dimaksud Aram itu. Ibu Qotrun Nada.
Lalu dengan memelas, Aram memohon kepada Ibu agar membeli semua kue kami yang tersisa. Ibu Qotrun Nada tersenyum geli. Walau pada akhirnya beliau memborong semuanya.
“Ini kesukaan Ibu. Gagatas,” ujar beliau tersenyum.
Kami boleh ber-pede diri masuk kelas. Dagangan kami laku semua. Sesuai prediksi Aram, kelompok terakhir yang tiba, adalah yang paling kesulitan menjual. Itu kelompok Mei. Kasihan aku dengan mereka.
Kejutan baru datang ketika kami sedang bersantai itu. Langkah kaki cepat mendekati kelas. Aku mengenali langkah derap kaki itu. Cepat-cepat macam orang menari, berbunyi kompak macam simfoni. Tiada lain, guru kesenian.
Astaga, ini pasti tentang Ujian Praktek Kesenian. Aku menahan nafas.
“Tugas kesenian kalian, membuat sulam taplak meja. Ukurannya 2x1 meter. Sulaman sekreatif mungkin. Bikin berkelompok, 6 orang. Dikumpul terakhir satu hari sebelum Ujian Nasional. Tolong sampaikan ke kawan-kawan yang tidak ada di ruangan ini.”
Kemudian beliau berlalu. Macam tidak peduli kami mendengar tugas yang beliau berikan atau tidak.
Aku menepuk dahi. Aku tidak cocok dengan sulam menyulam atau jahit menjahit. Aku benar-benar tidak suka.
Mozaik 44
Pontang-panting Mencari Kelompok
Kali ini situasinya terbalik. Kemarin di kelompok kewirausahaan, aku memegang kartu As, yaitu ibuku. Sekarang aku tidak punya kartu apapun, jadi mau tidak mau, aku harus melakukan tindakan yang cukup hina, bergerilya menawarkan diri dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Berharap ada yang menerima.
Masalahnya, apakah ada yang mau menerima anggota macam aku, yang bahkan tidak bisa menjahit?
Kabar baiknya, kesulitan menjahit ini, tidak hanya dialami oleh aku saja. Kesemua pria di lokalku juga mendapat masalah serupa. Aram yang cukup mafhum dengan kekurangan dirinya saja, yang mengaku-ngaku bisa menjahit.
“Cincai saja itu Az.”
Aku mulai bergerak. Pertama-tama, tentu saja, aku menawarkan diri pada Lia. Siapa tahu, kali ini, kelompoknya agak lowong. Hanya saja, lagi-lagi, peluangku tertutupi oleh batu yang sama.
“Maaf Az, kelompok kami sudah penuh.”
“Penuh? Siapa saja yang kamu ajak?”
“Ehm, aku, Mei, Isna, Shinta, Halwa dan Nasri.”
(Usah risau dengan nama-nama unik itu kawan, karena semua nama itu kukarang saja).
Hatiku protes. Kenapa lagi-lagi Nasri. Tapi melihat Mei ada di sana, kurasa semuanya wajar-wajar saja. Baiklah, apa boleh buat. Kucoret kelompok Lia dari daftarku.
“Mungkin kamu bisa coba masuk ke kelompok April Az, katanya mereka kekurangan orang,” saran Lia sebelum aku beranjak meninggalkannya.
Aku segera mencari April. Kutemukan dia di kantin. Langsung kuutarakan maksudku tanpa berbasa-basi.
“Aku welcome saja Az, kalau kamu mau masuk kelompokku. Lagipula kelompokku baru 4 orang.”
Alhamdulillah. Masih ada ruangan. Hatiku bersorak. Ini menyangkut pasal nilai, aku tidak pilih-pilih, yang penting punya kelompok.
“Tapi, aku tidak bisa menjahit, Pril.”
Mata April yang bulat makin membulat. “Astaga, kalau begitu, aku tidak bisa menerima kamu Az. Maaf.”
Aku langsung kecele. “Masa tidak bisa Pril. Ayolah, tolong aku.”
“Tidak bisa Az, kami memerlukan orang yang bisa menjahit.” Skakmat-lah aku. Ingin sekali aku mengungkit soal kebaikan hatiku pada April di masa silam, tapi itu akan membuat aku terlihat tidak sebijak karakter lain, di novel best seller.
Adzan dzuhur berkumandang. Para murid Quart School bergegas menuju mushola. Aku tiba paling awal, pikiranku kusut dengan persoalan kelompok kesenian ini. Mungkin selepas shalat, aku bisa menemukan solusi yang baik. Itulah harapanku.
Saat aku hendak keluar dari mushola, di pelataran, sebuah suara memanggilku, “Az.” Lekas aku menoleh, di sumber suara, Mawar melambai, menyuruhku mendekat. Bersamanya ada dua gadis berkacamata. Teman-teman sekelasku juga.
“Az, sudah dapat kelompok kesenian?” Mawar bertanya.
Mataku berbinar. Aku sudah bisa mencium bau-bau pertolongan Tuhan. Kugelengkan kepala pada Mawar.
“Mau ikut kelompok aku tidak?”
“Seriusan nih?”
“Iya Az, seriusan. Kemarin kamu menolongku saat kelompok kewirausahaan. Kamu mau menampungku di kelompokmu, anggap saja balas budi.”
Ingin sekali, aku mengatakan aku tidak bisa menjahit, tapi kuurungkan. Aku menggantinya dengan ucapan terima kasih. Tanpa pikir panjang, aku terima tawaran Mawar. Urusan aku bisa atau tidak menjahit, bolehlah nanti-nanti dikatakan.
Picik sekali pemikiranku itu.
“Siapa saja anggota kelompokmu, Ar?”
Pelan-pelan kutanya Mawar saat dua gadis berkacamata temannya tadi sudah pergi. Sengaja kuselipkan panggilan “Ar” itu. Mawar tertawa kecil mendengarnya.
“Kita berempat, tambah Hamed. Kurang satu orang Az.”
Aku ber-oh panjang.
“Ar, sebenarnya aku tidak bisa menjahit,” ucapku pelan.
“Tidak perlu risau Az. Kamu duduk tenang saja nanti. Karena kamu sudah punya tugas spesial nantinya.”
“Tugas spesial?” aku bertanya. Tugas spesial macam apa itu.
“Kamu ingat kalimatku kemarin bukan Az? Saat kamu hendak pulang dari rumahku?”
Aku mengangguk. “Tentu saja aku mengingat itu.”
“Tugasmu adalah memperbaiki hubunganmu dengan Syifa. Nanti, kita menjahit di rumahku. Aku sudah bicara juga dengan Syifa, katanya dia mau melihat bagaimana kita menyulam. Jadi dia akan datang juga ke rumahku. Siap-siap ya Az. Jika kamu menikmatinya, ini akan jadi momen yang menyenangkan.”
Aku meneguk liur.
Mozaik 45
Pintu Gerbang Dunia Lain
Aku tahu Mawar akan melakukan apapun untuk mempertemukan aku kembali dengan Syifa. Apapun itu. Aku bisa melihat itu dari wajahnya yang sungguh-sungguh. Kuat sekali keinginannya itu, entah kenapa. Malangnya kawan, aku pun tahu dari petualanganku selama ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kupetik.
Jangan pernah menghalangi keinginan kuat seorang wanita. Karena dia akan melakukan apapun, tidak ada yang bisa menghalanginya. Aku menghela nafas.
Baiklah, mungkin sudah waktunya mengikuti arus, bukan melawannya. Mungkin saatnya aku menerima baik-baik fakta bahwa aku masih ingin berhubungan dengan Syifa. Sebelum semua berubah jadi serba canggung, sebaiknya aku perbaiki sendiri dulu, hubunganku dengan gadis bermata cemerlang itu. Mungkin aku harus mengambil langkah pertama.
Membuka blok sialan yang menghambat hubunganku dengan dia. Masalahnya, bagaimana caranya?
Cara paling praktis, tentu saja dengan menemui Syifa secara baik-baik, di kantin misalnya, saat dia sedang makan di sana. Kemudian jelaskan secara perlahan pada dia tentang blok itu. Aku menghela nafas. Itu cara yang mustahil. Aku pasti sudah kehabisan darah sebelum berucap.
Cara lain, yang sangat tidak praktis, adalah meminta bantuan salah satu temannya. Teman-teman Syifa selalu duduk di kantin setiap istirahat kedua, mereka berderet rapi, macam pagar. Bedanya mereka cantik-cantik. Masalahnya, tak satupun dari mereka, yang aku kenal.
Hendak meminta bantuan orang lain, akan semakin riskan jadinya. Aku tidak bisa mempercayai sembarang orang. Hubunganku dengan Syifa, adalah sumber gosip terpanas di Quart School. Salah sedikit, bisa menimbulkan gelombang ciye yang luar biasa.
Aku tahu aku harus mencari seseorang untuk membantuku. Orang itu harus bisa kupercaya, harus akrab dengan Syifa, dan memiliki mulut cukup rapat agar tidak menimbulkan gosip. Kawan, engkau tahu siapa yang bisa melakukan itu untukku?
Variabel-variabel itu terus berputar dalam otakku. Bermalam-malam aku merenungkan hal itu. Siapa yang bisa membantuku. Akhirnya di satu malam Jum’at Legi tanggal ke-18 bulan purnama memancing manusia serigala, masuklah ilham itu ke dalam kepalaku.
Mungkin ada satu orang yang bisa, Ibu Qotrun Nada.
Bergegas aku chat beliau, jam menunjukkan pukul 21.27 WITA.
“Selamat malam Bu, Azka ingin bicara empat mata. Penting. Bisakah Bu?”
Selang beberapa menit kemudian, chatku itu langsung berpendar. Ibu membalas. “Iya Az, ada apa? Silahkan saja datang ke ruangan Ibu sehabis shalat Dhuha. Insya Allah ibu ada waktu.”
Urusan ini berakhir dengan cukup mudah.
Keesokan harinya, aku memberanikan diri, atau tepatnya mempermalukan diri sendiri dengan menerobos kantor dewan guru di jam istirahat pertama. Guru-guru sedang makan saat aku ke sana. Semuanya melongo. Aku pura-pura tidak tahu diri saja, terus berjalan ke ruangan wakasek kesiswaan, ruangan Ibu Qotrun Nada.
Ah kawan, ternyata tidak tahu diri adalah sikap yang cukup menyenangkan.
“Ada apa Az? Kok mendadak begini?” sambut Ibu Qotrun setelah menjawab salamku.
Malu-malu aku menjelaskan, bahwa aku meminta bantuan beliau untuk membukakan blok Syifa atas kontak Whatsapp-ku. Ibu menyernit kening.
“Ada apa nih Az, kok tiba-tiba sekali. Kamu ngebet ingin chat-an dengan Syifa?” tanya beliau lagi. Aku menarik nafas. Aku sudah membayangkan akan diinterogasi habis-habisan.
Kujelaskan lagi mengenai kuatnya keinginan Mawar untuk memperbaiki hubunganku dengan Syifa.
“Baik Az, ibu paham duduk permasalahannya….”
Kupotong penjelasan Ibu dengan menyebut-nyebut soal pentingnya silaturahmi. Ini adalah senjata terbaikku untuk menghadapi Ibu Qotrun. Beliau tersenyum simpul dengan penjelasanku.
“Baik. Baiklah Az. Ibu akan membantumu. Nanti malam Ibu akan chat ke Syifa. Kamu tunggu kabar baiknya ya.”
Dadaku rasanya hendak meledak karena senang.
Malamnya, sekitar pukul 9 malam. Handphone-ku berbunyi. Nada dering “hai”. Perlukah kuulang kawan, nada dering “hai”. Hanya ada satu orang pemilik nada dering itu di deretan kontakku. Lekas-lekas kubuka handphone, dan genap di sana, di penampang WA-ku tertulis satu nama, di barisan paling atas, lengkap dengan fotonya yang cantik.
Syifa.
“Maafkan aku Az.” Itulah bunyi pesan dia.
Gemetar aku membaca pesan itu. Sudah lama aku tidak menerima pesan dari Syifa, hampir aku lupa dengan sensasinya. Rasanya aku ingin meloncat-loncat. Sekarang aku bingung hendak membalas apa.
“Aku yang seharusnya minta maaf Syif.” Akhirnya balasan seperti yang bisa kuketik. Klise, klise sekali.
“Ibu Qotrun yang bilang padaku tadi. Baru saja. Sungguh Az, ini adalah hanya salah paham. Waktu itu WA-ku error, kontakku hilang semua. Ketika ada pesan bernada gombal masuk, langsung aku blok. Tak tahu kalau itu ternyata kamu. Sebenarnya heran juga, kenapa Azka tidak pernah muncul lagi selama berbulan-bulan. Aku ingin bertanya padamu, tapi terlalu malu. Maafkan aku ya Az.”
Gemetar lagi aku membaca pesannya yang panjang itu. Kini aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah pesan lain masuk, dari Ibu Qotrun Nada.
“Gimana Azka? Adakah Syifa men-chat kamu?”
“Iya Bu, ada.”
“Ibu harap kamu ingat batasannya ya Az.”
Aku harap yang ibu maksud sebagai “batasan” itu bukan terus membalas chat Syifa sampai pukul 12 malam. Ada banyak hal yang kami bicarakan. Hal-hal yang tertunda selama lebih dari 6 bulan. Membuka blok dari Syifa, ibarat membuka sebuah pintu, pintu ke sebuah dunia yang sangat mengasyikkan.
Mozaik 46
Satu Hari Setelah Itu
“Syif, aku minta maaf, atas semua tulisan yang ada di buku ekonomi kamu,” itulah chat terakhir yang kukirim pada Syifa, sebelum aku tidur. Sengaja kututup tanpa salam, agar aku bisa nyambung chat dengan dia esok pagi. Betul-lah, chat Syifa sudah menunggu saat aku bangun.
“Tulisan apa Az?”
Aku tersentak. Seriuskah, dia belum membuka dan mengecek buku itu. “Tulisan macam-macam Syif. Kamu tidak mengeceknya?”
“Sebentar ya, aku cek dulu.” Syifa kembali membalas. Bar statusnya online di pagi ini.
“Aku sungguh minta maaf. Aku cuma menulis namaku di sana. Sisanya kerjaan teman-temanku.”
Lima menit tidak ada jawaban
Sepuluh menit, chat-ku berpendar biru. Tapi tidak ada balasan.
Tiga belas menit. Aku mulai gelisah. Seharusnya aku tidak perlu mengungkit kasus kanvas cinta itu, siapa tahu setelah ini Syifa marah dan memblokku sekali lagi. Kacau sekali. Untunglah ternyata itu tidak terjadi.
“Inikah Az?”
Chatnya diiringi 3 emot tertawa berderai-derai. Semoga itu adalah pertanda baik.
“Aku minta maaf Syif. Sungguh, maaf.”
“Astaga Az. Tidak perlu minta maaf. Ini cuma tulisan. Hei lagipula ini kreatif sekali. Hehehe.” Sekali lagi dia menyelipkan emot tertawa berderai-derai itu.
Oh Tuhan, kreatif katanya.
“Kamu tidak marah-kan Syif?”
“Tidak Az, tenang saja. Boleh ceritakan, bagaimana tulisan sekreatif ini, bisa mampir di bukuku.”
Segera aku ceritakan tentang episode kanvas cinta. Kubayangkan Syifa tertawa di seberang sana.
Itu adalah pengawal hari yang sempurna.
Di sekolah, sudah menunggu Pak Kepala Sekolah dan Bapak Wakasek Kurikulum, ditemani Ibu Pembina Olahraga. Kami murid-murid semester 6, diminta beliau berkumpul di aula. Ada apa gerangan?
“Dua hari lagi, kalian akan Ujian Praktek Olahraga,” ujar Ibu Pembina Olahraga berucap dingin. Aku tidak terkejut. Di ujung semester 6 ini, ujian bisa datang kapan saja, dahsyat. Datang silih berganti.
Beberapa orang murid mengangkat tangan, menanyakan teknis ujian. Ujian praktek olahraga selalu menjadi momok paling menakutkan.
“Di lapangan Bumi Melayu. Ada tiga macam ujian yang harus kalian hadapi. Kesemuanya melibatkan kelentukan, kekuatan dan ketangkasan. Siapkan saja diri kalian, makan makanan yang sehat. Tidur yang cukup.”
Ujian ini tidak akan mudah.
Setelah Ibu Pembina Olahraga selesai memberikan arahannya, giliran Pak Kepala sekolah yang mengambil alih. Aku memanjangkan leher, melihat Ibu Qotrun Nada, tapi rupanya beliau tidak hadir di tempat. Untuk urusan ini, sepertinya Ibu tidak dilibatkan.
“Tim koordinator ujian akhir sekolah sudah dibentuk, mereka sudah rapat. Mereka sudah menyusun jadwal. Mulai dari senin ini, ujian akan dilaksanakan. Kalian masih ingat, apa reward-nya bukan? Tidak perlu Bapak sebut nama lagi bukan? Nasri Abdillah, Shiela Camalia? Bintang-bintang paling terang di Quart School.”
Sengaja betul Pak Kepala sekolah menyebut kedua nama itu. Tujuan beliau, tentu saja untuk memompa semangat kami semua untuk bersaing. Hanya saja, jika membaca sejarah, hati siapapun akan ciut. Nasri dan Shiela sebenarnya tidak bersaing ketat. Tuan Profesor nan jenius sahabatku itu, seringkali tidak mau repot-repot melakukan itu. Nilainya berselisih cukup jauh dengan Shiela, Nasri biasa nangkring di posisi kedua Bintang Pelajar Quart School. Hanya saja, antara Nasri dengan peringkat ketiga, (semester kemarin diduduki oleh Mei) berjarak sangat jauh. Sehingga Persaingan nampak mustahil.
Namun biar demikian, aku bertekad memberikan perlawanan. Aku memang duduk di luar lima besar klasemen bintang pelajar Quart School, tapi aku memiliki keinginan besar untuk bisa melampaui Nasri atau bahkan Shiela. Dengan Syifa sekarang di sisiku, apapun bisa kulakukan.
Ingin sekali aku mempersembahkan kejeniusanku untuk gadis bermata cemerlang itu.
Mozaik 47
Ujian Praktek Olahraga
Pagi kesekian dalam hidupku.
Ada dua hal yang paling tak kuharapkan terjadi di pagi hari. Yang pertama adalah matahari terbit dari barat, yang kedua, mengetuk pintu rumah Wahid saat matahari bahkan belum muncul. Ya kawan, aku melakukan tindakan itu.
Ini hasil kesepakatan kami tadi malam. Semua berawal dari arahan tambahan Ibu pembina olahraga. “Kalian harus tiba di lapangan, pukul 7.15 WITA. Lewat dari itu, ada ujian tambahan.”
Karena aku sangat malas untuk datang ke lapangan itu sendirian, (masa aku berdiri di tengah lapangan Bumi Melayu yang luas itu seorang diri, di pagi buta?), aku memutuskan mengajak beberapa orang. Wahid mengajakku barengan, jadi klop-lah. Masalahnya adalah, Wahid minta dijemput.
“Ide bagus. Aku bisa sekalian bergabung dengan rombongan kalian,” ujar Nasri berbinar-binar. Aku tidak jadi menolak tawaran Wahid. Akhirnya, aku dan Nasri menjemput Wahid menuju rumahnya. Hanya saja, kemudian aku singgah, sedangkan Nasri melanjutkan perjalanan. “Tunggu saja di situ Az, ada yang harus kujemput dulu.”
Ah, dasar. Pasti yang dia maksud, Mei.
Kami tiba di lapangan dengan terkagum-kagum. Setiap tahun datang ke lapangan ini untuk upacara, baru sekali ini aku tahu betapa luasnya Lapangan Bumi Melayu. Mungkin karena biasanya banyak orang di sini. Kali ini, yang adalah kemah-kemah berbaris di pinggir lapangan. Suasananya ganjil.
“Itu kemah peristirahatan peserta. Salah satunya pasti punya kita,” terang Mei. Kalau ada kepanitiaan dalam satu acara, pasti Mei ikut di dalamnya. Dan seperti kuduga, dia dijemput oleh Nasri.
“Ayo kita cari kemah milik kita.” Nasri beranjak, langsung menyusur lapangan. Kami mengekor di belakangnya.
“Jadi ujian macam apa yang akan kita jalani hari ini, Ey?” aku bertanya. Mei melotot. Panjang ceritanya tentang sapaan “Ey” itu kawan, aku tidak ingin bercerita tentang itu sekarang.
“Kudengar ada sit-up, push-up dan lari jarak jauh.” Mei menerangkan, nafasnya setengah mendengus. Aku memang sengaja menggodanya sedikit tadi.
“Ah kalau itu, cincai saja,” ujar Wahid, sambil pura-pura membersihkan lengan bajunya. Dia boleh sombong, karena memang demikian adanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Wahid soal olahraga.
Kami sampai di tenda lokal 4. Kejutan menanti di sana. Aram berbaring melingkar.
Kami bertiga memasang wajah jijik. Mei menunjukkan ekspresi orang membuang kucing terlantar.
“Astaga kalian. Selamat pagi, mari istirahat dulu,” Aram menutupi mulutnya yang menganga lebar, dia menguap, “aku datang terlalu pagi.”
“Seharusnya kau pemanasan, Ram.” Wahid memberi instruksi. Aram malah menggeliat macam cacing, “iya sebentar lagi Hid. Astaga, aku bangun terlalu pagi,” dia menguap lagi.
Aku sebenarnya tidak terlalu yakin untuk ujian praktek olahraga seperti ini. Olahraga dan aku tidak pernah berdamai sejak kelas 1 SD. Mungkin karena itu postur tubuhku tidak atletis macam Wahid.
“Tidak usah risau Az,” Nasri menepuk bahuku, “aku juga tidak berbakat dalam olahraga. Dan aku pikir, Quart School cukup bijak untuk meluluskan muridnya tanpa harus melihat nilai ujian praktek olahraganya.”
Semoga saja Nasri benar.
Sesi pertama adalah ujian sit-up. Seorang instruktur olahraga yang tampangnya agak diprofesionalkan, turut mendampingi Ibu pembina olahraga, memantau langsung sesi ujian kami. Kami sit-up berpasangan, satu orang sit-up, satunya lagi menghitung dan mencatat.
Aku tembus 35 kali, Nasri 32 kali. Tidak buruk.
Sesi kedua, adalah ujian push-up. Yang ini aku agak ngos-ngosan karena berat badanku berat, menyulitkan aku untuk push-up maksimal. Tak jarang, tubuhku tidak turun sampai standar, langsung aku angkat lagi.
Aku hanya mendapat 16 kali, dan langsung ambruk. Nasri dapat 25.
“Ini Az, air mineral. Jaga stamina, sehabis ini lari cepat.” Nasri menyodorkan botol. Aku menerimanya. Berterima kasih. Sementara Aram dan Wahid nampak tertarik memperhatikan para perempuan push-up. Sungguh pemandangan yang asyik bagi mereka.
Sesi terakhir, adalah lari keliling lapangan sebanyak 4 kali. Kau percaya itu kawan? Lapangan ini lebih luas dari lapangan sepakbola, dan kami disuruh lari mengitari pinggirnya sebanyak 4 kali? Mematikan.
Aku, Aram, Nasri, Hamed dan Wahid memutuskan lari bersama-sama. Instruktur setuju, dan segera mencatat nama kami berlima. Begitu bel ditiup, Aram langsung lari sejadi-jadinya. Nasri mencoba mengekor di belakangnya, larinya juga cepat. Aku, Wahid dan Hamed tertinggal di belakang.
Aram sudah setengah putaran lebih lari, aku baru seperempat. Dia cepat sekali. Hamed mencoba mengejar, mati-matian. Begitu juga Nasri. Dia hampir berimbang dengan Aram, karena postur tubuhnya kurus saja. Dinamis dia bergerak.
Wahid berlari berimbang dengan aku. Dia tersenyum-senyum. Santai sekali. Heran aku, padahal Wahid pasti bisa mencapai kecepatan seperti Aram. “Tidak perlu cepat-cepat Az. Ini bukan tentang kecepatan. Kita perlu taktik. Tidak boleh lari terlalu cepat di putaran pertama, nanti kau tidak bisa lari lagi di putaran ketiga.”
Aku manggut-manggut. Benar juga. Aram mulai merasakan kebenaran kalimat Wahid tadi. Di putaran ketiga, dia tersengal-sengal. Nyaris jatuh pingsan. Nasri muntah-muntah. Hamed tinggal berjalan kaki. Ajaib, kini aku dan Wahid berlari beriringan.
Semakin lama, Wahid meningkatkan temponya. Kini dia berlari secepat kilat. Aram melihat itu, langsung bergegas meningkatkan kecepatannya, kini kurasa dia menggunakan sebagian dari kemampuan tenaga dalamnya. Nasri, yang pulih dari muntah-muntah, ikut memacu tenaga. Mereka kini berlomba di putaran keempat. Seru.
Sementara aku, yang memang tidak cocok berolahraga, kembali tertinggal. Rasanya tidak sanggup lagi aku mengejar. Biarlah. Sekali lagi kukatakan pada diriku sendiri, sebagaimana tadi kalimat Nasri.
Setelah semua berakhir, kami berlima sama jatuh terampar ke tanah. Tersengal-sengal.
Tanganku iseng meraih handphone. Tujuanku sudah jelas, men-chat Syifa. Dia juga sudah selesai lari.
“Lelah ya Syif?”
“Hehe iya Az. Lelah banget. Tapi kamu tetap keren.”
“Keren dari mana ya.”
“Keren dari sananya lah.”
Oh Tuhan, tenagaku rasanya langsung kembali.
Mozaik 48
Hari Pertama Ujian Akhir Sekolah
Setelah panitia sibuk selama satu minggu, akhirnya hari ini ujian akhir sekolah dimulai.
Kami sudah mendapatkan informasi jadwal ujian, tiga hari sebelum ujian dimulai. Plus sebuah kartu aneh berwarna hijau seukuran kertas A6. Kartu ujian kami. Di sana tertulis informasi nomor Induk siswa nasional, dan ruangan tempat ujian kami nanti.
Aram tersenyum ketika membandingkan kartunya dengan kartuku dan kartu Nasri. “Kita satu ruangan Az. Di ruang 6. Ini akan menyenangkan.” Tentu saja yang dimaksud Aram sebagai menyenangkan itu, adalah dia bisa bertanya padaku dan Nasri, saat ujian. Secara diam-diam.
Aku menyadari fakta yang tak kalah menyenangkan ketika masuk ke dalam ruangan ujian. Rupanya sistem yang dipakai panitia adalah acak, jadi siswa yang terkumpul di satu ruang bisa berbeda lokal. Sistem yang sama, juga membuat aku satu ruangan dengan Syifa. Berdekatan malah. Aku menyungging senyum memikirkan fakta itu.
“Sayang sekali, aku tidak bisa satu ruangan dengan kalian. Sepertinya aku harus belajar lebih giat,” ujar Wahid. Dia sering main ke ruangan kami saat istirahat. Dia bertanya beberapa hal pada Nasri.
Hari pertama, mata pelajaran Agama dan Bahasa Indonesia. Itu pembukaan ujian yang baik. Soal-soalnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Aku beri satu tips kawan, jika kamu mengerjakan soal ujian, tarik dan hembuskan nafas sebanyak 10 kali sebelum mulai menjawab. Rasanya bakal plong.
Aku melakukan itu selama ini, sejak dari SD. Dan di sini aku sekarang.
Di waktu istirahat, aku terkadang mencoba untuk mengobrol dengan Syifa. Tapi lidahku tersekat di tenggorokan. Terkadang Aram yang coba mengajak Syifa ngobrol, sambil mengerjip nakal ke arahku. Ketika melihat hal itu, cepat-cepat aku mengingatkan diriku agar tidak salah tingkah.
Satu hal yang membuatku risau, adalah kemampuan dan kapasitasku dalam menjawab soal-soal ini. Bukan soal-soal yang terlalu rumit, tapi aku rasa, ada satu atau dua soal yang aku luput dalam menjawab. Bagaimana aku bisa mengimbangi Nasri atau Shiela. Ketika kutanya tentang bagaimana dia menjawab, Nasri mengangkat bahu, “biasa saja,” ujarnya. Frasa biasa saja itu, artinya dia bisa melibas soal-soal itu dengan mudah.
Di hari pertama ujian sekolah itu juga, Mawar memberikan informasi penting padaku. Soal kelompok kesenian. “Az, soal kelompok menjahit itu, kita tidak bisa menjahit di rumahku.”
“Kenapa Ar?”
“Papa dan Mama pergi ke luar daerah selama 10 hari. Dan aku dilarang membawa orang asing ke rumah, selama mereka tidak ada.”
“Lalu bagaimana?”
“Syifa bersedia menyediakan rumah. Kamu sepakat atau tidak?”
Astaga, ini pasti bagian dari rencana Mawar. Sungguh tidak bermutu rencananya itu, klise sekali alasannya. Bahkan kawan bisa merasakan hal itu.
Selain Mawar, Aram juga menyinggung-nyinggung soal kelompok kesenian. Rupanya temanku itu belum mendapat kelompok, dan berharap bisa masuk ke kelompokku. Jelas, dengan opsi yang baru ditawarkan Mawar, aku tidak bisa membiarkan Aram masuk ke kelompokku.
“Aku tidak bisa mengajakmu, Ram.”
“Kenapa Az?”
“Karena aku juga diajak-ajak ke kelompok ini.”
“Suruh Mawar memasukkan aku ke kelompok.” Dia berkeras
“Tidak bisa Ram. Anggota kelompok sudah penuh.”
“Pasti masih bisa Az. Ibu akan memberi pengecualian untukku. Daripada aku tidak punya kelompok.” Dia makin bersikeras.
“Aku tetap tidak bisa membiarkanmu masuk ke kelompok, Ram.”
“Astaga kenapa pula Az?”
“Alasan sentimentil.”
Aram meledak, “alasan macam apa itu. Sungguh alasan kau itu tidak bermutu.”
“Kau adalah bangau yang memancing di air keruh.”
Aram terpana dengan peribahasa yang kukeluarkan. Tapi dia terus memasang alasan. Aku tetap berkelit dan bersikeras tidak mengizinkannya masuk ke kelompokku. Aku tidak bisa membayangkan kehebohan apa yang akan terjadi, jika dia bergabung ke rumah Syifa.
Begitulah hari ini berakhir.
Mozaik 49
Lia Cemburu?
Aku memang menyesalkan kemampuanku menjawab soal yang terasa masih sangat pas-pasan. Namun tak bisa kupungkiri pula, bahwa periode ujian akhir sekolah ini adalah periode yang paling menyenangkan. Ini menyangkut hubunganku dan Syifa yang semakin membaik dari hari ke hari.
Semenjak aku membuka blok-nya itu, percakapan kami mengalir deras. Aku rutin men-chat-nya setiap malam. Menanyakan apakah ada bagian pelajaran yang tidak dia mengerti. Kami sering mendiskusikan tips-tips menjawab soal yang baik.
Tak pelak pula, perbaikan hubunganku dengan Syifa ini segera menyebar ke seluruh penjuru. Itu bermuara pada satu tindakan cerobohku saat ujian praktek olahraga kemarin. Aku sengaja membiarkan Wahid melihat ponselku saat aku sedang mengirimi Syifa chat. Sejak itu, Wahid mulai menebar tindakan keciyean lagi.
Aku tutup telinga, pura-pura tidak tahu saja. Toh ternyata Syifa tidak marah. Buktinya gadis itu tetap mau membalas chat-chat dariku.
Hari ini di kantin. Entah kebetulan atau bagaimana, aku dan Syifa berpapasan. Dia menuju warung sate, dan aku ke kedai kopi Paman Pirates. Tempatnya bersebelahan. Aku melambaikan tangan, tersenyum. Syifa balik memberiku senyum. Wahid dan Aram datang belakangan, tidak sempat melihat momen akbarnya.
“Kebelet banget kau ke kantin Az…”
Wahid buru-buru memotong kalimat Aram dengan menunjuk ke arah Syifa. Aram manggut-manggut. “Oh aku tahu Az, rupanya begitu. Kau tidak sabar bertemu dengan Syifa,” Aram berujar dengan suara keras, “baik, tidak apa. Aku maklum. Sudahkah kau sapa cintamu itu Az?”
Aku mengangguk santai, “iya sudah.”
Aram kehilangan kata-kata. Kejadiannya mungkin bakal lain jika aku memasang ekspresi salah tingkah.
“Jadi sudah fix kembali ke Syifa nih Az?” bisik Aram dengan suara rendah.
“Lha, memang kemarin aku kemana?” tanyaku balik. Masih dengan ekspresi santai.
“Seingatku kemarin, kau pacaran dengan Shiela. Pasangan paling couple goals di Quart School.” (Itu Aram yang mengucapkannya, jadi jangan salahkan aku atas konteks kalimatnya).
“Ah sudah kuputusi dia itu.”
Wahid tersedak. Ekspresinya saat melihat ke arahku, macam orang baru membongkar makam Fir’aun.
Gosip kedekatanku kembali dengan Syifa, juga tentu saja terdengar oleh Lia. (Atau secara teknis, aku-lah yang memberitahu Lia bahwa Syifa telah membuka blok-ku).
Di sinilah kemudian terjadi reaksi unik.
Aku masih rutin men-chat Lia. Menjelang Ujian Akhir ini, dia juga sering bertanya dan mengajakku berdiskusi di ruang chatting. Misalnya malam ini, karena besok Ujian Mata pelajaran sosiologi, Lia mengeluhkan cara guru mengajar yang menurutnya tidak masuk ke otaknya. Memang kawan, mengajar sosiologi sepertinya memerlukan keahlian khusus.
“Ah pelajaran itu sebenarnya mudah saja, Li,” (aku mulai memanggil Lia dengan sebutan “Li” sejak aku tahu Nasri memanggil dia demikian), “sosiologi itu hanya tentang hubungan antar manusia. Tak usah kau risaukan. Kalau kedua manusia bisa akur, maka itu namanya kerja sama, tapi kalau dua manusia tidak akur, maka itu artinya konflik.”
“Ah andai aku bisa membuat logika mudah sepertimu Az.”
“Aku bisa memberimu banyak tips Li. Tenang saja. Karena itulah aku ada di sini untukmu,” balasku sentimental.
“Terima kasih Az. Aku juga ingin menitip satu tips untukmu Az. Kamu jangan sering-sering memberi contekan, hehe.”
Astaga Lia, aibku terbuka di hadapan kawan pembaca.
“Terima kasih atas tips kamu Li,” aku akhiri chat dengan emot mencium penuh cinta. Kawan yang sering memakai Whatsapp tentu saja mengerti emot semacam apa yang aku maksud.
“Emotnya itu cukup untuk dia saja.”
“Eh?” aku menyernit alis.
“Aku + kamu = dia. Eh kenapa aku jadi kacau begini.”
Hei aku juga bertanya. Kenapa Lia jadi begini.
Karena momennya bersamaan dengan ujian mata pelajaran sosiologi, aku anggap saja, Lia cemburu. Kesimpulan yang mudah bukan? Berbekal dengan kesimpulan itu pula, aku datang ke ruangan 5 esok hari. Khusus untuk mengajari Lia. Berasyik masyuklah kami berdua di situ. Sampai jadi tontonan Mei dan Wahid.
Mozaik 50
Aku Benar-benar Berdiri di Depan Rumahnya
Hari ini aku kembali ke ruang ujian 5. Tapi bukan untuk mengajari Lia, melainkan menemui Mawar. Ada urusan penting yang harus kuselesaikan dengan dia.
“Ar, jadi kapan kita akan mulai menjahit?” tanyaku. Aku mengambil duduk berhadapan dengan dia.
“Kamu tidak sabar mau ketemu Syifa ya Az?”
Aku berdecak kesal, “jangan membelokkan topik Ar. Kamu tahu, batas pengumpulan tugas itu adalah hari Ujian Nasional. Artinya hanya menghitung hari. Aku takut, tugas itu tidak akan selesai.”
Mawar malah tertawa. “Kamu tenang saja masalah itu Az. Aku yakin bisa menyelesaikan semua jahitan itu. Tak sulit. Yang sulit itu adalah mencari waktu yang pas. Aku sudah memberitahu padamu bukan, kita meminjam rumah Syifa. Mana bisa sembarangan memakai rumah orang.”
Aku berdecak semakin rancak. Urusan ini jadi rumit karena ulah Mawar sendiri. “Pokoknya pekerjaan kita harus selesai ya Ar. Aku tidak mau nilaiku tercoreng.”
“Tenang saja Az. Aku tahu kok, apa resiko mengajak orang cerdas sepertimu ke kelompokku.”
Pembicaraan selesai.
Dua hari kemudian. Aku datang ke ruang 5 lagi. Melihat kedatanganku, Mawar tersenyum-senyum. Dia sangka bisa merayuku dengan senyumnya itu, karena itu berhasil.
“Ar,” aku langsung berdecak.
“Iya Az. Aku tahu. Pokoknya kamu tenang saja. Itulah intinya. Tugas ini pasti selesai. Lama-lama, melihatmu seperti itu, aku benar-benar menyangkamu tidak sabar bertamu ke rumah Syifa.”
Aku berdecak lagi. Mawar tertawa kecil.
“Baiklah Az. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Hari ini kita akan ke rumah Syifa. Hari ini kita mulai pengerjaan tugas kesenian itu. Kamu siap bukan?”
Alhasil, aku mengerjakan soal hari itu dengan perasaan kebat-kebit. Nyaris saja teori ekonomi aku sangka teori evolusi. Syifa sempat menyapaku hari itu, saat kami bertemu di lorong.
“Dengar-dengar kamu mau ke rumahku hari ini Az,” ucapnya, tertawa kecil.
“Eh iya.” Aku hanya bisa memasang ekspresi nyengir.
“Barengan kalau begitu nanti ya Az.”
Oh Tuhan, aku panas dingin.
Pulang sekolah, Mawar dan dua gadis berkacamata sudah menunggu di parkiran. Hamed, yang selesai soal lebih dulu, bergabung dengan mereka. Sedangkan aku, ehm, benar-benar berjalan beriringan dengan Syifa. Meski kami tidak saling berbicara. Aku terlalu gugup.
Yang paling mengejutkan hari itu, adalah ada Wahid bergabung dengan rombongan Mawar. Terheran-heran aku melihat dia.
“Oh aku,” katanya seolah aku ingin bertanya, “aku ikut kelompok Mawar Az. Kenapa wajahmu terkejut begitu, kau tidak senang aku sekelompok denganmu?”
Tidak Hid. Aku merutuk kenyataan yang tidak membiarkan aku lolos dari para pemburu gosip. Terlambat untuk mencegah dia sekarang. Kecuali aku meniru gaya pembunuh bayaran.
“Apalagi aku dengar kelompok kita akan numpang menjahit di rumah Syifa. Pasti mengasyikkan ya Az,” Wahid terkekeh kejam. Aku rasa dia sudah merencanakan sesuatu. Kau sama seperti Aram, Hid. Bangau yang memancing di air keruh. Awas kalau kau macam-macam.
“Ayo kita berangkat. Nanti ke-sore-an baru selesai.” Mawar memajukan kendaraannya. Syifa mengekor. Kemudian dua gadis berkacamata, Wahid dan Hamed, dan paling belakang, aku. Gemetar.
Mawar membelok di komplek perumahan yang sama dengan rumahnya, saat aku mengantarnya tempo hari. Bahkan belokan gangnya juga sama. Dia singgah sebentar di depan rumahnya. Menunjuk-nunjuk. Hamed mengacungkan jempol.
“Ini rumahku.”
“Besar sekali.” Wahid bergumam.
Mawar meneruskan perjalanan. Kami menuju ujung gang. Kali ini Syifa yang membelok tajam, menuju rumah terakhir yang ada di situ. Dia masuk ke dalam, meletakkan sepeda motornya, kami mengikuti.
Inilah detik-detik paling men-terpana-kan dalam hidupku kawan.
Di depanku sekarang berdiri rumah Syifa. Megah sekali. Seakan menengok tidak peduli pada pemuda miskin dari pelosok sepertiku. Hei tapi siapa sangka setelah semua blok dan keciyean itu, aku bisa sampai di sini.
Hari ini aku benar-benar berdiri di depan rumah Syifa.
“Assalamualaikum.”
Mozaik 51
Syifa Jaim, Azka Minder
Astaga benar-benar rumah yang sangat besar.
Iya kau benar, ini sangat besar.
Aku tidak salah menebak. Syifa adalah orang kaya. Apakah aku ini cukup pantas untuknya. Melihat ini semua…
Iya kau pantas. Kau adalah Azka. Salah satu orang paling jenius yang pernah dijumpai Syifa dalam hidupnya. Kau ingat bukan cerita Mawar tempo hari?
Iya tapi status ekonomi yang begini, membuat anak kampung pelosok macam aku benar-benar minder. Aku insecure.
Astaga Bung, sekarang bukan waktunya memasang wajah dramatis. Sekarang masuklah ke dalam dan tunjukkan pada Syifa, siapa Azka yang sesungguhnya. Kalau perlu tunjukkan pada ayah dan ibunya.
Tapi rumah sebesar ini…
Berhentilah berbicara, sebelum aku masukkan kepalamu itu ke dalam toilet!
***
Perdebatan itu terus mengalir dalam pikiranku. Hei aku baru melihat bagian luar rumah besar ini, dan garasinya, tempat sebuah mobil sedan warna putih terparkir. Itu sudah memberiku gambaran yang lebih dari cukup, tentang status sosial keluarga Syifa. Dan biar kuberitahu satu fakta memuakkan kawan, status sosial seperti ini, telah membunuh banyak sekali cinta sejati yang tulus. Ada-ada saja caranya.
Aku berusaha menekan keminderanku.
Mungkin karena aku terlalu lama di luar, Mawar sampai memanggilku.
“Ayo masuk Az. Ngapain di luar situ. Kamu bukan satpam.”
“Eh,” aku tersentak.
“Astaga, jangan bilang kamu sudah salah tingkah Az. Ayo, tidak apa-apa. Masuk. Anggap saja rumah sendiri, atau mungkin kelak rumah ini memang akan menjadi rumahmu sendiri.”
Dasar Mawar. Inti dari kisah tugas praktek kesenian ini nampaknya akan terpusat pada Syifa dan Azka. Aku memberanikan diri masuk. Menghampiri Wahid dan Hamed yang duduk mematut kain di ruang tengah.
Kali ini aku putuskan untuk tidak terlalu memperhatikan interior rumahnya. Karena makin dilihat, makin aku minder.
“Kau lihat ini Az,” Wahid membentangkan kain warna biru itu, “Mawar pintar sekali memilih warna. Biru adalah warna terbaik.”
Kawan yang ingat bagaimana debat kusirku dengan Wahid tentang sepak bola pasti langsung mafhum, kemana arah kalimat Wahid itu.
Aku tersenyum masam. Sebagian masih gugup. Kualihkan percakapan pada Mawar yang sedang memilih-milih benang.
“Jadi gimana mekanisme kita menjahit ini Ar? Apakah ada pembagian tugas?” tanyaku. Wahid sempat bertanya, kenapa aku memanggil Mawar begitu, kujawab bahwa itu adalah panggilan orang-orang yang dekat dengan dia. Giliran Wahid tersenyum masam.
“Nah itu,” cetus Mawar, “aku terinspirasi dengan cara kamu dan Aram merekayasa tugas praktek kewirausahaan kita kemarin itu.”
Aku heran sekali.
“Karena aku tahu, baik kamu Az, Wahid ataupun Hamed sama tidak bisa menjahit, jadi untuk membuktikan kalian telah mengerjakan tugas ini, yang kita butuhkan adalah rekayasa.”
Aku, Wahid dan Hamed terpana.
Alhasil satu jam lebih kami melakukan skenario rekayasa fotografi itu. Foto-foto yang menunjukkan kami ikut terlibat dalam proses menjahit ini. Mawar pandai mengatur posisi dan merancang angle kamera. Aku tahu, rekayasa seperti apapun adalah menipu, tapi apa boleh buat. Hei setidaknya rekayasa yang kami lakukan ini tidak merugikan siapapun.
“Ini rumah Syifa-kan?” Wahid bertanya, setelah sesi rekayasa selesai.
Mawar mengangguk.
“Tapi kok dia tidak kelihatan?”
“Mungkin dia malu bertemu Azka,” ujar Hamed asal-asalan.
“Tidak mungkin,” aku mendesis.
“Tidak sepenuhnya salah,” ujar Mawar, “tadi Syifa bilang dia ingin memasak untuk kita makan siang. Tapi ya ini terlalu lama. Mungkin dia ingin pamer kerajinan di depan Azka.” Kalimat Mawar disambut ciye oleh yang lain.
Kemudian dari dalam kamar, muncul seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Mawar melambai padanya, “Kausar,”
“Dia ini adik Syifa,” terang Mawar, “Kausar ngapain tadi?”
“Kausar tadi tidur siang,” katanya, dengan intonasi yang belum sempurna.
Wahid yang agaknya berjiwa “kebapakan” segera akrab dengan Kausar. Dia mengajak Kausar main helikopter. Aku bengong saja. Bengong selama mungkin.
Tidak lama kemudian, giliran Syifa dan ibunya yang muncul dari dapur. Kalau aku tidak salah ingat, Mawar bilang, nama beliau, Tante Shimala. Beliau menenteng mangkuk sup panas dan piring-piring yang sudah tersusun. Di belakangnya, Syifa membawa rantang nasi yang mengepul-ngepul.
“Nah mari kita makan dulu. Untuk tamu-tamu yang datang dari jauh. Hehe.” Tante Shimala terkekeh. Mata Wahid langsung terbelalak melihat kepala ikan yang mencuat dari dalam mangkuk sup.
Makanan hari itu rasanya enak sekali. Kurasa Tante Shimala sempat menyebutkan apa nama menu makanan kami saat itu, tapi aku tak hirau. Aku lebih fokus, secara diam-diam, mengamati Syifa. Jilbabnya basah oleh peluh. Sedang kubayangkan dia telah susah payah membuat masakan ini untuk mengesankan Azka.
Setelah selesai makan siang dan semua sisa piring disingkirkan, Mawar segera mengambil ancang-ancang. Dia hendak memasang rekayasa lagi. “Rekayasa terakhir yang melibatkan kita semua, kita berfoto dengan kain setengah jadi ini.”
Hei, rupanya setengah dari tepian kain persegi panjang itu telah bermotif, Mawar cepat sekali bekerja.
“Syif, tolong fotokan ya.”
“Oke. Mana Kameranya?”
“Eh handphone-ku habis baterai,” ujar Hamed. Dari tadi memang rekayasa menggunakan kamera handphone Hamed.
“Hid?” Mawar menunjuk Wahid.
Wahid angkat bahu, “aku lupa bawa handphone. Punyamu saja, Mawar.”
“Handphone-ku juga habis baterai. Ya sudah pakai handphone Azka saja.”
“Eh Aku?”
“Iya Az, cepat keluarkan handphone-mu, serahkan pada Syifa. Biar pekerjaan kita ini selesai.” Mawar mengeluarkan perintah. Bagiku, dia sedang melakukan rekayasa di atas rekayasa. Patah-patah aku beringsut, menyerahkan handphone-ku, yang maaf-maaf kata, butut, pada Syifa. Wahid sempat berujar pada Kausar, “Kausar, Azka itu calon kakak iparmu nanti.”
Tentu saja Kausar tidak paham. Kemudian terdengar koor ciye yang membahana. Itu pukulan telak. Mereka menyerang Syifa tepat di rumahnya sendiri. Mematikan. Syifa tersenyum tipis, kemudian menggamit lengan Kausar.
“Ayo kita beli es krim.”
Setelah Syifa berlalu, aku mendelik seram pada mereka semua. “Apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian gila?” Lihat, Syifa beranjak pergi. Mawar balas menatap seram.
“Kau aneh Az. Ini adalah kesempatan emas untuk bisa ngobrol dengan Syifa. Eh kamu, jangankan ngobrol, satu baris kata saja tak aku dengar dari tadi. Come on Az. Aku sudah menyediakan panggung.”
Panggung omong kosong. Kalian malah membuat Syifa pergi dengan cara seperti itu.
Namun, Syifa tidak pergi terlalu lama. Dia kembali dengan menenteng kantong plastik besar. Ternyata isinya es krim. Syifa mengambil tiga, menyerahkannya pada Kausar. “Nih, berikan ke ayah dan ibu juga.” Lalu Kausar beranjak masuk kamar.
Kami mendapat masing-masing satu es krim mochi merk lokal itu. Mulanya aku menolak pemberiannya, karena aku gugup sekali. “Ambil Az,” kata Syifa, lembut. Alamak kawan. Wahid terkekeh nakal, “Azka minta disuapin tuh kayaknya.”
Buru-buru kuambil es krim itu.
Mozaik 52
Aku Harus Kembali Ke Sana
Selesai dengan rekayasa terakhirnya, Mawar memutuskan untuk menghentikan kegiatan hari ini. “Eh sudah berakhir?” aku bergumam, sedikit keberatan.
“Kenapa Az, masih betah di sini?” Wahid di sebelahku terkekeh. Aku menyikutnya.
“Iya. Sebenarnya inilah rencanaku. Aku memanggil kalian semua untuk melakukan sedikit rekayasa. Setelah foto bukti itu jadi, kalian tidak usah terlibat lagi. Toh kalian tidak bisa menjahit.” Mawar menunjuk aku, Wahid dan Hamed. Tampangnya menunjukkan isyarat bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak becus.
“Kalau begitu kabar baik. Aku bisa liburan.” Wahid mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lalu high five dengan Hamed. Sama-sama bersorak. Aku buru-buru memalingkan muka. Aku tidak ingin terlihat keberatan dengan keputusan Mawar itu.
Karena pada dasarnya aku memang keberatan.
Aku rela ikut dalam tugas ini, bahkan aku rela belajar menjahit seandainya dengan begitu, aku masih boleh berlama-lama di sini. Masih bisa berada di dekat Syifa. Walau cuma untuk sekedar curi-curi pandang. Tapi keputusan Mawar sudah bulat.
“Kalian serahkan saja pada kami. Pokoknya beres urusannya. Ayo kita pulang. Hari sudah sore.”
Mawar benar. Matahari nun di barat sana, sudah siap masuk ke peraduannya. Atau mengejar setoran terbit di belahan bumi Amerika. Satu persatu anggota kelompok mengucapkan terima kasih pada Tante Shimala, berpamitan. Aku sengaja mengulur waktu sehingga aku yang terakhir meninggalkan tempat ini.
Tuhan, berilah aku sedikit kesempatan untuk ngobrol dengan Syifa.
“Hati-hati di jalan Az,” Syifa mendekat, memegangi pagar. Aku menengok ke arahnya, mencoba menyunggingkan senyum.
“Iya Syif. Terima kasih ya, atas makanannya, tempatnya, dan semuanya.”
Hari itu, aku meninggalkan rumah Syifa dengan satu tekad. Aku akan kembali lagi ke sana. Bagaimanapun caranya.
Malamnya, setelah selesai shalat Isya dan memastikan bahwa Syifa tidak sedang sibuk, aku melayangkan chat padanya. Tidak ingin berlebihan, cuma bilang terima kasih, memuji rumahnya, dan basa-basi lainnya. Tapi di balik itu, aku juga sedang merancang strategi kelas dewa. Kuharap setelah itu, biarlah percakapan mengalir sebisanya.
“Eh Syif, gimana tadi menurutmu, aku pas di rumahmu?” tanyaku.
“Gimana apanya nih Az?”
“Ya aku. Aku tidak malu-maluin-kan?”
“Hehe, tidak kok Az. Kamu malah diam saja tadi. Macam orang tak bisa ngomong. Hehe. Tapi aku maklum kok.
Alamak. Hidungku membesar.
“Rumah kamu enak Syif. Bikin betah.”
“Hehe, baguslah kalau begitu Az. Datang saja sering-sering.”
“Ah mana bisa, kalau aku ke sana sering-sering nanti dikira apa lagi,” balasku lagi. Umpan pertama.
“Iya juga sih Az.”
Sial, umpanku tidak dia sambar. Terpaksa mengulur umpan kedua. Terang-terangan. “Gimana kalau kita buat kelompok belajar Syif?”
“Eh kelompok belajar?”
“Iya Syif. Kita belajar bareng-bareng, di rumah kamu.” Aku mulai memaksa.
“Ide bagus Az. Sudah lama aku ingin belajar secara serius denganmu. Terutama soal matematika itu. Pusing kepalaku melihat soalnya. Belajar di sekolah tidak akan pernah cukup. Benarkah nih Az? Kamu mau mengajariku di rumah?”
“Boleh tuh Syif.”
“Yeeeeeyyy,” balasnya. Bersorak.
“Eh senang banget sepertinya.” Aku sebenarnya juga senang.
“Iya dong Az. Bisa belajar dengan kamu, itu kabar baik. Melengkapi hari yang sangat berkesan ini.”
Kode ini. Pasti kode. Bisik hatiku.
“Kenapa jadi berkesan?”
“Ya kamu tahu Az. Hari ini rumahku ramai sekali. Ada kamu, ada kawan-kawan yang lain juga. Dan kakiku terlindas pagar.”
“EH TERLINDAS PAGAR?”
Aku tersentak. Reflek mengetik huruf besar semua.
“Iya Az?”
“Lalu gimana kondisi kakimu? Sakitkah?”
“Sakit sekali Az. Luar biasa.” Pagar rumah Syifa adalah pagar geser. Silakan dibayangkan bagaimana rasanya.
“Kapan terjadinya?”
“Pas kamu mau pulang dan lambai-lambai.”
“Astaga, maaf ya Syif. Aku jadi merasa bersalah. Maaf banget.”
“Eh tidak separah yang kamu bayangkan Az. Cuma tergencet sedikit. Aku masih bisa berjalan kok. Tenang saja.”
Kode lagi ini. Pasti. Hatiku berbisik lagi. Segera kuingatkan agar hatiku tidak usah menduga macam-macam.
Mozaik 53
Nasehat Paling Berharga
Sudah kentara betul bahwa aku kalah dalam perebutan Piala Quart School Champion yang prestisius itu. Ada banyak sekali soal yang tak bisa kujawab dengan meyakinkan. Ada banyak jawaban yang lolos dari perhitunganku. Jadi, meski pemenang piala itu belum diumumkan, aku sudah mewanti-wanti hatiku agar tidak berharap macam-macam. Kucoba menghibur diri untuk fokus merebut dana beasiswa Ujian Nasional itu saja.
Ah sehebat-hebatnya Piala, itu cuma Piala. Tapi uang 28 juta soal lain.
Akan tetapi, syarat untuk bisa mendapatkan uang sejumlah itu, adalah mengunci posisi ketiga sebagai pemegang nilai UN tertinggi se-kabupaten. Hei jangankan se-kabupaten, satu Quart School saja aku kalah saing. Mentalku down sebelum bertanding.
Demi menegakkan kembali martabatku, dan terutama demi menunjukkan kejeniusanku pada Syifa, hari ini, di akhir Ujian Sekolah, aku datang ke ruangan Ibu Qotrun Nada. Ingin meminta nasehat dari beliau. Barangkali beliau punya tips hebat.
Ibu Qotrun tersenyum-senyum mendengar aku berkeluh kesah.
“Azka,” ujar beliau memulai nasihat, “bagus sekali semangatmu itu. Tapi Ibu rasa kamu kurang yakin dengan dirimu sendiri.”
“Eh iya Bu,” aku garuk kepala menanggapi, “bagaimana-lah Azka bisa menyaingi dua orang itu. Kalau dari semester 1 sampai sekarang-pun, Azka ranking 1 saja tidak pernah.”
Ibu tersenyum lagi. Seolah masalahku itu gampang saja.
“Kamu tahu-kan Az? Bagaimana kunci sukses?”
“Ikhtiar, doa dan tawakkal,” sahutku cepat. Ibu Qotrun memang sering menyebut-nyebut soal itu.
“Nah itu kuncinya. Kamu sudah tahu. Sudahkah kamu praktekkan?”
“Sudah Bu. Hasilnya kurang meyakinkan. Ada banyak sekali soal yang jawabannya lolos dari pengetahuan Azka.”
“Berarti kamu belum mengamalkan ketiga kunci itu.”
Hatiku berdecak sebal. Aku sudah belajar mati-matian. Aku sering berdoa. Dan aku tawakkal kok.
“Azka, Ibu akan bahas lagi ketiga kunci tadi padamu hari ini. Semuanya tidak terpisah satu sama lain. Yang pertama, usaha. Ikhtiar. Maksimalkan ikhtiarmu. Bukan hanya dengan belajar seperti kamu biasanya. Melainkan belajar melebihi biasanya. Maksimal. Bahkan kalau perlu, kamu belajar lebih keras daripada Nasri dan Shiela. Bagaimana caranya itu, kamu selidiki berapa jam belajar mereka. Jika mereka belajar 4 jam, kamu harus belajar 7 jam. Kamu harus ada di atas mereka.”
Aku mulai terpana.
“Lalu mengenai doa, kamu harus benar-benar serius Az. Berdoalah secara benar-benar, mintalah kepada Allah agar kamu diberi kekuatan terbaik untuk memenangi ini semua. Kekuatan Allah itu sangat besar Az, jika Dia ingin terjadi, maka terjadilah.”
Aku terpana.
“Dan terakhir, tutup dengan tawakkal. Saat kamu datang ke sini, kentara sekali kalau tawakkalmu kurang. Kamu tidak benar-benar percaya pada Allah akan hasilnya. Jadi nanti, begitu kamu keluar dari ruang ujian, pasrahkan semuanya. Allah tahu yang terbaik untukmu.”
Aku semakin terpana. Ini adalah nasehat terbaik yang diberikan Ibu Qotrun Nada.
Mozaik 54
Belajar Matematika dan Sedikit Obrolan
Ini episode kedua dari kunjunganku ke rumah Syifa. Kali ini cuma seorang diri. Sesuai kesepakatanku dengannya, aku datang ke rumahnya di hari Kamis Sore. Empat hari lagi, Ujian Nasional dilaksanakan.
Yang pertama menyambutku di depan rumah, adalah Tante Shimala. Kurasa beliau tidak sengaja keluar rumah saat aku tiba. “Nak Azka,” ujar beliau. Aku senang, beliau mengingat namaku. Kusambar tangan Tante Shimala untuk kucium. Takzim.
“Syifanya ada Tante?”
“Eh ngapain nih mencari Syifa?” beliau bertanya balik. Intonasi beliau sebenarnya ramah dan lucu, tapi aku langsung panas dingin.
“Eh Syifa tidak bilang ya Tante, katanya mau belajar matematika bareng. Jadi Azka datang ke sini. Hehehe.” Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal, memasang ekspresi cengengesan.
“Oh astaga, baik sekali kamu Azka. Mau mengajari Syifa. Anak tante itu memang agak lemah matematikanya. Hehe.”
Aku nyengir lagi. Tante Shimala masuk ke dalam rumah, dan mengajakku mengikutinya. Aku berhenti di ruang tengah, di sana sudah ada meja panjang (yang pada kunjungan pertamaku tidak ada). “Tunggu saja di sini ya Azka. Syifanya lagi mandi.”
Sembari menunggu, aku membuka buku dan membaca lagi teori-teori matematika yang kira-kira diperlukan Syifa. Aku bertekad mengajarinya betul-betul hari ini. Teori-teoriku itu tidak boleh terlupa lagi macam sebelumnya.
“Makasih sudah mau repot-repot datang dan mengajari orang macam aku ini Az.”
Itulah sambutan Syifa ketika dia keluar dari kamar. Bau wangi semerbak. Dia menenteng buku di tangannya. Mengambil duduk di seberangku. Aku salut, meski ini di rumahnya, dia tetap memakai pakaian tertutup, lengkap dengan jilbab warna ungu. Baru bersitatap dengannya sedikit, aku sudah tersenyum. Senang sekali bisa dapat waktu berdua begini dengan Syifa. Tanpa ada pemburu gosip yang melihat dan ikut campur.
Pelajaran matematika itu pun dimulai.
Kutanya Syifa, bagian bab mana yang tidak dia kuasai. Apakah tentang trigonometri, matriks, atau malah gabungan keduanya. Syifa membolak-balik buku yang dipegangnya, kemudian menunjuk. Aku terbelalak.
Persoalan barisan dan deret aritmatika. Alamak. Kenapa malah pelajaran yang semudah itu?
“Aku pusing sekali Az, pas lihat Pak Farhan membahas pelajaran ini. Angka-angkanya macam keluar begitu saja.”
Aku manggut-manggut. Aku ingat saat Pak Farhan menjelaskan tentang bagian ini. Bagi Pak Farhan sang matematikawan nyentrik, menghitung deret aritmatika tidak memerlukan rumus tertentu. Beliau bisa menebaknya dengan sekali sebut. Untuk urusan yang lebih rumit, beliau punya rumus tersendiri yang khas. Syifa benar, jika menggunakan rumus Pak Farhan itu, angka-angka seolah keluar dengan sendirinya. Ajaib sekali. Tapi sayang kawan, aku tidak bisa menjelaskan rumus itu. Terlalu rumit jadinya.
Jadi aku menggunakan rumus lawas. Rumus yang telah lama tercantum di buku-buku teks pelajaran, a+(n-1)b.
“Jadi Syif, sebenarnya memakai rumus ini cukup mudah. a+(n-1)b bisa dibaca sebagai “anib” agar mudah mengingatnya. Menjalankannya pun juga mudah, a adalah suku pertama, n adalah angka yang ingin kita cari, dan b adalah beda antar suku. Mudah saja ini Syif.”
Sengaja aku hamburkan kata mudah dalam konteks kalimatku. Dalam sebuah forum, aku pernah membaca, bahwa mengubah psikologi murid adalah cara baik untuk menanamkan pelajaran agar meresap. Dan cara termudah mengubah psikologi, adalah dengan mensugestikan bahwa semua itu mudah saja.
Nyatanya tidak. Syifa tetap kelimpungan. Aku benar-benar tidak tahu kalau level “lemot”-nya itu sampai di titik di mana dia kesulitan menghitung 8x5. Perlahan-lahan kuulang lagi, selalu kukatakan bahwa ini mudah saja. Tapi makin kukatakan, Syifa makin tertekan.
Pukul 4 sore, satu jam setelah aku memulai pelajaran dengannya, Syifa mulai bisa menemukan ritme. Bersorak dia ketika berhasil menyelesaikan satu soal matematika tentang deret aritmatika. Merinding aku membayangkan bagaimana mengajari dia tentang pelajaran yang lebih rumit. Tapi sebagaimana orang yang sedang jatuh cinta, aku akan bertekad untuk mengajari Syifa, sesulit apapun itu. Walau dia adalah orang paling bodoh di dunia sekalipun.
Pukul 5 sore. Aku meneguk air mineral yang disediakan secara baik hati oleh Tante Shimala. “Kita sudahi dulu ya untuk hari ini Syif.”
“Hehe iya Az. Aku rasanya sudah tak berkepala lagi.”
“Belajar matematika itu mudah saja Syif.”
“Astaga kamu ini dari tadi mengatakan mudah terus Az,” Syifa tersenyum lucu.
“Hehe. Supaya kamu terpengaruh dan merasa itu benar-benar mudah Syif. Hehehe.”
“Makasih Az.”
Kemudian hening. Hening yang lama. Aku tidak ingin cepat-cepat pergi dari rumah ini. Lihat Syifa di depanku sekarang. Tak sampai se-meter, begitu cantik, begitu riang. Tanpa ada siapapun yang bisa men-ciye-kan. Aku berdehem-dehem. Memajukan satu buah topik.
“Maaf Syif.”
Nah dia menyernit. Mungkin kawan juga. Kenapa Azka tiba-tiba minta maaf.
“Gara-gara aku, kamu masuk ke dalam masalah. Soal ke-ciye-an itu…”
“Tidak apa-apa Az. Astaga kamu tidak perlu memikirkan tentang itu Az. Biarkan saja. Itu tidak mempengaruhi siapapun. Jangan terlalu dianggap Az, angin lalu saja itu.”
Aku ternganga. “Tapi dulu kamu bilang…”
“Iya Az. Mungkin awalnya risih. Tapi lama-lama aku terbiasa. Toh apapun yang aku katakan, keciyean itu tetap ada. Jadi masa bodo-lah. Kamu tidak perlu memikirkan itu Az. Aku tidak menyalahkanmu, tidak pula marah padamu.”
“Lalu dulu kamu keluar dari rohis. Karena keciyean itu-kan?”
“Sepertinya kamu salah paham Az. Aku tidak keluar dari rohis karena alasan itu. Tapi karena alasan lain. Jadi bukan salah kamu kok.”
Aku hanya bisa nyengir lucu. Jadi selama ini cuma aku yang berlebihan?
Menjelang hari itu berakhir, Syifa sempat menyisipkan satu kalimat. Kalimat yang membuat aku senang sekali. “Az, jadi selama ini kamu menghilang, pura-pura tidak kenal, menjauh dari aku, karena semua keciyean itu? Kukatakan sekali lagi Az. Kamu tidak perlu melakukan itu. Jadilah Azka yang kukenal di awal-awal semester 3. Azka yang menyenangkan, banyak senyum. Kan aku bisa tidak segan minta bantuan kalau kamu begitu Az. Hehe.”
Aku merasa hatiku digenggam tangan yang hangat.
Mozaik 55
Silakan Maju Abang...
Kunjungan keduaku ke rumah Syifa itu hari Kamis itu bukan yang terakhir. Bukan pula yang paling mengasyikkan. Dalam catatanku, aku mencatat bahwa ada 4 kali kunjunganku ke sana, dan kunjungan yang ketiga, adalah yang paling menakjubkan. Yang paling kuingat-ingat kelak seumur hidupku.
Hari itu Sabtu.
Ujian Nasional kian dekat. Kemarin kartu ujian Nasional sudah diberikan oleh panitia ujian. Aku yang merasa telah gagal di Ujian Akhir sekolah, kini membidik reward di Ujian Nasional ini. Jungkir balik aku belajar. Sesuai pesan Ibu Qotrun Nada.
Sementara Syifa semakin tertekan dengan kemampuan matematika-nya itu. Aku mati-matian mensugestinya. Tapi kukira itu gagal. Jadi Syifa melayangkan permintaan. Sebuah permintaan yang menurutnya berat sekali, tapi bagiku adalah anugerah terbesar yang datang dari langit.
“Az, aku masih khawatir dengan Ujian Nasional Matematika itu. Aku mohon kamu sekali lagi, mengajari aku. Bisa-kan Az?” ujarnya di ruang chat pada Jum’at malam.
“Tentu saja, Syif. Kapan dan dimana kita mau belajar?” balasku cepat-cepat.
“Di rumahku lagi ya Az. Enak soalnya, hehe.”
“Boleh Syif,” boleh banget. Asyik aku ke rumahnya lagi. Hatiku bersorak.
“Besok ya Az.”
“Siap Syif. Tenang saja. Mudah saja.”
Kurasa dia tertawa masam membaca chatku barusan.
“Oh ya satu lagi Az. Bisa tidak, kamu datangnya pagi. Jadi kita bisa belajar habis-habisan. Hehe.”
“Oh bisa kok Syif. Besok ya, pukul 8 aku sampai di rumahmu.” Setelah pesan itu terkirim, genap aku bersorak. Besok, hari Sabtu, aku bakal menghabiskan waktu seharian penuh dengan Syifa.
Saat aku sampai di rumahnya, Syifa ternyata belum mandi. Tante Shimala yang memberitahuku. Jadilah aku kembali membuka buku di ruang tengah tempat kami belajar kemarin. Saat sedang asyik mencoret-coret kertas, aku mendengar langkah kaki halus menyelinap dari belakang. Syifa di sana. Menenteng handuk. Saat itulah, untuk pertama, dan satu-satunya aku melihat Syifa tanpa penutup kepala. Rambutnya berurai indah.
“Aku mandi dulu ya Az. Hehehe.”
Aku mematung. Oh Ibu, delapan belas tahun hidupku, tak pernah aku melihat pemandangan semenakjubkan itu.
Rumah Syifa hari ini agak ramai. Tentu saja karena adiknya Syifa, Kausar, ada di rumah. Tak peduli aku sedang membaca buku, dia menarik tanganku, mengajak aku main bola. Mungkin itu karena dia tidak punya kakak laki-laki, jadi ini adalah kesempatan emas.
Aku tidak punya kemampuan semacam Wahid yang bisa langsung klop dengan kanak-kanak. Tapi aku sendiri punya seorang adik laki-laki, jadi kukira aku masih bisa meladeni Kausar. Hei siapa tahu Wahid benar, Kausar akan jadi adik iparku suatu hari nanti.
Sungguh itu adalah impian yang berat kawan.
Dia bersorak-sorak ketika aku gagal menangkap bola yang ditendangnya. “Hore goollll!”
Aku tersenyum lucu saja. Bermain-main dengan adik Syifa cukup menyenangkan.
Sekitar 9 tendangan berikutnya, permainan akhirnya dihentikan, karena Syifa sudah muncul. Kali ini Syifa tampil rapi dengan busana tertutup. Harus kukatakan kawan, meski sudah dibungkus rapat begitu, Syifa tetap cantik.
“Kausar ya, cukup dulu belajarnya. Bang Azka mau belajar dulu sama kakak.” Suara Syifa menginterupsi
Kausar ber-”yah” kecewa.
“Kausar, nanti kita main lagi,” aku menyahuti sambil mengangkat jempol. Dia bersorak-sorak lagi, lalu masuk ke kamarnya.
“Kamu cepat akrab dengan adikku ya Az.”
“Lumayan. Dia aktif sekali.”
“Oiya jelas.”
“Kita langsung mulai saja?’
“Silahkan Az.”
Lalu kami langsung menguliti setiap inci dari materi matematika yang diberikan Pak Farhan itu. Hari itu, kami belajar non-stop dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Semua pelajaran tuntas kubahas. Syifa memang terlihat kelimpungan menghitung. Tapi lama-lama dia manggut paham. Tiap dia terlihat frustasi, kuulangi lagi kalimat bahwa matematika itu mudah saja. Dia tersenyum.
Hei kurasa trikku telah berhasil.
Pukul 3 sore. Tante Shimala-lah yang menginterupsi agar kami berhenti sejenak. “Ajakin Azka makan dulu Syif,” ujar beliau.
Syifa manggut. Dia segera merapikan peralatan belajarnya. “Kamu mau makan apa Az?”
“Eh, aku apa aja boleh Syif. Hehehe.”
“Ya kalau begitu nasi sama garam aja ya.”
Kami berdua terkekeh. Syifa pamit ke dapur, bilang mau menyiapkan makanan, dan menyuruh aku menunggu. Saat dia lengah, aku kabur. Menghilang dari ruang tengah.
Apakah aku langsung pulang hari itu? Tentu saja tidak kawan. Aku cuma bergegas menuju mushola dekat rumah Syifa, untuk shalat Dzuhur. Saat makanan sudah terhidang, aku kembali.
Oh Tuhan, banyak sekali makanan di meja itu. Lezat-lezat. Dan lihat Syifa sedang mengatur posisi mangkuk, piring dan cangkir. Pemandangan yang betul-betul indah. Tadi sepagian, aku mengajari dia, dan dia hanya murid privatku. Kebaperanku ditekan naluri keilmuan. Tapi sekarang di meja makan, dia tak ubahnya istri yang cekatan menyiapkan makanan untuk suami tercinta.
“Tadi kemana Az?”
“Shalat Dzuhur,” jawabku singkat.
“Astaga, kukira kamu pulang. Padahal bisa saja shalat di rumah sini.”
“Aku takut merepotkan Syif.”
“Sudah makan dulu. Jangan ngobrol terus, nanti nasinya dingin.” Tante Shimala menginterupsi lagi.
Alhasil kami beralih fokus ke makanan yang ada di hadapan masing-masing. Saat menyuap nasi pun, masih saja kusempatkan untuk melirik nakal ke arah Syifa. Kami begitu dekat, begitu intens. Apalagi cuma berdua saja di ruang tengah ini.
Di tengah-tengah keasyikan menyuap nasi, awan bergelayut dari langit. Hujan turun dengan deras.
“Eh, kamu nanti aja ya Az, pulangnya. Nunggu hujan teduh dulu. Jangan nekat menerobos. Nanti kamu sakit,” kata Syifa, reflek begitu mendengar hujan turun. Aku manggut saja.
Jadi, sembari menunggu hujan teduh, aku menepati janjiku untuk menemani Kausar bermain. Syifa di sana, duduk dan mencoba mengerjakan beberapa soal, kemudian menyuruhku mengoreksikannya.
Pukul 6 sore, aku memasuki babak paling akbar dalam hidupku. Setidaknya sampai cerita ini ditulis.
Hujan akhirnya reda. Aku menarik nafas. Saatnya pulang. Tapi kemudian aku teringat satu hal. “Oh ya Syif, aku numpang shalat Ashar aja ya, takutnya tak sempat kalau di rumah.”
“Oh boleh Az. Aku juga belum shalat. Yuk barengan saja kita, jamaah. Mumpung ada kamu sebagai imam. Wudhu di kran di teras, Az.”
Apa? Apa katanya tadi? Imam?
Kukira shalatnya di ruang tengah juga. Ternyata tidak. Syifa melambai, memanggilku ke kamarnya. “Ayo Az, sudah siap.”
Aku menghela nafas lagi. Hari ini, aku menjejakkan kaki di tempat yang tak pernah aku bayangkan saat pertama kali merasa suka pada Syifa. Aku ada di kamarnya sekarang. Sajadah sudah dihampar. Syifa sudah memakai mukena. Dia mempersilahkan aku maju. Menjadi imamnya. Aku merasa ada tangan halus yang ikut mendorongku.
Inilah momen terbaik dalam hidupku. Mengangkat takbir sebagai imamnya. Di kamarnya. Luar biasa rasanya. Diam-diam hatiku berdoa, agar suatu saat aku benar-benar bisa jadi imamnya sebenar-benarnya. Hei, kapan lagi waktu terbaik berdoa selain saat beribadah menghadap sang pemilik langit?
Momen shalat Ashar itu hanya berlangsung 15 menit.
“Kamu tidak dimarahi-kan Az, kelamaan keluyuran?” tanya Syifa. Aku sudah duduk di kendaraan. Siap-siap pulang.
“Tidak kok,” aku nyengir, “kalau aku tidak bilang mau kemana. Hehe.”
“Jadi kamu tidak bilang mau ke sini?”
“Cuma bilang ke ibu. Ke ayahku tidak bilang.”
“Astaga Az.”
“Ya habisnya kalau aku bilang-bilang, biasanya dicari oleh ayahku.”
“Wah ayahmu kok mirip ayahku ya. Apa semua rada-rada begitu ya, para ayah.”
“Nanti kalau kelak aku jadi ayah, aku janji tidak bakal begitu.”
Syifa tersenyum malu.
Kau mengerti maksudku, kawan?
Mozaik 56
Buih-buih Cinta Nur Syifa Muliyana
Selamat datang kawan.
Agaknya setelah sejauh ini, kita harus saling memberi selamat. Aku mengucapkan selamat karena kawan telah membaca sampai di sini, ini adalah bagian terbaik dari ceritaku. Sebaliknya, kawan juga harus memberiku selamat, karena aku tiba di puncak kedekatanku dengan Syifa.
Inilah kisah paling mendebarkan dalam saga cerita cinta Humadi Azka dan Nur Syifa Muliyana. Bacalah kawan.
Hari pertama ujian nasional digelar, adalah kali pertama pula aku berjumpa dengan Syifa di Quart School setelah les privat di rumahnya. Hari ini benar, ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia, tapi pikiranku terus dibayangi matematika.
Aku bertemu Syifa di parkiran hari itu. Entah bagaimana bisa, kami datang berbarengan, dan meletakkan sepeda motor bersisian. Ketika Syifa melepas helm-nya, dia melempar senyum ke arahku.
“Selamat pagi Az. Kenapa bengong di sini?” dia terkekeh pelan.
“Nungguin kamu. Eh, maksudku, kenapa kamu datang lebih pagi dari biasanya,” buru-buru aku alihkan topik.
“Ini hari ujian yang penting Az. Nilai yang akan kupakai untuk melamar pekerjaan. Jadi aku harus berusaha keras, termasuk mencoba datang agak lebih pagi dari biasanya.”
“Mantap sekali Syif. Semangat ya.”
“Iya Az, kamu juga. Mau bareng ke ruangan? Sepertinya ruangan kita sama lagi.”
“Kebetulan sekali Syif.”
Kemudian kami tertawa kecil bersamaan.
Seisi Quart School gempar melihat aku berjalan bersisian dengan Syifa. Hei kami memang nampak akrab hari ini, Syifa bergurau tentang bagaimana dia belajar keras matematika kemarin. “Sampai tak berkepala lagi Az, rasanya aku.”
Lalu kami tertawa lagi.
Sepanjang lorong, siapapun yang sempat mengetahui hubunganku dengan Syifa dan sempat men-ciye-kan aku, dan kini melihat aku berjalan bareng Syifa, akan melongok. Termasuk Aram, Wahid bahkan Mawar dan Mei. Dalam slow motion wajah Wahid mirip biawak komodo sedang menyensor panas.
“Ciye Az, jalan bareng bebeb. Luar biasa. Ciye, ciye,” koor yang kunanti-nanti akhirnya tiba. Lagi-lagi sepanjang jalan. Kami seperti raja dan ratu berkunjung ke negeri tetangga. Banyak yang menonton, banyak yang bersorak. Dan sebagaimana raja dan ratu, aku dan Syifa cuma membalas dengan lambaian tangan.
Apa kata Syifa kemarin? Bersikap biasa saja Az.
Jangan tanya bagaimana perasaanku sekarang kawan. Dulu aku pernah bergurau dengan Syifa, tapi tidak jalan bareng, dan aku senang. Pernah juga jalan bareng, tapi tidak banyak berbicara, dan aku juga senang. Apalagi sekarang, bisa jalan bareng dan bergurau dengan dia, bertukar senyum, saling menyemangati. Perasaanku naik berlipat-lipat.
Saat aku masuk ke ruangan, sama sekali tidak ada rasa tegang atau apalah itu yang seharusnya kurasakan. Saat membaca soal, rasanya cincai saja. Soal ujian Nasional yang setaraf SMA itu seolah soal ulangan adikku yang baru SD kelas 1. Mudah sekali aku menjawabnya. Belakangan kutahu, setelah membaca banyak buku tentang introspeksi, motivasi (dan juga konspirasi), aku tahu yang merasukiku di hari-hari ujian nasional itu, adalah the power of happines. Kekuatan kebahagiaan. Kekuatan yang mampu melelehkan baja, jika kawan ingin tahu.
Tak pelak pula, selepas me-recovery hubunganku dengan Syifa, aku jadi tidak ingin jauh-jauh dari dia. Selain mencoba mengobrol dengannya di sekolah, aku juga mencoba men-chat-nya. Kebetulan gayung bersambut. Syifa aktif membalas pesan-pesanku, hingga kami terus berbalasan hingga tengah malam.
Ada dua malam yang percakapannya terus terngiang di telingaku sampai sekarang. Yang pertama, malam Rabu, menjelang Ujian Nasional Bahasa Inggris. Mafhum karena keahlianku bukan di situ, jadi aku tidak terlalu berusaha keras.
Aku malah asyik bercengkrama dengan Syifa. Kami saling pindai masa lalu. Syifa sempat bilang dia penasaran sekali dengan masa laluku. Memang aku sedikit menceritakan soal riwayat pendidikanku di rumahnya kemarin.
“Kamu pernah pacaran tidak Az?”
Aku terhenyak dengan pertanyaannya itu. Pertanyaan yang sungguh tidak terduga.
Kujawab, “iya aku pernah. Pas masih SMP. Pas lagi labil-labilnya.”
“Berapa orang mantanmu Az? Hehe.”
“4 orang Syif,” balasku lagi.
Mungkin bagi kawan sekalipun aku tidak pernah bicara banyak tentang masa laluku. Nantilah itu kawan, kuceritakan di lain kesempatan.
“Wow, banyak itu Az, hehe. Ngapain saja pas pacaran tuh Az?”
“Biasa saja. Macam ABG, chattingan, telponan, nanti ke sekolah bareng-bareng. Begitulah.”
“Romantis sekali Az, hehehe.”
Momen kita shalat kemarin, bagiku seribu kali lebih romantis.
“Itu masa lalu Syif. Jauh tertinggal di belakang sudah.”
“Oh iya, kalau di Quart School bagaimana Az? Ada yang kamu taksir?”
“Oh ada,” balasku tenang, “coba tebak,” bunyi pesan keduaku.
“Mungkin gadis cantik lokal 2 itu, Shiela-kah nama dia itu. Aku dengar kemarin kamu pacaran dengan dia.” Membaca balasan Syifa, aku menyumpah-nyumpah. Kenapa dia harus mengungkit bagian itu.
“Ah itu kemarin pura-pura saja. Shiela takut ada orang yang macam-macam ke dia, jadi aku dimintanya melindungi dia, dengan pura-pura memasang status.”
Syifa mengirimi balasan emot tertawa berderai. “Iya deh Az. Pas pertama masuk Quart School, adakah yang kamu suka? Kan masih terasa aura labil SMP-nya tuh.” Bunyi pesan keduanya.
“Oh ada, Icha Aprilianty.”
Syifa terus membalas dengan cepat, “oh April. Tahu aku Az. Teman aku juga tuh. Ciye, jadi kamu suka dengan dia rupanya.”
“Ah, sekali lagi itu hanya masa lalu Syif. Tertinggal di belakang.”
“Nah kalau sekarang, masih ada kah yang kamu suka Az?”
“Oh masih ada.”
“Serius, siapa?”
“Kamu.”
Aku yakin dia skakmat. Hanya bisa memasang ekspresi nyengir atau bahkan mungkin blushing.
Satu malam lainnya, yang tak kalah berkesan, adalah malam Sabtu, sekitar 33 jam setelah Ujian Nasional berakhir.
Aku ingin sekali men-chat Syifa lagi, tapi malam ini aku kehabisan topik. Ujian Nasional telah berakhir, tidak ada pelajaran lagi yang bisa dijadikan pembuka obrolan. Jadi malam ini, aku terus menerus mencoba mengetik pesan pembuka, dan selalu kuhapus, karena rasanya tidak etis. Mulai dari “assalamualaikum”, “hai Syifa,” sekedar sapaan “Syif”, sapaan klise “lagi apa”, sampai tulisan “I love you.”
Tanpa aku sadari, kelakuanku mengetik-menghapus lagi itu, memicu reaksi di penampang utama WA dia. Yaitu tulisan mengetik di ruang chatting Azka.
“Tadi mau ngetik apa?”
Deg… Aku tidak salah kawan. Syifa mengirimiku chat lagi. Apakah aku terlalu baper, atau dia memang memantau nomorku? Ah jangan-jangan nomorku disematnya di bagian teratas Whatsapp-nya. Segera kutarik pemikiran tak bermutu seperti itu.
“Eh tidak Syif. Tidak apa. Hehehe.”
“Lho kok jadi misterius begitu Az.”
“Ah tidak kok, tidak misterius itu Syif. Aku tidak berbakat bermisteri-misteri. Buktinya aku tidak pernah berhasil menulis cerita misteri.” Balasanku panjang dan bersemangat. Karena aku berhasil menemukan topik yang pas.
“Oh iya itu Az, kata Lia kamu suka bikin cerita-cerita gitu. Beneran kah?”
“Iya Syif, aku bikin novel.”
“Wow, hebat sekali, Az. Novel tentang nih? Boleh aku tahu?”
“Tentang kamu, Syif.”
“Ah masa Az. Masa tentang aku. Apa yang diceritakan juga tentang aku.”
Sungguh aku tidak berdusta Syif. Para kawan pembaca adalah saksi bahwa aku menghabiskan 100 chapter lebih untuk menuliskan semua hal tentang kamu.
“Iya Syif. Seriusan.”
“Makasih Az, aku merasa tersanjung.”
“Hehe tidak apa-apa Syif. Aku senang mengabadikan momen di antara kita.”
“Aku senang dengan orangnya.”
Sampai di sini, kawan. Sampai di sini, aku benar-benar terpaku. Apa katanya? Apa yang barusan dia ketik? Coba kueja baik-baik. Kau juga eja kawan, aku takut, aku rabun dekat. Aku-senang-dengan-orangnya.
Astaga. Syifa. Hatiku rasanya terbang.
Karena terguncang oleh chat-nya barusan, aku tidak lanjut membalas. Astaga. Terlalu mengejutkan kawan.
Sekitar pukul 10 malam. Masuk lagi pesan. Rupanya Syifa men-chatku lagi. Hei, dia men-chat-ku lagi.
“Az, kamu di sana lagi apa.”
“Lagi nyari inspirasi Syif.”
“Oh pantas lama. Aku boleh tanya sedikit Az?”
“Silakan.”
“Boleh kamu jelaskan, apa maksud dari foto profilmu itu Az? Salah fokus terus aku. Hehehe.”
Sekedar info kawan, saat itu, aku memasang foto profil Whatsapp yang agak aneh. Berupa nomor “19” yang dibentuk artistik. Sila kawan menebak-nebak, apa sebenarnya maksudku, nanti kuberitahu.
Mozaik 57
Kamu Diterima Kok...
Hari sabtu pagi, setelah semalaman menghabiskan waktu chat dengan Syifa. Aku dipanggil Ibu Qotrun Nada, untuk mengikuti kegiatan rohis. Aku menurut saja. Kegiatan Panahan kata Ibu.
Ibu Qotrun Nada dan para agen rohis yang lain tercengang melihat aku mampu membidik lurus dan tepat sasaran di tengah-tengah. Bahkan orang paling ahli dalam memanah-pun, hanya memiliki peluang 1:5 untuk membidik tepat di tengah. Ingin aku katakan pada mereka, bahwa itu tadi the power of happiness.
“Azka, sepertinya lagi senang banget.” Ibu Qotrun menegurku saat menyusuri lorong. Aku memang sedang tersenyum-senyum. Tak lepas-lepas sebenarnya senyumku sejak tadi malam.
“Ibu tunggu lho ceritanya. Azka. Sepertinya ada banyak cerita yang keluar dari hidupmu, setelah ibu membukakan blok itu Az.”
Aku masih nyengir-nyengir saja.
Kegiatan rohis baru selesai setelah pukul 5 sore. Ibu Qotrun Nada meminta aku menunggui beliau mengerjakan tugas-tugas pekerjaan beliau.
Dengan masih mengulum senyum, aku menyusuri jalanan. Matahari menggantung di sisi barat, aku teringat sesuatu, aku belum shalat ashar. Sepertinya aku perlu mencari tempat shalat, kemungkinan tidak sempat jika aku memaksakan diri ke rumah.
Saat itulah aku mendapat ide cemerlang. Aku bisa numpang shalat di rumah Syifa. Hei masa bodo-lah dengan banyaknya masjid yang berada di jalan raya, aku lebih suka singgah di rumah Syifa. Kuharap Tuhan bisa memahami jalan pemikiranku barusan.
Sampai aku di rumahnya, Tante Shimala dan Kausar ada di beranda rumah. Begitu melihat aku, Kausar langsung bersorak. “Horeee, abang kembali lagi.”
Aku menyambar tangan Tante Shimala, menciumnya, dan bergegas mengutarakan maksudku yang sebenarnya. “Azka izin shalat ashar di di sini boleh-kan, Tante?”
“Eh boleh kok Az. Masuk, masuk. Syifa juga ada di dalam.”
Aku bergegas melepaskan sepatuku, menuju kran yang aku ketahui kemarin. Lalu melangkah masuk.
“Eh Azka?” Syifa berdiri menyambutku.
“Aku ingin numpang shalat ashar Syif. Boleh?”
“Silakan masuk Az. Ke kamar aku. Bentar aku carikan sajadah.”
“Makasih Syif.”
Aku tidak mau cepat-cepat menyelesaikan shalatku, tapi begitu selesai, aku ingin cepat-cepat meninggalkan kamar ini. Bisa gila aku membayangkan Syifa memakai gaun-gaun cantik yang tergantung di dinding kamarnya.
“Makasih ya, Tante.” Aku kembali mencium tangan beliau saat berpamitan. Tangan Tante Shimala, tangan dari seseorang yang kelak kuharap jadi ibu mertuaku.
“Azka. Kamu rajin sekali Nak. Andai saja kamu tinggal di sini, mushola kami pasti ramai.”
Aku terkekeh mendengar kalimat beliau itu. “Hati-hati di jalan, Azka.” Syifa melambaikan tangan padaku saat aku pulang. Itulah kunjungan keempatku ke rumah Syifa.
Sekaligus kunjungan terakhirku ke sana.
“Az, kenapa tadi kok datang ke rumahku? Padahal-kan banyak masjid jika kamu mau shalat di masjid. Hehe.”
Syifa membuka chat-nya dengan aku.
“Aku ingin ke rumah kamu Syif. Hehe. Rumah kamu nyaman, adem.”
“Wah bagus deh kalau kamu merasa nyaman.”
“Eh kok bagus?”
“Ya tidak apa-apa Az. Bagus, nyaman-kan berarti betah. Hehehe.”
“Eh kenapa, Syif?” aku mendesak.
“Hehe. Lupakan Az.”
Jangan salahkan aku Syif. Tolong-lah jangan membuat aku menebak-nebak. Secara simultan, aku menafsirkan kalimatnya, sebagai: bagus deh kalau kamu betah Az. Bagus. Kamu memang sudah diterima di rumahku Az, tinggal menunggu kamu siap melamar aku.
Kan rumit kalau begini.
“Aku mau menanyakan hal lain, Az.”
“Iya Syif?”
“Bisakah kamu menjelaskan soal foto profil kamu itu Az?”
Oh iya, aku lupa soal itu, kawan.
“Foto profilku itu adalah angka “19”. Angka 19 itu dalam abjad adalah huruf “S”, dan huruf itu tentu saja, kamu, Syifa.”
“Oh astaga Az. Kamu ini.”
“Hehe.”
“Makasih Az. Makasih juga kamu telah mati-matian mengajariku kemarin.”
“Iya Syif. Tenang saja masalah itu. Aku dengan senang hati kemarin itu.”
“Padahal aku lemot-nya minta ampun kemarin itu. Hehe.”
“Kuakui, kapasitasmu dalam menghitung memang lebih lambat. Tapi tidak masalah. Aku suka itu.”
“Suka katanya.”
“Eh beneran Syif.” Menyenangkan sekali melihat chat-chat Syifa itu. Aku ibarat kata sedang menggantung bintang-bintang dengan dia. Tapi sekarang, tanpa kusadari, roda kehidupanku mulai berputar, ke bawah.
Mozaik 58
Hari Ketika Dia Benar-benar Pergi
“Az, tidak lama lagi aku akan pindah.”
Itulah bunyi chat Syifa. Kami masih menjalankan rutinitas saling chatting untuk mengisi malam. Aku sebenarnya takut. Aku tahu, sejak mendengar kabarnya di awal semester 4 lalu, aku sudah tahu, aku sudah tahu kalau hari itu bakal tiba. Tapi aku coba tutupi. Aku coba mengingkarinya. Aku tidak pernah ingin membicarakannya.
Syifa akan pergi, meninggalkan Bumi Melayu. Itu topik yang sangat sensitif bagiku. Dan sekarang, dia sendiri yang ingin membahasnya.
“Iya Syif. Aku sudah dengar kabar itu. Jujur saja, aku tidak senang mendengarnya.”
“Ya mau bagaimana lagi Az. Inilah jalan yang diambil keluargaku.”
“Aku sedih sekali mengetahui ini Syif.”
“Iya Az. Aku juga sedih, meninggalkan Bumi Melayu, meninggalkan teman-teman paling akrabku di sini. Hidup hampir 3 tahun di sini, aku merasa sama seperti kalian, aku orang Bumi Melayu.”
“Jadi kamu mau pindah kemana? Dan kapan?”
“Rabu depan Az. Ke Pontianak.”
ASTAGA! RABU DEPAN! Itu benar-benar mengejutkan, dan yang lebih penting, itu benar-benar sebentar lagi. Ini hari sudah hari Minggu. Berarti 3 hari lagi.
“Kukira kamu pergi setelah pesta perpisahan. Lalu bagaimana dengan ijazahmu dan semuanya.”
“Aku sudah titipkan ke temanku. Semua masih bisa diurus. Ayahku perlu cepat ke sana, mengurus pekerjaan.”
“Aku tak bisa berkata-kata Syif. Sungguh, aku tidak bisa berkata-kata.”
“Makasih Az. Sudah menemani dan mengajari aku. Hehe.”
Ingin sekali aku mengungkit soal perasaanku pada dia. Tapi aku terlalu kalut. Aku tidak berkutik. Yang ada malah kalimat klise. “Syif. Jangan lupakan Bumi Melayu dan semua temanmu yang ada di sini ya.”
Ingin sekali aku menambahkan kata jangan lupakan aku. Tapi aku tak sanggup menuliskan hal itu.
Kau tahu kawan, perpisahan paling menyedihkan, berlangsung dalam senyap. Aku hadir hari itu. Hari Rabu, Syifa mengadakan perpisahan simbolis dengan Quart School. Ibu Qotrun yang memprakarsai, aku yang menyarankan. Lima temannya hadir di sana, mereka berpelukan satu persatu. Aku juga ada di sana, tepekur. Lima kawan Syifa masih asyik berpelukan, menangis. Menyinggung-nyinggung soal kapan kira-kira akan bertemu lagi. Aku menghela nafas.
Meski pedih, aku tidak meneteskan setitik pun air mata di Quart School. Aku baru menangis saat menemani Syifa pulang. Iya kawan, dia yang minta. Aku menjaga jarak, menatap punggungnya.
Hei, sejak awal semester 3, memang cuma dialah, cewek yang aku suka. Perlahan semua kenangan menyeruak dari ingatan. Syifa yang menegurku saat menguap, Syifa yang mengajakku makan siang, Syifa yang memintaku memperbaiki makalahnya, Syifa saat minta ajari matematika, Syifa di hari administrator, Syifa yang jaim di rumahnya, sampai Syifa yang shalat bersamaku di kamarnya.
Hei, kami melalui banyak hal. Dengan banyak penyesalan. Aku membuang banyak sekali peluang untuk berdekatan dengan dia selama ini. Tapi sia-sia sudah memikirkan itu semua. Syifa benar-benar akan pergi.
Aku sering mendengar ada orang mati sengsara menahan rindu yang meluap. Rindu tak tertahan. Rindu yang mungkin tidak pernah bisa ditebus. Aku tak tahu bagaimana aku bisa menyandang perasaan rindu seberat itu. Ah jangankan itu….
Belum juga dia pergi, aku sudah merindukannya,
Mozaik 59
Duniaku Terbalik Dalam Satu Hari
“Syif, hati-hati di jalan. Semoga kamu selamat sampai di tempat yang kamu tuju.”
Aku hanya bisa menitip doa. Menitip doa agar dia selamat di perjalanan, doa agar suatu hari nanti, kami bisa bertemu lagi, dan yang terpenting, doa agar Tuhan menjaga hatinya di sana.
Aku menatap langit. Kosong. Dalam ceritaku, tidak ada adegan romantis di mana sang pria mengejar gadisnya sampai ke bandara, memaksa merangsek, mengucapkan beberapa patah kata, berjanji saling menjaga hati, sampai keduanya bertemu kembali. Tidak kawan, dalam ceritaku, tidak ada momen semacam itu.
Sejak awal, ini adalah kisah tentang aku. Ini adalah kisah hidupku, maka segalanya, hanya berlangsung sepihak. Hanya padaku.
Hari-hari pertama seusai Syifa pindah adalah hari-hari terberat yang pernah aku jalani. Kesedihan, penyesalan, kekhawatiran, dan utamanya ketakutan terus membayang. Syifa pindah di tengah-tengah suasana kedekatan kami yang paling puncak. Aku nyaris mendapatkan hatinya. Tapi sedekat apapun, itu hanya nyaris. Syifa akhirnya pindah.
Aku sangat takut, suatu hari nanti, dia kembali, bersama seorang pria, yang tentu saja lebih segala-galanya dibandingkan aku, dan membawa anak-anak mereka. Mengerikan kawan, mengerikan sekali.
Sekolahku setelah Ujian Nasional adalah kehampaan. Aku tidak merasa senang. Tidak pula sedih. Aku merasa, lahan Quart School yang digarap mewah untuk pendidikan, kini terasa gersang. Bak padang pasir. Tidak ada lagi roh yang membuatnya hidup.
Karena Syifa-lah yang telah meniupkan roh itu padaku.
Selain semua perasaan sedih yang bergumpal campur aduk, aku juga terkena semacam sindrom kelainan jiwa yang aneh. Kini setiap melihat cewek yang berlalu di jalanan, aku serupa melihat Syifa. Syifa, Syifa dan Syifa di mana-mana. Apalagi kalau melihat cewek yang naik sepeda motor yang sama warnanya dengan Syifa. Aku pasti teringat dia. Diam-diam aku meneteskan air mata.
Sindrom itu semakin parah dalam seminggu. Tidak hanya Syifa, kini aku melihat setiap wanita paruh baya, serupa melihat Tante Shimala, dan setiap melihat anak kecil, aku serupa melihat Kausar.
Ah kawan, kurasa penyakit gilaku ada di ambang pintu.
Mozaik 60
Aram dan Wahid, Dua Sobat Baik
Ini masih tentang kisah yang sedih kawan. Periode paling sulit dalam hidup Humadi Azka. Aku kesal, marah, kecewa, sedih, sekaligus rindu dalam saat yang sama. Di hari-hari menjelang kelulusan ini, menu minumku di kantin juga turut berubah. Secara radikal.
Paman Pirates saja, sampai heran dengan apa yang aku pesan. Kopi pahit, sepahit-pahitnya, dengan temperatur yang sepanas-panasnya. “Astaga Az. Kau pasti sudah gila, minuman ini bahkan tidak bisa diminum.” Begitu kata beliau saat menghidangkan minum padaku di hari ketiga.
Bersamaku, ke kantin adalah Aram dan Wahid. Kami memang sudah ditakdirkan menjadi sekondan. Dua teman baikku itu, secara teknis juga tahu apa yang kurasakan. Mereka tahu Syifa pindah, dan mereka tahu seberapa senewennya aku karena hal itu.
Sayangnya, mereka tidak merasakan hal yang sama. Bagi mereka, Syifa hanya gadis biasa. Syifa tidak memiliki pesona se-memukau sepupunya, Mawar Alvera. Atau memiliki prestasi mencolok macam Shiela. Syifa tidak punya semua itu. Lain bagiku, Syifa adalah segalanya.
Lalu atas dasar persahabatan, mereka berdua mencoba menghiburku. Wahid memasang ekspresi lucu berkali-kali, meski lawakannya tidak selucu apa yang kira-kira dia tertawakan. Sedangkan Aram, mencoba menyitir beberapa nasehat yang menurutnya ampuh.
“Kalau dia memang jodoh kau, terpisah sejauh apapun, dia balik lagi ke kau kok Az. Tenang saja.”
Aku menggeleng lemah. Aku sudah bosan mendengar semua kalimat klise semacam itu.
“Kau tak percaya Az? Aku punya seorang teman yang telah membuktikan kalimat itu. Ampuh Az.”
“Hei, apa itu berarti aku juga bisa berjodoh dengan Mawar kalau begitu Ram?”
“Oh kalau yang itu, tidak mungkin terjadi. Jauh panggang dari api, Hid. Karena tidak jodoh, jadi tidak bisa disatukan.”
“Enak saja kau Ram, kau pikir kau Tuhan, bisa menerawang masa depan.”
“Oh tidak. Aku tidak bisa menerawang masa depan. Tapi tadi malam Tuhan datang ke rumahku, untuk memberitahu tentang jodoh dan masa depan kau Hid. Merinding aku mengetahuinya.”
“Memangnya seperti apa masa depanku itu?”
“Di masa depan, kakimu buntung, kau akan jadi bujang selapuk-lapuknya, dan kau akan tumbuh tanduk di kepala.”
Wahid menyemburkan kopi ke wajah Aram. Atas ramalan “Tuhan” yang diberitahukannya. Entah bagaimana dengan kawan, tapi aku yang sedang dalam kondisi terpuruk, bisa tertawa oleh lelucon gelapnya itu. Apalagi mendengar Aram berbicara dengan kondisi kuyup oleh kopi. “Apa boleh buat Hid, itulah masa depanmu.”
“Kupukul kau kalau tidak berhenti mengoceh tentang itu Ram.”
“Ayolah Hid. Lihat, kini Azka sudah tertawa lagi.”
Wahid memandang ke arahku. Dia terlihat senang bisa membuat aku tertawa.
“Ayolah Az, tertawa lagi. Senang lagi. Kepindahan Syifa hanyalah batu kecil yang harus kamu lalui dalam hidup. Kamu harus bangkit lagi.” Wahid ikut menyitirkan kalimat.
“Oh ya Az. Kenapa kamu memesan kopi pahit?” Aram bertanya.
Aku tersenyum masam. “Ini filosofi hidup Ram. Aku berharap, kepahitan yang kurasakan dalam hidupku sekarang, mengalir ke kopi ini, dan sebaliknya, kehangatan kopi ini mengalir ke hidupku yang dingin.”
“Bukan main Az.”
Hei, entah bagaimana cara Aram memancingku berteori, membuat aku merasa lebih baikan.
Mozaik 61
Ibu Qotrun Nada Turun Tangan
Tapi efek adukan cangkir kopi dan lawakan Aram itu hanya bertahan sebentar. Tepat saat aku meninggalkan kedai Paman Pirates, perasaan ngilu sendu itu datang lagi.
Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Sesakit apapun rasa ini, aku tetap harus waras. Aku terus men-sugesti diriku sendiri. Aku sebenarnya punya masalah dengan sakit saraf, jadi aku tidak boleh lengah.
Hei, biar aku memutus nadiku, biar aku mati bersimbah darah, Syifa tidak akan kembali. Dia sudah pergi, selamanya.
Untuk menenangkan diri, aku kembali menghadap Ibu Qotrun Nada. Meminta nasehat beliau.
“Kamu masih tidak mau menceritakan apa yang terjadi padamu dan Syifa sejak Ibu membukakan blok-mu Az?” Ibu Qotrun tersenyum nakal menatapku.
“Tidak sekarang Bu. Azka merasa sangat sesak di bagian ini,” aku menunjukkan kepalaku, “mungkin sebentar lagi, Azka akan gila, Bu.”
“Astaga Az, jangan bicara seperti itu.” Ibu Qotrun naik pitam.
“Azka serius Bu. Masalah ini benar-benar berat.”
“Kamu mesti bersabar Az. Ini cobaan buatmu,” Ibu menunjuk kursi, menyuruhku duduk.
“Sulit Bu. Sulit bersabar. Apalagi melawan kejutan dari sang waktu macam begini,” jawabku, berfilosofi.
“Bukan,” Ibu menggeleng kuat, “kamu tidak sedang melawan waktu. Kamu sedang melawan ketakutanmu sendiri. Dan kamu harus bersabar melawannya itu.”
“Eh ketakutan Bu?”
Aku dan Ibu duduk berhadapan. Beliau memandangiku lekat-lekat. Aku tahu, beliau sedang berusaha menembus ragaku, untuk menerawang pemikiranku. Ibu sangat lihai melakukan itu.
“Iya Az, ketakutan. Itulah yang sekarang membebanimu. Yang membuat kamu sedih. Jauh di lubuk hatimu yang terdalam, kamu cuma takut. Takut kehilangan Syifa.”
Aku mau tidak mau mengangguk. “Dengan jarak ratusan kilometer sekarang, tanpa harapan bisa bertemu, tentu saja Azka takut Bu.”
“Azka. Kalau memang jodoh, urusan ini gampang saja.”
“Sayang sekali, urusan ini hanya mudah di lisan saja Bu. Praktiknya tidak mudah.” Aku menyahut. Alamak, selama ini, mana pernah aku membantah pada Ibu Qotrun. Namun, kali ini, mungkin pengecualian. Semoga Ibu bisa memahaminya. Aku benar-benar muak dengan cerita klise.
“Hei, kamu ingat cerita Ibu soal Nabi Adam dan Hawa Az? Seperti itulah jodoh. Juga ingat kata orang tua kita dulu-dulu. Cara menguji cinta sejati adalah dengan melepasnya. Jika dia memang cinta sejati, maka dia akan kembali, tapi jika dia tidak kembali, maka dia bukan yang sejati.”
Aku bungkam. Kehilangan selera untuk menyahut. Juga segan dengan Ibu Qotrun Nada.
“Ibu cuma berpesan, Azka jangan sampai putus asa. Azka harus tetap sabar.”
Aku diam.
“Azka harus kembali bersemangat. Masih banyak yang harus kamu lakukan di dunia ini.”
Aku masih diam.
“Astaga Az,” suara Ibu meninggi, “andai Ibu punya kuasa menyuruh Syifa kembali ke sini, maka Ibu akan lakukan itu. Sayang Ibu tidak punya. Jadi kamu harus terus sabar.”
Aku menghela nafas. Ibu menghela nafas. Urusan ini semakin tidak menyenangkan.
Mozaik 62
Titik Balik
Kurasa masalah yang kutanggung ini benar-benar berat. Jangankan Aram dan Wahid, Ibu Qotrun Nada saja hanya bisa mengulang-ulang kalimat klise dan basi untuk menasihatiku.
Kemarin, aku mencoba minta pendapat Nasri. Panjang lebar aku bercerita pada dia. Dia menutup matanya sebentar, menghayati ceritaku. Kemudian mulai berbicara.
“Az, aku tidak terlalu mengerti masalahmu ini, aku tidak pernah merasakannya. Tapi jelas, masalahmu ini sangat menarik.”
“Lanjutkan, Nas.”
“Masalahmu ini bisa didefinisikan menurutku dalam tiga kata. Berlebihan, membingungkan dan tidak ilmiah.”
Kemudian Nasri meracau. Tapi tidak satupun ceracau-nya itu, masuk akal dan bisa menjadi penawar bagi hatiku. Kutinggalkan Nasri. Bahkan orang paling jenius sekalipun tidak bisa menemukan solusi bagiku.
Ah kawan, kurasa aku harus mempertimbangkan bagaimana caranya aku mati.
Apakah aku harus menabrakkan diri ke salah satu kendaraan besar yang berlalu lalang di jalan besar Bumi Melayu. Atau aku terjun ke sungai dari jembatan besar yang ada di Sungai Barito itu. Berhubung aku tidak bisa berenang, sepertinya mudah saja melakukan itu. Atau aku harus mengiris nadiku dengan pisau, lalu jatuh bersimbah darah. Sepertinya itu heroik. Atau lagi, aku meminum racun serangga dan mati dengan keadaan mulut berbusa.
Mana yang kau pilihkan untukku kawan?
Sayangnya tidak kawan. Aku tidak mati. Aku tidak akan mati hanya karena kehilangan Syifa. Masih ada jalan terbuka untukku. Ada satu orang yang ternyata bisa menyelamatkan aku.
Orang itu adalah Lia.
Bersambung>>>>
(10 chapter tersisa)
Bagian terakhir diselesaikan pada
Minggu, 03 Januari 2021
Pukul 21:46
WITA
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰