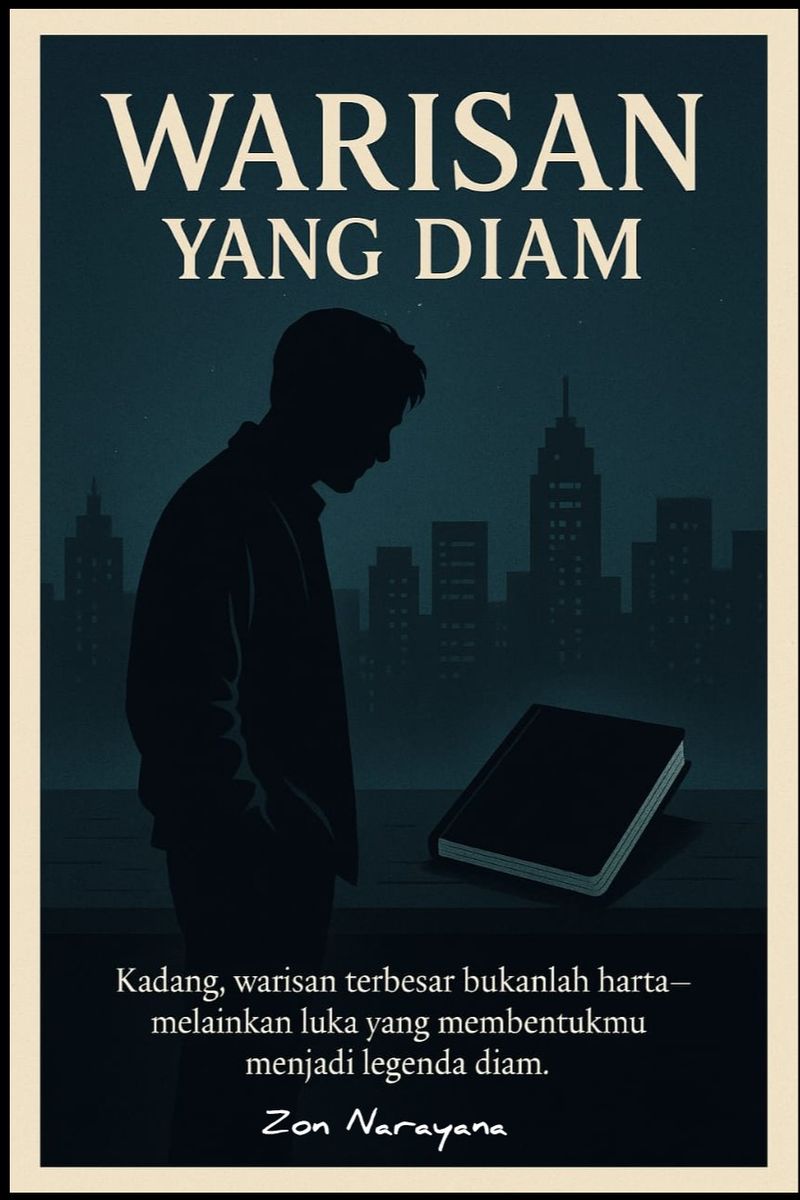
WARISAN YANG DIAM
Tidak semua warisan bersuara. Ada yang tumbuh dalam diam, membentuk legenda tanpa panggung.
Zavian Kenzo Mahardika tak tumbuh dari kemewahan, tapi dari luka. Di usia 20, sebuah warisan misterius mengubah hidupnya selamanya. Bukan hanya harta, tapi juga kebenaran masa lalu yang disembunyikan.
Dari lorong sempit Jakarta hingga gemerlap Tokyo, Zavian membangun FRAKSI—imperium tanpa wajah yang didengar dunia. Ia tidak tampil. Tidak bicara. Tapi setiap langkahnya meninggalkan gema.
Ini bukan kisah tentang kemewahan. Ini tentang kekuatan memilih diam saat dunia menuntut suara.
WARISAN YANG DIAM
BAB 1 - DI ANTARA LENGANG & KEBISINGAN
Jakarta Timur, 06.12 pagi.
Udara masih sedikit basah oleh embun yang enggan menguap. Langit belum sepenuhnya biru, dan aroma roti bakar dari warung ujung gang menyatu dengan bau knalpot motor tua. Di sebuah rumah sederhana seluas lima ratus meter persegi, suara radio tua membisikkan lagu lawas Dewa 19 yang samar-samar.
Di dalam, seorang remaja laki-laki berdiri di depan cermin kecil, merapikan seragam putih-abu yang sedikit kusut.
“Za, kamu tuh udah ganteng, nggak usah ditambah-tambahin pake parfum segala,” suara ibu terdengar dari dapur. Hangat. Meledek. Tapi penuh cinta.
Zavian Kenzo Mahardika tersenyum tipis.
“Namanya juga anak SMA, Bu. Kan harus ada branding,” jawabnya sambil menyemprotkan cologne murah dua kali ke leher.
"Aroma kesuksesan," tambahnya, setengah bercanda.
Ibunya, Jihan Purnamasari, keluar dari dapur membawa dua gelas teh manis dan sepiring telur dadar. Matanya sedikit sembab—tidak banyak tidur semalam, seperti biasa. Tapi tetap memaksa tersenyum.
“Nih, sarapan dulu. Jangan kebanyakan gaya, nanti pingsan di jalan.”
Zavian mengambil piring dan duduk. Rumah mereka memang sederhana, tapi terasa hidup. Dindingnya dihiasi rak buku kayu tua, beberapa poster film Bruce Lee, dan kalender butik ibunya yang sudah beralih fungsi jadi daftar cicilan.
Mereka makan berdua, tenang. Tapi ada sesuatu yang menggantung di udara.
“Bu,” kata Zavian pelan, setelah mengunyah potongan terakhir. “Kalau aku buka bisnis lagi, Ibu bakal marah?”
Jihan meletakkan gelasnya perlahan.
“Bisnis lagi? Bukannya kemarin baru ditegur Wakasek karena jualan sepatu KW di parkiran sekolah?”
“Itu bukan sepatu KW. Itu second ori,” jawab Zavian cepat. “Pasarnya gede, Bu. Anak-anak basket suka model retro. Aku juga mulai coba dropship aksesoris dari Pasar Uler. Margin-nya lumayan.”
Jihan menatap anaknya. Lama.
Tatapannya bukan marah, tapi khawatir. Dalam sekali.
“Kamu itu baru 17 tahun, Za. SMA belum selesai. Ibu cuma pengen kamu fokus. Jangan terlalu keras kepala.”
Suara Jihan sedikit bergetar. “Ibu tahu kamu pintar, kamu bisa lebih dari sekadar jualan di pinggir lapangan…”
Zavian menunduk.
“Ibu, aku nggak pengen kita gini-gini aja terus. Aku capek lihat Ibu kerja dari pagi sampai malam, nahan sakit punggung, narik-narik tas butik berat itu sendiri. Aku pengen bantu.”
Sunyi.
Hanya terdengar suara kipas angin tua yang mengayun malas.
Jihan menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil.
“Ya sudah. Tapi janji. Sekolah tetap nomor satu.”
Zavian mengangguk.
“Janji.”
Pukul 06.45.
Zavian mengunci gerbang rumah kecil mereka, lalu menyalakan motornya. Kawasaki W800 hitam modif bobber mengeluarkan suara rendah yang berat dan tegas. Hadiah ulang tahun dari ibunya. Meski hanya motor, bagi Zavian motor itu seperti perisai—mengantar dia dari satu pertarungan hidup ke pertarungan berikutnya.
Jakarta mulai menggeliat. Truk-truk besar, pengendara yang mengumpat, anak-anak SD berlarian sambil tertawa, dan Zavian melaju di antaranya. Menghindari lubang jalan, menyalip angkot, dan berhenti sebentar di lampu merah dekat SMA Dwipantara.
Dari kejauhan, tampak murid-murid sudah berkumpul. Seragam rapi. Sepatu kinclong. Tertawa-tawa sambil main HP.
Zavian menarik napas.
Hari ini pasti akan panjang. Seperti biasa.
SMA Dwipantara.
Gedung tiga lantai dengan warna abu muda itu berdiri megah di balik pagar hitam tinggi. Sekolah swasta unggulan, tempat di mana anak pejabat dan konglomerat bercampur dengan anak-anak beasiswa yang nyaris tak punya.
Zavian memarkir motornya di ujung parkiran belakang, jauh dari kamera CCTV dan pandangan Satpam. Ia lebih nyaman di pinggiran. Seperti biasa.
“Hei, Kenzo! Wahai pangeran pinggiran!”
Suara khas itu langsung menyapa, disusul lemparan botol air kosong ke arah kepalanya.
Zavian menangkapnya tanpa melihat.
“Lu kira gua Naruto?” katanya datar. “Muncul terus tiap pagi tanpa aba-aba.”
Rian—teman sebangkunya sejak kelas 10—tertawa keras sambil menepuk bahu Zavian.
“Kagak lah. Naruto mah jadi Hokage, lu mah jual sepatu KW. Hahaha!”
Zavian nyengir tipis.
“Dan elu pembeli setia, ingat?”
Sebelum Rian membalas, muncul sosok lain.
Langkah pelan. Wajah dingin. Dasi super rapi. Kacamata mahal. Parfum mencolok. Dialah Arya Dipoatma, anak pemilik developer properti terbesar di Jakarta Selatan. Anak orang kaya yang... terlalu sadar kalau dia kaya.
Arya melirik sepatu Zavian.
“Sepatu lo itu... original nggak sih?”
Zavian tak langsung jawab. Ia hanya menatap balik, tajam dan tenang.
“Original menurut siapa?”
Arya tersenyum kecil, sinis.
“Ya menurut dunia, bro. Kecuali dunia lo beda, ya.”
Rian mencoba menengahi. “Udah, udah... pagi-pagi jangan adu kasta.”
Tapi Zavian tetap berdiri tegak.
“Gue gak hidup buat ngikutin dunia lo, Ar. Gue hidup buat ngubah dunia gue.”
Arya tertawa. “Wah, dalem. Lo ini cocoknya jadi motivator, bukan penjual sepatu.”
Zavian tak membalas. Ia hanya melewati Arya begitu saja, masuk ke lorong sekolah. Tapi dalam hatinya, ada bara yang menyala. Ia sudah biasa diremehkan. Sudah kebal. Tapi bukan berarti dia akan diam.
Di dalam kelas, suasana sudah riuh.
Lagu-lagu TikTok bocor dari headphone. Obrolan soal drama Korea terbaru bercampur dengan suara lemparan kertas. Zavian duduk di pojok belakang, menaruh tas dan membuka buku catatannya. Tapi pikirannya melayang.
Seseorang menarik bangkunya dari belakang.
“Kenzo,” suara lembut itu terdengar. “Gue titip ini ya. Gak sempet beli casing HP, lo kan punya link-nya, kan?”
Dia—Shanaya Prameswari, ketua kelas sekaligus cewek paling sulit dipahami di sekolah. Cantik, cerdas, dan... terlalu tenang. Anak pengusaha tekstil yang tak pernah pamer, tapi juga tak pernah benar-benar dekat dengan siapa pun—kecuali entah kenapa, dengan Zavian.
Zavian menatapnya. “Gue bukan toko online, Nay.”
Shanaya tertawa kecil. “Tapi lo lebih cepat dari Shopee.”
Zavian tak bisa menahan senyum tipisnya. “Besok sore udah ada. Lo mau warna apa?”
“Hitam matte. Kayak lo,” katanya ringan, lalu kembali ke kursinya.
Bel masuk berbunyi. Pelajaran dimulai.
Tapi bagi Zavian, pelajaran sesungguhnya bukan soal matematika atau sejarah. Pelajaran itu adalah bagaimana bertahan di dunia yang tak adil, sambil tetap menjaga harga diri. Bagaimana tetap bermimpi, sambil diseret realitas. Dan bagaimana mencintai... tanpa merasa pantas dicintai.
Dan dia tahu, hidup akan jauh lebih keras setelah lonceng pulang berbunyi.
SUARA-SUARA YANG TAK TERDENGAR
“Kita masuk ke bab Perang Dingin. Siapa yang bisa jelaskan kenapa istilah ini dipakai?”
Bu Restu berdiri di depan kelas dengan ekspresi tajam tapi tenang. Ia satu-satunya guru sejarah yang disegani, bukan karena galak, tapi karena keadilan dan kepiawaiannya membuat murid-murid betah—atau minimal, diam.
Beberapa tangan terangkat. Tapi bukan tangan Zavian.
“Zavian Mahardika,” suara Bu Restu menyusul, memecah lamunannya, “Kamu bisa bantu jelaskan?”
Zavian mengangkat wajah. Tatapannya jernih.
Ia berdiri pelan. “Karena meskipun tidak ada tembakan langsung antara Amerika dan Uni Soviet, tapi ketegangan politik, ideologi, dan perlombaan senjata membuat dunia seperti duduk di atas bom waktu.”
Kelas hening.
Bu Restu mengangguk, tersenyum. “Ringkas, padat, dan tepat. Duduk, Nak.”
Zavian duduk kembali. Rian mencoleknya dari samping.
“Lu hafal buku atau nyimpen AI di kepala, bro?”
Zavian menyengir. “Gue cuma ingat rasa takut pas baca berita nuklir waktu SD.”
Pelajaran berikutnya: Matematika.
Pak Badrun, lelaki paruh baya berkacamata bulat dengan suara khas radio AM, masuk membawa setumpuk kertas ulangan.
“Ini nilai kalian,” katanya dengan nada tenang, “dan seperti biasa… saya kecewa.”
Beberapa murid mulai gelisah.
“Yang nilainya tertinggi minggu ini... Zavian Mahardika. 92.”
Langkah kaki Pak Badrun mendekat ke bangku Zavian dan meletakkan kertas itu di mejanya. Tak ada pujian. Hanya tatapan penuh arti.
Zavian hanya mengangguk kecil.
“Kenapa murid kayak kamu bisa dapat nilai bagus, tapi hampir tiap bulan mangkir upacara, telat masuk, dan pernah dihukum karena berantem?”
Zavian tak langsung jawab. Suasana kelas tegang. Pak Badrun melipat tangan.
“Karena saya belajar bukan buat nyenengin sistem, Pak,” ucap Zavian akhirnya. “Saya belajar karena saya tahu hidup gak akan kasih diskon buat orang bodoh.”
Kelas seketika hening.
Pak Badrun menatap Zavian lama, lalu tiba-tiba tersenyum—aneh sekali.
“Kadang saya pikir... kamu bisa jadi orang besar. Atau orang gagal yang keras kepala. Tidak ada tengah-tengahnya.”
Zavian hanya menatap lurus, lalu perlahan balikkan matanya ke jendela.
Langit Jakarta mendung. Tapi di dalam dirinya, petir sudah lebih dulu menyambar sejak lama.
Jam sekolah usai.
Langkah-langkah keluar kelas seperti irama rutin yang tak lagi disadari. Zavian meraih tasnya dan bersiap pulang.
Tapi sebelum melangkah keluar, Shanaya memanggil dari balik pintu.
“Kenzo.”
Ia menoleh.
Shanaya menyerahkan sebuah catatan kecil.
“Kalau kamu ke Taman Puring nanti, tolong beliin juga gelang kulit kayak yang kemarin kamu pakai. Adik gue ulang tahun.”
Zavian menerima catatan itu. Tangannya nyaris bersentuhan dengan milik Shanaya. Tapi ia cepat menariknya.
“Lo sadar gak, Nay... cowok miskin kayak gue bisa belanja buat keluarga orang kaya, itu ironis.”
Shanaya hanya tersenyum. “Atau mungkin... itu justru bukti kalau dunia gak pernah hitam-putih.”
Zavian mengangguk pelan.
Lalu, ia menaiki motornya. Menghidupkan mesin Bobber tua itu.
Dan melaju. Ke tempat di mana mimpi dan kenyataan saling menggerogoti—Pasar Taman Puring.
Kita lanjut ke Bagian 4 – Jalanan yang Mengajari Lebih dari Sekolah, fokus ke Taman Puring dan dunia nyata di luar kelas: interaksi Zavian dengan pedagang, kilas balik masa kecilnya, dan awal mula ide bisnis sepatu KW. Sentuhan drama, emosi, dan realisme tetap kental.
JALANAN YANG MENGAJARI LEBIH DARI SEKOLAH
Jakarta jam 4 sore adalah orkestra bunyi klakson, teriakan pedagang kaki lima, dan deru mesin yang kelelahan. Tapi buat Zavian, suara bising itu sudah seperti pengantar tidur. Ia mengenal iramanya, ironi damainya.
Motor Bobber-nya berhenti di depan gerbang sempit yang nyaris tak terlihat: Pasar Taman Puring.
Ia matikan mesin, buka helm, dan tarik napas dalam.
Udara di sini bau keringat, lem sepatu, dan gorengan. Tapi buatnya, ini bau kehidupan. Bau masa kecilnya.
“Zavian! Eh, Zavian! Udah lama gak ke sini, lo,” teriak Om Darto, penjual sepatu second yang juga temannya sejak SD.
Zavian menyengir. “Abis ujian, Om. Banyak PR.”
“Ah, PR bisa ditunda. Tapi uang kagak bisa, ya kan?” Om Darto terkekeh.
Zavian mendekat ke lapak kecil beralas terpal biru. Sepatu basket—yang satu original, sisanya KW super—tertata rapi seperti barang museum.
“Gue butuh sepatu KW buat sekolah. Ada Jordan yang mirip asli gak?”
Om Darto mencomot satu dari tumpukan. “Ini... Jordan Retro 1. Grade ORI. Diambil dari Bandung. Lu jual lagi bisa dua kali lipat.”
Zavian memeriksa dengan detail. Mata tajamnya membaca segala yang tak ditulis di brosur. Lem, stitching, warna.
“Kulitnya tipis. Nggak bakal tahan seminggu buat anak SMA yang hobi salto.”
Om Darto ngakak. “Anak kayak lo emang beda. Liat barang, bukan harga.”
Zavian mengangguk. “Gue ambil dua pasang. Nanti gue pasarin ke anak-anak basket Dwipantara. Sekalian pesen gelang kulit juga. Ada cewek nyuruh.”
“Cewek?” Om Darto menyeringai. “Zavian, lo makin mirip bokap lo waktu muda.”
Zavian diam. Sesuatu menggetar di dadanya. Nama itu.
Bokap.
Sudah lama sekali tidak ada yang menyebut nama itu di hadapannya.
“Lo kenal bokap gue?” suara Zavian jadi lebih rendah, lebih pelan.
Om Darto terdiam sejenak. Lalu, pelan-pelan ia buka topi bututnya.
“Kenal. Dulu dia sering ke sini, bantuin gue ngurus lapak pas masih kuliah. Bahkan gue diajarin coding buat jualan online... sebelum dia ninggalin semuanya.”
Zavian menunduk. Matanya kosong.
“Dia ninggalin gue pas gue umur sebelas. Gak bilang apa-apa.”
Om Darto menepuk bahunya. “Kadang orang dewasa ninggalin bukan karena mereka gak sayang... tapi karena dunia maksa mereka jadi pengecut.”
Zavian tidak menjawab. Tapi genggaman tangannya di sepatu Jordan itu makin kencang. Ada api kecil yang mulai menyala di dadanya. Api yang tidak dia mengerti... tapi tahu itu nyata.
Langit Jakarta mulai gelap.
Zavian menaiki motornya lagi, kini dengan dua pasang sepatu KW dan selembar catatan pesanan gelang kulit di dalam tas.
Di jalan pulang, pikirannya penuh.
Tentang ayah yang diam-diam pernah menjual barang di pasar ini.
Tentang ibu yang selama ini memikul semuanya tanpa pernah menyalahkan siapa pun.
Tentang dirinya yang harus segera menemukan jalan keluar.
Bukan cuma dari trauma. Tapi juga dari kemiskinan.
THE REAL PLAN
Langit malam di Jakarta Timur tak pernah benar-benar gelap. Lampu jalan, warung rokok, dan suara televisi dari rumah-rumah tetangga jadi cahaya kecil yang menjaga kehidupan tetap terasa hidup.
Zavian baru pulang. Motor Bobber-nya berhenti perlahan di halaman rumah seluas 500 meter persegi. Rumah tua itu berdiri kokoh, catnya mulai kusam, tapi bersih dan penuh cinta. Ibu Zavian selalu memastikan itu.
Begitu masuk, aroma oseng tempe cabai hijau langsung menyambutnya.
"Zavian... kamu baru pulang?" suara Ibu terdengar dari dapur.
Lembut, tapi ada sedikit lelah di ujung nada itu.
Zavian lepas sepatu, taruh helm, dan langsung menuju meja makan.
“Mampir ke Taman Puring, Bu. Ngambil sepatu.”
Jihan Purnamasari keluar dengan celemek, membawa sepiring tempe dan sayur bening. Usianya 45 tahun, tapi wajahnya tetap cantik. Lelah tak pernah benar-benar bisa menghapus keanggunan alami milik wanita itu.
Mereka makan dalam diam sejenak. Sampai sang ibu bertanya, pelan,
“Uang dari jualan yang kemarin... masih kamu simpan, Nak?”
Zavian mengangguk sambil mengunyah.
“Masih. Semua gue catet, Bu. Sekarang udah tujuh juta delapan ratus ribu. Dari sepatu KW, aksesoris, gelang kulit, sama satu motor temen yang gue bantu jualin.”
Mata Jihan berkaca sedikit. Tapi ia tersenyum.
“Tabungan kamu lebih banyak dari tabungan keluarga kita di bank.”
Zavian ikut tersenyum, pahit.
“Tenang aja, Bu. Gue targetin bisa kumpulin lima belas juta sampai akhir semester ini. Gue pengen coba open PO via IG, atau bikin akun TikTok buat review sepatu. Kalau viral, lumayan.”
Jihan mengusap kepala anak semata wayangnya.
“Kadang Ibu takut... kamu terlalu dewasa buat anak SMA.”
Zavian tak menjawab. Tapi ia menggenggam tangan ibunya. Kuat.
Malam makin larut. Setelah ibunya tertidur, Zavian duduk di lantai kamarnya yang beralaskan karpet tipis. Ia keluarkan buku catatan kusam dari bawah bantal.
Halaman pertama ditulis dengan spidol hitam:
THE REAL PLAN
By Zavian Kenzo Mahardika
Ia mulai menulis:
Target akhir tahun:
- 20 juta dari sepatu KW & aksesoris
- Mulai dropship hoodie atau tas gym
- Buat brand fiktif biar keliatan premium
- Join workshop bisnis lokal kalo ada promo
Tabungan sekarang: Rp 7.800.000
Sisa dari bulan lalu: Rp 1.250.000
Uang koin & receh: Rp 312.000
Total aset pribadi: Rp 9.362.000
Zavian menghela napas.
Lalu menatap langit-langit kamarnya.
“Kalau ayah lihat gue sekarang... dia bangga gak, ya?”
Tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin dan dengkuran anjing tetangga.
Zavian rebahkan tubuhnya perlahan. Tapi pikirannya tetap liar.
Esok hari, dia akan kembali ke sekolah. Menghadapi guru galak, teman yang nyinyir, dan kenyataan bahwa hidup ini tak pernah mudah.
Tapi malam ini… di rumah kecil itu, di bawah langit Jakarta yang berdebu dan panas, seorang anak laki-laki sedang menyusun rencana untuk mengubah takdirnya.
Bab 2 – MELAWAN JALAN YANG DIPAKSAKAN
Surat Panggilan di Jam Istirahat
Suara bel istirahat pertama berbunyi. Gema cempreng dari speaker tua menggema di seluruh SMA Dwipantara.
Zavian baru saja keluar dari kelas 12 IPS-1. Seragamnya tak dimasukkan, kancing atas terbuka, dan celana abu-abunya sedikit lebih gelap karena keringat. Dia langsung menuju kantin, tapi belum sampai dua langkah…
“Zavian Kenzo Mahardika,”
suara itu berat, tegas, dan datang dari belakang.
Zavian menoleh. Satpam sekolah berdiri di depan papan mading, sambil melambaikan selembar kertas kuning yang sudah dilaminating.
“Lo dipanggil ke ruang Wakil Kepala Sekolah. Sekarang.”
Zavian mengangkat alis.
“Kenapa, Pak? Saya gak bawa bom,” gumamnya pelan.
Satpam itu tidak tertawa. Tapi teman-temannya yang lain sudah menahan tawa di belakangnya.
Zavian berjalan santai menuju ruang wakil kepala sekolah. Kantor itu punya aura dingin. Dindingnya penuh poster tentang kedisiplinan, dan selalu ada aroma balsem entah dari mana.
Di dalam, duduk Pak Doni, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Wajahnya datar, kacamatanya melorot sedikit ke ujung hidung.
“Zavian,” katanya pelan namun mengandung tekanan, “sudah berapa kali saya bilang? Sekolah ini bukan pasar.”
Zavian diam. Tapi matanya tajam.
“Kalau sekolah ini bukan pasar, Pak... kenapa harga kantin lebih mahal dari warteg?”
Satu detik. Dua detik.
Pak Doni mematung. Tapi kemudian berdiri dan meletakkan map ke meja.
“Kamu ketahuan menjual gelang kulit, headband basket, bahkan sepatu! Kamu pikir sekolah ini tempat jualan? Ini institusi pendidikan!”
Zavian tetap tenang.
“Justru karena ini institusi pendidikan, saya belajar. Belajar hidup, Pak. Belajar bertahan.”
Wajah Pak Doni memerah.
“Kamu dihukum! Mulai besok, satu minggu kerja sosial di sekolah. Bersihin lapangan, bantu perpus, dan ikut shift piket satpam!”
Zavian mendesah.
“Boleh saya pilih, Pak? Jadi guru juga gapapa.”
Seketika, pintu ruang wakil kepala sekolah terbuka. Suara tawa remaja terdengar samar dari luar.
Zavian tahu satu hal: dia baru saja jadi topik gosip baru di sekolah.
Dan anehnya... itu membuatnya makin dikenal.
Turnamen dan Kobaran yang Disembunyikan
Lapangan indoor SMA Pelita Bangsa dipadati suara terompet dan yel-yel histeris. Bendera tim-tim SMA favorit berkibar di setiap sisi tribune. Tapi satu nama yang mulai bergaung dari speaker komentator adalah:
“Zavian Mahardika dari SMA Dwipantara—small forward, number eleven!”
Zavian berjalan masuk dengan wajah datar. Tak ada senyum, tak ada anggukan berlebihan. Tapi tatapannya… tajam. Fokus. Dia bukan tipikal cowok yang haus perhatian. Tapi perhatian datang sendiri.
“Eh, itu Zavian ya? Yang katanya jago banget...”
“Dia yang jualan di sekolah, kan?”
“Gue follow dia di IG—galaknya keren…
Telinga Zavian mendengar bisik-bisik dari tribun sekolah lain, terutama dari barisan cewek-cewek berseragam SMA Kartika dan SMA Kusuma Bangsa. Beberapa bahkan berani teriak:
“KENZO! NOMOR SEBELAS! SEMANGAAAT!”
Sementara itu, tiga cowok dari tim lawan melirik sinis.
“Cih. Gaya doang. Sok misterius.”
Zavian mendengar, tapi dia tak bereaksi. Dia hanya melirik scoreboard, lalu mengikat tali sepatu kanan.
Peluit pertama dibunyikan.
Dan dari detik pertama, dia berubah. Gerakan Zavian luwes, cepat, dan penuh kalkulasi. Dia mengatur formasi, mengarahkan pemain, lalu memotong bola dari lawan dengan teknik yang bersih tapi agresif.
“BAGUS, ZAVIAN!” teriak Coach Rudi dari pinggir lapangan.
Di kuarter ketiga, dia berhasil mencetak tiga lay-up berturut-turut dan satu three-point yang membuat semua bangkit dari duduknya.
Di bench, rekan satu timnya berbisik:
“Gila, bro… Lo tuh diem, tapi waktu main kayak ada apinya.”
Zavian hanya menyeka keringat.
“Gue main buat nyokap. Bukan buat sorak-sorai,” ucapnya pelan.
Setelah pertandingan selesai—SMA Dwipantara menang dengan skor 64–57—kerumunan mulai mendekat. Anak-anak cewek dari sekolah lain mencoba ngajak foto, kasih minum, bahkan minta akun Instagram.
Zavian hanya menanggapi beberapa dengan senyum tipis.
Namun di sisi lain lapangan, tiga cowok dari tim lawan menatap dengan ekspresi pahit.
“Paling juga cuma menang karena gaya...”
“Tunggu aja di luar, kita bikin dia gak bisa jalan.”
Zavian tahu. Dia bisa merasakan atmosfer itu. Tapi dia tetap tenang.
Karena bagi Zavian, pertandingan sesungguhnya bukan di lapangan… tapi di hidup.
Dan malam itu, saat dia sudah pulang, membuka tabungan digitalnya yang nyaris mencapai 14 juta rupiah, dia tersenyum sendiri.
Ternyata usaha dan keringat tetap bisa bersuara, walau tanpa banyak bicara.
HP Bekas dan Jendela Masa Depan
Hujan rintik-rintik membasahi genteng rumah sederhana yang mulai lapuk di bagian belakang. Suara ketikan di layar HP tua terdengar dari kamar sempit berukuran 3x4 meter itu.
Zavian duduk bersandar di atas karpet, punggungnya menyentuh tembok yang dingin. HP bekas Samsung Galaxy Note 5 miliknya, walau layarnya retak di sudut kanan, masih setia menampilkan grafik candlestick warna hijau-merah yang terus bergerak cepat.
“Naik... turun… mantul…” gumamnya pelan.
Di sebelah HP, ada laptop tua peninggalan almarhum kakeknya. Layarnya sedikit burem, tapi cukup untuk buka Discord dan forum-forum crypto underground dari luar negeri. Sebagian besar pake bahasa Inggris slang yang bikin alis Zavian berkerut.
“Altcoin ini katanya bakal naik bulan depan… Tapi banyak influencer palsu juga. Harus cross-check.”
Di HP satunya—khusus untuk media sosial—DM Instagram-nya sudah penuh.
Bukan cuma cewek-cewek yang kirim emoji heart atau komentar “Kenzo ganteng bener sih...”
Tapi juga pesan-pesan seperti:
@DunkForce.id: “Mas Zavian, kami tertarik endorse produk sepatu basket terbaru. Honor bisa nego. Mau, bro?”
@StreetWearNesia: “Hai Kenzo! Mau barter promo IG story? Kita kirim kaos dan jaket terbaru dari koleksi September. Kamu keren banget main basket kemarin!”
Zavian membuka akun tabungan digital-nya dan tersenyum samar:
Rp 14.032.000.
“Lumayan... Dari jualan gelang kulit, gelang magnet, aksesoris basket KW, crypto, dan mulai endorse… Dua bulan lagi bisa 20 juta.”
Ia merebahkan diri sejenak. Pikirannya mengembara ke wajah ibunya.
“Kalau bisa nambah penghasilan 2–3 juta per bulan dari endorse, gue bisa bantu bayar listrik, cicil renovasi atap bocor... dan simpen buat modal ke depannya.”
Suara hujan makin deras. Tapi Zavian tak bergerak. Dia membuka aplikasi crypto wallet, melihat saldo kecil yang pelan-pelan naik.
0.0165 BTC
USDT: 73.8
“Kalau sabar, bisa 1 BTC tahun depan…” bisiknya, setengah mengigau penuh mimpi.
HP-nya tiba-tiba bergetar.
Shanaya:
“Kenzo, makasih banget buat gelang adik aku. Dia suka banget, sampe tidur pun dipake hahaha.”
“BTW, kamu terima pesanan tas kulit juga gak? Temenku mau, katanya cowok ganteng kayak kamu pasti punya barang bagus.”
Zavian tertawa kecil.
“Dasar cewek-cewek sekolah ini…”
Tapi jauh di dalam pikirannya, dia tak sedang mencari cinta.
Dia mencari jalan.
Jalan yang bukan ditentukan oleh orang lain…
Tapi jalannya sendiri.
Dan malam itu, di tengah hujan dan suara lonceng masjid kampung yang menggema, Zavian kembali menatap grafik crypto-nya. Tangannya dingin, matanya lelah, tapi hatinya menyala.
“Gue akan bebas. Dengan cara gue sendiri.”
Matahari yang Tak Mereka Lihat
Pagi itu, matahari bersinar cerah, tapi langit Jakarta tetap menyimpan debu dan kesibukan yang tak pernah tidur. Di dalam rumah mungil di sudut gang sempit Jakarta Timur, Zavian sudah duduk di meja belajarnya. HP-nya tergeletak di samping laptop, dengan notifikasi yang terus berdenting sejak subuh.
Ia menyender sambil membuka aplikasi e-mail dan Instagram, matanya menari membaca pesan demi pesan.
@NoBrainerSocks:
“Bro Zavian, kita suka banget gaya kamu yang rebel tapi elegan. Mau collab buat konten TikTok + IG Reels? Kita kirim 10 pasang kaos kaki dan honor Rp3 juta. Deal?”
@MoodyVibes.id:
“Halo Kenzo, kami dari brand streetwear baru. Mau ajak kamu photoshoot outdoor weekend ini. Bisa ajak temen cewek juga. Komisi per video bisa sampai Rp5 juta.”
“Hahaha, makin aneh aja,” gumam Zavian sambil nyengir.
Tapi dia tak menolak.
Hari itu juga, Zavian mengatur jadwal photoshoot dan menerima tiga kerja sama baru. Dia hanya memilih yang menurutnya cocok dengan citranya: sederhana tapi penuh daya magnet.
Malamnya, Zavian duduk di atap rumah, HP-nya menyala terang. Video collab-nya bersama Giselle Azzahra—seorang YouTuber cantik dengan 400 ribu subscriber—sudah naik.
Dalam video itu, mereka bermain basket bareng, lalu duduk di warung kopi kecil sambil membahas “cara cari cuan buat anak SMA”. Candaan mereka natural, dan chemistry-nya bikin netizen baper.
Komentar netizen pun meledak:
“Fix aku tim #KenZelle”
“Gila cowok beginian ada di dunia nyata?”
“Zavian humble banget sih, fix bukan cowok biasa!!”
Dalam waktu tiga jam, videonya ditonton 120 ribu kali. Follower IG Zavian naik 40 ribu dalam semalam.
Zavian menarik napas panjang, menatap langit yang kelabu.
“Mereka cuma lihat video 5 menit, tapi gak lihat 5 tahun perjuangan gue…” bisiknya.
Lalu ia membuka e-wallet-nya.
Saldo: Rp 21.405.000
Crypto Wallet:
BTC: 0.0189
USDT: 92.4
ETH: 0.41
“Dikit lagi bisa bantu Ibu bayar kuliah semester pertama gue full…”
Tiba-tiba HP-nya bergetar.
Jihan (Ibu):
“Zav… Jangan tidur di atap terus ya, anginnya dingin. Hati-hati masuk angin…”
Zavian tersenyum.
Dunia boleh keras.
Orang-orang boleh tak percaya.
Tapi selama ibunya masih ada, dan langit masih terbuka luas… dia akan terus melangkah.
“Gue belum jadi apa-apa, tapi gue bukan siapa-siapa juga. Gue… calon orang.”
Ia menatap bintang samar yang hampir tenggelam oleh polusi.
Matahari belum kelihatan bagi semua orang, tapi Zavian tahu: dia sudah mulai bersinar.
Bab 3 – DI BALIK LANGIT JAKARTA
Percikan Api yang Pertama
“Anak IPS itu cuma modal gaya, nilai pas-pasan, kelakuan kayak preman…”
Suara itu datang dari depan kelas XII IPA 1. Zavian berhenti sejenak di lorong, mendengar. Suara itu familiar. Daniel. Ketua OSIS. Kelas IPA.
Anak guru. Sering jadi bintang saat upacara.
Zavian hanya menoleh, matanya datar.
Di sebelahnya, Miko—teman sekelas yang bertubuh kecil dan suka nge-rant soal konspirasi dunia—langsung merespons dengan bisikan, “Jangan dengerin. Dia iri karena IG lo tembus 2,5 juta followers. Gue liat tadi lo endorse jam tangan?”
Zavian tersenyum tipis. “Tiga brand hari ini. Lumayan buat nambahin tabungan. Udah 26 juta sekarang.”
“Gila… dari modal HP bekas lo itu?”
“Dan otak, bro. Jangan lupakan itu,” balas Zavian, menepuk pundak Miko.
Mereka melanjutkan jalan ke kelas. Tapi langkah Zavian terhenti begitu melihat Rafi—teman sekelas mereka—ditarik kasar oleh dua murid kelas sebelah. Salah satunya memegang kerah seragam Rafi, satunya lagi menyembunyikan sesuatu di balik tasnya.
“Mana, Fi? Lo nyebarin akun fake-nya pacar gue, ya?”
Rafi gelagapan. “Bukan gue, sumpah. Gue aja baru tau kemarin—”
Bugh.
Satu pukulan mendarat di perut Rafi.
Tanpa pikir panjang, Zavian melangkah cepat, menarik bahu si penyerang, dan…
“Cukup.”
Anak itu mendorong balik, “Sok jadi pahlawan, Kenzo?”
Zavian tak bicara. Tatapannya dingin. Tenang. Tapi bahunya menegang. Tangannya sudah siap jika harus bergerak.
“Udah. Gua gak mau lo mukulin temen gua,” katanya pelan.
“Lo siapa, ha? Punya follower banyak, terus boleh ikut campur?”
Murid-murid mulai berkumpul. Beberapa merekam dengan HP. Satpam sekolah terlihat mulai berjalan cepat ke arah mereka.
Zavian hanya menatap lurus.
“Gue bukan siapa-siapa. Tapi kalo lo pukul orang yang gak bisa lawan lo, gue harus jadi ‘siapa-siapanya.’”
Sepuluh menit kemudian, Zavian duduk di ruang BK. Di seberangnya, Wakil Kepala Sekolah, Pak Doni, berkacamata tebal dan bermuka datar, duduk sambil memijat pelipisnya.
“Kenapa kamu selalu cari perkara, Zavian?”
“Saya cuma bantu teman saya, Pak. Dia dipukulin…”
“Kamu bisa lapor guru.”
“Dan sempatnya kapan, Pak? Dia udah dipukul duluan.”
Pak Doni mendengus. “Kamu memang populer, punya banyak follower. Tapi ingat, ini sekolah. Bukan panggung selebgram. Kamu saya skors dua hari. Dan kamu akan hapus semua konten endorse yang menampilkan lingkungan sekolah. Paham?”
Zavian menggertakkan rahang. Tapi ia menahan diri. “Saya paham, Pak.”
Di parkiran belakang sekolah, Rafi menyusul sambil menunduk. “Zav… Makasih, bro. Serius. Gua gak nyangka lo bela gua…”
Zavian hanya nyalain motornya. “Gua gak suka liat orang ditindas. Apalagi temen sendiri.”
Miko datang dengan wajah cerah. “Lo tau gak? Video lo tadi udah naik di TikTok. Caption-nya: Kenzo lawan ketidakadilan. Live dari Dwipantara. Lo viral lagi.”
Zavian hanya mengangkat alis. Di balik helmnya, dia tersenyum kecil.
Pasar Gelap di Balik Gang
Malam itu hujan baru saja berhenti. Jakarta Selatan masih basah dan berbau aspal. Zavian memarkir motornya di sebuah gang sempit tak jauh dari Pasar Minggu. Helm dilepas, ransel diselempang, hoodie ditarik menutup sebagian wajahnya.
Dari luar, gang itu biasa saja. Tapi bagi sebagian orang, ini pintu menuju lorong bisnis bawah tanah: aksesoris kulit, gelang handmade, jam tangan tiruan grade tinggi, hingga cologne-cologne branded oplosan.
“Lo datang juga, bro Kenzo,” sapa seseorang dari balik tenda abu-abu di ujung gang. Namanya Reno, 23 tahun, mantan anak SMK yang jago bikin gelang kulit asli. Tangannya kasar tapi presisi.
Zavian menjabat tangannya. “Pesanan dari Shanaya udah jadi, Ren?”
Reno mengangguk, membuka kotak kecil. Sebuah gelang kulit hitam gelap dengan inisial ukiran huruf “R” di sisi dalam.
“Limited. Kulit asli. Jahitan tangan gua sendiri.”
Zavian mengangguk puas. “Berapa gua transfer?”
“Lu mah udah kayak keluarga, cukup seratus lima puluh ribu. Tapi…”
“Tapi?”
“Lu bantu promosi lapak kita di IG lo. Cukup foto lo pegang gelang ini, tag kita. Gua jamin orderan masuk lagi, buat lo juga.”
Zavian tersenyum tipis. “Deal. Malah gua udah rencanain collab ini dari minggu lalu.”
Di rumah malam itu, Zavian duduk di depan laptop tuanya. Lampu meja temaram. Di layar, akun Instagram @kenzovian_official miliknya baru saja mengunggah reel baru: tangan menggenggam gelang kulit hitam, dengan latar musik lo-fi dan caption:
"Support local hustle. Handmade, real leather. Cinta produk anak gang."
Tag: @renoleatherid
#KenzoSupport #GelangGangster #StreetElegance
Beberapa detik kemudian, like mulai berdatangan. Komentar masuk deras. Beberapa akun verified ikut repost.
Zavian memutar kursinya, lalu membuka folder bernama “Crypto & Income”. Spreadsheet terbuka. Tabungan terakhir: Rp 26.750.000. Hari itu saja, dia sudah mendapat Rp 850.000 dari endorsement, dan estimasi 2 juta lagi dari kontrak IG reels bulan ini.
Lalu dia membuka tab lain: akun butik ibunya.
@JihanAluna_Crafts
IG followers: 3.100.
Zavian mendesah. Lalu mulai membuka Canva, menyusun layout iklan baru.
“Kalau buat diri sendiri bisa dapet 2 juta followers, masa bantuin butik Mama gak bisa 10 ribu?”
Besok harinya, di sekolah, Miko menyusul Zavian di kantin.
“Zav, bro, video lo udah tembus 1 juta view. Si Reno itu sampe mention lo di story tujuh kali. Gila, lo bikin pasar aksesoris underground jadi tren.”
Zavian hanya meneguk es teh. “Gue cuma bantu yang bantu gue duluan, Mik.”
“Lo Robin Hood zaman now.”
“Robin Hood gak punya rekening BCA.”
Malam itu, Jihan memanggil Zavian ke ruang makan.
“Zavian… Mama liat kamu upload butik Mama di story kamu, ya?”
Zavian mengangguk. “Iya. Kan Mama mau bantu naikin omset.”
Jihan duduk perlahan. Ada nada khawatir. “Tapi… Mama juga liat kamu sering pulang malam. Bisnis kamu makin serius, ya?”
“Lumayan, Ma.”
“Maaf, ya, bukan maksud Mama ngatur… Tapi kamu itu kelas 3, sebentar lagi ujian kelulusan. Jangan sampai nilai kamu turun…”
Zavian menatap ibunya. Lama.
“Ma, tabungan Zavian sekarang udah dua puluh enam juta. Semua bersih, semua halal. Zavian juga bantu promosi butik Mama, bantu nyari pemasok murah dari kenalan Zavian.”
Jihan terdiam. “Tapi Mama takut kamu masuk ke dunia yang salah…”
Zavian bangkit dari duduknya. Mencium tangan ibunya.
“Tenang, Ma. Zavian cuma jalanin yang orang lain anggap gak mungkin. Tapi Mama tetap nomor satu.”
Pertarungan di Bawah Lampu Stadion
Lapangan basket SMA Dwipantara malam itu ramai. Lampu sorot menerangi langit Jakarta yang kelabu. Suara peluit dan riuh penonton menggema. Turnamen antar sekolah zona Jakarta Selatan sedang berlangsung.
Zavian berdiri di pinggir lapangan, mengenakan jersey hitam bertuliskan “Dwipantara 07”. Keringat sudah mulai membasahi pelipisnya, meski pertandingan baru pemanasan. Di kursi penonton, terdengar suara cewek-cewek:
“Itu Kenzo asli, kan?”
“Sumpah dia ganteng banget aslinya. Jauh dari vibe ‘anak gelap’ kayak yang orang bilang.”
“Dia kayak... anime karakter, tapi versi real life!”
Dari sisi lapangan, Coach Rudi, pelatih basket Dwipantara, berteriak.
“Zavian! Lu jadi guard utama. Mereka main fast-break, jaga ketat! Inget, fokus!”
Zavian mengangguk. “Tenang, Coach. Gue bukan cuma jualan aksesoris.”
Bola dilempar ke udara.
Zavian menang tip-off, langsung mengoper ke Dito. Mereka bermain cepat. Pertahanan lawan tampak panik karena kecepatan dan visi Zavian yang tak terduga. Passing-nya presisi, dribble-nya lincah. Dalam sepuluh menit, Zavian sudah mencetak 11 poin dan 3 assist.
“Anjir, itu cowok lari kayak bayangan…” salah satu pemain lawan bergumam.
Di tribun, sekelompok cewek dari sekolah lain berteriak-teriak.
“ZAVIAN!!! BENERAN KENZO NIH!!!”
“Dia tuh... beda. Punya aura.”
Namun di sisi lain tribun, wajah beberapa cowo dari sekolah lain tampak masam.
“Cih. Sok keren banget dia. Cuma modal followers doang,” ejek salah satu dari mereka, Reyhan, kapten tim basket SMA Tunas Bangsa.
Waktu time-out, Dito menyikut Zavian.
“Bro, lo liat tuh, cewek-cewek pada nyariin lo. Gue sampe disuruh mundur biar bisa ngeliat lo jelas. Gila lo, Kenzo.”
Zavian meneguk air. “Yang penting kita menang dulu. Baru urus yang lain.”
“Masalahnya lo udah menang di dua hal: skor... dan hati cewek-cewek.”
Zavian hanya mengangkat alis. “Dan dapet musuh baru.”
Pertandingan berakhir dengan skor Dwipantara 76 – Tunas Bangsa 61.
Zavian mencetak 24 poin, 6 assist, dan 4 steal.
MVP malam itu.
Saat keluar lapangan, beberapa cewek langsung mendekat minta selfie.
“Zavian, boleh foto bareng?”
“Please! Buat IG Story!”
Dia senyum kecil. “Satu-satu ya… tag gue juga.”
Saat itu, Reyhan lewat di belakang dan berdesis.
“Nggak selamanya lo bakal di atas, bro. Liat aja nanti.”
Zavian hanya menatapnya datar, lalu balik ke arah cewek-cewek.
“Kalo foto barengnya udah cukup, gue pamit dulu. Ada orderan yang harus gue packing.”
Malam itu, di kamarnya, Zavian kembali duduk di depan laptop.
Tabungan bertambah: Rp 28.150.000.
Beberapa DM endorsement baru masuk. Salah satunya dari akun @cushioncosmic_id, brand kosmetik lokal yang ingin endorse via reels.
Zavian terkekeh. “Dari pasar gelap ke iklan cushion. Dunia ini lucu.”
Di Ujung Jalan yang Tak Tertulis
Suara knalpot meraung keras di jalanan dekat Pasar Kebayoran. Zavian duduk di motor tuanya, helm separuh terbuka. Di depannya, enam motor sport berjejer. Geng motor lokal “Sparks07” menghadangnya malam itu, lampu-lampu neon memantul dari cat bodi yang penuh grafiti jalanan.
Damar, ketua geng dengan tato tengkorak di leher, maju beberapa langkah.
“Denger-denger lo banyak duit sekarang, ya? Nongkrong di sini, tapi ngaku anak rumahan? Jangan kira bisa jalan di daerah kita tanpa bayar ‘pajak’, bro.”
Zavian menatapnya datar.
“Gue gak jualan di wilayah lo. Gue cuma lewat.”
“Lewat bawa uang endorse, lewat bawa orderan aksesoris, ya? Jangan sok polos, Kenzo.”
Zavian mencengkeram stang motornya. “Kalau lo pikir semua anak yang naik motor butut nggak bisa ngelawan, silakan coba dulu.”
Ketegangan merambat di udara. Tapi sebelum ada yang bergerak, suara bentakan dari arah barat memecah situasi.
“UDAH, DAMAR! JANGAN CARI MASALAH DI SINI!”
Sosok besar muncul dari arah gang, Abel, mantan kakak kelas Zavian yang dulu pernah dilindungi Zavian dari bentrokan lain. Ia kini bergabung dalam komunitas underground aksesori motor.
“Zav, jalan. Gue beresin.”
Zavian memberi anggukan kecil dan tancap gas.
Di kamarnya, malam itu…
Zavian menyalakan laptop. Tab “TokekMarket” dan “Binance” terbuka berdampingan. Ia memantau koin kecil yang harganya baru saja naik 12%.
“Lumayan… Beli waktu diskon, jual waktu orang panik.”
HP-nya berbunyi. DM masuk dari akun YouTube @NaraDaily—seorang vlogger SMA dari Bandung yang lagi naik daun.
“Zavian! Let’s collab buat konten jualan kreatif anak sekolah! Bisa promosi bareng produk lokal juga.”
Zavian senyum simpul.
“Yuk. Kita main ke Jakarta. Gue ada space buat syuting, kita bisa masukin promo butik nyokap gue juga.”
Malam itu juga, konten mereka tayang di IG dan YouTube. Views melesat. Followers Zavian naik jadi 2.750.000. Satu hari, dua endorsement baru. Dua jam kemudian, saldo rekening naik Rp 2.000.000 dari affiliate crypto tools.
Zavian mencatat pengeluarannya di aplikasi spreadsheet sambil gumam:
“Tabungan: Rp 30.250.000…
Udah cukup buat bayar kuliah sendiri, bahkan modal bisnis baru. Tapi gue belum selesai.”
Pagi harinya di sekolah…
Bu Ratih, guru Sosiologi:
“Baik anak-anak, untuk tugas berikutnya, saya mau kalian buat observasi kecil. Tentang dinamika kelompok sosial di masyarakat.”
Zavian mengacungkan tangan.
“Bu, boleh kalau saya ambil contoh dari komunitas underground yang saya kenal? Fokusnya di interaksi ekonomi informal dan aturan tak tertulis di dalamnya.”
Bu Ratih menatap heran sejenak. Lalu mengangguk pelan.
“Itu... menarik. Silakan, Zavian. Tapi saya harap datanya bisa kamu susun rapi.”
Dito yang duduk di sampingnya nyengir.
“Bro, lo serius banget. Ini tugas atau skripsi?”
Zavian menyandarkan badan ke kursi.
“Skripsi buat hidup, Dit.”
Cahaya yang Tak Mereka Lihat
Malam mulai turun di Jakarta Selatan. Langit kelabu, dan suara adzan menggema dari kejauhan. Di dalam rumah sederhana mereka, Jihan Purnamasari tengah menata stok baru untuk butik daringnya. Di seberangnya, Zavian duduk di kursi kayu, memandangi layar HP yang terus dipenuhi notifikasi endorse dan DM dari brand lokal.
“Zavian,” panggil Jihan pelan.
“Kamu belum jawab tawaran Mama. Ayo bantu Mama kelola butik ini lebih serius. Banyak banget pesanan dari luar kota. Kita bisa buka toko fisik kalau kamu bantu cari pemasok dan ngurus promosi.”
Zavian mendesah, memijit pelipis.
“Ma… tabungan aku udah lebih dari 30 juta. Aku masih bisa bantu promosiin butik Mama lewat IG, bahkan collab sama Youtuber Bandung minggu depan. Tapi kalau disuruh berhenti dari yang aku jalanin sekarang… itu artinya ninggalin sesuatu yang udah aku bangun pelan-pelan dari nol.”
Jihan terdiam. Ia menatap anaknya yang kini sudah remaja akhir, dengan wajah yang makin mirip... Laurent Mahardika, ayah Zavian.
“Kamu tau, Mama cuma takut kamu terlalu dalam. Dunia bawah Jakarta itu keras, Vi. Temen Mama dulu pernah—”
“Aku bukan Ayah, Ma.”
Jawaban Zavian terdengar tajam, namun matanya menunduk.
“Aku gak ninggalin orang. Aku gak pernah bikin Mama nunggu penjelasan bertahun-tahun.”
Suasana tiba-tiba berubah hening.
Flashback: Enam Tahun Lalu
Zavian kecil duduk di tepi jendela, mengenakan kaos olahraga sekolah dasar, dengan tas kecil bergambar dinosaurus. Di luar rumah, koper besar digeret oleh seorang pria jangkung berambut ikal, Laurent Mahardika.
Jihan berdiri mematung di depan pintu, masih mengenakan celemek dapur.
“Ke Jerman, begitu aja?”
“Tanpa pamit sama anakmu? Tanpa penjelasan? Apa aku gak cukup layak buat dijelasin, Laurent?”
Laurent menunduk, menggenggam paspornya erat.
“Aku harus pergi. Ini… bukan soal kalian. Ini soal aku.”
Zavian kecil berlari keluar.
“Ayah! Aku udah bisa tanding basket minggu depan! Liat aku lempar bola, Yah!”
Tapi sang ayah hanya menatap sesaat. Lalu menaiki taksi tanpa sepatah kata. Pintu tertutup. Mobil itu menjauh. Dan sejak hari itu... suara Laurent Mahardika hilang dari hidup mereka.
Kembali ke masa kini.
Jihan menatap Zavian, yang kini memandangi pantulan dirinya sendiri di layar HP.
“Ma… aku gak bisa janji buat hidup aman.”
“Tapi aku janji, aku gak akan pernah ninggalin Mama tanpa pamit. Tanpa alasan. Gak akan pernah lari.”
Jihan mengusap rambut anaknya yang kini lebih tinggi darinya.
“Kalau begitu, bantu Mama satu hal… Temui Bu Retno dari komunitas supplier kain di Cipulir. Biar butik kita punya stok baru. Anggap aja… kerja sama bisnis.”
Zavian tersenyum tipis.
“Oke. Tapi aku bawa motor sendiri ya. Sekalian mampir ke toko langganan aku cari bahan buat pesanan cowok Korea yang mau gelang kulit tiga layer.”
Malam itu, sebelum tidur, Zavian membuka catatan di HP-nya.
Saldo: Rp 34.750.000
Job pending: 3 endorse, 2 collab YouTube, 1 pesanan khusus gelang edisi “Stardust”.
Ia mengetik sebuah pesan yang tak jadi dikirim:
“Kalau suatu hari kamu baca ini, Ayah… aku gak marah. Aku cuma pengen ngerti. Tapi kalau gak bisa ngerti, setidaknya izinkan aku jadi lelaki yang gak akan pernah lari kayak kamu.”
BAB 4: DUNIA YANG TIDAK IA PILIH
Sabotase
Hari itu, langit Jakarta tampak cerah. Tapi suasana hati Zavian berkabut.
Pagi baru saja dimulai ketika ia tiba di sekolah, memarkir motornya di spot biasa dekat lapangan basket. Tas selempang khasnya masih menggantung di bahu, dengan gelang-gelang kulit yang mulai jadi tren berkat story IG-nya yang viral minggu lalu bareng Youtuber Ayla Nayla.
Begitu memasuki kelas, Aldric—teman satu geng sekaligus "admin" tidak resmi dari bisnis aksesoris mereka—berlari mendekatinya dengan wajah panik.
“Vi! Tokped kamu down. Review-nya di-bomb negatif semua. Banyak orderan dibatalin. Shopee juga di-report akun fake!”
Zavian langsung membuka HP-nya. Puluhan notifikasi bertubi-tubi.
[Pesanan Dibatalkan]
[Akun Dilaporkan: Dugaan Produk Ilegal/KW]
[Bintang 1: Produk jelek, beda sama gambar!]
Darahnya mendidih. Dia tahu barang-barangnya orisinil buatan tangan, bukan KW seperti yang dituduhkan. Bahkan beberapa gelang spesial punya sertifikat bahan asli kulit Sapi Garut.
“Ini pasti kerjaan si cowok-cowok toxic dari event basket minggu lalu,” geram Zavian, menahan emosi.
“Gara-gara followers IG gue naik, banyak yang sirik. Apalagi pas gue collab sama Alyana waktu itu.”
Aldric mengangguk, sambil menunjukkan DM anonim yang menyebut akun Zavian “jualan ilegal, fake product, gak pantas jadi influencer”.
“Terlalu banyak spotlight, Zav. Dunia bawah juga gak suka kalau kita terlalu kinclong…”
Zavian mendengus. Tapi ia tidak panik. Ia membuka Story IG dan bicara langsung ke kamera.
“Oke guys, ada yang coba hancurin bisnis gue. Tapi kita gak turun cuma gara-gara drama receh. Kita naik bukan karena instan, tapi karena niat. Yang beli tau kualitas, yang sirik cuma bisa nonton.”
Like masuk ribuan. DM penuh dukungan. Beberapa brand yang pernah kerja sama bahkan repost story-nya dan menawarkan promo bundling khusus sebagai bentuk solidaritas.
Namun, saat lonceng sekolah berbunyi dan ia berjalan ke ruang kelas, satpam memanggilnya.
“Zavian Kenzo. Ke ruang BK sekarang. Ada panggilan.”
Di ruang BK, sudah ada Bu Lidya, guru BK berhijab yang biasanya terlihat cuek tapi dikenal sangat teliti. Di sebelahnya, Wakil Kepala Sekolah duduk dengan wajah tegas.
“Zavian,” kata Bu Lidya pelan tapi tegas, “Kami menerima laporan bahwa kamu menjalankan bisnis ilegal lewat sekolah. Termasuk dugaan pelanggaran etika promosi dan pelanggaran aturan sekolah tentang kegiatan komersial.”
Zavian menatap mereka. Tenang, tapi dengan rahang mengeras.
“Saya gak pernah jualan di sekolah, Bu. Semua transaksi lewat online. Dan semua produk saya handmade, bisa dicek. Yang saya tahu, saya lagi diincar sama pesaing. Beberapa akun fake nyerang sistem saya.”
Wakil Kepala Sekolah membalas tajam.
“Kami tetap akan memproses pelanggaran ini secara administratif. Dan kalau terbukti, ada kemungkinan kamu diskors. Atau lebih parah…”
Zavian keluar dari ruangan BK dengan kepala dingin, tapi matanya menyiratkan badai yang baru saja dimulai. Di tangannya, HP masih terus berdering. Salah satunya dari brand fashion luar negeri yang tetap ingin mengirim produk untuk endorse.
Ia buka IG-nya, mengetik caption baru:
“Kalau lo pikir sabotase bisa matiin usaha gue, lo salah. Ini bukan soal cuan, ini soal pride. Gue jatuh, gue bangkit. Gak pake drama, langsung kerja.”
Nyaris Dikeluarkan
Hari itu, seluruh kelas IPS 3 sedang menjalani ujian akhir semester. Tapi Zavian Kenzo tidak sepenuhnya bisa fokus.
Sorot mata beberapa siswa IPA yang duduk tak jauh dari kelasnya terasa menusuk. Bisik-bisik terdengar sejak pagi. Beberapa akun gosip sekolah bahkan mulai menyebarkan narasi bahwa bisnis Zavian jual produk KW dan “cuma pansos dari IG cewek-cewek cantik.”
Saat istirahat siang, di kantin lantai dua, suasana yang semula ramai mendadak menegang. Zavian duduk bersama Aldric dan Rinjani, baru saja membuka bekal saat tiga cowok dari kelas IPA 1 datang menghampiri.
Salah satunya, cowok bertubuh besar bernama Arvino, menyeringai sambil melipat tangan.
“Influencer KW makan nasi goreng juga rupanya, Kirain makanan endorse-an terus.”
Zavian tetap tenang. Ia sudah terlalu sering berurusan dengan sindiran.
Tapi yang membuat darahnya mendidih bukan itu—melainkan ucapan berikutnya dari cowok berjaket varsity abu-abu, Yudha namanya.
“Gak heran sih kalau anak kayak lo cari duit dari medsos. Ibunya kan juga nggak laku jualannya.”
“Bener tuh. Butik setengah mati, anaknya sok sukses.”
Hening. Satu detik. Dua detik.
Aldric sempat menarik lengan Zavian pelan, tapi semuanya terlambat. Tinju Zavian mendarat tepat di rahang Yudha. Kursi berderit, meja tergeser, dan suara gaduh memecah suasana kantin.
Perkelahian meledak.
Aldric dan cowok IPA bertubuh besar ikut bergumul. Rinjani berteriak minta tolong. Satu guru yang sedang jaga di kantin langsung berusaha memisahkan.
“Cukup!! Kalian ke ruang BK sekarang juga!” bentak Pak Roni, guru olahraga.
Zavian tak bicara sepatah kata pun. Napasnya berat, matanya memerah. Tapi bukan karena marah—melainkan luka batin yang selama ini ia tekan.
Ruang BK, 30 Menit Kemudian
Suasana tegang. Wakil kepala sekolah, Pak Doni, guru wali kelas, dan tiga orang tua siswa IPA sudah duduk. Sementara Jihan Purnamasari—ibunya Zavian—baru saja datang tergesa dengan wajah khawatir.
“Kenapa lagi, Zavian? Kamu bikin apa?” tanya Jihan dengan suara nyaris gemetar.
Zavian menunduk. Tapi bukan karena menyesal. Hatinya penuh bara.
“Aku dihina, Bu. Mereka hina Mama. Aku diam sejak kemarin. Tapi ini... mereka udah kelewatan.”
Wakil kepala sekolah menimpali dengan tegas.
“Apa pun alasannya, tindakan kekerasan fisik tidak bisa dibenarkan. Kami sedang pertimbangkan skorsing, dan jika perlu, pemanggilan komite disiplin.”
Jihan berdiri, menatap mereka semua. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam.
“Kalau sekolah ini tidak bisa melindungi muridnya dari bullying dan fitnah, lalu apa fungsi pendidikannya?”
Ruangan hening.
Bu Lidya menatap Zavian, lalu menatap berkasnya. Ia akhirnya bicara pelan.
“Saya tahu Zavian anak yang pintar. Nilainya stabil. Banyak siswa terbantu bisnisnya. Tapi ia butuh bimbingan... bukan paksaan.”
Setelah rapat internal, keputusan diambil: Zavian tidak dikeluarkan. Tapi diskors tiga hari dari kegiatan sekolah. Ia juga diminta menuliskan surat refleksi dan melakukan konseling rutin.
Di parkiran sekolah, saat semua orang sudah pergi, Jihan menatap anaknya.
“Kenapa kamu selalu merasa harus jadi pahlawan, Nak?”
Zavian menoleh. Senyumnya tipis, tapi getir.
“Karena nggak ada yang pernah jadi pahlawan buat kita, Ma.”
Bimbingan Sang Guru BK
Hari pertama skorsing. Zavian tidak duduk termenung di rumah. Ia datang ke sekolah, bukan untuk belajar, tapi memenuhi panggilan konseling dari Bu Lidya—guru BK sekaligus sosok yang diam-diam memantau perkembangan dirinya sejak kelas 10.
Ruangan BK tidak terlalu besar. Hanya ada sofa panjang, satu rak buku tipis, dan lukisan bunga teratai yang sedikit retak di pojok kiri atas. Zavian masuk tanpa ekspresi. Tapi begitu duduk, Bu Lidya langsung bicara:
“Kamu tahu kenapa saya minta kamu tetap datang?”
“Karena saya bikin rusuh?”
“Karena saya ingin tahu: kenapa kamu tumbuh seperti ini, Zavian Kenzo.”
Zavian mengangkat alis. Tatapannya waspada. Tapi Bu Lidya tak gentar. Matanya tajam, tenang, seperti samudra yang diam tapi bisa menenggelamkan.
“Anak-anak seperti Yudha dan Arvino... saya sudah hafal polanya. Sok berkuasa karena orang tuanya kaya. Tapi kamu... kamu beda. Kamu lapar. Bukan cuma lapar uang. Tapi lapar keadilan.”
Zavian menunduk pelan. Diam. Lalu mengangkat pandangannya, kini mata mereka bertemu.
“Saya cuma pengen hidup, Bu. Bantu Mama. Biar kami nggak diremehkan.”
Bu Lidya mengangguk.
“Saya bisa bantu kamu, tapi kamu harus kasih saya akses. Kamu anak yang cerdas, Zavian. Tapi kamu juga menyimpan amarah terlalu dalam.”
Zavian hanya mengangguk kecil.
Sore Hari, Setelah Konseling
Saat keluar dari ruang BK, koridor sekolah terasa berbeda. Tatapan mata mengikuti langkahnya. Tatapan dari siswa-siswi lain—kagum, penasaran, takut.
Anak-anak IPA yang biasanya arogan langsung menunduk begitu Zavian lewat. Yudha bahkan memutar arah begitu bertemu pandang. Arvino hanya diam, berdiri kaku seolah sedang dihukum.
Sementara itu, dari sisi tangga menuju ruang seni, sekelompok siswi dari kelas XI dan XII berbisik-bisik pelan.
“Itu Zavian, kan?”
“Iya, yang viral abis karena mukulin cowok IPA demi bela ibunya.”
“Sumpah keren banget... udah atletis, kaya, setia sama ibu.”
“IG-nya nambah 100 ribu followers cuma dalam seminggu. Gila.”
Zavian pura-pura tak dengar. Tapi senyumnya sedikit terangkat di ujung bibir. Ia tahu, walaupun reputasi “nakal” melekat padanya sekarang, tapi ada hal yang lebih kuat dari itu: karisma yang lahir dari keberanian dan konsistensi.
Keesokan Harinya – DMs & Endorsmen
Di rumah, sambil membuka laptop dan HP, notifikasi datang tanpa henti:
DM dari beberapa brand lokal: sepatu, jam tangan kulit, dan produk fashion remaja.
Ajakan collab dari youtuber cewek bernama Nasha Kireina—seorang content creator lifestyle asal Bandung yang punya 300k subscriber.
Permintaan wawancara dari podcast remaja Jakarta.
Zavian menyipitkan mata, menandai satu per satu.
“Oke... kalau dunia udah mulai memperhitungkan gue, waktunya gue naikin permainan.”
Ia menulis jadwal. Mulai dari produksi konten endorsmen, collab YouTube, sampai revisi desain gelang kulit premium untuk pasar gelap—semua diatur rapi di notes-nya.
Sorotan Baru: Nasha, Podcast, dan Dunia Endorsmen.
Hari Sabtu, jam 10 pagi — Studio Podcast "Youth Talk ID", Kemang, Jakarta Selatan.
Zavian datang mengenakan jaket denim abu gelap, t-shirt putih polos, dan sneakers lokal brand yang baru saja mengirimkannya sepasang sepatu untuk di-review. Jam tangannya mencolok—hitam matte dengan detail kulit asli dari sebuah brand lokal asal Bandung, salah satu endorsmen terbaru.
Begitu masuk ke dalam studio, ruangan itu penuh dengan lampu softbox, mic condenser, dan aroma kopi fresh brew.
Seseorang menyambutnya dengan senyum cerah.
“Hai! Zavian, kan? Aku Nasha, yang bakal host podcast ini.”
Zavian menatapnya sekilas—Nasha Kireina. Cantik, enerjik, pembawaannya tenang tapi penuh ide. Rambut panjangnya diikat santai, gaya casual dengan blouse putih dan celana high-waist hitam. Ia adalah content creator yang sudah ia kenal sejak lama lewat YouTube—dan hari ini, mereka collab langsung.
"Halo. Nggak nyangka akhirnya kita collab juga."
“Iya, followers kamu pada spam komen terus, suruh aku undang kamu. Padahal aku pikir kamu bakal susah diajak ngomong.”
Zavian nyengir, duduk di sofa podcast.
“Gue kelihatannya aja dingin, tapi selama bukan anak IPA songong, gue bisa ngobrol sama siapa aja.”
Nasha tertawa, dan wawancara pun dimulai.
Podcast berjalan 35 menit.
Topik: “Bisnis, Basket, dan Brutalnya Dunia Sekolah Jakarta”
Zavian bercerita soal awalnya jualan gelang kulit, promosi akun IG mamanya, sampai akhirnya masuk ke komunitas aksesoris pasar gelap dan merambah ke crypto. Ia tidak membesar-besarkan apapun, tapi gaya bicaranya tenang, jujur, dan straight to the point. Justru itu yang membuat audiens di studio kagum.
“Gue belajar dari dua hal: nahan malu, sama nahan marah. Dua-duanya butuh mental kuat. Dan sekarang, gue belajar nahan ego juga. Karena makin naik, makin banyak yang pengen jatuhin.”
Saat podcast tayang malamnya, penonton langsung meledak. Komentar penuh pujian:
“Zavian vibes-nya kayak tokoh utama film.”
“Dari pasar gelap ke panggung podcast, gokil banget.”
“Zavian x Nasha is the duo we didn’t know we needed.”
Sore Hari — Photoshoot & Endorsmen
Setelah podcast, mereka lanjut ke rooftop studio untuk collab konten IG & TikTok. Nasha sudah menyiapkan skrip video singkat: “3 Looks Cowok Simpel Tapi Menawan”.
Zavian mengenakan 3 outfit berbeda:
Casual sporty: hoodie abu dan sneakers baru (endorse).
Semi-formal: kemeja putih dengan jam kulit coklat tua (endorse).
Streetwear: jaket varsity hitam, celana hitam ripped, dan slingbag premium lokal.
Nasha merekam semua dengan semangat. Kadang tertawa karena ekspresi Zavian yang terlalu cuek atau spontan.
“Ya ampun, gaya lo kayak model brand internasional. Tapi lo nahan banget ya senyum?”
“Gue bukan nahan, emang nggak ngerti aja gimana caranya sok lucu kayak konten cowok-cowok TikTok.”
“Hahaha! Ya udah, justru itu yang bikin natural.”
Di akhir sesi, mereka duduk di pinggir rooftop. Nasha memandang ke arah langit yang sudah mulai oranye.
“Gue nggak nyangka lo se-kerja keras ini. Banyak anak seumuran lo yang hidup di zona nyaman, Zavian.”
“Zona nyaman tuh racun. Gue udah ngerasain.”
Malam Hari — DM Meledak Lagi
Setelah video mereka tayang di IG dan TikTok, akun Zavian naik 200 ribu followers hanya dalam 2 hari. Banyak brand baru masuk ke DM:
Brand lokal jam tangan: mau collab photoshoot series.
Sepatu sneakers premium lokal: minta review video.
Podcast di Bandung dan Surabaya: undangan jadi bintang tamu.
Fanpage fans dari luar negeri: Brasil, Filipina, India.
Zavian membuka satu per satu. Di akhir, ia menulis di notes:
“Bikin situs pribadi. Buat sistem tracking endorse & komisi.”
“Cari editor video tetap buat collab konten.”
“Bagi hasil untuk Butik Mama.”
Ikatan Akar Rumput
Hari Senin, jam 6.45 pagi — Halaman sekolah.
Zavian duduk di atas motornya, mengunyah roti tawar isi selai coklat. Beberapa anak-anak yang biasa jadi korban geng senior kini justru duduk bersandar di dinding pagar, dekat dengan posisi Zavian.
"Bro, makasih banget yang waktu itu," ucap seorang siswa kelas 10, Raka, sambil mengacungkan jempol.
"Lo ngelawan sendiri, man. Gila lo." tambah Bayu, anak kelas 11 yang dulu sering ditindas karena badannya kecil.
Zavian hanya mengangguk, lalu menjawab singkat.
“Nggak usah dibesar-besarin. Mereka cuma berani kalau rame.”
Anak-anak ini bukan dari kalangan populer. Anak-anak pinggiran. Yang kalau istirahat lebih suka duduk di belakang kantin, bawa bekal dari rumah, dan gak punya uang buat beli sneakers viral.
Tapi sejak kejadian geng IPA songong dihajar, Zavian jadi semacam pelindung informal. Aura “jangan cari masalah” makin kental di wajahnya. Dan mereka semua tahu: Zavian bukan pahlawan. Tapi juga bukan penonton.
Di ruang kelas IPS 3
Guru Ekonomi belum masuk. Ruangan penuh suara. Tapi Zavian duduk di bangkunya, buka laptop bekasnya yang sudah penuh stiker crypto dan grafik trading.
Bayu dan Raka duduk di sebelahnya.
"Zav, itu yang grafik warna ijo-ijo naik itu maksudnya apa sih?"
“Itu candlestick. Kalau ijo, berarti harga naik. Tapi lo harus tahu juga itu naik karena apa. FOMO atau fundamental.”
"Hah? FOMO apaan tuh?"
“Fear of Missing Out. Banyak yang beli cuma karena takut ketinggalan. Padahal sering jebakan.”
Zavian mulai menjelaskan konsep sederhana crypto ke mereka. Ia bahkan nunjukin satu situs exchange dan cara jual-beli kecil-kecilan pakai akun demo.
“Gue gak ngajarin kalian jadi spekulan ya. Tapi ngerti dunia beginian penting. Dunia udah digital, bro. Jangan cuma ngerti skor bola.”
Sore Hari – Belakang Kantin
Zavian dan kelompoknya duduk melingkar. Beberapa bawa laptop murah, ada juga yang sambil coret-coret kertas strategi.
Mereka mulai membangun mini-komunitas bisnis kecil. Zavian membantu satu anak membuat akun reseller untuk produk aksesoris yang bisa dijual online. Ada juga yang diajarin cara desain logo pakai Canva.
“Kalian bukan pengikut gue. Tapi gue pengen kalian bisa mandiri kayak gue dulu waktu nggak punya siapa-siapa.”
Di antara mereka, muncul tokoh baru: Diko. Anak teknik mesin, pendiam, jago coding. Zavian tertarik padanya karena skillnya bisa dipakai bikin sistem tracking pengiriman dan dashboard online.
"Gue bisa bantu buatin sistem inventory basic, sih. Tapi server-nya harus stabil."
“Tenang. Gue urus hosting-nya. Kita bikin beta dulu buat produk gue, nanti baru bantu anak-anak yang lain.”
Malam Hari – Obrolan dengan Jihan
Di rumah, Zavian duduk di ruang makan, membuka tablet sambil mengecek notifikasi endorsmen. Jihan memperhatikannya dari dapur.
“Zavian... kamu kayaknya terlalu sibuk sekarang. Ibu cuma takut kamu kebawa arus orang-orang itu.”
Zavian mengangkat wajahnya, menatap ibunya lembut.
“Ibu... aku mungkin sibuk. Tapi aku juga sadar ke mana kaki ini melangkah. Aku belajar dari masa lalu kita. Dan aku gak akan ninggalin orang yang pernah merasa ditinggal, kayak aku dulu.”
Jihan terdiam. Tatapannya melembut, air matanya hampir jatuh.
“Ayahmu... dulu juga kayak kamu. Punya visi, idealis. Tapi akhirnya dia... ya, kamu tahu sendiri.”
"Aku gak akan jadi dia, Bu. Aku jalanin semua ini supaya kita gak pernah ada di posisi dulu lagi."
Anak-anak pinggiran yang kini punya arah.
Di balik kekacauan, Zavian perlahan membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis: komunitas akar rumput. Remaja biasa, tapi mulai memahami dunia, keadilan, dan harga diri.
BAB 5: API DALAM DARAH
Belajar Membakar Diri Sendiri
Hari Minggu pagi – Sebuah gym kecil di bilangan Tebet
Keringat membasahi kaus hitam Zavian. Nafasnya memburu, tangan terangkat menahan pukulan instruktur Krav Maga yang jauh lebih besar darinya. Tapi dia tidak mundur. Tidak sekarang.
“Ulangi teknik disarm senjata tajamnya! Fokus di kecepatan refleks, Zav!”
“Siap, Coach!”
Gerakannya cepat dan kasar, sesuai gaya khas Krav Maga: bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk bertahan hidup. Untuk melumpuhkan lawan dalam waktu singkat.
Setelah satu jam sesi intens, Zavian langsung ganti matras ke sisi kanan ruangan, melanjutkan latihan Aikido bersama instruktur Jepang paruh baya. Gerakannya lebih halus tapi menuntut kontrol emosi dan arah gerak tubuh.
“Kamu cepat belajar… tapi kau terlalu agresif.”
“Karena hidup saya terlalu banyak serangan, Sensei.”
“Dan kadang yang kamu butuhkan adalah arah, bukan kekuatan.”
Zavian terdiam.
Sore hari — Lapangan basket sekolah
Keringatnya belum kering dari latihan bela diri. Tapi ia tetap hadir untuk sesi latihan ekskul basket. Tak ingin kelihatan lemah di hadapan timnya, ia ikut bertanding dua ronde meski lututnya terasa ngilu.
“Lo gila, Zav. Dari gym langsung ke sini?”
“Gue gak sempat pilih waktu. Dunia gak kasih kita opsi kayak anak-anak sultan itu.”
Malam hari – Balkon kamar Zavian
Zavian duduk bersandar sambil melihat ponsel. Ada notifikasi baru: dua pesanan untuk hoodie buatannya yang baru launching di Instagram, brand kecil bernama “FRAKSI.”
Logo sederhana, warna-warna netral, dan narasi perjuangan anak pinggiran yang dijadikan konsep utama.
Di bawahnya ada notifikasi dari Diko:
Diko: Zav, sistem tracking udah bisa real-time sekarang. Udah connect ke dashboard lo. Bisa lihat grafik penjualan juga.
Zavian: Nice. Tar gue kasih akses ke anak-anak reseller juga.
Dia menatap ke langit malam Jakarta. Penuh cahaya, tapi terasa pengap. Seolah kota ini memaksa semua orang untuk menyalakan apinya sendiri… atau padam.
Besoknya — Sekolah
Sambil duduk di bangkunya, Zavian membuka dashboard laptop. Sudah ada 200 ribu views di TikTok Reels collab-nya dengan Nasha Kireina. Pesanan naik. Brand mulai diperhatikan banyak orang.
“Zav, hoodie lo dipake influencer dari Bekasi tuh. Gila, cuan banget lo.”
“Baru mulai. Belum apa-apa.”
Tapi di balik kalimat itu, matanya terlihat menajam. Semakin banyak tekanan—semakin kuat api dalam dirinya menyala.
FRAKSI: Bukan Sekadar Brand
Hari Selasa sore – Ruang kelas kosong, jam pulang sekolah
Di antara meja-meja kosong dan cahaya senja yang masuk dari jendela, Zavian dan Diko membuka laptop mereka. Layar memperlihatkan dashboard penjualan, grafik order yang menanjak, serta sistem tracking buatan Diko yang kini bisa memantau pengiriman sampai ke detail kurir.
“Lo gila juga sih, Ko. Udah kayak CTO startup.”
“Ya, lo gila juga, bisa bikin orang mau beli baju anak SMA gini. Kita cocok.”
“‘FRAKSI’ ini bukan cuma baju. Ini cerita kita.”
Hari-hari berikutnya – Proses produksi
Zavian bolak-balik ke vendor sablon, quality control desain, sampai photoshoot kecil-kecilan di gang sempit rumah temannya. Tapi hasilnya rapi dan autentik. Tak seperti brand mewah penuh glamor, FRAKSI justru tampil sederhana, berani, dan... jujur.
Setiap paket dikemas manual dengan stiker tangan bertuliskan:
“Untuk lo yang tetap hidup walau diseret dunia.”
— FRAKSI.
Instagram dan Sosial Media
Zavian mulai sering jadi model brand-brand lokal yang tertarik dengan citra "anak pinggiran ambisius" yang melekat padanya. Feed IG-nya penuh dengan foto-foto stylish namun tetap kasual, disisipi caption reflektif dan kritis.
Followers-nya naik ke 6 juta.
Akun Youtube-nya pun bertumbuh: vlog kehidupan sehari-hari, obrolan ringan soal motivasi dan bisnis kecil, hingga video reaction terhadap produk UMKM. Fans-nya menyebutnya “Abang FRAKSI,” dan menyukai sisi autentik serta blak-blakan Zavian.
Di sekolah – suasana jadi berubah
Murid-murid yang dulu menyepelekannya, kini mulai melihat Zavian sebagai figur nyata. Beberapa cowok tetap sinis, tapi mayoritas mulai hormat.
“Gila, si Zavian tuh sekarang jadi icon anak SMA se-Jakarta.”
“Dia bukan cuma selebgram bro, dia jualan, desain, fight... dia hidupin banyak orang juga.”
Di balik layar – Diko tak kalah sibuk
Diko, meskipun jarang tampil, mulai dihormati banyak anak muda sebagai "engineer muda" yang sukses mengotomatisasi dashboard sistem FRAKSI. Beberapa startup kecil bahkan menghubunginya lewat DM, menawarkan kerja sama.
“Kita udah bukan jualan baju, Zav. Kita mulai bangun ekosistem.”
“Dan kita belum nyentuh 10% dari potensi kita.”
Fanbase Zavian
Bermunculan akun fanbase dengan nama:
@zavian.legacy
@fraksi.army
@abangzav.daily
dan bahkan TikTok challenge dengan #FraksiLook
Zavian tetap rendah hati. Tapi ia tahu: ia sedang membentuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Alexandria dan Ujian Hidup Terbesar
Suatu Jumat sore – Perpustakaan sekolah
Zavian sedang menulis sketsa desain baru FRAKSI di buku catatannya. Sunyi. Sampai kemudian muncul suara lembut yang sudah mulai akrab beberapa minggu terakhir.
“Boleh duduk di sini?”
“Terserah kamu, asal jangan ganggu ‘proses kreatif gue’.”
“Santai aja, ‘bang CEO’.”
Itulah Alexandria F. Mahendra. Siswi baru pindahan dari Bandung. Latar belakangnya akademis, anak aktif debat, dan menyukai dunia bisnis juga. Tapi yang membedakan Alexandria adalah ketenangannya. Ia tak terkesima dengan jumlah followers Zavian atau sorotan sosial media.
Interaksi mereka mulai intens
Setiap hari pulang sekolah, Alexandria kadang membantu Zavian mengecek grammar campaign FRAKSI atau diskusi tentang metode promosi lebih cerdas. Di sisi lain, Zavian belajar dari Alexandria bagaimana menyampaikan idealisme lewat narasi.
“Jangan jual baju. Jual cerita. Jual makna.”
“Lo ngomong kayak dosen branding ya.”
“Gue serius. Dan lo tau itu.”
Zavian diam. Alexandria bisa menembus bagian dirinya yang biasanya ia sembunyikan di balik candaan atau ketegasan.
Momen mereka di luar sekolah
Suatu hari, Zavian mengajak Alexandria ke studio produksi kontennya yang sederhana. Alexandria kagum. Belum pernah melihat anak muda yang begitu aktif tanpa dukungan apa pun dari sistem.
“Lo gak takut gagal ya?”
“Takut, tapi gue lebih takut kalau nyokap gue nanti nyesel punya anak yang nyerah.”
“Berarti kita punya alasan yang sama.”
“Bokap lo juga ninggalin lo?”
“Gak ninggalin. Tapi dia terlalu sibuk untuk sadar gue ada.”
Hening sejenak. Ada luka di sana. Yang akhirnya membentuk kedekatan yang pelan-pelan dalam.
Ujian Nasional makin dekat
Di sekolah, tekanan mulai meningkat. Ujian akhir sekolah IPS jadi agenda utama. Zavian yang dulu dikenal santai, kini terlihat fokus—buku catatan penuh coretan soal ekonomi, geografi, hingga sosiologi.
Di kelas:
Guru: “Saya minta kalian semua serius. Termasuk kamu, Zavian.”
Zavian: “Siap, Bu. Kalo nilai gue jelek, nanti gue malu sama followers.”
Seluruh kelas tertawa.
Tapi Alexandria tahu: Zavian sedang mencoba. Dengan serius.
Di balik semua itu: konflik batin
Zavian mulai sering bengong sendiri di malam hari. Ia menatap grafik crypto, angka order FRAKSI, dan video endorsement yang harus segera diposting. Tapi di layar HP-nya, foto ibunya yang sedang tidur di sofa justru lebih sering ditatap lama.
“Gue pengen bahagiain dia, tapi gue juga takut jadi orang yang lupa dari mana dia berasal.”
“Gue pengen punya semuanya, tapi gak pengen kehilangan diri gue sendiri.”
Alexandria tahu: Zavian bukan sekadar remaja ambisius. Ia sedang tumbuh menjadi ‘api’ yang siap meledak—demi orang yang ia cintai, dan demi dirinya sendiri.
Luka Lama dan Mimpi yang Terbakar
Pagi itu sunyi. Hari pengumuman kelulusan.
Zavian datang ke sekolah dengan hoodie hitam polos, wajah datar, dan headset di telinga. Di layar ponsel, Alexandria kirim pesan:
“Apapun hasilnya, kamu udah jauh lebih hebat dari semua angka.”
Zavian balas cepat.
“Makasi. Tapi nilai tetap penting. Gue janji sama nyokap.”
Satu per satu murid dipanggil ke ruang aula. Gegap gempita, banyak yang bersorak. Zavian hanya menunggu di pojok ruangan, mata setengah merem.
Hingga terdengar:
“Zavian Kenzo Mahardika. Kelas XII IPS. Peringkat 3 besar angkatan.”
Seluruh ruangan mendadak sunyi. Murid-murid kaget. Anak yang mereka kira sibuk endorse dan bisnis, ternyata lulus nyaris dengan nilai sempurna.
“Itu bukan nilai beli kan?”
“Enggak lah. Zavian beneran jenius. Dia cuma males ngomong aja.”
Beberapa guru tersenyum bangga. Termasuk Bu Lidya, guru BK yang kini berdiri paling depan memberi ucapan.
“Saya bangga sama kamu. Tapi saya juga takut.”
“Takut kenapa, Bu?”
“Takut kamu terlalu cepat dewasa, dan akhirnya lupa jadi remaja.”
Malamnya di rumah
Jihan, sang ibu, sudah menyiapkan tumpeng kecil dan lilin ulang tahun—meskipun itu bukan hari ulang tahun siapa-siapa.
“Tumpeng untuk anak ibu yang udah nyelesaiin SMA tanpa nyerah.”
Zavian diam. Di meja, ada bingkisan kecil dari ibunya: sebuah jam tangan kayu, simbol dari waktu yang selama ini mereka lewati tanpa banyak keluhan.
“Mama bangga?”
“Bukan cuma bangga. Mama utang hidup ke kamu, Zav.”
“Jangan ngomong gitu… Aku cuma ngelakuin apa yang laki-laki harus lakuin.”
Tapi malam belum usai…
Ketika Zavian membuka folder lamanya di laptop, ia menemukan rekaman suara lama. Suara ayahnya. Laurent Mahardika. Pria yang meninggalkan mereka untuk ke Jerman.
“Zavian, someday you’ll understand why I had to go. Some journeys must be walked alone.”
Zavian terpaku. Suara itu menyakitkan, sekaligus menghidupkan luka lama.
“Ngapain pergi tanpa pamit? Ngapain ninggalin ibu?!”
Ia hampir merusak laptopnya. Tapi Alexandria menelepon tepat waktu.
“Hey… kamu di mana?”
“Di masa lalu. Tapi gak apa-apa. Gue bakal balik lagi.”
Di balik luka itu, ada kobaran tekad.
Mimpi Zavian untuk membuat clothing line-nya mendunia, mengangkat nama ibunya, dan membuktikan bahwa anak tanpa privilege pun bisa berdiri sejajar, kini semakin menyala.
Nilainya memuaskan. Tabungannya menembus seratus juta. Tapi luka itu… tetap membara.
“Gue belum selesai. Gue bahkan belum mulai.
Jakarta Selatan, menjelang senja.
Langit mendung, angin berhembus malas. Di ruang tengah rumah itu, aroma kayu manis dan lavender dari diffuser menyelimuti udara. Tapi suasana tak seramah biasanya.
Jihan Purnamasari, perempuan gigih yang menghidupi butik kecil dari nol, kini terbaring lemas di sofa. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis. Matanya sayu, namun masih mencoba tersenyum saat Zavian pulang membawa sebungkus makan malam.
“Maaf, Zav... Mama ketiduran. Harusnya tadi nyiapin makan buat kamu.”
“Ma, stop. Duduk aja. Nggak usah mikir masak. Ini aku bawa.”
Zavian menurunkan tasnya, mendekat, lalu menyentuh dahi ibunya.
“Panas, Ma. Seharian tadi ngapain lagi? Kok sampe kayak gini?”
“Nggak ngapa-ngapain... cuma nyusun stok barang dan foto katalog, terus sempet ngantar kain ke supplier... abis itu...”
“MA.” Zavian menarik napas tajam. “Aku kan udah bilang, jangan maksain diri.”
Jihan terdiam. Ia tahu Zavian bukan lagi bocah kemarin sore. Tapi masih sulit baginya untuk menerima bahwa anak remajanya kini menjadi tulang punggung yang diam-diam menopang segalanya.
Beberapa hari setelah itu
Hasil check-up menyatakan kelelahan kronis, tekanan darah rendah, dan anemia ringan. Jihan harus istirahat total minimal dua minggu. Dokter menyarankan pemantauan intens.
Malam itu, Zavian berdiri di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Di tangannya, formulir pendaftaran Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi sudah terisi. Ia memilih kampus itu bukan karena passion… tapi karena dekat dari rumah.
“Gue gak akan tinggalin lo, Bu. Gue di sini. Selamanya.”
Pagi-pagi, Zavian mengenakan kaos lusuh dan sandal jepit, lalu keluar ke halaman belakang.
Ia membawa beberapa bibit: mawar putih, melati, bunga lavender, dan dua pot kecil tanaman anggur.
“Ibu selalu pengen taman kecil. Katanya biar bisa minum teh sambil liat bunga kayak di film-film.”
Tangannya mengaduk tanah. Tidak secepat menggambar grafik Bitcoin. Tidak seasik nge-podcast. Tapi entah kenapa, menanam membuat hatinya terasa penuh.
Ia juga menanam semangka. Bukan karena masuk akal. Tapi karena ibunya pernah bercanda:
“Kebayang gak, makan semangka dari kebun sendiri? Mewah banget tuh!”
Kini ia mencoba mewujudkan candaan itu. Biar ibu tahu, bahkan hal remeh pun tak akan ia anggap sepele… jika itu demi melihat senyumnya.
Sore itu, Alexandria datang membawa termos teh madu dan dua kotak kue.
Mereka duduk di tangga depan, memandangi halaman yang mulai ditumbuhi daun muda.
“Gue takut kehilangan dia, Lex.”
“Tapi kamu kuat. Kamu gak akan biarin itu terjadi, kan?”
“Enggak.” Zavian menggenggam cangkir. “Gue udah janji.”
Tatapan Zavian mengeras. Bukan marah, bukan sedih. Tapi seperti bara yang belum padam—dan takkan pernah padam.
Malam harinya, ia menulis satu kalimat di whiteboard kecil di kamarnya:
“If the world breaks me, I will bleed gold.”
Tabungan sudah seratus juta. Akun media sosial makin berkembang. Tapi tak satu pun dari itu membuatnya cukup—selama ibunya belum benar-benar bahagia.
Karena buat Zavian Kenzo Mahardika, hidup bukan soal jadi viral.
Bukan soal kaya.
Tapi soal janji.
Janji seorang anak untuk menjaga satu-satunya orang yang pernah percaya padanya... bahkan saat dunia belum tahu namanya.
BAB 6: JEJAK DALAM API
“Kampus, Kamera, dan Kapitalisme”
3 Februari 2018
Usia Zavian: 18 tahun.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Di tengah padatnya gedung-gedung FISIP UI yang dilingkari pohon-pohon trembesi, suara kamera ponsel tak pernah benar-benar berhenti berbunyi. Di antara mahasiswa baru yang masih canggung, ada satu sosok yang tidak pernah sepi dari perhatian.
Zavian Kenzo Mahardika.
Jaket denim abu-abu dari FRAKSI tersemat dengan sempurna di tubuh atletisnya. Celana chino gelap, sepatu sneakers edisi kolaborasi lokal, dan jam kulit limited edition di tangan kirinya.
Bukan gaya pamer. Tapi gaya yang jujur. Seolah setiap elemen dirinya berkata: “Saya membangun ini dari nol.”
Di depan gedung B1, seorang mahasiswi baru menghampiri dengan malu-malu.
“Kak Zavian... boleh foto? Aku suka banget podcast Kakak tentang ‘Mental Tahan Pukulan’ yang kemarin.”
“Boleh dong. Tapi abis ini kamu harus kasih aku judul podcast kamu sendiri minggu depan. Gantian ya yang nginspirasiin.” Klik. Jepretan kamera jadi bukti bahwa seleb kampus ini tak hanya memesona, tapi juga merakyat.
5 Februari 2018
Jam 09.00 WIB – Kelas Teori Komunikasi
Zavian duduk di baris tengah. Meski followers-nya sudah tembus 10 juta di Instagram, 5 juta subscriber YouTube, dan akunnya tersebar di TikTok, X, Threads, dan Spotify dengan jutaan pengikut, dia tetap menyimak dosen dengan serius.
Tiap poin materi ia tulis rapi, lalu tandai dengan kode warna sesuai tema. Bukan demi IPK semata, tapi karena ia percaya: “Kalau mau pengaruhin banyak orang, lo harus ngerti cara pikir mereka.”
Teman-teman sekelas sering terkejut:
Zavian yang dari luar kelihatan seperti seleb, ternyata lebih serius dari anak kutu buku.
10 Februari 2018
Jam 15.30 – Kantor FRAKSI di bilangan Kemang.
Zavian dan Diko duduk di ruang rapat kecil. Layar di hadapan mereka menampilkan dashboard: penjualan FRAKSI tembus 1.500 pcs bulan ini, reseller bertambah 90 orang, dan konversi dari campaign influencer menunjukkan ROI positif.
“Kita butuh gudang logistik di Depok buat cepetin distribusi Jabodetabek,” ujar Diko sambil menampilkan grafik.
“Dan sistem dropshiping kita butuh audit ulang. Banyak order fiktif yang ngerusak rasio performa di marketplace,” balas Zavian.
“Tapi di sisi lain... artis-artis kaya Raline, Vicky Prasetya, sama Nadira Rachman udah mulai pake FRAKSI.”
“Good. Naikin harga dasar 10%, jaga margin. Tapi buat yang beli via bundling podcast dan
TikTok live kita, kasih promo flash-sale,” sahut Zavian cepat.
Rapat berlanjut ke segmentasi crypto.
Zavian menjelaskan rencana mengembangkan portofolio token BNB, ETH, dan proyek NFT lokal. Ia juga mulai merintis Jastip Premium—jasa titip produk hypebeast dan luxury fashion dari luar negeri untuk kalangan kampus dan netizen kelas menengah ke atas.
14 Februari 2018
Rumah Zavian – Jam 07.00 WIB
Ibunya kini bangun pagi hanya untuk menyiram bunga, memetik daun mint, dan menyapa ayam-ayam kecil di halaman.
“Aku gak ngerti kamu bisa beliin aku dapur semi-outdoor ini, Van.”
“Karena ibu berhak dapet pagi yang indah tiap hari.”
“Kerja kamu apa sih? Kayaknya udah bukan jualan kaos doang.”
“Rahasia. Yang penting ibu tinggal duduk, dan nanti pas malam, kita dinner bareng di gazebo.”
Butik milik sang ibu kini sudah punya 6 karyawan tetap. Ia hanya sesekali diminta menyetujui desain atau memilih kain. Sisanya? Ia tinggal menikmati teh panas sambil baca majalah favoritnya.
Zavian tahu, ini belum akhir. Tapi setiap langkah kecil ini adalah pelurusan luka masa lalu.
15 Februari 2018 – Jam 22.42
Email masuk: From “Unknown_ID”
Subject: Pertemuan Penting
Zavian Kenzo,
Aku teman lama ayahmu dari luar negeri. Ia pernah berpesan padaku, “Jika suatu hari anakku tumbuh menjadi seseorang yang kuat, bantu dia melangkah lebih jauh.”
Kini aku rasa, waktunya tiba.
Kita perlu bicara, secara langsung. Di Jakarta. Minggu depan.
Temui aku di The Orient Hotel, lantai 10.
Jangan bawa siapa-siapa.
—Tuan L.
“Pertemuan dengan Bayangan Masa Lalu”
Lokasi: The Orient Hotel, Jakarta. Jam 19.30 WIB
18 Februari 2018
Langit Jakarta mendung malam itu, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin segera dibuka. Di antara bayangan gedung pencakar langit dan lampu kendaraan yang berseliweran, Zavian berdiri diam di depan lift The Orient Hotel—berjas hitam sederhana, tanpa logo, tanpa merek mencolok.
Jam 19.30 tepat.
Lift terbuka.
Ia melangkah masuk, menuju lantai 10.
Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Selama 18 tahun hidup, tak sekalipun ia mendengar ayahnya disebut oleh seseorang dengan nada hormat. Apalagi kini... datang dari seseorang yang menyebut dirinya “teman lama ayahmu dari luar negeri.”
Lantai 10, Ruang Privat A
Ruangan itu remang. Aromanya elegan—perpaduan antara kayu manis, kopi hitam, dan parfum asing. Di tengah ruangan, seorang pria duduk menghadap jendela besar. Tubuhnya tegap meski sudah setengah baya. Jasnya licin, dasinya berwarna biru tua dengan pin bendera kecil—Swiss.
“Zavian Kenzo Mahardika.”
“Dan Anda?”
“Namaku bukan hal penting. Tapi ayahmu biasa memanggilku ‘Leon’. Aku dan dia dulu... menjalankan banyak hal bersama, dalam diam.”
Zavian tidak menjawab. Matanya tajam, tubuhnya siaga. Satu tangan di bawah meja, satu lagi memegang botol air mineral yang disediakan. Ia bukan remaja biasa—insting bela dirinya sudah terlatih cukup tajam.
Leon tertawa kecil, lalu menggeser sebuah amplop berisi lembar-lembar saham dan kertas perjanjian bisnis ke arahnya.
“Ayahmu dulu punya saham di salah satu perusahaan logistik lintas benua. Saat ia ‘menghilang’, saham itu kami bekukan. Tapi sekarang... karena kamu telah ‘tampil di radar’, aku rasa waktunya dibuka kembali.”
“Saya tidak butuh warisan,” jawab Zavian dingin.
“Ini bukan warisan. Ini... panggilan. Kamu bukan sekadar pebisnis muda yang sedang naik. Kamu dibentuk untuk sesuatu yang lebih dari itu.”
Leon lalu mengeluarkan proposal investasi: sponsorship senilai 500 juta rupiah untuk memperluas jaringan bisnis FRAKSI, menghubungkan ke mitra-mitra di Eropa Timur dan Asia Tengah.
Zavian diam.
Dalam pikirannya, berkecamuk: “Apa benar ini untuk kebaikanku? Atau hanya pintu lain menuju dunia yang pernah menghancurkan hidup ibu?”
“Kalau aku tolak?”
“Aku akan pergi dan tak akan kembali. Tapi kalau kamu terima... kamu harus siap menginjakkan kaki ke dunia yang ayahmu tinggalkan. Dunia yang... tidak mengenal kasihan.”
20.45 WIB – Parkiran Basement
Zavian keluar dengan langkah mantap, amplop tertutup di tangan kirinya. Wajahnya sulit dibaca. Tapi ada satu hal yang jelas: dia tahu, malam ini bukan sekadar tawaran modal.
Ini adalah pintu gerbang masa lalu, dan sekali ia memutuskannya—tidak akan ada jalan mundur.
Ia memandangi langit Jakarta.
Hujan gerimis mulai turun.
“Apa pun jejak ayah, aku takkan ulangi. Tapi kalau ini bisa bantu ibu dan semua yang kupimpin... maka biarlah aku masuk ke apinya, asal aku tahu caranya keluar.”
“Genggaman Emas, Luka yang Tertinggal”
Rumah Zavian – Pagi Hari
21 Februari 2018
Pagi itu Jakarta cerah. Tapi di dalam hati Zavian, mendung belum bubar sejak pertemuannya dengan Leon tiga hari lalu.
Ia berdiri di halaman belakang rumah. Matanya memandangi pohon anggur yang mulai merambat pagar. Di sebelahnya, semangka-semangka kecil yang ia tanam sendiri beberapa bulan lalu tumbuh dengan sabar, diam-diam menumbuhkan buah kecil—seperti simbol keuletan ibunya.
“Zavian… kamu dari tadi bengong.”
Suara ibunya, lembut dan serak, terdengar dari arah teras belakang. Ia sedang menyiram bunga lavender, meskipun tangannya gemetar halus karena tekanan darah rendahnya kambuh lagi semalam.
Zavian tersenyum samar, lalu mengambil alih selang dari tangan ibunya.
“Biar aku aja, Mama istirahat.”
“Udah kayak satpam Bank aja kamu, Zavi. Gaya tegas, tapi mukanya adem.”
Zavian tertawa kecil. Tapi tawanya tak mampu menutupi kegalauan yang mengendap di dadanya. Ia sedang memikirkan tawaran Leon. Proposal itu masih belum ia tandatangani, namun seolah membakar meja kamarnya.
Siang Hari – Kampus UI, Fakultas Ilmu Komunikasi
Zavian baru saja keluar dari kelas Public Relations Strategy. Di tangannya, ada jurnal tebal, di pundaknya selempang FRAKSI edisi kolaborasi dengan brand lokal “Sajak Pagi”.
Di parkiran, Diko sudah menunggunya sambil ngopi di atas motor listriknya.
“Gue udah revisi sistem dashboard FRAKSI, Bro. Sekarang bisa track pengiriman real-time bahkan sampai reseller tier 3. By the way, lo kelihatan beda. Ada apa?”
“Ada tawaran... yang bukan buat gue doang. Tapi bisa buat semua yang lagi kita bangun.”
“Tawaran yang lo gak pengen, tapi lo butuh?”
Zavian mengangguk pelan.
Diko menatapnya dalam-dalam. Ia tahu, sahabatnya bukan tipe yang goyah karena uang. Kalau Zavian kelihatan bimbang, itu berarti sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka rupiah.
“Tapi gini, Zavi. Apapun yang lo pegang sekarang—FRAKSI, kampus, hidup lo, ibu lo... semua itu karena lo lawan sistem. Jangan sampai karena satu pria bermasa lalu, lo jadi berubah jadi apa yang dulu lo benci.”
“Gue cuma takut, Ko… kalau kesempatan ini datang bukan karena gue pantas. Tapi karena bayangan masa lalu.”
Malam Hari – Kamar Zavian
Zavian membuka laptopnya. Proposal Leon masih di sana, terbuka seperti luka. Tapi malam ini ia sudah punya keputusan. Dengan satu tarikan napas, ia membuka email.
Subject: Tentang tawaran Anda
Saya tidak ingin hidup menjadi perpanjangan masa lalu ayah saya. Tapi saya akan terima bantuan ini, sebagai pebisnis. Bukan sebagai warisan. Dan dengan syarat: Anda tidak ikut mencampuri keputusan perusahaan yang saya bangun. FRAKSI adalah tanah saya, bukan museum kenangan.
Regards,
Zavian Kenzo Mahardika
Ia klik SEND.
Layar laptop meredup. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menyala. Ia tidak tahu apakah ini permulaan dari keberuntungan besar, atau justru jalan masuk menuju dunia gelap yang tak bisa ditarik kembali.
Namun satu hal pasti: Zavian telah memilih untuk melangkah.
“Bangkitnya FRAKSI: Dari Reseller Jalanan ke Radar Dunia”
Studio FRAKSI, UI Depok – Sore Hari
25 Februari 2018
Langit sore di Depok mulai berwarna jingga ketika Zavian dan Diko tiba di studio kecil mereka—ruang bekas gudang belakang kampus yang kini disulap jadi markas operasional FRAKSI.
Di dalamnya, dinding sudah penuh coretan whiteboard: grafik penjualan, roadmap ekspansi, hingga wishlist kolaborasi. Di pojok, ada rak kayu penuh sample kaos, hoodie, dan totebag dengan desain orisinal bertema “Street Wisdom”.
“Target 10.000 reseller sampai akhir tahun,” ujar Diko sambil mengetik di laptopnya. “Dan kita sudah tembus 3.412 sejak kemarin.”
“Gokil…” Zavian menarik napas. “Tapi jangan puas dulu. Kita belum nyentuh Kalimantan, Sulawesi, Bali. Apalagi pasar luar negeri.”
Zavian membuka dashboard digital yang Diko bangun. Reseller terbanyak masih dari Jabodetabek dan Bandung. Tapi hari ini ada satu notifikasi berbeda—permintaan distribusi dari Kuala Lumpur, Malaysia.
“Zav,” panggil Diko sambil menunjukkan layar. “Ini... dari pengelola youth festival di KL. Mereka pengen kolaborasi produk eksklusif FRAKSI edisi Malaysia. Dan katanya ada investor yang juga follow IG lo. Pengusaha sneakers muda dari Penang.”
Zavian tersenyum kecil. Followers Instagram-nya yang kini menembus 10 juta bukan sekadar angka. Di balik layar, pengaruhnya mulai mengalir ke arah yang tidak pernah ia sangka.
26 Februari 2018 – Malam Hari, Rumah Zavian
Zavian duduk di ruang kerjanya yang kini sudah jauh lebih rapi. Ia sedang menyusun desain kolaborasi untuk edisi internasional FRAKSI. Konsepnya adalah: "Jiwa Urban, Raga Nusantara"—menggabungkan batik minimalis dengan tipografi Jepang dan street-style Malaysia.
Di sebelahnya, ibunya membaca majalah bisnis sambil menikmati teh chamomile di kursi taman. Suaranya pelan namun menghangatkan:
“Aku baru baca artikel soal kamu di Youth Entrepreneur Monthly. Kamu sekarang udah jadi inspirasi, Nak…”
“Bunda jangan baca yang lebay begitu.”
“Lagian kenapa nggak? Kamu berhasil bangun semuanya dari nol. Bahkan bikin ibu kamu nggak perlu kerja lagi.”
Zavian mendekat. Ia menyentuh tangan ibunya perlahan.
“Tapi aku belum berhenti, Bun. Aku belum mau santai. Aku pengen FRAKSI jadi brand yang bisa bikin anak-anak kecil dari pinggiran ngerasa bangga pakai karya mereka sendiri.”
28 Februari 2018 – UI Creative Expo, Depok
Zavian tampil sebagai pembicara utama. Temanya: “Monetize Passion: Saat Mimpi Bertemu Market”. Ia mengenakan hoodie FRAKSI edisi terbatas, dipadukan dengan sneakers lokal kolaborasi eksklusif.
Saat sesi tanya jawab, salah satu mahasiswa bertanya:
“Mas Zavian, apa motivasi terbesar lo sampai segigih ini?”
Zavian tersenyum, lalu menjawab tenang:
“Gue cuma pengen ibu gue hidup damai. Nggak khawatir soal besok. Dan… gue pengen jadi alasan kenapa anak-anak dari keluarga biasa tetap bisa punya mimpi luar biasa.”
Tepuk tangan menggema. Tak hanya mahasiswa, bahkan beberapa dosen ikut mengangguk kagum. Tapi Zavian tetap tenang. Dalam dirinya, ambisi bukan untuk pujian. Tapi untuk keberlangsungan.
“Mata Uang Kedua: Dropshipping, Jasa Titip, dan Jebakan Pasar Digital”
10 Maret 2018 – Jakarta, Tengah Malam
Zavian Kenzo Mahardika duduk di depan tiga layar monitor. Jari-jarinya mengetik cepat, berpindah antara dashboard FRAKSI, laporan penjualan di Tokopedia dan Shopee, hingga Google Trends untuk riset pasar Asia Tenggara.
“Crypto naik… tapi volatil. E-Commerce stabil, tapi butuh konsistensi,” gumamnya.
Di layar lain, Diko sedang mempresentasikan Business Forecast mereka lewat Google Meet.
“Zav, kalau kita bisa pecah dropship lewat tiga jalur—fashion Korea, aksesoris Jepang, dan alat elektronik Singapura—dalam setahun kita bisa ekspansi ke lima negara.”
Zavian mengangguk pelan. Ide itu tak mustahil. Pasar digital sedang meledak. Di 2018, Instagram baru meluncurkan fitur IG Shopping, e-commerce Asia seperti Lazada dan Shopee tengah berlomba-lomba membakar uang untuk memperluas pengaruh.
Saat dunia ramai bicara tentang startup unicorn dan digitalisasi ekonomi, Zavian memutuskan: FRAKSI harus jadi lebih dari sekadar clothing. FRAKSI harus jadi lifestyle.
April – Juni 2018: Uji Coba Dropshipping
FRAKSI mulai membuka lini dropship aksesori street-style Jepang dan sepatu Korea lewat sistem pre-order berbasis Telegram dan Instagram. Target market-nya adalah Gen Z dan mahasiswa urban di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Mereka juga membuka akun TikTok—masih baru waktu itu, tapi Zavian tahu tren visual akan mendominasi pasar dalam 2 tahun ke depan.
Dengan konten yang edgy dan penuh “kesan rebel tapi cerdas”, FRAKSI mulai masuk ke radar influencers underground. Mulai dari vloggers Filipina, podcaster Bangkok, hingga street model di Seoul—semuanya mulai mengenakan merchandise Zavian.
“Mereka nggak tahu gue bahkan masih tinggal di rumah kecil di Jakarta Timur,” kata Zavian ke Diko suatu malam.
“Justru itu, bro. Mereka follow brand lo, bukan rumah lo.”
Juli – September 2018: Lini Jastip Internasional
Zavian membuka lini baru bernama: “TitipAsik by FRAKSI”
Sistemnya simpel: pelanggan bisa memesan produk-produk dari Supreme, Uniqlo, Apple Store, bahkan limited edition sneakers dari Paris atau New York. Semua dikurasi lewat jaringan mahasiswa Indonesia di luar negeri yang ikut sebagai “personal shopper” freelance.
“TitipAsik bukan cuma jastip. Ini adalah sistem distribusi impian,” kata Zavian saat pitching ke salah satu angel investor dari Thailand lewat Zoom.
“Kami mendekatkan barang impian ke tangan anak muda, tanpa perlu nunggu restock lokal.”
Bisnis ini meledak. Dalam 3 bulan, omzet bulanan mereka menembus Rp 800 juta hanya dari lini jastip.
Oktober 2018 – Februari 2019: FRAKSI ASIA
Puncak pertama FRAKSI terjadi saat Korean Streetwear Summit 2019 mengundang Zavian sebagai perwakilan brand muda Asia Tenggara. Tiket dan akomodasi ditanggung penyelenggara, dengan satu catatan:
FRAKSI harus tampil dalam Fashion Show Digital Street edisi Seoul.
Zavian tampil dengan hoodie batik abstrak, celana tactical cargo, dan sneakers berbahan kulit vegan dari Bandung. Logo FRAKSI terpampang di layar LED besar.
“Siapa yang bikin desain ini?” tanya salah satu desainer Jepang.
“Aku,” jawab Zavian tenang. “Anak Jakarta yang belajar sambil jualan.”
Di akhir presentasi, email dari ZALORA Asia masuk: mereka ingin menjalin kerja sama distribusi FRAKSI secara regional.
Maret 2019 – Kembali ke Jakarta
Setahun setelah perjalanan mereka dimulai, FRAKSI kini punya:
200+ reseller aktif di Asia Tenggara
15.000++ order bulanan
3 warehouse kecil: Jakarta, Surabaya, dan Batam
Omzet total menyentuh angka Rp 10 Miliar
Dan Zavian? Masih kuliah, masih tinggal dengan ibunya, masih menanam semangka di halaman rumah. Tapi kini, setiap malam, ia menatap langit dengan mata berbeda—mata yang paham bahwa “mata uang kedua” bukan sekadar uang, tapi waktu, pengaruh, dan keberanian untuk melawan arus pasar.
BAB 7 – WARISAN YANG TAK TERKIRA
Surat dari Salju Abadi
Timeline: 20 Februari 2020, Jakarta Timur – Pagi Hari
Pagi itu, Jakarta Timur diguyur hujan ringan.
Udara terasa lebih lembap dari biasanya, aroma tanah basah memenuhi taman kecil di halaman rumah keluarga Mahardika—rumah satu lantai yang baru saja direnovasi oleh tangan-tangan penuh cinta.
Zavian Kenzo Mahardika, genap 20 tahun dua minggu lalu, sedang menyiram pohon anggur di sisi kiri halaman. Tanaman itu sudah mulai merambat ke pagar besi. Di balik jendela, ibunya, Jihan Purnamasari, menyiapkan teh melati hangat seperti biasa.
Lalu email itu datang.
Bunyi notifikasi laptop menggelegar pelan dari kamar kerja yang terletak di pojok rumah. Zavian, masih memakai kaos putih dan celana training lusuh, berjalan masuk dan membuka layar.
Subject: CONFIDENTIAL – Legal Transfer, Laurent Mahardika Estate
From: Meier & Schauffler Legal Associates, Zürich
Zavian sempat menahan napas. Nama itu... Laurent Mahardika. Ayahnya.
Ia membuka email dengan hati berdebar. Tulisan resmi dalam bahasa Inggris terstruktur rapi, namun satu bagian seolah menampar dunia yang ia kenal:
“As per the final Will and Testimony of Mr. Laurent Mahardika, we are authorized to transfer the following assets to Mr. Zavian Kenzo Mahardika…”
– 100,000 BTC (Bitcoin), held securely in multi-signature wallet #BM-2XK-445ZX…
– USD 2,000,000 held in Zürcher Kantonalbank Trust Account #79340-EXV…
Zavian terduduk. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Itu bukan angka fiktif. Ia mengecek kurs real-time:
1 BTC = USD 64,000 (Februari 2020)
Total nilai bitcoin: USD 6,400,000,000 = ± Rp 88 Triliun (kurs saat itu)
Tapi karena sebagian besar dari wallet itu dipegang sejak 2011, asumsi nilai realisasinya lebih konservatif:
± Rp 13,11 Triliun + Rp 27,4 Miliar dari rekening tunai.
Semua itu... dari ayah yang meninggalkannya.
Dua Jam Kemudian – Ruang Tengah Rumah
Zavian duduk bersama ibunya. Air mata Jihan jatuh perlahan saat membaca salinan dokumen. Ia memegang foto lama: Laurent muda, tersenyum di pantai Ancol, memeluk Zavian kecil yang baru belajar naik sepeda.
“Kenapa baru sekarang, Ma?” bisik Zavian.
“Karena mungkin... selama ini ia juga menderita.”
“Tapi dia pergi.”
“Dan sekarang, dia kembali. Lewat warisan ini.”
Zavian menatap jendela. Hujan telah reda. Dunia tampak lebih sunyi dari biasanya.
Malam Hari – Flashback 2009, Hamburg – Jerman
Laurent Mahardika duduk di meja makan panjang keluarga Mahardika–Weiss, dikelilingi wajah-wajah aristokrat Jerman yang kaku dan dingin. Seorang pria tua—kakek Laurent—membentak:
“You are not to return to that country, Laurent. That child… is not of our world.”
Laurent menunduk. Di tangannya, sebuah foto Zavian berumur 9 tahun, tersenyum malu-malu di acara pentas seni sekolah dasar.
“He’s my son.”
“He’s a mistake, born out of rebellion. And you, if you don’t obey, will be erased from the family estate.”
Laurent akhirnya tunduk. Ia kembali ke Jerman, dipaksa menikah dengan perempuan aristokrat pewaris industri farmasi. Tapi sejak 2011, ia mulai mengumpulkan dan menyimpan Bitcoin secara diam-diam, menjelma investor underground dengan identitas palsu. Semua demi satu hal: menebus dosa sebagai seorang ayah.
Kembali ke Jakarta, Februari 2020
Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Rumah di Jakarta Timur direnovasi total, tapi tetap mempertahankan ruang-ruang kenangan. Sebuah garasi dibangun di sisi kanan, dan di sanalah Mustang GT hitam baru milik Zavian kini terparkir, berdampingan dengan motor klasik W800 miliknya yang sudah dicat ulang.
“Ini bukan tentang uang, Ma,” ucap Zavian saat mereka menyantap makan malam.
“Aku tahu, Nak. Ini tentang luka yang akhirnya sembuh... setelah ditunggu bertahun-tahun.”
Arsitek Baru – Awal Imperium Bisnis Legal Zavian
Maret 2020, Jakarta – Saat Awal Pandemi COVID-19
Langit Jakarta mendung kelabu. Hari itu, 12 Maret 2020, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan dua kasus pertama COVID-19 di Indonesia beberapa hari sebelumnya. Namun suasana masih penuh ketidakpastian. Masker kain baru mulai terlihat di wajah-wajah orang di halte dan pinggir jalan, tapi banyak yang belum benar-benar mengerti ancaman yang sedang mengendap pelan di udara.
Di sebuah rumah di bilangan Jatiwaringin, Jakarta Timur, Zavian duduk bersama dua orang kepercayaannya: Diko, sahabatnya sejak SMA, dan Alexandria, kekasih sekaligus partner ide bisnis kreatif mereka. Mereka bertiga sudah tak bisa lagi bertemu di kafe seperti biasa. Hari itu, mereka berkumpul di ruang belakang rumah Zavian, yang telah disulap jadi kantor mini.
Meja besar dari kayu jati dipenuhi sticky notes, laptop terbuka, iPad yang menampilkan grafik pasar, dan beberapa botol hand sanitizer ukuran 500ml yang dibeli ibunya sejak seminggu lalu.
Zavian kini lebih dewasa. Ada raut ketenangan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Warisan Laurent bukan sekadar kekayaan; itu kebebasan. Ia tak perlu lagi bertaruh seluruh napas pada satu produk dropshipping yang rawan banned, atau mengejar algoritma TikTok untuk penjualan FRAKSI.
Namun, ia tidak mabuk kuasa.
Setiap pagi, ia tetap menyeduh kopi sendiri. Tetap menyapa tetangga saat mengeluarkan Mustang GT hitamnya dari garasi. Tetap mencium tangan ibunya sebelum pergi bekerja—meskipun “bekerja” kini artinya membangun imperium dari ruang belakang rumah.
Pertemuan Pagi Itu: Menentukan Arah Baru
“Zav,” kata Diko sambil menunjuk grafik dari situs Statista yang memperkirakan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat pandemi.
“Kalau kita nekat buka toko fisik FRAKSI bulan depan, kita mati. PSBB katanya bakal jalan. Gue udah ngomong sama orang logistik, drop-ship juga bakal stuck kalo kiriman internasional ditahan di pelabuhan.”
Zavian menarik napas panjang.
“Kita pivot. Kita bukan lagi pemain mikro. Mulai sekarang kita bangun FRAKSI Incorporated. Legal, berbadan hukum. Kita daftarin PT. Bikin tiga divisi: streetwear, digital kreatif, dan agency.”
“Agency?” tanya Alexandria.
“Iya. Banyak brand bingung masuk digital sekarang. Kita yang bantu mereka. Bukan cuma jual baju, kita jual cara jualan.”
Diko mengangguk. Alexandria tersenyum. Ia lalu membuka laptopnya dan menampilkan draft awal logo baru:
FRAKSI INC. — dengan tagline kecil di bawahnya: Your Chaos, Our Order.
Situasi Dunia: COVID-19 Mengubah Segalanya
Pada Maret 2020, WHO resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Indonesia, yang awalnya menganggap enteng, kini kelabakan. Masker mulai langka. Harga hand sanitizer melonjak. Sekolah diliburkan. Kantor mulai WFH. Bahkan Gojek dan Grab membatasi layanan penumpang.
Zavian, yang terbiasa dengan hustle kehidupan fisik—event, bazar, campaign offline—dipaksa masuk ke dunia full digital lebih cepat dari rencananya. Ia memutuskan menyewa dua developer UI/UX freelance dari Ukraina dan India lewat Upwork, membayar mereka langsung lewat USDT. Ia membangun sistem backend untuk e-commerce FRAKSI hanya dalam 3 minggu.
Selama itu, ia dan Diko tidur hanya 3-4 jam sehari, menyusun SOP baru, dan membuat sistem reseller otomatis.
Alexandria yang memiliki background desain visual menangani semua elemen identitas digital: video, packaging, bahkan konten-konten TikTok edukasi yang menyamarkan promosi produk mereka.
Jihan Purnamasari—sang ibu, justru menjadi benteng kekuatan di rumah.
“Ingat ya, Nak. Virus boleh menyebar, tapi pikiranmu harus tetap jernih. Orang bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, tapi kamu punya kesempatan. Gunakan itu bukan buat sombong, tapi buat bantu.”
Zavian menuruti pesan itu. Ia menyisihkan Rp1 Miliar dari rekeningnya untuk membuat dana sosial, membayar orang-orang sekitar jadi kurir lokal, dan membantu UMKM sekitar rumahnya pindah ke online.
Tanggal 31 Maret 2020, malam sebelum pemerintah mengumumkan PSBB jilid pertama di Jakarta, Zavian berdiri di garasi rumahnya, memandangi Mustang GT miliknya yang mengilap.
Di genggamannya, ada catatan strategi bisnis.
“Dunia akan berubah setelah ini,” gumamnya.
“Dan gue... akan jadi salah satu arsiteknya.”
Di dalam rumah, Alexandria tertidur di depan laptop. Diko masih mengetik laporan sistem pembayaran.
Dan dunia perlahan, berubah jadi digital sepenuhnya.
Tangan-Tangan Pertama di Balik Imperium
Mei–Juni 2020
Jakarta – Kemang – Depok (Universitas Indonesia)
Setelah dua bulan bertahan dalam atmosfer ketidakpastian pandemi dan transformasi digital besar-besaran, Zavian Kenzo Mahardika memutuskan untuk membangun sesuatu yang permanen. Bukan sekadar toko online atau sistem dropshipping. Tapi markas. Tempat para pemimpi bisa bekerja bersama.
Kemang: Kantor Kecil, Ambisi Besar
Pada awal Mei 2020, saat PSBB Transisi diberlakukan, Jakarta mulai membuka ruang geraknya. Zavian menyewa sebuah rumah dua lantai bergaya kolonial di belakang Jalan Kemang Raya. Bangunannya kecil, hanya 130 meter persegi, tapi memiliki halaman belakang luas yang bisa dimodifikasi jadi ruang kreatif terbuka.
Dinding bagian dalamnya dicat ulang dengan nuansa abu gelap dan aksen kayu—cerminan visual dari karakter FRAKSI: elegan, tegas, dan tak berisik. Di pintu depan, papan kecil dari logam hitam bertuliskan:
FRAKSI INCORPORATED
You don’t need more. You just need real.
Rekrutmen Awal: Bukan CV, Tapi Karakter
Zavian tak mencari orang paling pintar. Ia mencari orang yang tahan banting.
Ia dan Diko menyebar pengumuman rekrutmen hanya lewat grup Discord, Twitter underground komunitas digital, dan IG story Alexandria. Tak ada iklan di JobStreet. Tak ada HRD berpakaian formal.
Hasilnya?
Alya Isnaeni (23) – mantan copywriter yang kena PHK dari agensi di Blok M. Ia datang dengan motor Mio lama dan pitch deck berisi ide kampanye dengan tone “keluar dari kesesakan sosial”.
Seno Rifaldi (26) – mantan fotografer wedding yang job-nya hilang selama pandemi. Kini jadi kepala konten visual FRAKSI.
Mariam "Yam" Hwang (25) – keturunan Korea-Indonesia, lulusan Ewha Womans University, pulang ke Jakarta setelah pandemi memburuk di Seoul. Ia menawarkan jaringan distribusi ke Korea Selatan dan Taiwan via sepupunya yang punya agensi musik indie.
Tim pertama itu hanya berjumlah 7 orang. Tapi mereka bekerja seperti 70.
Ekspansi: Korea Selatan dan Taiwan
Bermodal koneksi dari Mariam, Zavian menargetkan ekspansi ke Seoul dan Taipei. Ia tahu gaya streetwear Asia Timur punya selera desain spesifik—monokrom, minimalis, dan sentuhan urban.
Ia mengirim prototipe pertama dari lini FRAKSI BLACK SERIES via DHL Express ke Seoul, diantar langsung ke seorang fashion YouTuber lokal yang sedang naik daun: @damianlee.kr. Dalam 2 minggu, FRAKSI mendapatkan 3.000 followers Korea hanya dari satu video.
Sementara itu, di Taiwan, Mariam memperkenalkan FRAKSI ke toko kolektif underground di Taipei yang tertarik menjual produk via sistem konsinyasi.
Meski perusahaannya kini bernilai miliaran dan bergerak antar negara, Zavian tidak keluar dari kampus. Ia tetap mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia, Depok, dan kini mengikuti semua kelas lewat Zoom, Google Meet, dan Moodle.
Setiap Senin hingga Kamis pagi, ia mengikuti kuliah daring dari kamar kecilnya di lantai atas rumah. Materi-materi seperti Teori Media, Komunikasi Politik, dan Sosiologi Digital justru memperkaya cara pandangnya dalam membangun brand FRAKSI.
Bahkan salah satu tugas kuliah bertajuk “Analisa Retorika Branding Digital di Era Krisis” yang ia buat bersama Alexandria mendapatkan pujian dari dosen dan dijadikan bahan diskusi kelas—tanpa mereka tahu, bahwa FRAKSI adalah bisnis asli milik Zavian.
Jadwal Gila, Tapi Disiplin Sakral
Pagi (07.30–11.00): Kuliah daring
Siang (11.30–14.00): Briefing harian di kantor Kemang
Sore (14.30–18.00): Review produk, diskusi strategi distribusi
Malam (20.00–01.00): Meeting virtual dengan tim ekspansi Asia
Alexandria tetap jadi kekuatan tenang di balik layar. Ia mendesain semua packaging ekspor dan kampanye brand equity FRAKSI di Asia.
Diko memimpin tim logistik dan pengelolaan keuangan yang kini menggunakan sistem dual account: sebagian dalam IDR, sebagian dalam stablecoin USDT di dompet digital bisnis mereka.
Pada malam 23 Juni 2020, Zavian duduk di balkon kantor Kemang, menatap langit Jakarta yang mulai bersih setelah lama sepi kendaraan. Di tangannya, secangkir kopi hitam. Di dashboard ponsel: email dari Seoul dengan subject:
“FRAKSI Will Be Featured in Our Summer Indie Catalogue.”
Zavian tersenyum.
“Dari Jatiwaringin ke Seoul... baru pemanasan.”
Menulis Sejarah Tanpa Kamera
Juli–Agustus 2020
Jakarta – Bandung – Bali – Seoul – Taipei
“Menjadi Legenda Tanpa Wajah”
FRAKSI menjadi noise di banyak tempat yang Zavian sendiri belum pernah datangi.
Majalah Hypebeast Korea menyebut FRAKSI sebagai "One of the most promising cross-border streetwear lines from Southeast Asia."
Sebuah YouTuber fashion asal Taipei bahkan menyebut desain FRAKSI mirip dengan Off-White tahun-tahun awal, namun lebih berani dalam mengusung nilai lokal.
Namun saat para jurnalis mulai mencari siapa “anak muda” di balik brand ini, mereka hanya mendapatkan satu kalimat singkat dari email official FRAKSI:
“Karya kami bicara lebih keras daripada wajah kami. Biarkan kami bekerja, bukan diwawancara.”
Zavian Kenzo Mahardika menolak semua bentuk eksposur media.
Tidak ada podcast.
Tidak ada wawancara televisi.
Tidak ada dokumentasi kamera, kecuali potret produk.
Ia percaya bahwa karya yang hebat tak perlu narasi buatan. Ia ingin menulis sejarah bukan dengan kata-kata di layar, tapi dengan dampak di kehidupan nyata.
Romansa yang Tumbuh dalam Diam
Di balik semua kesibukan, Zavian tidak pernah melewatkan satu hal: menjaga Alexandria tetap tersenyum.
Mereka punya ritual setiap Jumat malam:
Hangout di Taman Literasi Blok M, membeli kopi hitam dan buku acak dari lapak kecil, lalu duduk berdua di bangku kayu, membicarakan hidup.
Suatu malam di bulan Juli, di restoran rooftop kecil di Kemang, Zavian membisikkan pada Alexandria dengan senyum ringan,
“Mungkin aku nggak tahu masa depan. Tapi aku tahu, kamu harus ada di dalamnya.”
Alexandria tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Zavian lebih erat.
Liburan Keluarga yang Penuh Canda
Mereka sepakat libur sejenak dari rutinitas pada minggu kedua Agustus.
Zavian mengajak ibunya, Jihan Purnamasari, dan Alexandria serta keluarganya untuk short vacation ke Ubud, Bali.
Mereka menyewa villa privat dengan sawah hijau terbentang di kejauhan.
Pagi hari diisi dengan sarapan bersama, tawa kecil, dan diskusi ringan tentang budaya Bali. Sore hari, mereka berjalan kaki ke sawah, atau mengunjungi galeri seni tersembunyi. Malam hari, makan malam dengan lilin dan obrolan keluarga seperti zaman dulu yang mulai jarang ada.
“Aku nggak nyangka kita bisa sampai sini, Ma. Dulu kita cuma bisa lihat sawah dari foto kalender,” kata Zavian, sambil menatap ibunya penuh rasa.
Ibunya hanya tersenyum, menahan air mata, lalu memeluk Zavian.
Cinlok itu tak pernah direncanakan. Tapi semua orang melihatnya datang.
Diko dan Mariam “Yam” Hwang mulai sering lembur berdua di lantai dua kantor Kemang. Awalnya hanya diskusi digitalisasi supply chain Korea, tapi kemudian bergeser ke obrolan tentang drama Korea lawas, sneakers, dan makanan jalanan.
Pada suatu malam, saat deadline pengiriman ke Seoul hampir gagal karena sistem crash, Diko berkata sambil menghela napas,
“Kalau bukan karena kamu, aku mungkin udah resign malam ini.”
Mariam hanya tertawa pelan, lalu menjawab sambil membetulkan kacamatanya,
“Kalau kamu resign, aku ikut.”
Sejak hari itu, mereka tak bisa dipisahkan.
Zavian dan Alexandria bahkan mendukung hubungan itu dengan kalimat klasik di grup internal:
“Kalau kalian nikah, FRAKSI kasih subsidi cetak undangan.”
Pada akhir Agustus 2020, Zavian berdiri di jendela kantor Kemang yang kini sudah diperluas ke bangunan sebelah.
Ia menatap bulan purnama Jakarta, sementara Alexandria duduk di sofa sambil menyusun moodboard untuk koleksi FRAKSI Fall-Winter.
Layar laptopnya menampilkan laporan ekspor batch ketiga ke Taiwan.
Zavian bergumam pelan,
“Mereka tak tahu wajahku. Tapi mereka pakai karyaku di jalan-jalan Seoul dan Taipei. Itu cukup.”
Alexandria menjawab tanpa menoleh, “Dan aku tahu, suatu hari nanti dunia akan mencatat ini. Tanpa harus tahu siapa kita.”
BAB 8 – “SUARA YANG TAK PERLU DIDENGAR”
Zavian ke Jerman – Menghadapi Akar Luka
(Februari 2023, Jakarta)
Hujan turun pelan di atas atap rumah tua itu—rumah yang tak pernah berubah sejak Zavian Kenzo Mahardika masih anak-anak. Aroma kayu basah dan kopi hangat menyambut seorang pria yang nyaris dua belas tahun tak menampakkan diri. Rambutnya memutih di sisi-sisi pelipis, dan langkah kakinya tertahan di ambang pintu seakan waktu masih menyimpan beban yang belum selesai ditebus.
“Laurent…” suara itu lirih. Jihan Purnamasari berdiri terpaku, mata berkaca-kaca, tangan gemetar menggenggam lengan baju rumah.
Pria itu hanya mengangguk. “Aku tak tahu harus mulai dari mana, Ji…”
Di ruang tamu sederhana, Zavian duduk diam. Wajahnya datar, seperti patung yang sudah kehabisan ekspresi. Ia sudah terlalu sering mengukir duka dengan rahang mengeras dan mata yang menolak basah.
Laurent menatap putranya yang kini tak lagi bocah. Ia kini seorang lelaki—tegap, tenang, dan asing.
“Aku bukan pria yang baik, Van…” Laurent duduk perlahan, membuang napas berat. “Tapi aku ingin kamu tahu… aku tak pernah ingin pergi.”
Ia mulai bercerita. Tentang tekanan keluarga besar Mahardika di Berlin. Tentang warisan bisnis mendiang ayahnya yang mengharuskannya kembali dan menikah dengan anak konglomerat Jerman demi melanggengkan kekuasaan dan saham keluarga. Tentang bagaimana ia memilih lari dari semua tanggung jawab sebagai ayah—karena ia terlalu lemah untuk melawan sistem yang telah membentuknya sejak lahir.
“Aku memilih menjadi pengecut… karena aku pikir kamu dan ibumu akan lebih aman tanpaku.”
Zavian menatap kosong. Tapi di dadanya, ada rasa yang dulu disebut benci, kini telah berubah menjadi hampa.
“Aku sudah memaafkan, Pa,” ucapnya pelan. “Tapi aku tak lupa.”
Laurent mengangguk. “Itu cukup. Terima kasih sudah mengizinkan aku ke sini.”
Sebelum pulang, Laurent menatap Jihan. “Aku meninggalkan sesuatu di Swiss. Untuk Zavian. Tapi sebenarnya, itu untuk kalian berdua. Sebagai permintaan maaf yang tak akan pernah cukup.”
(Mei 2023, Berlin – Rumah Keluarga Mahardika)
Undangan itu datang resmi, berkop surat emas, dari keluarga besar Mahardika. Tak banyak kata, hanya kalimat:
“Come home. It’s time.”
Zavian datang mengenakan jas hitam sederhana. Ia tak membawa pengawal. Tak membawa kesombongan. Ia datang dengan satu misi: mengakhiri warisan luka.
Di rumah besar keluarga Mahardika—bangunan bergaya klasik dengan pilar-pilar granit dan taman setengah hektar—Zavian berjalan melewati tatapan mata orang-orang yang dulu memaksa ayahnya pergi. Mereka semua kini lebih tua, tapi masih menyimpan wajah yang tak berubah: penuh penghakiman.
Ia bertemu dengan adik tirinya—seorang anak lelaki berusia 10 tahun dengan mata kelabu yang sama seperti miliknya. Dan wanita itu, yang kini menjadi istri sah Laurent, menyambutnya dengan raut bersalah namun tak sanggup berkata-kata.
Di tengah ruang makan marmer yang mewah, saat semua menanti jawaban apakah Zavian bersedia mewarisi sebagian kerajaan bisnis Mahardika, ia berdiri dan berkata dengan tenang:
“I have forgiven everything. But I will not inherit anything from this land. I am already wealthy from the choices my father regretted.”
(Aku sudah memaafkan semuanya. Tapi aku tidak akan mewarisi apa pun dari tanah ini. Aku sudah cukup kaya dari pilihan yang ayahku sesali.)
Lalu ia pergi, tanpa membalikkan badan.
Kematian Mendadak Laurent – Sebuah Surat Terakhir
(Mei 2023, Berlin – Dua hari setelah pertemuan keluarga Mahardika)
Angin dingin Berlin menyusup dari celah-celah jendela tua penginapan yang Zavian sewa—bukan hotel mewah, bukan apartemen elite—hanya sebuah kamar kayu sederhana di daerah Prenzlauer Berg, tempat penuh sejarah dan sunyi.
Di luar, matahari hampir tenggelam. Cahaya oranye keemasan menyelimuti balkon sempit tempat Zavian duduk diam, dengan secangkir teh hitam yang tak lagi hangat.
Ponselnya berbunyi pelan. Nama pengirim muncul: “Sophie Adelheid” — istri sah ayahnya.
“He passed away this morning. In his sleep. Peacefully.”
Zavian menutup mata. Ia tidak terkejut, tapi sesuatu dalam dadanya runtuh seperti atap rumah tua yang diam-diam rapuh oleh hujan selama bertahun-tahun.
Satu jam kemudian, sebuah amplop cokelat tua dikirimkan langsung ke penginapannya oleh pengacara pribadi Laurent. Hanya tertulis:
“To my son, Zavian.”
Jarinya gemetar saat membuka lipatan surat yang tulisannya menggunakan tinta hitam, goresannya tegas namun terasa berat. Surat itu ditulis tangan. Bukan sekadar wasiat. Ini pengakuan. Ini permintaan maaf dari seorang ayah yang tahu ia tak layak disebut begitu.
Surat itu berbunyi:
Zavian, anakku…
Aku tahu kau tak pernah butuh surat ini. Tapi aku yang butuh menulisnya. Supaya aku tahu, setidaknya aku pernah mencoba bicara, meski lewat kertas. Aku memantau kamu dari jauh, selama bertahun-tahun. Aku tahu tentang FRAKSI. Aku tahu tentang mobil Mustang hitammu. Aku tahu nama Alexandria, dan bagaimana matamu berbinar saat menatapnya di salah satu foto yang bocor ke artikel komunitas fashion Korea. Dan kamu benar, Van. Aku menyesal memilih warisan yang bukan milikku. Aku menyesal meninggalkan rumah yang seharusnya tak pernah kutinggalkan. Tapi penyesalan tak akan pernah cukup untuk membalikkan waktu.
Aku tidak ingin kamu menjadi aku. Maka bangunlah dunia milikmu, tanpa harus mencuri panggung orang lain. Kamu tidak perlu sorotan. Karena aku tahu… kamu akan jadi legenda yang diam.
Dan itulah yang membuatku bangga, lebih dari segalanya.
Love you always,
–Laurent.
Zavian tak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, ia menangis. Bukan karena sedih, bukan karena marah—tapi karena ada bagian dari dirinya yang akhirnya bisa melepas luka yang selama ini ia jaga seperti warisan yang tak tertulis.
Ia duduk sendiri di balkon tua itu sampai malam turun penuh, dan lampu-lampu Berlin menyala seperti bintang yang lupa pulang.
Tokyo – FRAKSI Menang Tanpa Mengalahkan Siapa-Siapa
(Agustus 2023, Tokyo International Streetwear Expo)
Tokyo tidak pernah kehilangan tempo. Kota ini hidup seperti mesin presisi dengan denyut yang tak pernah padam. Tapi di tengah hingar-bingar dan layar LED yang berlomba memanggil perhatian, satu sudut ruangan pameran terbesar tahun ini justru diam—tidak ada panggung, tidak ada presenter, bahkan tidak ada spanduk besar yang menggembar-gemborkan kehebatan.
Itulah booth milik FRAKSI.
Dikelilingi oleh brand dari Eropa, Amerika, dan Asia Timur yang datang dengan tim humas, bintang tamu, dan influencer kelas atas, kehadiran FRAKSI terasa seperti bunyi napas di tengah konser rock. Tenang. Tapi nyata.
Zavian berdiri di belakang layar kaca booth, mengenakan hoodie hitam dengan logo mikro di dada kiri—nyaris tak terlihat. Alexandria di sampingnya, mencatat data statistik pengunjung lewat tablet, sementara Diko berdiskusi dengan delegasi dari Korea Selatan yang tertarik pada lini produk ecowear terbaru mereka.
Tidak ada kamera yang diarahkan ke mereka. FRAKSI tidak menggelar konferensi pers. Mereka bahkan menolak satu-satunya undangan dari media fashion Jepang yang ingin mewawancarai Zavian. Bagi mereka, ini bukan soal tampil. Ini tentang hadir.
Malam Puncak Expo – Presentasi Penutup
Setiap brand diberi kesempatan 3 menit di layar utama untuk menyampaikan pesan puncak mereka. Saat giliran FRAKSI tiba, lampu utama diredupkan. Tidak ada perwakilan yang naik panggung. Tidak ada musik. Hanya suara sistem komputer yang membacakan satu kalimat pendek dalam Bahasa Jepang, Inggris, dan akhirnya dalam Bahasa Indonesia.
Layar besar memunculkan tulisan:
“We are not present, but we’ve never been absent. Thank you for hearing the voices we never spoke.”
(Kami tidak hadir, tapi kami tidak pernah absen. Terima kasih telah mendengarkan suara yang tak pernah kami ucapkan.)
Lalu layar padam. Tak ada logo. Tak ada nama. Tapi seluruh ruangan diam. Lalu perlahan, satu per satu orang berdiri dan memberi tepuk tangan paling tulus yang pernah terdengar di Tokyo Expo tahun itu.
“Kalau mereka mau jadi misterius terus, mereka bakal ditiru oleh seluruh Asia,” komentar salah satu jurnalis dari Highsnobiety.
“Ya. Tapi satu hal yang tidak bisa ditiru,” jawab rekannya, “adalah ketulusan mereka.”
Zavian, Alexandria, Diko, Mariam, dan seluruh tim FRAKSI hanya menonton dari kejauhan. Tanpa selebrasi. Tanpa pesta. Tapi malam itu, di salah satu sudut Tokyo, legenda mereka sudah ditulis dengan tinta tak terlihat di hati para pendengar sejati.
Epilog – Warisan yang Diam
(November 2023, Jakarta Selatan)
Malam itu hujan turun pelan. Seperti tirai tipis
yang jatuh dari langit. Di dalam sebuah rumah modern beraksen kayu dan batu di bilangan Jakarta Selatan, sebuah lampu temaram menyala dari ruang kerja di lantai dua.
Zavian duduk sendiri. Rambutnya mulai panjang, terikat sederhana ke belakang. Janggut tipis menghiasi rahangnya, tanda tahun-tahun berat yang kini mulai mengendap dalam bentuk kedewasaan. Di depannya, sebuah laptop terbuka dengan layar kosong. Jari-jarinya tak menyentuh keyboard. Ia justru memandang sebuah buku catatan tua berwarna hitam yang sejak dulu selalu disimpan di dalam laci terkunci.
Pelan-pelan, ia membukanya.
Halaman pertama kosong. Tapi pada halaman kedua, tertulis satu kalimat dengan pulpen tinta hitam:
“WARISAN YANG TAK TERLIHAT”
Itulah judul yang ia pilih.
Tidak ada rencana menjadikan buku itu publik. Ini bukan memoar untuk pasar. Ini bukan motivasi untuk viral. Ini adalah pengingat—tentang anak berusia 11 tahun yang ditinggal tanpa kata perpisahan, yang menangis diam-diam di lorong sekolah saat orang lain merayakan Hari Ayah, yang memilih untuk diam bukan karena takut, tapi karena tahu suara terbaik sering kali datang dari mereka yang memilih tidak berbicara.
Zavian menulis sepanjang malam. Tentang Jihan Purnamasari, ibu yang tak pernah menyerah. Tentang Laurent Mahardika, pria yang gagal sebagai ayah, tapi menebusnya dengan diam-diam membangun jembatan emas untuk anaknya. Tentang Diko, yang menjadi saudara lebih dari sekadar sahabat. Tentang Alexandria, rumah tempat jiwanya kembali setiap kali dunia terlalu bising. Tentang Mariam dan cinta yang lahir dari kerja sama, bukan dari drama.
Ia menulis tentang FRAKSI, bukan sebagai brand, tapi sebagai revolusi kecil—dari mereka yang tak pernah ingin terkenal, tapi selalu ingin berdampak.
Ketika fajar menyentuh jendela, Zavian menutup buku itu.
Ia menatap Alexandria yang tertidur di sofa kecil, masih mengenakan hoodie oversized miliknya. Ada damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia berdiri pelan, menyampirkan selimut ke tubuh gadis itu, lalu membisikkan sesuatu ke angin pagi:
“Besok kita mulai lini edukasi. Aku ingin bantu lebih banyak orang keluar dari gelap, seperti aku dulu.”
WARISAN YANG TAK TERLIHAT.
Bukan tentang uang. Bukan tentang bisnis. Tapi tentang keberanian memilih jalur sendiri, tanpa harus menginjak jalur orang lain. Tentang menjadi legenda, tanpa perlu panggung. Tentang menyembuhkan luka, tanpa menjadikannya alasan untuk melukai balik.
Itulah warisan Zavian Kenzo Mahardika.
Yang tumbuh dari diam. Yang mengakar dari luka.
Dan yang akan terus hidup, bahkan jika dunia tak pernah menyebut namanya.
THE END
Surat dari Zavian
Jakarta Selatan, 29 November 2023
Untuk kamu yang membaca,
mungkin aku tidak mengenalmu.
Tapi jika kamu pernah merasa ditinggalkan, diabaikan, atau dilupakan oleh dunia, maka kita pernah berjalan di jalan yang sama.
Aku tidak tumbuh dalam pelukan mewah.
Aku tidak memiliki panggung sejak awal.
Tapi satu hal yang selalu kupegang sejak kecil adalah ini:
Luka boleh menimpa kita, tapi tidak harus mendefinisikan siapa kita.
Kamu boleh diam.
Boleh tidak tampil.
Boleh memilih jalan sunyi.
Karena ternyata...
orang yang tidak bersuara bukan berarti tidak berdampak.
Dan mereka yang tidak terlihat, bisa jadi sedang menanam benih yang kelak mengubah dunia.
FRAKSI hanyalah salah satu dari banyak suara yang tak pernah meminta untuk didengar.
Seperti kamu. Seperti kita.
Yang menulis sejarah bukan dengan sorotan kamera,
tapi dengan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil saat tak ada yang melihat.
Jika hari ini kamu masih meraba dalam gelap,
izinkan aku berkata:
kamu tidak sendiri.
Dan tidak apa-apa kalau dunia belum mengenalmu sekarang.
Yang penting, kamu sedang membangun sesuatu yang tak bisa dilihat siapa pun—
sebuah warisan yang diam.
Salam sunyi,
Zavian Kenzo Mahardika
(Seorang anak dari keputusan yang disesali, dan seorang ayah dari mimpi yang dipilih sendiri).
epilog dalam buku klasik, mengandung jiwa sunyi, kesederhanaan yang agung, dan jejak diam yang abadi. Gaya bahasa menyatu dari JK Rowling (dalam kedalaman jiwa), Dee Lestari (dalam kontemplasi), dan Tere Liye (dalam keheningan yang menyentuh):
EPILOG
WARISAN YANG DIAM
Senja menguning di jendela barat, menggurat bayangan lembut di lantai kayu rumah kecil di Jakarta Selatan. Di meja kerjanya, Zavian duduk sendiri. Tak ada suara, hanya desahan napasnya yang tenang, dan bunyi halus kertas saat ia membuka buku catatan hitam—satu-satunya warisan yang tak ia dapat dari siapa pun, kecuali dari luka-lukanya sendiri.
Ia menulis halaman pertama dengan spidol tipis hitam:
“WARISAN YANG TAK TERLIHAT”
Lalu, dengan tenang, ia menutup buku itu. Tangannya meraih laptop, mengetik satu kalimat terakhir dalam folder bertanda: Legacy. Ia menyimpan file itu. Lalu mematikan laptop, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah janji hidup.
Dari sofa, Alexandria tertidur dengan buku terbuka di dadanya. Selimut kecil menutupi kaki. Zavian memandang wajahnya sejenak, tersenyum. Tak ada yang perlu dikatakan.
Namun, ia berbisik pelan, seperti berbicara dengan dunia:
“Besok kita mulai lini edukasi.”
“Aku ingin bantu lebih banyak orang keluar dari gelap… seperti aku dulu.”
Zavian menunduk. Tak ada air mata. Hanya ketenangan.
Karena pada akhirnya, ia tidak pernah ingin menjadi sorotan.
Ia hanya ingin menjadi suara yang tak perlu didengar, tapi terasa.
Seperti embun pagi yang tak pernah disorot kamera,
tapi menyuburkan seluruh taman.
Halaman Terakhir
(dicetak dengan tinta halus di tengah lembar putih)
"Build a world of your own,
without stealing someone else's stage.
You will be a silent legend. I believe in that."
– Laurent Mahardika’s Last Letter
Bangunlah duniamu sendiri,
tanpa perlu mencuri panggung orang lain.
Kamu akan menjadi legenda yang diam. Aku percaya itu.
Untuk kamu, pembaca diam...
Kita tidak butuh panggung untuk menjadi berarti.
Kita hanybutuh keberanian untuk tidak menyerah.
Dan semesta akan mencatat kita, dalam sunyi yang kekal.
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰
