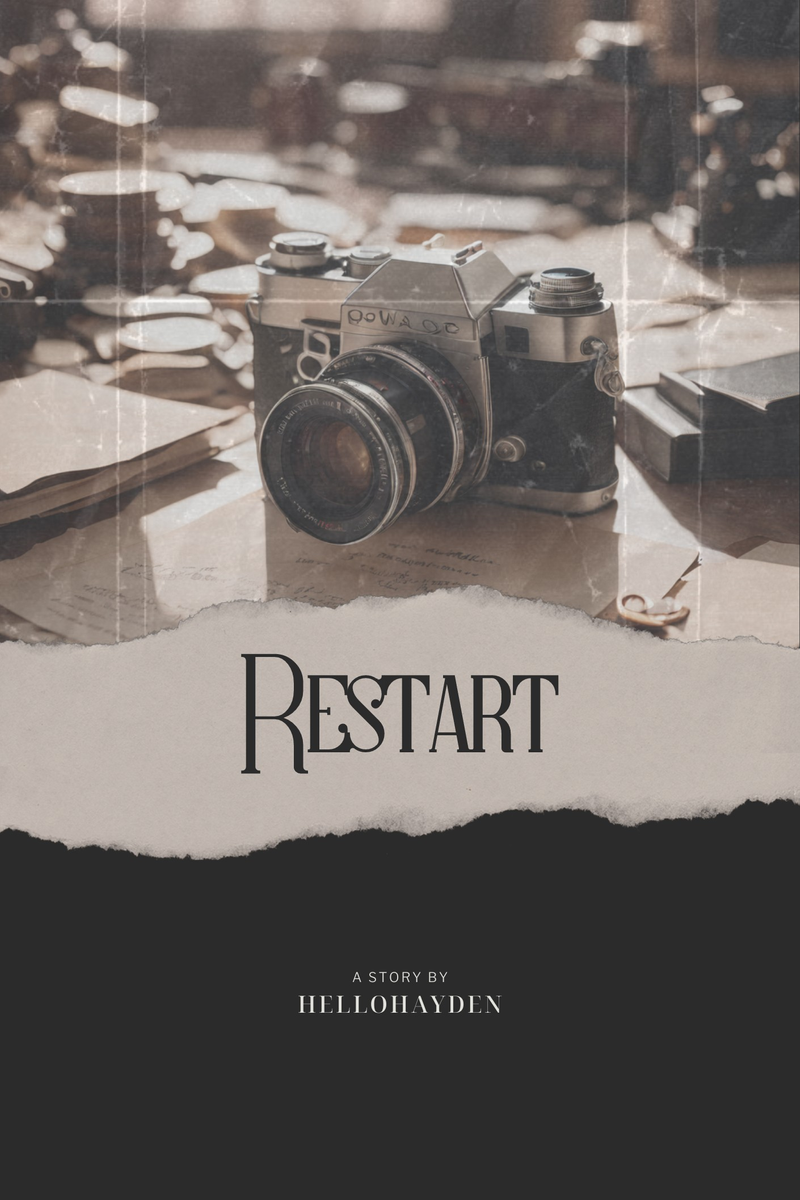Cek teaser bab 28 di → https://www.instagram.com/p/C8LlwBnx4Rr/
(WARNING 21+)
Tangan Aruna yang tadi melingkari perut, kini dia gunakan untuk membuat wajahku menghadapnya, mengusap-usap alisku dengan jempolnya, “Makasih, Gam. Itu lebih baik dari pernyataan cinta manapun yang pernah aku dengar.”
“Dari laki-laki lain?”
“Dari laki-laki lain di sinetron atau di film-film roman picisan.”
Aku tertawa sesaat, lalu mencium keningnya.
Pagi-pagi buta aku sudah bangun dan setengah berlari menuju parkiran. Sepertinya berita yang datang dini hari tidak pernah menjadi berita baik. Sudah tiga kali, dan ketiganya berhasil membuat jantungku melompat. Berita nenek Ares meninggal, telepon dari mbak minuman mengenai kebakaran, lalu dini hari ini, handphone berdering dan nama Aruna terpampang di layar. Dengan tenang Aruna berbicara dari seberang telepon, suaranya semakin tipis bahkan bagian-bagian akhir nyaris tidak terdengar. Yang aku tangkap dari pembicaraan itu hanya urgensi untuk datang membawakannya pakaian ganti. Alasannya kenapa, aku belum tahu pasti. Tidak terdengar. Dan aku bukan orang yang akan bertaruh dengan waktu hanya untuk bertanya ini itu untuk sesuatu yang dibutuhkan cepat. Azan subuh berkumandang saat aku sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Walau udara masih dingin sekali, aku berkeringat karena tegang yang aku rasakan.
Sampai pada lantai empat, aku disambut oleh seorang perawat yang kemudian mengantar ke ruang khusus untuk istirahat. Dia berjalan sedikit di depan sambil menceritakan kronologisnya. Aruna yang sepertinya tahu kondisi tubuhnya tidak baik memutuskan istirahat sebentar, membuat teh hangat. Namun sayangnya, sebelum duduk, Aruna tiba-tiba pingsan dan teh yang masih mengepulkan asap itu menyiram tubuhnya. Perawat itu juga mengatakan tekanan darah Aruna sedang rendah. Aku gusar dan sungguh khawatir membayangkan bagaimana perihnya air panas mengenai kulit Aruna.
“Silahkan.” Kata perawat itu sambil membukakan pintu.
Aruna duduk di sofa bed, dengan infus yang tergantung di tiang dan terpasang pada lengannya. Dia mengenakan piyama pasien berwarna kuning, yang diikat hanya pada sisi kiri
“Hai…,” ujarnya lemah.
Aku segera duduk di sampingnya dan membawa kepalanya ke dada. Mendekapnya. Badannya terasa dingin.
Oh, Arunaku sayang. Aku mencium puncak kepalanya. Aku melepas pelukan, kedua tanganku memegang pipinya, memegang leher dan pangkal lengannya hingga siku, “Ada minyak angin gak? Badan kamu dingin,” tanyaku.
“Udah. Tadi udah dibalurin,” jawabnya sambil memperbaiki selang infus, “aku pengen ganti baju.”
Aku membuka ransel, mengambil kaos dan menyerahkannya pada Aruna.
Aruna berjalan pelan menuju kamar mandi, membawa tiang itu bersamanya. Aku ikut memegang tiang walau rasanya tidak membantu apa-apa.
“Aku masuk? Kamu perlu bantuan?” tawarku padanya saat dia akan menutup pintu kamar mandi. Aruna menggeleng, “Aku bisa sendiri. Jangan-jangan kamu lupa kalau aku perawat.” Senyum Aruna tampak lemah. Aku mengangguk saja.
Sesaat setelah Aruna menutup pintu terdengar suara dentingan pendek-pendek dari besi, mungkin Aruna tengah melepas-pasang infus. Aku berdiri di samping pintu PVC biru muda, bersandar pada dinding, dan menatap ruangan putih bersih yang berbau alkohol menyengat. Hanya ada sofa bed, satu meja kerja lengkap dengan kursi dan lemari brankas besi.
“Runa, kamu kelelahan. Kemarin-kemarin kamu sibuk bantuin studio. Sekarang, udah dua minggu ini, sejak akhir tahun sampai kemarin, kamu tiap libur bukan istirahat malah ke Tangerang,” kataku.
“Aku kan udah bilang, ada urusan di sana, Gam,” jawabnya segera. Suaranya menggema dari kamar mandi. Aku menggigit bibir. Sebenarnya, akhir tahun lalu, sehari sebelum tahun baru, aku sempat melarang Aruna pulang ke Tangerang karena sudah terlihat lesu. Tapi dia bersikeras. Alasan pertama yang dia kemukakan adalah adanya urusan penting. Ketika alasan itu tampak tidak memuaskanku, dia beralih mengatakan akan membantu Bu Sarah dengan kliniknya. Aku diam, tapi dia pasti tahu saat itu aku tetap berat hati karena kondisinya tidak baik saat pergi. Karena tidak ingin perkara ini menjadi perdebatan panjang, baik saat itu maupun sekarang, lagi-lagi aku memilih bungkam. Itu jelas kelemahanku, tidak cerewet, tidak menuntut. Malas ribut. Napasku terhela panjang lalu tiba-tiba ingatanku terlempar pada satu sore yang masih mengganjal –yang aku kurasakan kini ada sangkut pautnya dengan urusannya di Tangerang.
24 Januari 2019, satu hari sebelum Aruna berangkat ke Tangerang (lagi).
“Aku ingin ke makam.”
Aruna yang tengah menulis pada sebuah kertas tiba-tiba mengatakan itu tanpa menoleh ke arahku. Nadanya datar, tidak ada emosi. Begitu juga dengan raut wajahnya.
“Makam?”
“Ya. Makam ibuku.”
Aku tidak mengatakan apa-apa, masih menunggu Aruna melanjutkan pembicaraannya.
“Banyak hal yang mau aku ceritakan ke ibuku.”
Apa orang mati bisa mendengar? Seolah tahu apa yang sedang aku pikirkan, Aruna segera menjawab, “Terkadang berbicara kepada orang mati rasanya lebih baik. Kamu merasa didengarkan. Terus terang, juga merasa diperhatikan.”
“Jadi besok kamu ke Tangerang itu mau ke makam? Bukan bantuin Bu Sarah siap-siap pembukaan klinik?” tanyaku.
“Hmmm…, aku ingin ke makam. Bisa atau gak-nya aku belum tahu.”
“Oh.”
“Apa kamu pernah begitu?”
“Gimana?”
“Bicara di makam Bapak kamu?”
“Enggak. Aku berdoa. Paling juga bersihin rumput teki yang tumbuh liar.”
“Apa kamu pernah ingin bicara?”
“Pernah. Pas studio kebakaran,” aku memencet tombol off pada tablet, menutupnya, menghampiri Aruna yang duduk di meja belajarnya, “kamu kenapa? Ada masalah apa?” tanyaku sambil memijat bahunya.
Dia diam. Tangannya yang memegang pensil berhenti menari-nari di atas kertas buram.
“Kamu bisa cerita ke aku.” Aku berusaha meyakinkannya.
Dia masih memilih bungkam, lalu kembali menulis sesuatu yang sepertinya bagian pekerjaan, “Seandainya… ini seandainya,” katanya kemudian.
“Ya?”
“Kamu tahu rahasia teman kamu dan dia mohon ke kamu untuk gak cerita ke siapapun.”
Sesaat, aku merasa Aruna mengetahui pekerjaan Ares dan sedang berusaha memancingku untuk bercerita, “Ya, terus?”
“Terus rahasia itu jadi semacam kesepakatan di antara kalian. Kesepakatan yang sama-sama menguntungkan.”
Bukan. Ini bukan tentang Ares. Aku menunggunya selesai bercerita sambil mengusap-usap rambut Aruna dengan cermat, seperti seorang penata rambut yang sedang bekerja untuk pelanggannya, “Hmm … Kamu gak mengancam teman kamu, kan?” candaku.
Aruna terkekeh, “Ini bukan cerita aku, loh?”
Dia meyakinkanku, namun aku tahu cerita ini sepenuhnya tentang dia dan seorang temannya.
“Kalau ternyata, teman kamu itu gak lakuin kesepakatan seperti di awal, kamu bakal beberkan rahasianya gak?” lanjut Aruna lagi. Dia masih menulis dengan tenang. Aku diam dan merenungkan cerita Aruna. Situasi ini mengarahkanku pada rahasia Ares. “Runa, kamu akan tetap menyimpan apa yang terjadi di antara kalian dan apa yang menjadi rahasianya bahkan setelah kalian tidak berteman lagi. Itu yang namanya integritas.”
Aruna mengangguk, “Integritas, ya?”
“Ya”
“Terus untuk teman yang gak menepati kesepakatan itu, kamu sebut apa?”
“Pengecut.”
Aruna kembali mengangguk, tapi kini ragu-ragu. Lalu saat dia sadar sesuatu, dia melepas pensil untuk segera memegang rambutnya yang sudah selesai aku kuncir dengan gelang lain yang biasa melingkar pada pergelangan kiriku. Dengan cepat Aruna meraih cermin di samping speaker. Lalu tertawa melihat pantulannya sendiri yang tampak jenaka, Aruna si kepala air mancur.
Tidak lama, Aruna keluar. Infus tidak lagi terpasang, dia mengemas sisa-sisa pemasangan infus itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Mengeluarkan tiang dari kamar mandi dan memberikan padaku. Kami kembali duduk di sofa. Baju kaos –sebenarnya punyaku– yang kebesaran di tubuhnya itu hanya memperlihatkan sepertiga lengannya dan aku tidak melihat tanda luka bakar.
Perawat yang mengantarku tadi masuk setelah mengetuk pintu. Dia mengulurkan satu kantong kertas berwarna cokelat kepada Aruna yang ternyata isinya obat.
“Krimnya udah dioles?” tanyanya.
“Udah, Kak.”
“Derajat satu. Pembengkakan ringan. Gak ada blister, kan?”
Aruna menggeleng cepat.
“Oke. Itu ada analgesik dan vitamin. Makan banyak protein.”
Aruna mengangguk, “Apa kata Bu Hera?”
“Oh? Belum angkat telepon. Ntar aku kabari aja gimana-gimana nya.” Ujarnya sambil melipat baju pasien yang dikenakan Aruna tadi dan mengambil kantong sisa infus.
“Cepat sembuh.” Ujarnya lagi sambil mengusap bahu Aruna. Lalu pergi setelah meminta tiang infus yang sedari tadi aku pegang saat mendengarkan obrolan mereka.
Kami meninggalkan ruangan istirahat. Lorong-lorong menjadi saksi bagaimana Aruna tidak terlihat seperti seorang yang baru saja pingsan. Langkahnya memang lebih pendek dari biasa, tapi dia cukup tegap. Dengan suara lemah Aruna menceritakan bahwa perawat yang memberinya obat adalah seorang supervisor. Kami berhenti pada loker. Aruna memutar anak kunci pada pintu tengah kiri. Sebuah buku panjang dan kertas-kertas dimasukkan ke tas selempang. Saat dia sibuk memilih barang yang akan dibawa pulang, aku memperhatikan dua foto selfie kami yang tidak hanya dipajang, tetapi juga ditulis tangan yang menyatakan tanggal jepretan dan tempatnya. Aku mengusap foto-foto itu bergantian dan senyumku terkembang.
“Yok!” ajak Aruna. Dia sudah siap dengan jaket jeans-nya.
Aku memutuskan meninggalkan motor di rumah sakit dan kami pulang dengan taksi agar Aruna lebih aman. Benar saja, selama perjalanan, Aruna bersandar pada bahuku dan tertidur. Dia kembali terlihat pucat saat kami turun dari taksi dan langkahnya semakin pelan saat memasuki gedung.
“Naik.” Aku berjongkok di depannya. Ransel kini aku sandang di depan dada dan tas selempang Aruna menggantung di leherku bak kamera. Tanpa berusaha menolak, Aruna naik ke punggungku. Saat itu aku sadari, badannya terasa dingin dan lembab. Dia kembali menyandarkan kepalanya, aku yakin dia juga memejamkan mata.
Gina, tetangga kami di lantai dua, sedang membereskan rak sepatu, segera datang menghampiri. Suara pekikannya yang seperti tikus terjepit itu berhasil membuat Aruna mendesis. Berkali-kali Aruna mengatakan bahwa dia hanya kelelahan namun reaksi Gina terlalu berlebihan. Dia cenderung terlihat awam, bukan seperti mahasiswi keperawatan.
Dengan cerewet, Gina terus mengikuti kami hingga sampai di kamar Aruna.
“Gin? Kalau boleh, tolong belikan sarapan di depan. Bubur ayam,” kataku pada Gina sambil menyodorkan beberapa lembar uang.
Dia menghitung uang itu, “kebanyakan, Mas.”
“Beli buat kamu sekalian.”
Dia mengangguk dan langsung pergi.
Aruna yang sudah terbaring di kasur hanya bisa memejamkan mata.
“Kamu butuh apa?”
Aruna menggeleng.
“Makan dulu, ya?”
“Ya ….”
Aku sedang merebus air untuk teh saat Gina masuk. Dia membantu Aruna duduk dan berusaha memaksa Aruna makan dengan menyuapinya. Tapi sepertinya Aruna memilih makan sendiri. Lalu mereka tampak berbincang. Gina keluar sambil mengucapkan terima kasih atas sarapan yang juga aku belikan untuknya. Teh yang aku buat diminum Aruna dengan perlahan. Keringat bercucuran dari dahinya. Aku menyeka keringat itu, menyibak rambut yang menempel pada wajahnya, menyelipkan ke balik telinganya serta memijat pelan telapak tangannya. Kini tubuhnya terasa jauh lebih hangat. Mungkin juga karena dia berselimut menutupi pinggang dan seluruh kakinya.
“Baju kamu lembab. Ganti, yuk?” Aku membujuknya.
Aruna mengangguk, aku berdiri dan kembali lagi dengan membawa baju ganti, “Bagian mana yang kena air panas?” tanyaku.
“Dada.”
Kedua alis dan kelopak mataku naik bersamaan mendengar itu. Aku menatapnya seolah bertanya kembali. Aruna mengangguk, “Iya. Dada,” katanya lagi.
“Aku boleh lihat?”
Mata Aruna memperlihatkan keengganan. Bagiku itu sudah mewakili jawaban yang akan keluar dari mulutnya yang kini bergerak-gerak ragu untuk mengatakannya dengan benar.
Aku mengusap kepalanya, “Kamu gantilah. Aku balik badan.”
Aku memutar badan menghadap jendelanya yang sudah sejak setahun terakhir berganti pemandangan menjadi bangunan gedung kost lain. Dalam kepalaku, ada semacam perdebatan mengenai apa yang dimaksud Aruna dengan dada. Aku sedikit bingung saat perempuan mengatakan “dada”. apakah itu termasuk keseluruhan bagian dada beserta payudara, atau hanya area datar di atas payudara. Kami, para pria, menyebut “dada” sebagai seluruh bagian dari bawah leher hingga atas perut. Tapi bagi perempuan?
“Gam?” panggil Aruna yang secara langsung membungkam suara-suara di dalam kepalaku.
Apa yang aku pertanyakan diam-diam tadi langsung terjawab saat aku menoleh. Dada. Bagian itu ternyata bagian datar di atas payudara. Aruna hanya mengenakan bra, merah tua, dengan renda-renda tipis menyelimutinya. Dan juga renda merah itu sedikit menerawang pada sisi kiri dan kanan. Membuatnya terlihat … indah? Sungguh memesona. Aku terkesima dengan suguhan pandangan yang molek.
Gamma brengsek!
Aku mengumpat diri sendiri sesaat setelah menyadari di atas bra itu, warna merah lain menyebar pada kulitnya hingga bahu kiri dan kanan. Aku tercengang dan menaksir-naksir bagaimana reka kejadian pingsan, menerka-nerka bagaimana perih yang dia rasakan. Aruna yang tadinya meremas selimut–mungkin dia membutuhkan keyakinan kuat dan keberanian lebih untuk memperlihatkan tubuhnya– kini satu tangannya dengan cepat bergerak menutupi dadanya.
“O-obat. Aku mau minum obat,” ujarnya terbata-bata.
Aku tersentak, “Oh. Oh, ya. Ya.”
Aku berdiri, menyiapkan air dan menyambar obat di atas meja belajarnya. Dia sudah mengenakan pakaian saat aku duduk lagi di kasur.
Aruna minum tiga jenis obat.
“Ini mau dioles lagi?” tanyaku sambil membaca salep berukuran telunjuk.
“Iya.”
Aku memberikan salep itu. Aruna mengoleskan salep yang dia tuang sebesar biji jagung pada tiga jarinya, dengan lihai mengusap-usap dadanya melalui celah bawah baju.
Entah apa yang dia pikirkan, tapi sejak dia memperlihatkan tubuhnya, dia banyak menunduk. Mungkin dia malu, mungkin juga merasa canggung. Tapi aku sama sekali tidak bermaksud mesum. Aku benar-benar hanya ingin melihat lukanya –untuk aku yang terpana, itu diluar kendali kepala. Aku bahkan menahan diri untuk tidak menyentuh luka itu agar suasana tidak menjadi jauh lebih kikuk.
“Kamu hari ini tes jam sepuluh, kan? Gak siap-siap? Motor kamu tinggalin di rumah sakit.” Aruna mengingatkanku mengenai ujian di salah satu BUMN. Perusahaan agribisnis itu sedang merekrut karyawan, termasuk di bidang yang sesuai dengan pendidikanku. Sepuluh hari lalu aku melamar, lima hari setelahnya aku dinyatakan lulus tahap administrasi. Hari ini adalah tes pertama dengan ujian kompetensi bidang.
Aku melirik jam dinding, ini masih jam enam pagi. Cahaya matahari juga belum terurai sempurna. “Masih banyak waktu. Kamu istirahatlah,” kataku.
Dia sedang menerima telepon dari Pak Ari saat aku merapikan selimutnya. Pak Ari yang khawatir sepertinya mengatakan akan segera datang, tetapi Aruna berhasil menenangkan.
“Kalau Bang Budi udah pulang, kita bisa video call. Gak perlu ayah jauh-jauh ke sini.” Begitu ujar Aruna.
Bang Budi, anak tetangga Pak Ari. Pak Ari dan tetangga di sekitarnya hanya menggunakan ponsel lawas sehingga Bang Budi –yang bekerja di Bandar Lampung dan hanya akan pulang selama dua hari setiap akhir bulan– menyulih profesi menjadi agen diskominfo untuk tetangga-tetangganya. Handphone-nya sudah tidak milik pribadi sebab akan dipinjam sana-sini oleh orang tua untuk menelepon anaknya yang jauh, termasuk Pak Ari.
Setelah telepon itu mati, Aruna tersenyum sendiri mengingat betapa rewel sang ayah ingin berada di sini. Lalu dia tertidur membawa senyum itu.
Menjelang berangkat tes, aku tetap berada di kamar Aruna. Duduk di lantai sambil bersandar pada sisi kasurnya, membaca buku teks untuk persiapan tes sambil sesekali memperhatikan Aruna. Sejak bolak-balik Jakarta-Tangerang di hari liburnya, dia terlihat semakin kuyu. Aku hanya bisa menghela nafas melihatnya begitu, protes pun dia anggap angin lalu. Berharap apapun urusan yang tidak pernah dia ceritakan itu segera selesai.
-oOo-
Pukul dua belas siang, aku keluar dari ruangan tes dengan kesal. Selain soal-soal tes itu tidak relevan dengan posisi yang aku lamar, aku juga harus bersaing dengan teman-teman dan beberapa senior.
Yang paling mengejutkan, aku bertemu Tyas. Kami dengan sengaja duduk bersebelahan lalu saling melempar pandangan apa-apaan ini ketika membaca soal pada layar komputer. Lalu terkikik.
“That was a total mind-bender!” Seloroh Tyas saat baru saja keluar dari ruangan.
Kami berjalan bersama ke parkiran. Sebelum pulang dia mengajakku makan siang. Aku menolak dengan mengatakan harus segera kembali karena Aruna sedang sakit. Tyas terkejut saat aku bercerita mengenai kondisi Aruna dan memutuskan ikut kembali bersamaku untuk menjenguk. Kami mampir di sebuah warteg, membungkus tiga nasi untuk makan siang. Aku bersama Tyas melaju dengan mobil merahnya menuju kost. Nyaris tidak ada perbincangan selama perjalanan selain membahas rencana ke depan dengan candaan. Itu juga hanya sebentar saat berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah. Tyas konsentrasi menyetir, aku menatap keluar jendela. Untuk pertama kali, aku benci memiliki photographic memory. Meskipun dilihat dengan durasi singkat, aku masih mengingat jelas tubuh bagian atas Aruna yang hanya ditutup bra merah dengan renda tipis menggoda dan menerawang pada sisi kiri dan kanan. Dengan pakaian lengkap, dia tampil cantik menggemaskan. Semuanya berubah hanya karena dia melepas selapis, membuatnya terlihat indah menggoda. Sialnya lagi, saat ini aku tersenyum. Gila!
You know she makes my life complete.
And you know I told you so.
She's the one, she's the one, she's the one.
Aku bersenandung dalam hati mengikuti lirik lagu She’s The One dari Ramones yang sedang diputar di radio.
Mengatakan tidak bermaksud mesum, kini aku malu sendiri mengetahui aku tidak bisa menampik pikiran seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani.
Aruna tampak senang Tyas datang. Wajahnya tidak pucat lagi, rona pipinya muncul kembali. Dia sudah berganti pakaian dan sepertinya sudah mandi. Wangi khasnya menguar dari pori-pori. Kami makan bersama. Setelah itu, aku meninggalkan mereka untuk menjemput motor di rumah sakit dan sepertinya akan langsung ke studio. Kakak Fahmi meminta bantuanku menjadi fotografer pendamping prewedding. Tyas mengatakan dia tidak ada agenda lagi dan bisa menemani Aruna hingga aku kembali.
“Gak perlu sampai begitu, Yas. Aku udah gak apa-apa,” tolak Aruna dengan sopan. Jelas sekali dia tampak tidak enak menerima banyak kebaikan.
“Gak apa-apa, Mbak. Dulu Mbak sedia terus buat mama. Sekarang gantian, dong!” jawab Tyas cepat dengan wajah cerianya.
Aku pergi dengan perasaan ringan. Namun tidak sebagaimana ringannya perasaanku saat pergi, justru saat kembali aku merasa kacau balau sepanjang perjalanan. Tiga jam setelah berkutat dengan kamera dan calon pengantin yang banyak menuntut, manja dan rewel, Tyas menelepon mengabarkan dia memutuskan kembali karena Aruna kedatangan tamu.
“Ibu-ibu sama anaknya kayaknya, Kak.” Jawab Tyas saat aku tanya siapa.
“Anak kecil?”
“Bukan. Seumuran kita kayaknya, malah lebih. Cowok.” Jelas Tyas lagi.
Aku menutup telepon, kembali bekerja walau pikiranku kini disesaki tanya-jawab yang aku buat sendiri.
Bu Sarah? Bu Hafsari? Teman perawatnya? Laki-laki? Si Culun? Oh! Bisa jadi, sih. Si Culun dan seorang perawat senior.
Aku meninggalkan studio foto ketika langit masih berwarna jingga, dan saat sampai di kost, langit sudah lebih pekat. Aruna tidak mengangkat telepon. Pintu kamarnya terkunci dan tidak ada tanda-tanda seseorang berada di dalam. Aku benar-benar khawatir sebab dia pergi tanpa memberi kabar dan dalam kondisi yang belum baik benar. Aku tidak konsentrasi melanjutkan pekerjaan. Kubiarkan komputer menyala dengan aplikasi editing terbuka, lantas aku mondar-mandir di depan jendela, mengintip tiap kali mendengar kendaraan masuk ke pekarangan kost. Hingga kendaraan ketiga, termasuk taksi online yang hanya berhenti pada gerbang saja, yang turun bukan Aruna. Kendaraan keempat, sebuah mobil jenis crossover masuk dengan ban berdecit pada batu paving, Aruna turun dari kursi penumpang depan mobil putih itu. Seorang pria yang turun dari sisi pengemudi segera menghampirinya. Darahku berdesir seketika. Aku segera turun dengan langkah besar. Kami bertemu saat Aruna dan pria itu baru akan menaiki anak tangga.
Aruna terperangah dan mendongak melihatku.
“Kamu dari mana aja?” tanyaku segera sambil memegang bahunya.
“A-aku habis makan malam, Gam.” Aruna menjawab dengan terbata-bata.
“Hah?” Entah kenapa aku merasa kecewa mendengar jawabannya. Mungkin karena dia abai pada kondisinya yang kurang baik mungkin juga dia abai pada perasaanku.
“Maaf, Gam. Aku gak bilang.”
“Mas? Naik dulu aja.” Kata pria berkacamata, berambut klimis, kemeja biru muda rapi dimasukkan ke dalam celana kain hitam.
“Kamu bisa? Mau aku gendong lagi?” tanyaku memastikan kesanggupan Aruna.
“Bisa. Bisa, Gam,” ujarnya sambil menggenggam tanganku.
Kami melangkah pelan mengikuti Aruna. Pria klimis bergaya sok intelektual ini mengikuti di belakang.
“Gam? Ini Andre,” Aruna menoleh kebelakang, “Ndre. Ini Gamma.”
“Ya." Jawab kami serempak tanpa melihat satu sama lain.
“Andre ini keponakan Bu Sarah, yang aku pernah liatin fot–”
“Ya. Aku udah ingat,” aku menyela cepat. Tidak ingin membahas si Andre ini.
Aku dan Aruna berjalan sambil bergandengan. Pria sok intelektual ini mengikuti di belakang. Kami sampai di pintu kamar Aruna tanpa satu suara.
“Kapan kamu mau, kabarin aku. Kita bisa pergi ke sana makan kambing lagi,” ujar pria ini sambil memperbaiki posisi kacamata model vintage –aku taksir mungkin berbahan titanium– yang tampak berkilau pada wajahnya. Kalimatnya itu membuatku iri sekaligus sedih, seolah aku tidak mampu membawa Aruna makan di tempat entah mana yang dia dan Aruna datangi. Aruna belum membuka pintu. Dia seperti menunggu Andre ini pergi.
“Yok, Mas. Balik dulu.” Katanya sambil menepuk bahuku sebelum pergi.
Aruna memutar anak kunci saat Andre sudah tidak tampak lagi. Dia masuk dan aku menyusul.
“Obat udah?” tanyaku saat Aruna berdiri di sebalik pintu, membuka dan menggantung jaket jeans.
“Udah, tadi aku bawa.”
“Salepnya udah?”
“Nih, mau. Tapi aku mau cuci muka, gosok gigi juga.” Dia pergi ke kamar mandi. Aku seperti tadi pagi, menyiapkan minum hangat, memastikan selimutnya tidak lembab. Keluar kamar mandi, Aruna duduk di pinggir kasur, melirikku dengan ragu, jelas terlihat pada matanya itu rasa bersalah. Aku diam saja, berdiri bertolak pinggang melihatnya, “Hape kamu mana?”
Aruna menoleh pelan kepada tas selempangnya yang tergeletak di meja, “Aku baru aja mau cas hape pas Bu Sarah sama Andre datang, Gam.”
Aku hanya bisa menarik napas sedalam-dalamnya untuk menghambat kesal yang datang seperti ratusan anak panah dilontarkan.
“Andre itu cu–"
“Oles salep kamu.” Aku yang malas membahas Andre, Bu Sarah dan makan malam mewahnya hanya bisa menyanggah. Tidak ingin menambah serangan anak panah. Mungkin juga aku hanya ingin memagari kembali harga diriku yang sudah dibobol.
Aruna tampak gelisah. Saking gelisahnya salep itu sempat terjatuh dari genggamannya. Aku menegakkan bahunya yang sedang merungkuk mengambil salep yang tergeletak di lantai. Aku bersimpuh di depannya dan salep itu kini berada di tanganku, memencetnya dan membuat tiga titik krim pada jari seperti yang dia lakukan tadi pagi. Tanganku menyelinap masuk dari celah kaosnya, meraba-raba merasakan lukanya. Kulit pada bagian itu terasa sedikit panas dan kasar. Tangan kananku masuk kedalam kaos merah mudanya, mengolesi obat, sedangkan tangan kiriku menahan kaos itu agar tidak ikut terangkat. Kami berbalas tatapan. Dia menatapku sendu, aku menatapnya tajam. “Kamu kalau mau makan sesuatu, bisa ngomong aja ke aku. Aku usahain, aku cariin sampai ketemu,” kataku.
“Aku gak minta, Gam. Itu semua ide Bu Sarah. Tadi kami makan bareng.”
“Kalau kamu gak mau makanan warteg, bilang. Kalau mau kari kambing, mau pasta, sushi, nasi biryani, bilang. Apapun, bilang.”
“Gam…,” Nada membujuk itu lagi. Tapi aku yang sudah merasa dilangkahi pria lain kini tidak termakan bujuk dan rayu lagi.
“Jangan buat aku terlihat gak ada apa-apanya, Runa.”
“Gam! Warteg yang … bukan. Semua makanan yang kamu bawa. Semuanya. Semua yang kita makan sama-sama seribu kali lebih enak dibandingkan makanan lain yang pernah aku makan dari aku kecil sampai sekarang!”
Aruna terlihat emosional. Dia menunduk segera setelah menyadari nada suaranya tinggi. Aku mendongak melihatnya. Dari raut wajahnya, dia seperti ingin menangis. Aku selesaikan tugas mengolesi obat itu dengan baik. Mengangkat kaki Aruna yang menjuntai menginjak lantai untuk naik ke kasur, menyelimutinya, mengecup pipinya. Mengisi lagi segelas air hangat dan meletakkan pada mejanya, menyalakan lampu tidur serta memposisikan kipas agar tidak mengenai tubuhnya secara langsung.
“Kamu istirahat.” Kataku padanya yang kini berbaring sambil memeluk bantal strawberry.
“Kemarilah …,” Aruna mengulurkan tangannya. Wajah gundah itu dia paksakan tersenyum. Aku sungguh ingin keluar saja, merokok melepas kekesalan. Tapi matanya itu benar-benar lautan. Riaknya memabukkan, ombaknya menenggelamkan. Aku yang cenderung tidak lihai berenang tentu saja hanyut. Aku lemah dan aku telah kalah.
“Gam?” Aruna menepuk-nepuk sisi kasur yang senggang.
Aku menghampirinya. Masuk kedalam selimut dan memeluknya. Dia membuat dirinya nyaman dengan menyandarkan kepalanya pada dadaku.
“Maafin aku, ya?” ujarnya dengan mulut yang menempel pada kaosku.
(Kamu harus tahu kamu minta maaf untuk apa.) “Ya.”
“Kamu udah gak marah, kan?”
(Masih) “Enggak.”
Dia mendongak, “Pembohong yang buruk,” katanya sambil menyentuh ujung hidungku.
Aku tersenyum enggan, “Kamu bisa membaca ekspresiku seperti gambar yang diambil dengan lensa telefoto.”
“Jangan gitu,” ucap Aruna dengan tenang, dia melingkarkan tangannya ke perutku, “kamu satu-satunya.”
“Aku tahu,” aku mengusap-usap punggung tangannya, “untuk sesaat aku merasa, yah … bagaimana juga laki-laki itu gak suka kalau wanitanya diperhatikan laki-laki lain. Saat bersamaan itu menunjukkan ketidakmampuan aku, Runa.”
“Dia bukan memperhatikan aku. Dia cuma menuruti Bu Sarah.” Timpal Aruna segera.
“Ya. Aku tahu, akhir-akhir ini, jadwal aku berantakan. Pagi siang malam udah gak ada batas yang jelas lagi. Kita jarang sama-sama. Sebagian besar karena aku yang serabutan. Kamu sakit malah aku tinggal buat tes dan kerja. Aku …,” aku menelan pahit yang menggumpal di tenggorokan karena menjadi emosional, “aku lagi berusaha untuk masa depan yang lebih baik … buat kita. Buat kita, Aruna.”
Aruna mendongak melihatku yang menatap langit-langit dengan cahaya lampu yang bergerak warna-warni, berusaha mencari-cari sesuatu yang bisa mengalihkan perasaan sedih ini kepada sesuatu yang menyenangkan. Walau cahaya itu sudah biasa aku lihat, namun kali ini aku berpura-pura antusias seperti saat pertama dulu menyalakannya.
Tangan Aruna yang tadi melingkari perut, kini dia gunakan untuk membuat wajahku menghadapnya, mengusap-usap alisku dengan jempolnya, “Makasih, Gam. Itu lebih baik dari pernyataan cinta manapun yang pernah aku dengar.”
“Dari laki-laki lain?”
“Dari laki-laki lain di sinetron atau di film-film roman picisan.”
Aku tertawa sesaat, lalu mencium keningnya. Perasaanku sudah jauh lebih baik. Aruna merubah posisinya telentang, menarik-narik kaos bagian dadanya agar angin masuk.
“Kenapa? Panas, ya?” aku melirik kipas yang anginnya aku atur menembak dinding, “aku sengaja biar kamu gak masuk angin.”
“Bukan, perih kena kaos,” katanya.
“Buka aja. Biar nyaman tidurnya.”
Aruna menoleh segera, lalu terkekeh, “Aku kayaknya gak ada menarik-menariknya, ya. Nyantai banget kamu nyuruh buka. Tadi pagi aku grogi setengah mati, kamu kaget aja enggak.” Dia duduk sembari membuka kaos merah mudanya.
Aku melemparkan seluruh pandangan hanya kepada punggungnya, yang putih, bersih, wangi dan dihiasi tali yang saling berkait-kaitan berwarna biru tua atau hitam? Entahlah ini gelap dan cahaya bintang berseliweran tidak mampu menunjukkan warna asli tali ini. Tangan sialan ini mengusap-usap punggungnya. Sesekali kepalaku melegitimasi perbuatan tangan ini dengan alasan: badannya yang dingin butuh usapan agar menjadi lebih hangat.

Dia kembali menghempaskan punggungnya pada kasur, membuat tanganku terhimpit dan Aruna menggeliat tidak nyaman. Aku segera menarik tangan itu. Aruna masih menggumamkan kekecewaan sebab sepertinya aku terlihat kurang tertarik pada tubuhnya, menurutnya. Andai dia tahu bahwa bayangan tubuhnya tadi pagi benar-benar merepotkanku sepanjang siang.
“Kamu tidurlah…,” ucapku sembari merapikan rambutnya. Juga merapikan degupan jantungku yang berloncatan kesana kemari.
Dia memeluk boneka strawberry menutupi wajahnya dan berbalik menghadap dinding. Aku terkekeh melihatnya meributkan hal yang seharusnya dia syukuri, mencemburui sikapku yang justru seharusnya dia banggakan.
Aku mencium punggungnya sambil berbisik, “I don’t take advantage of a weak woman who is sick. Kalau kamu udah sembuh, baru deh …!”
Aku terkikik.
“Gak tahu, ah!” sanggahnya.
Malam itu, jam masih menunjukkan pukul delapan tapi Aruna sudah lelap. Aku yang tidak terbiasa tidur cepat lantas bangkit, mengambil laptop dari kamar, melanjutkan pekerjaan dengan meminjam meja belajar Aruna. Sekitar satu jam kemudian, ponsel Aruna bergetar singkat dengan notifikasi pesan dari Bu Sarah. Aku tidak membukanya, hanya saja notifikasi itu terpampang lengkap dengan isi pesan yang mengatakan BATALKAN APAPUN YANG SUDAH KAMU RENCANAKAN. INGAT SIAPA YANG SEBENARNYA BERKORBAN. KEMBALILAH. Dahiku mengerut dan menatap Aruna yang sedang pulas. Rencana? Berkorban? Ada apa sebenarnya, Runa?
CATATAN PENULIS
Hallo! Terima kasih sudah meluangkan wkatu membaca Restart!
Komentar di bawah, ya!
Salam,
HelloHayden.
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰