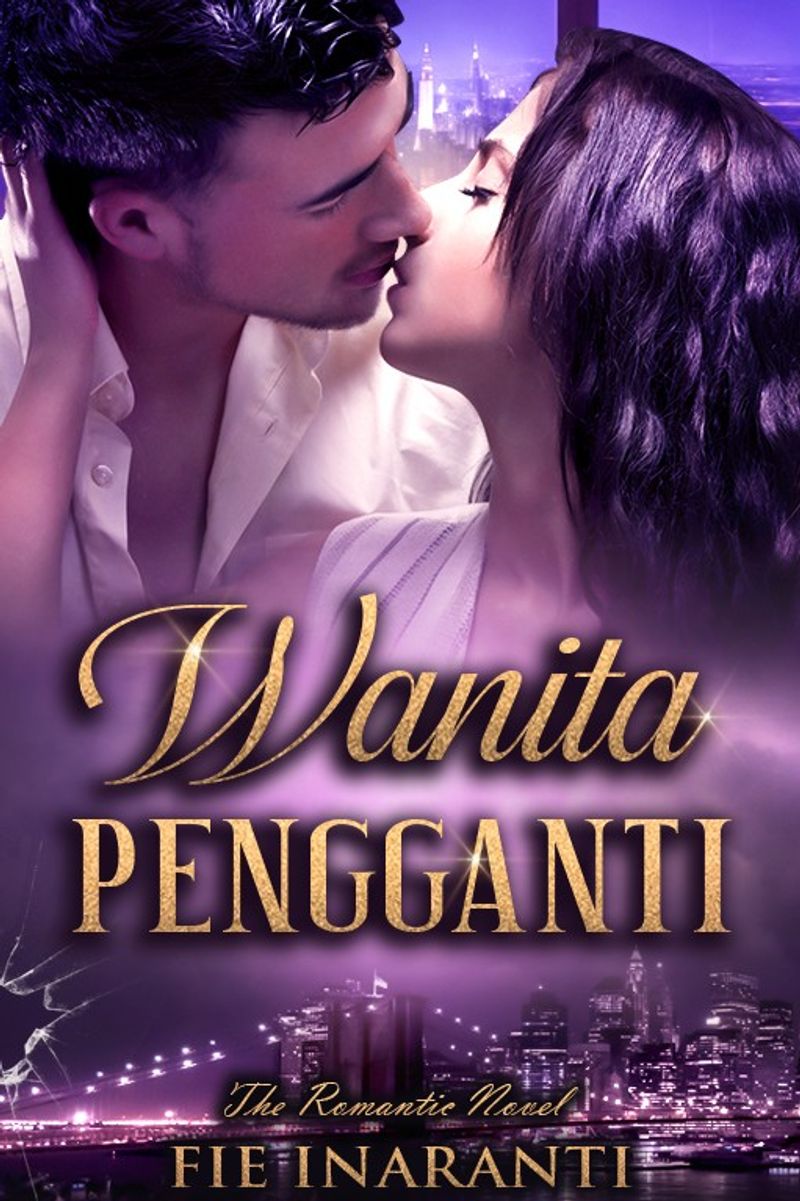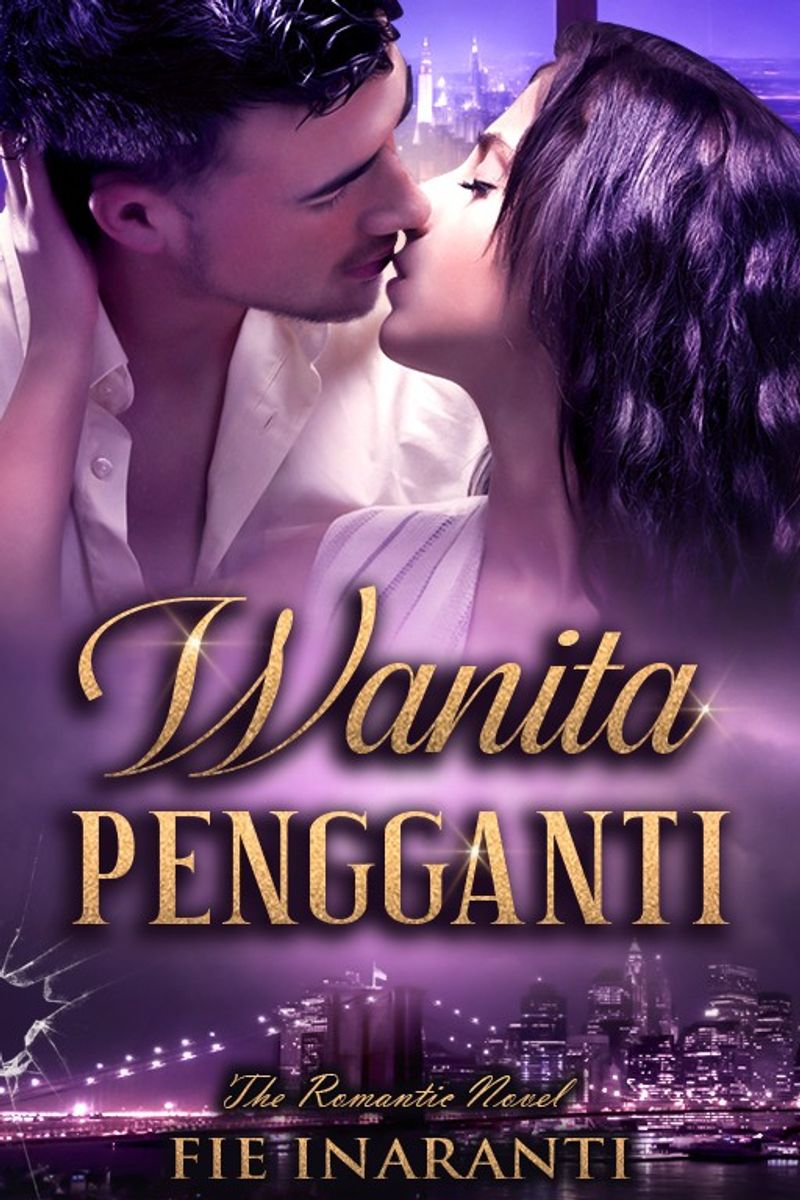
Avery Violetta, seorang dokter muda yang tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berbalik seratus delapan puluh derajat sejak kemunculan Richard Alexander di hadapannya. Lelaki itu tidak hanya mengusik ketenangan Avery, tetapi juga terus menerus menganggap Avery sebagai penebus dosa atas kematian kekasihnya.
Avery bahkan tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika Richard memaksa untuk menjadikan gadis itu sebagai pengantin wanitanya. Meski Avery tahu, tidak akan pernah ada cinta di antara mereka....
PROLOG
Wanita pengganti. Avery menarik kedua sudut bibirnya, tersenyum tipis setelah ia memalingkan wajah dari lelaki bermata tajam yang mengungkung tubuhnya dengan kedua lengan kekarnya. Tentu saja Avery tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi kenyataannya, Avery menyerah pada gairah, Membiarkan lelaki itu dengan lancang merampas keperawanannya.
Merampas? Ah, Avery tidak bisa menyebutnya demikian. Richard hanya meminta haknya sebagai seorang suami. Meski percintaan panas itu terjadi begitu saja, tanpa pernah direncanakan sebelumnya. Hubungan mereka yang sedingin salju, seketika meleleh ketika api gairah membakar keduanya. Dan sialnya, Avery menikmatinya.
Meski setelah itu, Avery menyesalinya. Percintaan apa? Omong kosong! Richard hanya mencintai mantan tunangannya. Bahkan mungkin ketika Richard menghunjamkan tubuhnya jauh ke dalam diri Avery, lelaki itu melihat Avery sebagai wanita lain. Seperti biasa, Avery hanya menjadi bayangan. Wanita pengganti yang sialnya tidak bisa menggantikan posisi wanita yang dicintai Richard.
Pernikahan itu hanyalah sebuah omong kosong. Sebuah penebus dosa yang sangat tidak adil bagi Avery. Avery memiliki dunianya sendiri, memiliki lelaki pilihannya sendiri. Lalu, Richard dengan lancang merampas semuanya dan menjebak Avery ke dalam pernikahan yang menjijikkan itu.
“Jika kau tidak menyukainya, kau boleh menganggap malam ini tidak pernah terjadi,” ucap Richard dengan dingin. Jemari kokohnya mengusap setitik air mata yang menitik di pipi Avery.
Avery hanya terdiam. Brengsek! Ucapan Richard serupa sebilah pisau yang menghunjam ke dada Avery. Dengan mudahnya kalimat itu keluar dari bibir Richard, bahkan hanya selang beberapa detik setelah ia meledakkan cairan panasnya di dalam tubuh Avery. Seolah kenikmatan itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Richard.
Lelaki itu menghela napas kasar, lalu menggulingkan badannya ke kiri. Berbaring telentang dan matanya menatap langit-langit kamar. “Aku tidak memaksamu, kau membiarkan ini terjadi. Kau juga menginginkannya.”
Avery menarik selimut hingga menutupi bahunya, tubuhnya bergerak untuk membelakangi Richard. Ia meringis perlahan, menahan perih di bawah sana. Tidak, ia sama sekali tidak ingin menanggapi ucapan Richard. Bukan karena ia masih terbawa oleh euforia ketika beberapa saat lalu mereka mendapatkan puncak kenikmatan dalam waktu yang sama.
Menyesalinya? Tentu saja. Seharusnya Avery menyerahkan keperawanannya pada lelaki yang dicintainya, bukan orang asing yang tiba-tiba saja hadir ke dalam kehidupannya. Avery membencinya, tetapi otaknya justru merekam dengan jelas setiap detik percintaan panas itu. Jantung sialannya berdetak cepat, dan seluruh sel-sel di dalam tubuhnya menikmati setiap sentuhan dan hentakan benda keras yang menerobos masuk menembus inti tubuhnya.
Tolong, Avery ingin lepas dari kegilaan ini. Avery ingin melarikan diri dari pernikahan ini. Avery ingin melepaskan diri dari lelaki brengsek yang sudah menjadikannya sebagai bayangan dari wanita lain. Ini terlalu menyakitkan!
“Oh, shit!” Richard menyugar rambutnya, lalu beringsut turun dari atas ranjang dan kembali memakai pakaiannya. “Aku sama sekali tidak menikmatinya, itu jika kau ingin meminta penilaianku.”
Avery menenggelamkan kepalanya di bawah bantal. Cukup, ia tidak ingin mendengar apa pun lagi.
***
PART 1
LUKA YANG BELUM TENGGELAM
***
Beberapa luka tak ikut tenggelam bersama bangkai pesawat. Ia justru mengapung, menepi, dan tinggal di dada yang ditinggal pergi
***
Langit masih kelabu saat angin laut menggulung ombak ke pantai, membawa aroma asin yang menyentuh wajah. Di sana, puluhan pasang mata memandang ke arah laut yang tak tahu belas kasihan. Tim penyelamat gabungan berlarian dengan cepat, melangkah sigap di atas pasir, membawa peralatan evakuasi. Helikopter berputar-putar di udara, menciptakan riuh yang menambah gemuruh di dalam dada setiap orang yang menunggu.
Pesawat Nebula Air dengan nomor penerbangan NAX-702 mengalami kecelakaan tragis pada perjalanannya menuju London. Air Traffic Control (ATC) menyatakan pesawat lost contact pada koordinat 07 derajat 47 menit 20 detik S. 107 derajat, pada ketinggian 2.500 meter. Pesawat yang mengangkut 170 penumpang dan 12 kru penerbangan itu jatuh di perairan laut.
Suara sirine ambulans menggema di udara. Di bawah tenda darurat yang didirikan di tepi pantai, tubuh-tubuh mulai berdatangan, basah, penuh luka, beberapa di antaranya tidak bernyawa.
Avery mengenakan jas hujan tipis yang diberikan oleh tim SAR. Rambut hitam wanita itu nampak kusut, tangannya bergetar namun tetap sigap memeriksa denyut nadi dan pupil para korban yang baru dievakuasi. Tangannya berlumuran darah, tapi ia tidak memedulikannya. Ia menekan dada korban yang tak lagi bernapas, memberi instruksi cepat pada petugas medis lain, lalu berpindah ke korban berikutnya.
“Dia masih hidup!” serunya. “Cepat ambil selimut termal!”
Avery mencoba fokus. Setiap tubuh yang datang selalu membuat napasnya tercekat. Tangannya sibuk menyelamatkan nyawa, tapi matanya berkali-kali mencuri pandang ke arah laut, ke tempat ayahnya menghilang. Ia bertahan dengan satu keyakinan, selagi ayahnya belum ditemukan, berarti masih ada harapan ayahnya akan kembali dengan selamat.
Namun, harapannya semakin pupus ketika seorang petugas muncul dari sisi dermaga dengan langkah cepat. Lelaki setengah baya itu membawa sebuah topi pilot berwarna biru tua berlambang Nebula Air. Topi itu basah, penuh pasir dan lumpur laut, tetapi masih utuh.
Avery menoleh dan matanya terpaku. Ia mengenal topi itu. Benang robek di tepi kanan, serta inisial I.R yang pernah Avery tuliskan di bagian dalam topi.
Refleks Avery melangkah mendekat, seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Tangannya terangkat, ingin menyentuh, mengambil dan memeluk barang terakhir yang bisa menghubungkannya dengan sang ayah.
Tapi, seorang pria dari otoritas penerbangan menahan pergelangan tangan Avery. “Maaf, Nona. Ini termasuk barang bukti.”
Suara Avery tercekat. “Tapi itu … milik ayah saya.”
“Justru karena ini milik Kapten Isaac,” jawab pria itu dingin. “Kami menduga penyebab kecelakaan ada pada kesalahan prosedur di dalam kokpit. Segala benda yang ditemukan di sekitar area kendali pesawat harus diamankan.”
Avery mematung. Topi itu dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam kotak bukti, bersama serpihan logam kokpit yang sudah lebih dulu ditemukan. Avery mengerjap. Cairan bening menderas dari matanya, menangis tanpa suara. Dadanya terasa sesak, dan ia mulai merasakan hampa di dalam hidupnya.
***
Richard berdiri tak jauh dari garis pantai. Jas hitamnya basah oleh embun dan angin laut yang menusuk tulang. Sorot matanya kosong, tapi waspada. Setiap kali sebuah kantong jenazah diturunkan dari perahu tim SAR, jantungnya berdetak cepat. Sampai detik ini, ia masih berharap tunangannya yang turut menjadi korban kecelakaan pesawat itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat.
Lelaki bertubuh tinggi tegap itu menatap lautan luas, berharap mendapatkan jawaban. Tapi, ia hanya menemukan kabut. Waktu terasa berjalan lambat, menyiksanya diam-diam. Lalu, pandangannya terpaku pada seorang wanita di tenda medis darurat.
Rambut wanita itu nampak basah dan kusut, wajahnya pucat, tetapi tangannya cekatan. Ia jelas bukan bagian dari tim SAR. Tapi wanita itu tetap membantu memberikan pertolongan medis. Membalut luka, memeriksa nadi, bahkan menangis diam-diam saat mengusap wajah seorang korban yang tak tertolong.
Richard menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu yang asing dan tak terjelaskan. Wanita itu terlihat kuat, tapi juga rapuh di saat bersamaan. Seolah sedang menahan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ia tunjukkan.
Dan kali ini, wanita itu berdiri mematung di depan sebuah topi pilot yang baru ditemukan. Sorot matanya pecah, seperti cermin yang retak dalam diam. Dan entah kenapa, ada sesuatu di dalam dada Richard yang juga ikut retak.
Richard tidak tahu siapa wanita itu. Hanya seseorang di antara sekian banyak orang yang berduka. Tapi anehnya, ia tak bisa berhenti memperhatikan sosok yang menarik itu.
“Tuan, sampai saat ini Nona Lily belum ditemukan. Hari sudah semakin sore, Anda ingin pulang sekarang atau menunggu sampai malam?” Seorang lelaki muda yang merupakan asisten pribadi Richard, menghampirinya.
Richard mengangguk dan menghela napas kasar. Sesaat kemudian, dia berkata, “Ethan, kau tahu siapa wanita itu? Yang di tenda medis, memakai jas hujan tipis, berambut hitam panjang.”
“Maksud Anda Dokter Avery?”
“Dokter Avery?”
“Dokter Avery Violetta, putri Kapten Isaac Ravees, pilot yang mengemudikan pesawat ini. Ah ya, Tuan. Menurut desas-desus yang saya dengar, kecelakaan pesawat disebabkan oleh kelalaian pilot. Kita tunggu investigasi selanjutnya, Tuan.”
Richard mengepalkan kedua tangan. Rahangnya mengeras, matanya kembali terpaku pada wanita itu. Dokter Avery Violetta. “Ethan, cari tahu semua tentang wanita itu.”
“Maksud Anda Dokter Avery?”
“Cari tahu semua tentangnya, asal-usulnya, bahkan sampai hal terkecil dalam hidupnya.” Nada suara Richard terdengar begitu tajam dan dingin.
***
Avery sedang menyalin data pasien selamat saat suara langkah berat menghentikan gerak tangannya. Ia menoleh dan mendapati seorang lelaki berdiri di ambang tenda. Tubuh tegapnya terbalut kemeja putih yang dilapisi jas hitam, wajahnya berahang tegas dengan bulu-bulu halus tercukur rapi, dan mata tajamnya menyimpan sesuatu yang membuat Avery tiba-tiba sulit bernapas. Kemarahan.
“Jadi kau putri Kapten Isaac.” Nada suaranya tenang, tapi dingin serupa balok es dengan ujung yang begitu runcing. Siap menghunjam dan memberikan luka pada siapa pun yang berada di dekatnya.
Avery beranjak dari tempat duduknya, mencoba tenang membalas tatapan lelaki di hadapannya. “Maaf?”
Richard melangkah masuk dan menghampiri Avery. “Kapten Isaac membawa pesawat itu ke dasar laut. Dan kau anaknya, berdiri di sini seolah kau juga salah satu korban.”
“Saya tidak menganggap diri saya sebagai korban. Saya hanya kehilangan ayah saya.”
“Aku kehilangan tunanganku. Kehilangan duniaku. Kehilangan masa depanku. Kami sudah merencanakan pernikahan bulan depan.” Richard mengepalkan kedua tangannya erat-erat. “Sekarang yang tersisa hanya nama di daftar korban hilang.”
Avery menunduk. Bukankah mereka memiliki luka yang sama? Luka yang menganga lebar atas kehilangan orang yang mereka sayangi.
“Saya turut berduka cita. Semoga tunangan Anda bisa segera ditemukan. Saya benar-benar menyesal.”
Richard mendekat selangkah, suaranya mengeras. “Jangan katakan kau menyesal. Kalimat itu tidak ada artinya jika datang dari putri orang yang menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi.”
“Kita belum tahu penyebab pastinya. Penyelidikan masih—“
“Kalau terbukti ayahmu lalai, dan tunanganku tidak ditemukan dalam keadaan selamat, maka aku bersumpah, aku pastikan hidupmu akan hancur.”
Avery terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam, tapi ia menahan air matanya. Ia masih berusaha memberanikan diri menatap mata lelaki di hadapannya. Mata tajam yang menyala penuh kebencian.
Mulut Avery setengah terbuka, mencoba menyusun kata-kata. “Dendam tidak akan membawa siapa pun kembali.”
“Tapi dendam … akan membuatku tetap hidup.” Lalu, tubuh tinggi tegap itu berbalik meninggalkan Avery.
Tenda itu terasa hampa setelah tubuh Richard menghilang di balik tirai. Suara debur ombak masih terdengar di kejauhan, seolah laut pun belum selesai menceritakan tragedinya. Di luar, lampu-lampu darurat berpendar redup, memantulkan cahaya kuning pucat ke wajah Avery yang masih membeku.
Wanita itu tertunduk. Tangannya terkepal. Bukan karena marah, tapi karena ia sedang mencoba bertahan dari tatapan lelaki asing itu beberapa saat lalu. Tatapan yang menelanjangi luka paling dalam yang bahkan belum sempat ia urai sendiri.
Dengan tangan gemetar, Avery menyeka air mata yang menetes di pipi. Untuk pertama kalinya, Avery merasa bahwa ia sedang dihukum atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Dan itu … sangat menyakitkan.
***
PART 2
DALAM DIAM YANG MENGUTUK
***
Jika aku adalah hukuman untuknya, maka hidupku adalah penjara. Dan setiap tatapan dari matanya adalah jeruji yang tak bisa kupatahkan
***
Richard melangkah gontai menaiki anak tangga menuju kamar. Langkahnya terhenti ketika sang kakek memanggilnya.
“Jadi bagaimana dengan pernikahanmu?” Tuan Liam Alexander, menatap cucunya dengan penuh harap.
“Kakek masih bisa berbicara pernikahan sedangkan calon istriku belum ditemukan?” protes Richard.
“Jika dia memang meninggal apa seumur hidup kau akan hidup melajang?”
“Kakek, berikan rasa empatimu sedikit saja.”
“Aku tidak peduli. Dengan tunanganmu atau bukan, aku ingin melihat pernikahanmu bulan depan. Jika tidak, kau tahu konsekuensinya.”
“Kakek! Untuk kali ini tolong mengertilah. Jangan membahas tentang pernikahan ini lagi. Setidaknya sampai Lily ditemukan.”
Tuan Liam melambaikan tangannya di depan wajah. “Usiaku semakin tua, aku ingin menyaksikan istrimu melahirkan pewaris untuk keluarga kita. Apa kau tega memupuskan harapan kakekmu ini hanya karena seorang wanita dan cinta? Cinta omong kosong. Kau bisa mendapatkan cinta dari wanita mana pun yang akan menjadi istrimu.”
“Cinta tidak sesederhana itu, Opa.”
“Pernikahan bulan depan, atau tidak sama sekali. Kalau perlu aku yang akan mencarikan calon pengantin untukmu.”
Titik. Kalimat Tuan Liam serupa titah yang tidak mungkin dibantah lagi. Lelaki itu bahkan dengan santai melangkah pergi tanpa perasaan bersalah karena sudah mengatakan hal itu pada cucu tunggalnya.
Richard mengepalkan kedua tangan. Marah? Tentu saja. Akan tetapi Richard tidak bisa melakukan apa pun kecuali pasrah. Masih ada kesempatan. Richard harap Lily bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat, meski kemungkinan itu sangatlah kecil. Tapi, tidak ada salahnya berharap, bukankah keajaiban bisa saja datang sewaktu-waktu?
***
Dua minggu setelah kecelakaan tragis pesawat Nebula Air, keluarga dan kerabat korban menggelar acara doa bersama dan tabur bunga. Sebuah kapal Angkatan Laut membawa ratusan kerabat yang berduka itu ke tengah lautan, lokasi di mana pesawat Nebula Air mengalami turbulensi dan berakhir jatuh di sana.
Di atas geladak kapal, lautan terbentang luas seolah tak merasa bersalah telah menyimpan begitu banyak nyawa di dasarnya. Satu per satu keluarga korban berdiri memeluk potret orang-orang yang mereka cintai. Kelopak bunga-bunga putih dilemparkan ke permukaan air, mengapung sebentar, sebelum akhirnya hanyut dan hilang, seperti mereka yang tak pernah kembali.
Richard mengawasi buket mawar yang mengapung di permukaan air. Bunga terakhir sebagai lambang cintanya untuk sang kekasih, cinta yang mungkin tidak akan pernah berakhir. Lily boleh saja pergi, tetapi bukan berarti cinta di antara mereka lenyap begitu saja. Ah, bahkan sampai saat ini Richard masih menganggap Lily tetap hidup. Richard tidak akan pernah mempercayai kematian kekasihnya, sebelum ia melihat jasad wanita itu di hadapannya.
Richard mengalihkan pandangannya pada geladak kapal paling ujung. Sejak tadi, ia mengawasi wanita dengan dress hitam serta selendang warna senada yang terpakai di kepalanya. Tubuh wanita itu nampak tegak namun wajahnya terlihat rapuh. Ia menggenggam setangkai krisan putih. Tangannya sedikit gemetar, tetapi tidak lagi menangis. Barangkali air matanya sudah habis. Mata sayunya terus memandang laut, berharap laut itu bersedia mengembalikan ayahnya.
Dalam satu gerakan, Avery melemparkan bunga krisan itu ke lautan. Hadiah terakhir untuk sang ayah. Wanita itu menarik napas panjang, mengisi pasokan oksigen untuk dadanya yang terasa begitu sesak. Lalu, tubuh langsing itu berbalik dan meninggalkan dek kapal.
Avery melangkah perlahan, menelusuri lorong kapal menuju kabin. Ia butuh ruang untuk sendiri. Tapi ia lupa, bahwa diam-diam seseorang terus mengawasinya dan mengikutinya.
Richard mendorong pintu kabin sebelum Avery sempat menguncinya. Wanita itu menoleh terkejut, tapi tidak sempat bicara. Pintu ditutup oleh Richard dengan kasar, dan suara benturannya memecah keheningan di antara mereka.
“Apa yang kau lakukan di sini?” Avery tentu saja masih mengingat siapa lelaki itu, orang asing yang bahkan Avery tidak tahu siapa namanya.
“Aku belum selesai bicara padamu.” Seperti biasa, suara Richard terdengar dingin dan terkesan memojokkan.
“Tolonglah, Tuan. Aku tidak ingin bertengkar di sini.”
“Sayangnya, aku datang ke sini bukan untuk berdamai.”
Richard melangkah mendekat. Avery mundur setapak, tapi tidak ada ruang untuk lari. Kabin itu terlalu sempit dengan dinding kayu memantulkan gema napas mereka yang berat.
“Kau masih bisa berdiri tegak, Nona. Sementara tunanganku bahkan tak sempat diberi pemakaman yang layak.”
“Aku juga kehilangan ayahku, Tuan.”
“Jangan samakan rasa kehilanganmu dengan milikku,” desis Richard. “Aku kehilangan masa depan, sementara kau tidak.”
“Lalu kenapa kau datang ke sini? Untuk menyalahkanku lagi?”
Richard kembali melangkah semakin dekat. Ia menatap Avery dalam-dalam. Suaranya rendah tetapi mengancam. “Karena aku tidak akan berhenti sampai kau membayar semuanya. Kau akan membayar kesalahan itu dengan seluruh hidupmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Ingat itu baik-baik, Nona Avery Violetta!”
Avery memejamkan mata. Bukan karena takut, melainkan karena hatinya terlanjur remuk oleh kata-kata lelaki di hadapannya.
“Aku bahkan tidak mengenal siapa dirimu, Tuan,” lirih Avery, nyaris tidak terdengar.
“Bagiku kau adalah hukuman yang dipilihkan semesta untukku.”
Hening sesaat. Avery urung membuka mulutnya ketika tiba-tiba kapal berguncang. Ombak menghantam sisi lambung kapal dengan keras. Kabin bergoyang. Rak kayu kecil di sudut kamar bergemeretak, dan dalam sepersekian detik tubuh Avery limbung, kehilangan keseimbangan.
“Ah!” serunya pelan. Tubuhnya terhuyung ke depan, tak sempat mencari pegangan, dan …
Bruk!
Avery menabrak dada bidang Richard. Refleks, lengan kekar Richard meraih Avery ke dalam dekapannya, menahan agar gadis itu tidak jatuh sepenuhnya. Jemarinya mencengkeram pinggang Avery dengan canggung. Dan meski hanya sedetik, tubuh mereka saling menyesuaikan.
Seketika napas Avery tertahan. Tubuh mereka begitu dekat sekarang, bahkan terlalu dekat untuk dua orang asing yang saling membenci. Wajah mereka hanya terpisah beberapa jengkal. Napas Avery menabrak dagu Richard. Napas Richard yang dingin dan berat, menguar di pelipis Avery.
Ada jeda. Sebuah ruang tipis di mana luka dan marah saling menatap, saling menyentuh. Tapi hanya sesaat.
Lalu Richard membuka mulut. Suaranya serak, rendah, dan tajam seperti pisau. “Bahkan ketika dunia membuatmu jatuh ke pelukanku, aku tetap ingin menjatuhkanmu lebih dalam lagi.”
Avery menunduk, menahan gemetar yang bukan hanya karena ombak, tapi juga karena luka baru yang digoreskan pria itu sekali lagi.
“Dengar baik-baik, Nona Avery Violetta. Jangan pernah berharap ada tangan yang akan menyelamatkanmu. Terutama tanganku.” Dan dengan satu dorongan halus namun dingin, Richard melepaskan pegangan itu.
Avery tak mampu berkata-kata. Matanya hanya menatap lantai kayu yang bergoyang pelan, seperti dadanya yang sedang dipukul-pukul dari dalam.
Richard menatapnya sekali lagi. Tatapan terakhir sebelum benar-benar pergi. Tatapan yang bukan hanya tajam, tapi penuh tuduhan, penuh luka, penuh kemarahan yang seolah tak akan pernah ada habisnya. Seolah Avery adalah luka hidup yang ingin ia cabik, bukan yang ingin ia sembuhkan.
Tanpa sepatah kata, Richard membuka pintu kabin dan melangkah keluar. Hembusan angin laut segera menerobos masuk, membawa serta bau asin, dingin, dan kesepian yang menggigit. Suara derit engsel pintu yang perlahan menutup terdengar seperti tanda akhir dari sebuah penghakiman. Lembut, tapi tajam. Seperti tatapan terakhir yang Richard lemparkan padanya, penuh kemarahan, penuh luka yang belum terbalas.
Dan kini, Avery sendirian. Sunyi menyergap kabin kecil itu. Tak ada suara kecuali degup jantungnya sendiri, berdentam pelan tapi berat. Ia berdiri kaku, tubuhnya baru saja dibekukan oleh semua ancaman Richard. Ancaman yang bukan sekadar kata, melainkan janji untuk menghancurkan. Janji yang menggantung seperti pisau di atas kepala.
Avery menarik napas dalam-dalam, rasanya udara tak pernah sesesak ini. Semua terlalu sempit untuk menampung ketakutan dan pertanyaan-pertanyaan yang terus berdatangan tanpa diundang.
Apa yang akan terjadi setelah ini?
Apakah lelaki itu benar-benar akan menghancurkan hidupnya?
Bagaimana bisa seseorang membenci begitu dalam sampai matanya tak menyisakan seberkas keraguan untuk melukai?
Avery menjatuhkan tubuhnya ke kursi kayu kecil di pojok ruangan. Punggungnya bersandar lemas, lututnya gemetar. Ia menatap tangannya sendiri yang dingin dan pucat. Rasanya, ia tak mengenali siapa dirinya lagi.
Avery menggigit bibirnya, menahan isakan yang akhirnya pecah perlahan. Satu tetes mata jatuh, lalu disusul yang lain. Menyakitkan. Sungguh, ini sangat menyakitkan.
***
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰