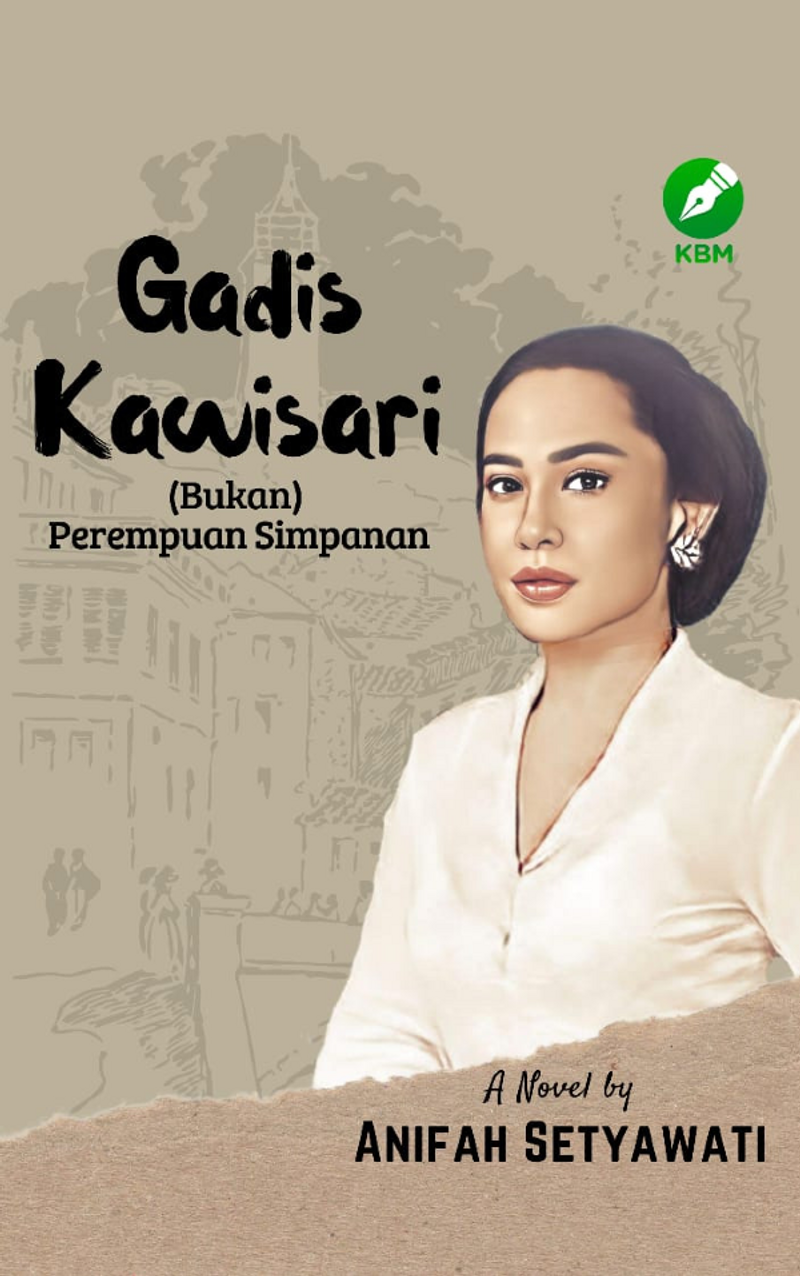Link E Book:
https://books.google.co.id/books/about?id=zeNyEAAAQBAJ&redir_esc=y
Link pemesanan Novel Cetak:
Tersedia Voucher Diskon 15K untuk pembelian full part Gadis Kawisari. Kode Voucher MARCH15
***
Surtinah, kuli kebun kopi di perkebunan Tretes yang terletak di lereng Gunung Kawi dijual bapaknya kepada kepala perkebunan demi jabatan mandor besar.
Surtinah harus meninggalkan desanya dan menjalani peran baru sebagai nyai atau gundik bagi Willem van Rijkaard.
Bagaimana Surtinah menjalani kehidupannya sebagai nyai?
Mampukah ia keluar dari sangkar emas milik tuannya ataukah justru memilih selamanya menjadi gundik?
Bab 1: Bunga Yang Terenggut Paksa (1)
Bagian 1: Nyai Surtinah
Tjokro memberanikan diri menatap lelaki Belanda yang duduk di balik meja. Ruangan berdinding separuh tembok, separuh kayu dengan atap seng itu terasa sangat panas. Punggung lelaki itu telah basah oleh keringat dan beberapa kali ia menyeka dahi dengan punggung tangan. Tjokro ingin sekali mengibaskan kaus lusuh yang membungkus tubuhnya, tetapi urung. Ia sendang mencoba memikat hati kepala perkebunan Tretes yang biasa dipanggil tuan besar. Jangan sampai ia bertindak tidak sopan dan kehilangan kesempatan emas.
“Kamu yakin mau menyerahkan anak gadismu padaku?”
Suara Willem van Rijkaard terdengar berat dan dalam. Tatapannya menerobos kedalaman rongga mata Tjokro. Seumur hidup menghirup udara tanah Hindia, Willem sudah sering mendengar kisah tentang orangtua yang menjual anak gadisnya pada laki-laki kulit putih untuk dijadikan nyai, kalau tidak ingin disebut gundik. Namun, hati kecilnya masih tidak percaya ada orangtua nir adab yang tega menjual anak demi jabatan rendah.
Jika bukan karena dorongan kawan-kawan sesama Belanda totok yang memiliki nyai, bahkan lebih dari satu, dan tawaran Tjokro, Willem tidak pernah punya keinginan untuk menjadikan gadis pribumi sebagai nyai di istananya. Ia ingin menikah baik-baik, memiliki istri dan anak yang lucu. Kalau sampai usia tiga puluh tahun ia masih melajang, semua karena kesibukan dan kehidupannya yang tidak pernah menetap lama di suatu daerah. Willem menghabiskan waktu sejak berusia dua puluh tahun untuk menjelajah perkebunan demi perkebunan dari tanah Sumatera hingga Jawa dan akhirnya sejak dua tahun lalu berlabuh di ujung timur Pulau Jawa ini, tanah yang membuatnya jatuh cinta sejak pertama kali tiba.
Tjokro mengangguk mantap. Selarik senyum tersungging di wajahnya. “Yakin, Tuan. Demi kebaikan kami sekeluarga.”
“Kamu tahu apa yang akan terjadi pada anakmu kalau dia jadi nyaiku?” Willem masih belum menarik pandangan dari wajah Tjokro.
Lagi-lagi lelaki bertubuh tinggi kurus itu mengangguk. “Tentu saya tahu, Tuan. Telah banyak orang bercerita perihal kehidupan seorang nyai dan saya yakin itu yang terbaik untuk Tinah. Dia tidak boleh terus-terusan menjadi gadis miskin.”
Willem mengembuskan napas kasar sembari menjatuhkan punggung pada sandaran kursi. “Kalau memang sudah yakin, esok lusa aku akan ke rumah untuk bertemu anak gadismu. Aku tidak ingin membeli kucing dalam karung dan harus kupastikan kalau dia memang layak menjadi nyaiku. Kamu tentu tahu kedudukanku di kalangan bangsa kulit putih.”
Mendengar ucapan Willem, seketika Tjokro merasa tubuhnya mengembang seperti balon saking bahagia. Sebentar lagi jabatan mandor besar ada dalam genggaman dan Surtinah akan mengecap kehidupan nyaman dengan meneer Belanda. Semua tahu, menjadi nyai sama seperti menjadi nyonya di rumah lelaki kulit putih. Meski tidak pernah ada pernikahan resmi, tetapi hidup mereka nyaman dan terjamin. Ia tidak ingin Surtinah menjadi gadis miskin seumur hidup.
Sebagai mandor besar, Tjokro akan mendapat gaji lumayan dan cukup untuk menaikkan derajat keluarganya. Kelak, Lanang dan Jaka tidak akan pernah ditolak ketika melamar gadis hanya karena mereka anak buruh miskin pemetik kopi seperti dirinya dulu. Kedua anak lelakinya akan mampu berdiri tegak menatap siapa pun karena mereka adalah anak mandor besar. Tjokro senyum-senyum ketika semua kisah indah di masa depan berebut lewat di rongga kepala.
“Tentu, Tuan. Datanglah kapan saja Tuan ada waktu. Saya yakin Tinah tidak akan mengecewakan Tuan. Kami telah mendidiknya dengan baik,” ujarnya kemudian.
Willem mengambil cerutu dari laci meja lalu menyalakannya. Sekian detik kemudian asap mengepul di depan parasnya yang tampan. Ia mulai merasa muak melihat Tjokro dan asap cerutu serupa kabut yang bisa menyamarkan wajah lelaki itu.
“Aku kira tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kamu boleh pergi sekarang, Tjokro. Aku masih banyak pekerjaan.”
“Baik, Tuan. Terima kasih banyak.” Tjokro menunduk dalam-dalam sebelum berlalu dari ruang kerja Willem di pabrik pengolahan kopi Tretes.
Tokro melewati ruangan besar di mana para pekerja tengah memilah biji-biji kopi dengan hati bungah. Senyum tidak pernah tanggal dari wajahnya ketika bertemu pandang dengan para pekerja yang ia kenal baik.
Setibanya di halaman pabrik, Tjokro meraih sepeda ontel dan mengayuh selekas mungkin menuju kebun kopi. Ia harus segera mengambil biji kopi yang telah dipetik ketiga anaknya.
“Cari tahu seperti apa anak gadisnya dan bagaimana perangainya,” ujar Willem seraya menatap orang kepercayaannya yang berdiri di sudut ruang kerja setelah kepergian Tjokro.
Lelaki bertubuh tinggi besar itu mengangguk. “Baik, Tuan.”
Willem menggerakkan dagu. “Kamu boleh pergi, Kardi. Segera laporkan apa yang kamu dapat padaku.”
Kardi membungkuk kemudian meninggalkan ruang kerja Willem.
Willem bangkit dan beranjak menuju jendela besar di sisi utara ruang kerjanya. Dari balik jendela ia bisa melihat keindahan Gunung Kawi yang menawan hati. Ia cukup betah di sini, tetapi perusahaan memindahnya ke Gementee Malang dan akan menempati kantor pusat NV Koffiepellerij di kota itu.
Ingatan Willem berkelana dan berhenti pada waktu pertemuannya dengan Herman Spellman yang akan menggantikan posisinya di pabrik kopi ini. Herman mengunjungi rumah yang ditempatinya tidak jauh dari pabrik untuk melihat-lihat suasana calon tempat kerjanya.
“Kamu kesepian, butuh seorang nyai untuk menghangatkan hidupmu, Frederick.” Spellman menuang kopi ke dalam cangkir lalu menyodorkannya pada Willem. Lelaki berusia lima tahun lebih tua darinya itu tersenyum penuh arti.
“Untuk apa? Aku sudah punya jongos, tukang kebun, dan babu. Kukira sudah cukup.” Willem menyeruput kopinya perlahan lalu membiarkan cairan pekat itu melewati rongga mulut. Ia memang merasa sudah cukup. Soal kehangatan perempuan, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mencari gadis yang akan menjadi istrinya.
Spellman mengibaskan tangan. “Kamu terlalu keras bekerja dan menghabiskan waktu di perkebunan sampai lupa menyenangkan diri sendiri.” Lelaki berambut pirang itu mengambil kotak cerutu dan menyodorkannya pada Willem. “Sudah saatnya ada perempuan menemani malam-malam yang dingin dan itu tidak bisa dilakukan jongos atau babumu.” Spellman tertawa. “Mereka tentu tidak bisa memijitmu, bukan?”
Asap cerutu bergulung-gulung di antara dua lelaki itu. Willem tercenung. Pikirannya mengembara. Ia terlahir di keluarga konservatif yang menjunjung kesetiaan dan ikatan pernikahan yang sah. Meski keluarganya tinggal di Batavia dan tidak akan tahu kalau di Malang ia mempunyai nyai, tetap saja Willem merasa malu. Lelaki dengan tubuh tinggi tegap itu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika salah satu di antara orangtua dan ketiga adiknya datang berkunjung dan mendapatinya memiliki perempuan simpanan.
“Pikirkan baik-baik, Kawan. Mempunyai nyai sama sekali bukan hal buruk. Hampir semua orang melakukannya, bukan?”
Willem mengalihkan pandangan ke halaman rumahnya. Tatapan matanya disambut anggukan bunga lili yang bergoyang ditiup angin.
“Lihatlah aku, tidak ada masalah dalam hidupku dengan mempunyai nyai. Lagi pula, perempuan pribumi tidak banyak menuntut dan bisa berhemat. Tidak seperti perempuan-perempuan totok yang suka menghabiskan uang dan waktu untuk pesta dansa-dansi.”
Bab 2: Bunga Yang Terenggut Paksa (2)
Willem menatap Spelman sekilas sembari meraih cangkir dan menyesap isinya perlahan. Saraf-saraf di kepalanya mencoba mencerna ucapan salah satu sahabatnya yang baru dikenalnya di Malang itu. Sejak awal bertemu di kantor pusat NV Koffiepellerij, Willem merasa cocok dengan pembawaan Spelman yang tenang dan hangat.
“Satu hal lagi, Frederijk, tidak selamanya kami terikat hubungan tanpa pernikahan dengan seorang nyai. Banyak lelaki totok menikahi mereka dan hidup bahagia. Aku pun akan melakukannya. Nyaiku baru saja mendapat nama Belanda dan sebentar lagi kami akan menikah secara resmi di gereja.” Wajah Spelman terlihat serius.
Willem mematikan cerutu di tangan dan meletakkannya di atas asbak. Tatapannya menelisik wajah Spelman. Ia tahu Spelman telah memiliki dua anak dari hubungannya dengan sang nyai, tetapi tidak pernah menyangka jika mereka akan menikah.
“Jadi, kamu tidak perlu ragu untuk memiliki seorang nyai. Kalau kamu cocok, kamu bisa menikahinya.” Spelman mengisi cangkirnya yang telah kosong. “Kedua anakku juga sudah berhak mencantumkan namaku di belakang nama mereka.” Lelaki bermata teduh itu mengukir senyum puas.
Willem bangkit dari kursi lalu berdiri menatap air mancur di kolam yang berada di tengah halaman rumahnya. Matahari mulai mendekati ufuk barat dan langit sedikit demi sedikit berubah warna. Ucapan Spelman mulai menyelusup ke dalam hatinya. Hingga petang menjelang dan Spelman memutuskan untuk beristirahat, tidak banyak kata terlontar dari lisan Willem. Pikirannya mulai gaduh dengan berbagai kemungkinan dan pertimbangan.
Semesta seolah tengah berpihak pada Willem. Satu minggu setelah kepulangan Spelman, Sukardi membawa Tjokro bertemu muka dengannya dan mengutarakan keinginan untuk menyerahkan gadis semata wayangnya dengan imbalan jabatan mandor besar. Willem mulai bimbang, antara bertahan dengan prinsip yang diyakini dan menjajal kehidupan baru dengan perempuan pribumi yang lebih dari sekadar babu.
Tawaran Tjokro membuat kedua matanya enggan terpejam. Tidak hanya sel-sel kelabu di kepala yang gaduh, hatinya pun ikut ribut. Setelah menimbang, Willem pun memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Tjokro demi memastikan keinginan lelaki itu dan bertemulah ia dengan salah satu buruh kebun kopi itu hari ini.
***
Surtinah mengusap wajah dengan ujung selendang yang terikat di pinggang. Siang itu matahari seolah bersinar lebih terik dari biasanya sehingga tubuhnya seperti berada di dalam kukusan yang diletakkan di atas tungku dengan api menyala. Beberapa kali ia berhenti untuk meneguk air dari kantung dari kulit yang dibawanya dari rumah.
Meski digelantang terik mentari, gadis berlesung pipit itu tetap memetik biji kopi dengan sabar lalu meletakkannya di dalam keranjang. Ia harus bekerja keras agar punya cukup tabungan untuk membeli pakaian baru. Baju-bajunya sudah terlalu usang, tidak ada lagi yang layak dipakai jika sewaktu-waktu harus menghadiri pernikahan kawan-kawannya.
Satu demi satu teman-temannya menemukan pujaan hati. Ia? Entah kapan. Sampai saat ini Surtinah hanya ingin bekerja sekeras mungkin agar bisa mengumpulkan banyak uang. Ia tidak ingin terus-terusan menjadi kuli dan hidup miskin. Siapa tahu dengan uang itu, selain bisa membeli baju juga bisa digunakan untuk membuka kedai di dekat pabrik kopi seperti yang dilakukan Sadirah, salah satu tetangga di desanya.
Surtinah turun dari tangga setelah krinjing di tangan penuh dan mengambil keranjang yang lain untuk diisi dengan biji kopi. Ia mengangkat tangga dan memindahkannya ke pohon berikutnya sementara keranjang yang terisi penuh ia tinggal di depan pohon pertama. Lanang, adiknya, atau bapak akan mengambilnya nanti.
Tinggi pohon kopi yang jauh melampui tubuh manusia menyebabkan gadis-gadis pemetik kopi harus menggunakan tangga saat mengambil biji berwarna merah menggoda dari dahannya. Sejak berumur sepuluh tahun, Surtinah telah menjadi buruh di perkebunan milik NV Koffiepellerij itu. Begitu pula kedua adik lelakinya sudah menjadi bagian dari kebun kopi ini di usia yang sama.
Matahari mulai merangkak ke barat sehingga sinarnya taklagi terasa menyengat. Kesiur angin menggerakkan dedaunan pohon kopi. Surtinah baru saja memenuhi keranjang kedua ketika mandor besar memanggil namanya.
Tergopoh, Surtinah memangkas jarak dengan mandor besar. “Ada apa, Tuan?” tanyanya hati-hati setelah berdiri berhadapan. Ia sedikit terkejut ketika Lanang berdiri di samping lelaki bertubuh agak gendut itu.
Mandor besar memberi isyarat pada Lanang untuk bicara. “Katakan apa keperluanmu.”
“Mbakyu disuruh pulang sama bapak sekarang,” ujar bocah lelaki berusia dua belas tahun itu.
“Masih ada satu keranjang lagi, Nang. Tanggung.”
Lanang menatap Surtinah gusar. Ia meremas kaus lusuh yang basah oleh keringat. “Tapi kata bapak Mbakyu harus pulang sekarang juga. Ditunggu meneer di rumah.”
Surtinah menelengkan wajah sembari menatap takpercaya wajah adiknya. Sejak kapan ada meneer Belanda menunggunya. Jangankan duduk berbincang, bertegur sapa saja hampir tidak pernah jika tidak sangat terpaksa. Siapalah dia, hanya kuli kebun, kasta terendah dalam perkebunan kopi.
“Kowe cepat pulang. Jangan buat Meneer Willem menunggu.”
Suara mandor besar mengagetkan Surtinah.
“Biar Lanang yang membawa kopimu ke pabrik. Sekarang juga kamu pulang.” Ucapan mandor besar tegas penuh tekanan.
Perintah mandor besar takbisa ditawar lagi. Meski kesal dan kecewa karena masih ada satu keranjang kosong, Surtinah membiarkan Lanang membawa dua kerangjang yang terisi ke pabrik sementara ia pulang ke rumah.
Sepanjang perjalanan pulang, kepala Surtinah disesaki berbagai pertanyaan dan tidak menemukan satu pun jawaban. Ia menyerah dan memutuskan menunggu hingga tiba di rumah agar semua persoalan terang benderang.
Semakin dekat dengan tujuan, Surtinah justru memperlambat langkah. Dari jauh ia bisa melihat delman milik Tuan Willem tengah berada di depan rumahnya. Ia tersirap ketika bertemu pandang dengan jongos Meneer Willem yang berwajah garang.
Perlahan, hati Surtinah mulai disesaki rasa waswas. “Ada masalah apa sebenarnya sehingga Tuan Willem bertandang ke rumahnya? Apakah bapaknya terlibat kejahatan di perkebunan? Apakah bapaknya punya hutang pada mandor besar dan luput membayar seperti yang terjadi pada Kirman, salah satu tetangga mereka?” batinnya rusuh.
“Nah, ini Surtinah, anak saya, Tuan.”
Ucapan sang bapak dan senyum sumringahnya menyambut kedatangan Surtinah.
Gadis berambut panjang itu membeku di ambang pintu.
Refleks Willem menoleh hingga pandangannya menerobos bola mata bening milik Surtinah.
Surtinah terkejut lalu mundur selangkah. Ia tidak mengira Tuan Willem datang ke rumahnya dan mencarinya. “Lelucon apa ini?” ujarnya dalam hati.
“Tuan Willem bukan penjahat, Tinah. Bersikaplah sopan padanya. Berikan senyummu.” Suara Tjokro terdengar lembut.
Ah, Surtinah benar-benar tidak mengerti dengan semua keanehan yang terjadi di depan mata. Sangat jarang bapaknya bersikap lemah lembut. Beban hidup dan tuntutan pekerjaan membuat lelaki itu sedikit temperamental.
“Berikan senyummu, Tinah.” Tjokro mengulang kalimat, kali ini dengan sedikit tekanan.
Surtinah mengangguk sopan lalu tersenyum samar memperlihatkan lesung pipit yang membuat wajahnya terlihat begitu manis seperti gulali di pasar malam.
Senyum Surtinah menerobos mata biru Willem lalu perlahan turun ke hati. Benar kata Sukardi, gadis Tjokro memang berparas cukup menarik.
Bab 3: Bunga Yang Terenggut Paksa (3)
Willem memutus kontak dengan Surtinah dan kembali menatap Tjokro. Ia bisa melihat jika paras gadis itu sebenarnya cukup cantik. Sinar matahari tropis tanah Hindia yang menjadikan kulitnya lebih gelap. Willem mantap menjadikan Surtinah sebagai nyai. Kelak, jika cocok, Surtinah akan menjadi lebih dari sekadar nyai sehingga tidak perlu menanggung malu kalau sewaktu-waktu bertemu dengan keluarganya.
“Baik, Tjokro, aku kira anak gadisnya layak tinggal di rumahku.” Suara Willem memenuhi ruang tamu yang tidak seberapa besar itu.
“Terima kasih, Tuan. Saya titip Tinah.” Senyum bahagia terkembang sempurna di wajah Tjokro. Bayangan kehidupan yang jauh lebih baik di masa datang berkelebat di benak. Hati Tjokro dipenuhi madu sementara hidungnya kembang kempis.
Surtinah menatap sang bapak dan Willem bergantian. Ia masih belum mengerti pembicaraan dua lelaki dewasa di hadapannya.
“Ini sebagian uang yang kita sepakati.” Willem menyodorkan kantung berisi lembaran gulden. “Hari ini aku harus berkemas karena lusa akan pindah ke Malang. Aku akan jemput anakmu satu minggu setelah tiba di sana.”
“Baik, Tuan.” Tjokro mengambil kantung dari tangan Willem lalu mengalihkan pandangan pada Surtinah yang masih mematung di ambang pintu. “Kemari, Nduk.”
Surtinah duduk di samping Tjokro. Taklama kemudian simboknya muncul dari dalam lalu memeluk tubuh Surtinah dengan air mata bercucuran.
“Mulai minggu depan kamu akan menjadi nyai Tuan Willem. Baik-baiklah mengurus Tuan Willem.”
Surtinah ternganga, takpercaya dengan apa yang ditangkap pendengarannya. “Ta-tapi, Pak?”
Gadis itu merasa tubuhnya diterbangkan angin kemudian terbanting ke tanah. Sekali pun tidak pernah terbersit dalam pikiran Surtinah untuk menjadi nyai. Otaknya masih cukup waras. Ia tahu seperti apa kehidupan seorang nyai.
“Ini semua demi kebaikanmu, Tinah. Demi kebahagiaan keluarga kita juga.”
Mata Surtinah mengembun, tidak menyangka justru sang bapak yang menyerahkannya pada lelaki Belanda untuk menjadi perempuan simpanan. Sungguh hina dan tidak terhormat!
Sumirah mengeratkan pelukan di tubuh Surtinah. Isaknya semakin keras. Keputusan Tjokro membuat hati perempuan berusia tiga puluh tahun itu lumat tak bersisa. Ia tidak bisa membayangkan kehidupan gadisnya setelah menjadi nyai. Sumirah tidak yakin akan bisa menghadapi dunia. Semua pribumi tahu kalau nyai hanya sebentuk kamuflase dari gundik atau gendakan.
Willem menarik napas panjang. Tangisan Sumirah membuat hatinya serasa diremas. Lelaki berambut cokelat itu bisa merasakan luka begitu di wajah perempuan itu. Namun, ia tidak mungkin membatalkan perjanjian dengan Tjokro karena akan menghancurkan kredibilitasnya sebagai kepala perkebunan. Tidak ada yang lebih hina selain menjilat ludah sendiri.
“Aku pergi dulu, Tjokro. Ingat, satu minggu lagi Kardi akan menjemput Surtinah dan membawanya ke Malang. Mulai besok, anakmu tidak perlu memetik kopi. Tinggal saja di rumah agar bisa bersiap-siap dan mengurus diri dengan baik.”
Tjokro mengiyakan perintah Willem.
Willem tersenyum puas kemudian bangkit dan berjalan keluar menuju delman.
Entah mendapat keberanian dari mana, Surtinah melepas pelukan Sumirah kemudian berlari mengejar Willem. “Tuan, tolong dengarkan saya,” teriaknya.
Tjokro dan Sumirah terpana, tidak menyangka Surtinah akan berbuat nekat.
“Tolong dengarkan saya.” Surtinah memegang kaki kanan Willem. “Saya tidak ingin menjadi nyai, Tuan. Tapi ada teman saya yang bersedia menjadi nyai. Dia pasti akan sangat senang bila Tuan bersedia memilihnya.” Surtinah masih berharap Willem mengurungkan niat.
Perkataan Surtinah membangkitkan amarah di hati Tjokro. Gegas ia berlari keluar. “Bocah kurang ajar!”
“Tolong saya, Tuan. Saya tidak ingin menjadi nyai. Sudilah kiranya Tuan memilih teman saya.” Surtinah tercekat di ujung kalimat. Air matanya luruh. Hatinya seperti ditikam belati berkali-kali. Sakit. Peruh. Hancur.
Tjokro mendekati Surtinah. Tangannya terulur hendak mencekal lengan anaknya.
“Biar aku yang bicara, Tjokro.”
Suara tegas penuh wibawa Willem menghentikan gerakan tangan Tjokro. Lelaki itu menunduk lalu mundur selangkah. Diam-diam ia jatuh iba pada Surtinah.
Kedua tangan Willem meraih lengan Surtinah lalu menariknya hingga gadis itu berdiri. Ia melukis senyum ketika saling bersitatap selama sekian detik. “Aku menginginkamu, Tinah. Bukan temanmu.” Pandangan Willem menerobos mata Surtinah yang menyiratkan rasa kesal, kecewa, marah, dan takut.
Surtinah membeku. mulutnya terbuka, tetapi tak satu pun kata terucap. Kepala dan hatinya gaduh. Namun, semua kalimat itu hanya berhenti di tenggorokan seolah sebongkah batu tersangkut di sana dan menghalangi deretan huruf itu keluar. Lidah Surtinah mendadak kelu.
“Jangan khawatir, aku bukan penjahat dan tidak akan menyakitimu.” Suara lelaki itu terdengar lembut. “Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik, Tinah.” Willem melepas lengan Surtinah lalu berjalan menuju delman.
Surtinah jatuh terduduk lemas di tanah. Entah mimpi apa semalam hingga nasibnya hari ini begitu kelam. Senja yang datang menyapa seperti akhir kehidupan Surtinah. Segala mimpi untuk merajut masa depan menjadi manusia merdeka dan bermartabat berhamburan dipeluk angin.
Sebuah tamparan mendarat di pipi Surtinah setelah kepergian Willem. “Bocah gemblung!” Tjokro menarik tubuh Surtinah masuk ke dalam rumah.
“Kenapa harus saya, Pak? Saya tidak mau jadi nyai, Pak. Saya tidak mau.” Surtinah memeluk kaki Tjokro. Isaknya memenuhi rumah berdinding gedek.
Jaka dan Lanang yang baru pulang dari pabrik tertegun di ambang pintu. Keduanya menatap tak mengerti Surtinah yang menangis di kaki Tjokro.
“Memangnya siapa lagi, hah? Jaka? Lanang? Kamu sudah gila! Tidak mungkin mereka jadi nyai!” Tjokro semakin muntab.
Kedua adik Surtinah ternganga. Lanang yang berusia dua tahun lebih muda, mulai mengerti duduk persoalannya. Ternyata kedatangan Willem untuk mengambil sang kakak dari kehidupan mereka.
“Kasirah pernah bilang kalau pengen jadi nyai, Pak. Dia pasti dengan senang hati menggantikan saya.”
“Ngawur, kamu!”
“Tinah benar, Pak. Coba Bapak temui Kasirah.” Sumirah ikut bersuara setelah sekian lama diam dan hanya menangis.
“Semua sudah bapak pikirkan, Bune. Ini demi kebaikan kita bersama. Tuan Willem sudah menerima anak kita dan tidak ingin diganti yang lain. Bersamanya Tinah tidak akan hidup susah dan setelah Bapak jadi mandor besar, derajat keluarga kita akan semakin tinggi. Keluarga kita tidak akan direndahkan lagi.”
“Tapi, Pak ….”
“Sudah, Bune, sudah. Tinah akan jadi nyai Tuan Willem. Titik!”
Tjokro melepas tangan Surtinah yang memeluk kakinya. Dengan langkah cepat ia meninggalkan rumah. Ia harus menyelamatkan diri dari rengekan Surtinah dan Sumirah.
***
Surtinah menjalani hari-hari yang muram setelah kedatangan Willem. Alih-alih merawat diri agar tampil cantik saat dijemput utusan Willem, ia justru enggan makan dan susah tidur sehingga wajahnya terlihat pucat dan kedua matanya seolah dilingkari cincin besar.
“Mbakyu, kamu bener-benar tidak ingin tinggal bersama Tuan Besar?” Lanang duduk di samping Surtinah yang tengah termenung di bibir amben.
“Apa kamu juga sependapat dengan bapak, Nang? Kamu ingin mbakyumu ini jadi budak londho?” Surtinah menatap sengit Lanang.
Lanang menggeleng. “Tidak, Mbakyu. Aku juga tidak ingin Mbakyu jadi Nyai.”
“Lalu?” sergah Surtinah cepat.
“Kenapa Mbakyu tidak kabur saja dari rumah dan pergi ke kota?” ujar Lanang kemudian.
Bab 4: Bunga Yang Terenggut Paksa (4)
Pertanyaan Lanang menyentak kesadaran Surtinah bahwa hidupnya belum berakhir. Masih ada kesempatan untuk menghindari nasib menyakitkan ini.
“Pergilah, Mbak. Mbakyu bisa pergi ke kota atau ke mana pun asalkan tidak lagi berada di desa ini.” Lanang menatap sendu sang kakak. Ia juga tidak ingin melihat marwah Surtinah hancur dengan menjadi gundik lelaki Belanda.
“Aku akan membantu Mbakyu lari.” Meski berat berpisah dengan Surtinah, tetapi Lanang menganggap kabur adalah pilihan terbaik bagi mbakyunya. Dengan meninggalkan desa ini, mbakyunya akan terbebas dari ikatan dengan Willem.
“Te-terima kasih, Nang.” Surtinah tersenyum masygul, tidak menyangka jika Lanang bisa berpikir lebih realistis ketimbang dirinya yang jelas berusia lebih tua. Seketika gadis berlesung pipit itu merasa malu. Berhari-hari ia menghabiskan waktu merutuki nasib dan kehilangan akal sehat untuk berpikir mencari jalan keluar.
“Tapi aku tidak tahu daerah lain di luar desa kita, Nang.” Kedua mata Surtinah berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan kabur keluar desa seorang diri. Simbok pernah mewanti-wanti agar jangan pernah pergi seorang diri terlalu jauh dari desa. Terlalu berbahaya bagi perempuan.
Lanang beranjak dari amben lalu membuka pintu kamar Surtinah. Ia melongokkan kepala dan memindai keadaan di luar bilik. “Aku dengar Tuan Haji Ismail akan pergi ke kota esok lusa,” ujarnya setelah kembali duduk di samping Surtinah. Suara Lanang seperti embusan angin sepoi yang menepuk kedua pipi Surtinah.
Surtinah menelengkan kepala sembari berusaha mencerna ucapan Lanang. Di desa tetangga ada seorang saleh yang konon berasal dari negeri yang jauh dan membuka sekolah yang selalu didatangi Lanang setiap hari Minggu karena pada hari itu semua buruh kopi libur.
“Aku tidak kenal Tuan Haji Ismail.”
“Besok sore sepulang dari pabrik, aku akan ke rumah Tuan Haji dan meminta izin agar Mbakyu bisa ikut ke kota.”
Air mata Surtinah jatuh satu-satu.
“Aku yakin, Tuan Haji tidak akan keberatan. Mbakyu Tinah pasti boleh ikut.” Lanang memegang kedua lengan Surtinah, berusaha meyakinkan sang kakak.
Hening.
Kedua orang itu sibuk dengan kecamuk pikiran.
Surtinah menyeka jejak air mata di pipi. “Aku akan mencobanya, Nang. Bujuklah Tuan Haji agar aku diizinkan ikut dengannya.”
Kedua sudut bibir Lanang terangkat. “Pasti, Mbakyu. Aku akan lakukan apa pun agar Mbakyu bisa lari.”
“Terima kasih, Nang.” Surtinah memeluk Lanang. Hatinya menghangat menyadari adiknya begitu peduli pada nasibnya.
Sejak kedatangan Willem, Surtinah telah kehilangan harapan pada Keluarganya. Simboknya jelas tidak akan punya nyali untuk melawan bapak. Sepanjang kehidupan Surtinah, belum pernah sekali pun melihat Sumirah berkata tidak pada titah Tjokro. Begitu pula dengan Jaka dan Lanang, mereka terlalu kecil untuk bisa melawan Tjokro. Namun, ternyata ia telah salah menduga. Justru Lanang yang mampu menggugah kesadaraannya.
“Mbakyu siap-siap saja. Besok, aku kabari setelah bertemu dengan Tuan Haji.”
“A-apa kamu yakin Tuan Haji orang yang bisa dipercaya?” Wajah Surtinah terlihat khawatir.
Lanang tersenyum. “Aku yakin Tuan Haji orang baik. Beliau dan istrinya banyak mengajarkan kebaikan pada kami.”
Surtinah menarik napas lega. “Baik, Nang. Aku percaya sama kamu.” Selarik senyum menghias paras manisnya.
Keesokan harinya, sepulang dari pabrik untuk menyetor biji kopi, Lanang pergi ke desa tetangga untuk menemui Tuan Haji Ismail. Ia sengaja bekerja lebih giat hari ini sehingga mendapat tiga pikul kopi, lebih banyak daripada hari-hari biasa yang hanya satu atau dua pikul. Ia ingin menyenangkan hati Tjokro agar diizinkan pergi ke rumah Tuan Haji.
Sesuai perkiraannya, Tjokro tidak keberatan Lanang menemui Tuan Haji. Sejak belajar di rumah lelaki dari timur jauh itu, perangai Lanang banyak berubah dan Tjokro senang melihat perubahan itu. Salah satunya karena ia jauh lebih rajin bekerja dan bisa membaca sehingga mandor besar sering memberi kesempatan pada Lanang untuk memberitahu teman-temannya jika ada pemberitahuan dari kepala perkebunan.
Tjokro juga tidak keberatan ketika Jaka ikut belajar pada Tuan Haji. Ia sangat berharap kedua anak lelakinya bisa mengangkat derajat keluarga dan keluar dari lingkaran setan kuli kebun kopi yang miskin. Tjokro yakin, hanya dengan kedudukan sebagai mandor besar dan kemampuan baca tulis Jaka dan Lanang, nasib keluarganya akan lebih baik.
Tirai malam telah menutupi bumi dengan sempurna. Suara jangkrik bersahutan ditingkahi gemeresak ranting dan batang bambu yang bergesekan karena ditiup angin. Surtinah duduk di amben depan rumahnya dengan gelisah. Sesekali ia bangkit, lalu berdiri di bibir jalan, mencari sosok Lanang dan Jaka yang belum juga terlihat batang hidungnya.
“Kenapa belum pulang ya, Nduk?” Sumirah duduk di samping Surtinah. Derit bambu terdengar ketika tubuh perempuan itu mendarat di atas amben. “Biasanya tidak selarut ini mereka di rumah Tuan Haji.” Mata Sumirah mulai berkabut. Jejak rasa khawatir terlihat di wajah yang mengelam karena terpaan sinar matahari. Perempuan itu terlihat lebih tua dari usia yang sesungguhnya.
Surtinah berdiri lalu pergi ke tepi jalan. Ingin sekali ia terbang dan mencari kedua adiknya. Jika sampai bapak pulang mereka belum kembali, ia khawatir Tjokro akan menghukum mereka dan menghambat rencana pelariannya.
Gadis itu mematung di tepi jalan, membiarkan kesiur angin memukul-mukul tubuhnya dan meriapkan anak-anak rambut. Surtinah berjalan perlahan ke arah desa sebelah ketika di kejauhan terlihat titik api yang semakin lama semakin membesar. Ia menarik napas lega ketika matanya menangkap bayang tubuh Jaka dan Lanang yang berjalan dengan langkah cepat.
“Lama sekali, Nang, Ka.” Surtinah menjajari Lanang menuju rumah mereka.
“Iya, Mbak, tadi ngobrol sama Tuan Haji, tahu-tahu sudah gelap.”
Surtinah menggeleng. “Kalian membuat simbok khawatir.”
“Oalah, Le, kalian ke mana saja? Kok, sampai malam begini baru pulang?” Sumirah mengguncang tubuh kedua anaknya ketika mereka sudah berdiri berhadapan.
“Nggak, ke mana-mana, Mbok. Ngobrol sama Tuan Haji saja.” Lanang tersenyum.
“Apa iya? Kok, sampai malam gini?” Tatapan sangsi Sumirah memindai wajah Jaka dan Lanang.
“Bener, kok, Mbok. Kami hanya pergi ke rumah Tuan Haji,” ujar Jaka meyakinkan.
Sumirah tersenyum lega lalu mengajak masuk ketiga anaknya.
“Lusa, pagi-pagi sekali, Tuan Haji, Nyai Fatimah, dan tiga anak mereka akan berangkat ke Surabaya untuk mengambil kiriman buku dari Batavia.” Lanang memulai pembicaraan serius usai menghabiskan sepiring singkong rebus. Kebetulan Tjokro sedang pergi sehingga mereka lebih bebas berbicara.
“Tuan Haji meminta Mbakyu datang besok sore dan menginap di sana. Aku tunggu di ujung desa. Nanti Mbakyu menyusul.”
Surtinah menatap Sumirah. Sorot matanya seolah meminta pendapat perempuan yang telah melahirkannya itu.
“Pergilah, Nduk. Simbok rela. Lebih baik kamu ikut Tuan Haji daripada tetap di sini dan hidup seatap dengan Tuan Londho tanpa menikah. Simbok nggak rela, Nduk, kamu seperti itu.” Mata Sumirah berembun sementara suaranya bergetar. Kecewa, sesak, dan sedih bergumpal-gumpal memenuhi rongga dada.
Bab 5: Bunga Yang Terenggut Paksa (5)
Ucapan Sumirah seperti guyuran air sumur di siang hari yang terik. Surtinah menjatuhkan kepala di pangkuan Sumirah. Air mata jatuh membasahi jarik simboknya. Restu perempuan yang melahirkannya adalah penerang di tengah ruwet dan gelap kehidupan dan ia lega mendapati Sumirah mendukung niatnya untuk kabur dari rumah.
Meski tidak ingin berpisah dengan simbok dan kedua adiknya, tetapi tidak ada pilihan lain bagi Surtinah selain pergi agar bisa bertahan hidup sebagai manusia merdeka. Menjadi kuli pemetik kopi saja sudah sering dianggap hina meneer-meneer Belanda dan harus menerima berbagai perlakuan tidak adil, apalagi menjadi nyai. Ia tidak hanya dianggap hina oleh bangsa kulit putih, melainkan juga oleh sesama pribumi. Dobel sakit hati.
“Bawalah ini untuk berjaga-jaga di jalan, Tinah.” Sumirah mengambil cundri dari gelungan rambutnya.
Surtinah mengangkat kepala. Ditatapnya dua benda mirip tusuk konde, tetapi batangnya berlekuk dan memiliki ujung runcing.
“Bawalah. Siapa tahu kamu membutuhkannya.”
Surtinah meraih dua cundrik berwarna keemasan itu dan menyelipkannya di antara gelungan rambut. “Terima kasih, Mbok.”
“Dan ini sedikit uang. Bawalah untuk bekalmu.” Sumirah mengambil buntalan kain dari stagennya dan meletakkannya di atas telapak tangan Surtinah.
Sekian detik kemudian, Lanang melakukan hal yang sama. “Ini sedikit simpananku, Mbak. Pakailah untuk bekal di jalan dan nanti di tempat baru.” Ia meraih kantung dari saku celana dan memberikannya pada sang kakak.
Mulut Surtinah terbuka seolah ribuan kata hendak terucap, tetapi taksatu pun yang keluar. Lidahnya kelu, tidak menyangka dengan kebaikan Lanang. Bocah lelaki itu benar-benar jauh lebih dewasa dari umurnya.
“Kata tuan haji, nanti Mbakyu akan dititipkan di rumah salah satu temannya di Surabaya yang punya toko besar. Mbakyu bisa bekerja di sana.”
Lagi-lagi Surtinah tidak mampu berkata-kata. Ia tidak menduga tuan haji berpikir sejauh itu sedangkan ia sendiri tidak pernah punya bayangan akan masa depannya. Hidupnya saat ini muram, segelap malam tanpa bintang dan ia tidak tahu arah. Namun, tuan haji yang bahkan tidak mengenalnya justru memberi jalan. Surtinah tergugu, menyadari betapa ia masih memiliki orang-orang yang peduli pada nasibnya.
Sekian lama ruang depan rumah Sumirah disergap beku yang menggigit. Ditingkahi suara jangkrik dan binatang malam lainnya, anak-beranak itu saling bertangisan.
“Mbok, Nang, saya sudah punya simpanan,” ujar Surtinah setelah kembali tenang. Diusapnya jejak air mata dan lelehan ingus dengan ujung kebaya. Ia mengembalikan uang pada Sumirah. “Saya kira itu untuk bekal di jalan. Lagipula, di Surabaya nanti saya akan bekerja. Simbok tidak usah khawatir.” Gadis itu melukis senyum. Sejurus kemudian, ia mengalihkan pandangan pada Lanang. “Kamu juga, Nang. Pegang uang ini untuk simpananmu. Suatu hari kamu akan membutuhkannya.”
Sumirah menyeka air mata. “Kami di sini masih bisa mencari uang, Nduk. Tapi namanya orang bepergian, nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Bawa saja uang ini.” Perempuan itu menggenggamkan buntalan kain di tangan Surtinah. “Jangan menolak pemberian orang, Nduk. Ora ilok,” putus Sumirah ketika melihat mulut Surtinah terbuka dan bersiap membantah.
“Bener kata simbok, Mbakyu.” Lanang mengikuti jejak Sumirah.
Sumirah menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Ia menyerah. Sekeras apa pun menolak, keduanya pasti akan tetap memaksanya.
“Sebentar lagi bapakmu pasti pulang.” Sumirah menghapus jejak air mata di wajah lalu membetulkan gelungan rambutnya. “Tadi bapak cuma pamit kenduren di rumah Lek Kirman.”
Surtinah dan kedua adiknya mengusap wajah.
“Kalian pergilah tidur. Jangan sampai bapak tahu rencana ini,” bisik Sumirah yang diikuti anggukan kepala ketiga anaknya.
Hampir sepanjang malam Surtinah tidak bisa memejamkan mata. Debaran jantungnya mengalahkan detak jam dinding usang di ruang tamu. Tjokro mendapatkan jam itu dari salah satu mandor besar yang pindah ke kebun kopi di kota lain. Bumi seolah begitu lambat berputar dan waktu merangkak seperti siput. Pagi yang dinanti takkunjung tiba.
Kokok ayam jantan seperti lonceng yang membangunkan Surtinah. Gadis itu lega, hari telah berganti. Gegas ia keluar bilik dan membantu simbok menyiapkan sarapan. Sepanjang waktu hingga saat makan pagi, semua mencoba bersikap biasa agar rencana mereka tidak terendus Tjokro.
“Kemarin suruhan Tuan Willem memberi uang untuk belanja.” Tjokro menyodorkan beberapa lembar gulden pada Sumirah. “Nanti, temani anakmu ke pasar. Beli baju-baju terbaik, selop, dan semua kebutuhannya. Kamu lebih tahu urusan perempuan.”
Gemetar tangan Sumirah menerima uang dari Tjokro. “Ba-baik, Pak.” Ia tersekat di ujung kata.
“Tuan Willem berpesan, Tinah harus berdandan secantik mungkin saat tiba di rumahnya.”
Sumirah menelan ludah sementara Surtinah tertunduk lesu dan kedua bocah lelaki di sisi amben lain mengunyah makan tanpa selera. Suara derit dipan tertangkap telinga karena Jaka bergerak-gerak gelisah.
***
Suara siulan Jaka menyentak Surtinah yang tengah duduk di dalam bilik. Ia menarik napas panjan, menghirup sebanyak mungkin oksigen, mencoba meredam gemuruh di dada. “Perjalanan akan segera dimulai,” bisiknya dalam hati. “Selamat tinggal, Tretes.”
Tangan Surtinah meraih dua buah cundrik yang diberikan simbok dan menyelipkannya di gelungan rambut. Uang untuk bekal di jalan telah disimpan dalam kantung kain dan terselip di antara stagen yang melilit pinggang. Surtinah merapal doa, berharap pelariannya berhasil.
Surtinah mencium punggung tangan Sumirah. Keduanya berpelukan cukup lama hingga siulan Jaka kembali terdengar. Gadis manis itu menghapus air mata di wajah Sumirah. “Doakan saya, Mbok. Suatu hari saya akan kembali.”
Sumirah mengangguk. Diciumnya kening dan pipi Surtinah. Keduanya bersipandang selama sekian detik. Takada kata yang terucap hingga Sumirah memberi isyarat pada anaknya untuk segera pergi.
Gegas tangan Surtinah meraih keranjang berisi bunga mawar dan kenanga lalu keluar lewat pintu belakang.
Sumirah menatap tubuh Surtinah yang semakin menjauh dengan pandangan kosong. Separuh jiwanya telah pergi dan entah kapan akan kembali.
Di bawah sinar matahari sore yang meredup Surtinah berjalan cepat menuju ujung desa. Beberapa kali ia berpapasan dengan warga yang baru pulang dari kebun kopi.
“Mau, nyekar, Lik.” Begitu selalu jawaban Surtinah ketika mereka menanyakan tujuan kepergiannya.
Senyum lega terbit di wajah Surtinah ketika matanya menangkap bayang tubuh Lanang tengah di bawah pohon sawo.
“Ayo cepat, Mbak.” Lanang celingak-celinguk, memastikan tidak ada orang lain di tempat itu.
Surtinah meletakkan keranjang bunga di dekat rumpun bambu kemudian berjalan di samping Lanang menapaki jalan penghubung desanya dengan Sumbermanggis. Mereka melangkah dalam diam diiringi gemeresak dahan pohon dan jantung yang berdegup kencang.
Kaki mereka belum melewati setengah jalan penghubung dengan Desa Sumbermanggis ketika terdengar suara keras memanggil nama Surtinah dan Lanang bergantian.
“Mau pergi ke mana kalian sore-sore begini?”
Langkah kaki Surtinah dan Lanang seketika terhenti. Keduanya bergeming, membeku dalam sergapan rasa takut. Tanpa melihat sumber suara, mereka tahu siapa yang tengah berbicara.
“Mau pergi ke mana kalian? Sebentar lagi hari gelap dan tidak ada pasar malam di Sumbermanggis.”
Surtinah dan Lanang saling berpandangan kemudian membalikkan badan.
Bab 6: Bunga Yang Terenggut Paksa (6)
Angin musim kemarau bertiup kencang menerbangkan debu-debu dan daun kering. Warna langit perlahan berubah dan suara jangkrik mulai terdengar di telinga. Surtinah mencekal lengan Lanang. Kedua matanya membulat sempurna. Ia merasa aliran darah di tubuhnya mendadak berhenti.
Sekilas, Lanang menatap paras pasi sang kakak lalu menatap lurus ke depan. Keringat dingin mengalir di dahi sementara sepasang matanya menatap jeri tiga lelaki yang berdiri beberapa jengkal di hadapannya.
“Mau pergi ke mana kalian sore-sore begini?” Suara lelaki tinggi besar yang tadi terdengar menggelegar kini sedikit melunak.
Lanang bergidik melihat tatapan Si Tinggi Besar yang seolah ingin menelannya dan Surtinah bulat-bulat.
“Di Sumbermanggis sedang tidak ada pasar malam, kan? Untuk apa kalian pergi ke sana?” Si Tinggi Besar memangkas jarak. Kini, dengan satu gerakan, tangannya bisa dengan mudah mencapai dua tubuh kurus yang berdiri kaku di depannya.
Semua warga di Tretes tahu kalau hanya pasar malam dan tontonan lainnya yang menyebabkan mereka pergi ke Sumbermanggis jelang petang. Tanpa keduanya, mereka lebih memilih berdiam diri di rumah. Pekerjaan sebagai buruh kopi telah menguras tenaga mereka.
“Kamu, Tinah, bukankah Tuan Willem tidak mengizinkanmu keluar rumah?” Kali ini lelaki bertubuh tinggi kurus dengan kumis bapang bersuara. Ia berdiri di samping Si Tinggi Besar.
“Kami ada sedikit urusan dengan Tuan Haji Ismail, Lek.” Lanang memberanikan diri bicara. “Yu Tinah ingin menitip untuk dibelikan beberapa barang di Surabaya.”
Mendengar jawaban Lanang, keberanian Surtinah yang sempat melorot hingga mata kaki kembali naik. Ia tersenyum. “Benar, Lek. Saya ada sedikit barang yang ingin dibeli.”
Si Kumis Bapang berjalan mengitari kedua remaja itu kemudian kembali berdiri di samping Si Tinggi Besar.
“Kalau hanya ingin ketemu tuan haji, kenapa bawa baju?” Secepat kilat Si Kumis Bapang merebut tas di tangan Surtinah.
Mulut Surtinah terbuka, tidak menduga Si Kumis Bapang akan mengambil tasnya.
“Siapa tahu kami kemalaman di rumah tuan haji dan harus menginap, Lek.” Lanang mencoba berkelit.
“Kalian tidak pintar berbohong, Anak-anak Manis.” Lelaki bertubuh pendek gemuk mendekati Lanang lalu menoyor kepalanya. “Cepat pulang atau kami harus berbuat kasar!” Hardikannya terdengar nyaring dan menyakitkan.
Surtinah dan Lanang bersitatap beberapa detik lalu mundur beberapa langkah.
“Kalian ingin bapak dan simbokmu digelandang ke hadapan Tuan Willem, heh?” Si Tinggi Besar meraih kaus Lanang dan dengan sekali sentak, tubuh bocah dua belas tahun itu terangkat ke atas.
Surtinah tersirap. Tulang-tulang penyangga tubuhnya seolah tercerabut paksa. Kesiur angin yang meriupkan anak rambut seperti tengah memberi kabar buruk akan takdir hidup yang harus dijalaninya.
“Le-lepaskan Lanang, Lek.” Ia berseru panik.
“Satu langkah saja kamu berjalan ke Sumbermanggis, tulang leher adikmu patah.” Suara Si Tinggi Besar merobek nyali Surtinah.
“Ja-jangan, Lek. Lepaskan Lanang.” Mata Surtinah mengembun. Bagaimana mungkin ia merelakan nyawa Lanang hanya agar ia bisa lari.
“Pergilah, Mbak. Aku nggak apa-apa.”
Surtinah menggeleng. “Enggak, Nang, enggak. Biar aku jadi nyai asal kamu dan simbok tetap hidup,” ujarnya pilu. “Tolong, lepaskan Lanang, Lek.”
“Kamu jalan dulu, baru aku lepaskan Lanang,” sahut Si Tinggi Besar.
Surtinah menuruti perintah Si Tinggi Besar. Ia berjalan gontai kembali ke Tretes. Taklama kemudian Lanang menjajari langkahnya. Mereka seperti dua pencuri yang tertangkap basah oleh penjaga desa.
“Bocah kurang ajar!” Tamparan Tjokro mendarat di pipi Lanang dan Surtinah bergantian ketika mereka sampai di rumah. Wajah lelaki itu kaku sementara kedua matanya seolah dipenuhi bara api.
Ketiga lelaki yang ternyata suruhan Tjokro agar mengawasi gerak-gerik Surtinah bergerak menjauh lalu berdiri di bawah pohon sukun. Mereka orang-orang kebun kopi dari desa lain.
“Kalian pikir bapakmu ini bisa dibohongi, hah?” Lagi sebuah tamparan mendarat di pipi kedua anaknya.
Sumirah menubruk Tjokro kemudian bersiumpuh di kaki sang suami. “Sudah, Pak, Sudah. Ini salahku. Aku yang menyuruh Tinah pergi dari rumah.”
“Diam di situ!” Hardik Tjokro pada Jaka yang ingin mengikuti jejak simboknya.
“Tinah, kamu ingin keluargamu hancur? Kamu ingin Tuan Willem murka dan membunuh kami, hah?”
Tubuh Surtinah bergetar hebat. Lumat sudah nyali di hati yang semat membara. Surtinah jatuh terduduk di tanah. Air matanya tumpah.
“Bawa anakmu masuk, Bune.” Tjokro menarik tubuh istrinya hingga berdiri berhadapan. Suaranya sedikit melunak dan otot-otot di wajahnya mengendur. “Bawa dia masuk dan siapkan dengan baik. Lusa, utusan Tuan Willem akan datang menjemput.”
Sumirah mengiyakan perintah suaminya. Ia merengkuh tubuh Lanang yang juga terduduk lemah di samping Surtinah. “Masuk, Le.”
Lanang mengangguk.
Jaka mengulurkan tangan, membantu Lanang berdiri.
“Maafkan, Simbok, Nduk.” Sumirah memeluk Surtinah. “Maafkan, Simbok. Ayo masuk.” Sumirah berdiri dan menarik tubuh Surtinah lalu membimbingnya masuk ke bilik.
Waktu bergerak cepat seperti putaran turbin di dekat rumah salah satu pegawai perkebunan. Hari yang ditentukan tiba. Dengan berat hati, Sumirah mendandani gadisnya.
“Nduk Tinah, Cah Ayu.” Sumirah menangkupkan kedua telapak tangan di pipi Surtinah. Ia baru saja selesai merias putrinya. Meski tidak tebal, tetapi cukup membuat Surtinah terlihat ayu dan menarik.
“Simbok tahu perasaanmu. Tapi Simbok harap kamu jangan putus asa. Teruslah mencari cara melepaskan diri dari Tuan Willem. Entah kapan waktunya, Gusti Penguasa Alam pasti suatu hari memberimu jalan.”
Surtinah bergeming. Semangatnya telah tercerabut dari tubuh. Ia seperti mesin penggiling kopi yang mendadak ngadat.
“Jangan pernah menangis lagi. Jangan biarkan orang menganggapmu lemah karena melihat air matamu tumpah.”
Surtinah membiarkan simboknya bermonolog. Ia telah habis kata.
Matahari sepenggalah ketika terdengar derap langkah kaki kuda yang semakin lama semakin jelas. Taklama kemudian terdengar Tjokro memanggil istri dan anaknya.
“Silakan duduk dulu, Kang.” Tjokro memberi isyarat pada Sukardi untuk duduk di amben.
“Aku tidak punya banyak waktu,” ujar Sukardi dingin.
Air muka Tjokro berubah sekian detik kemudian kembali normal. Ia kembali menyebut nama Surtinah dan memintanya keluar.
“Anak saya sudah siap, Kang.” Tjokro meraih lengan Surtinah.
Sukardi memindai tubuh gadis ayu di hadapannya. “Cantik,” batinnya bungah. “Tuan Willem pasti akan jatuh cinta.”
“Naikkan dia ke atas delman!”
Tjokro mengangguk lalu membawa Surtinah keluar. Di balik dinding pembatas ruang tamu, Sumirah tergugu. Andai tidak ingat dosa, ia ingin mengakhiri hidupnya saat itu juga.
Sukardi memerintahkan kusir menghela kuda ketika ia dan Surtinah telah berada di atas delman. Detik berikutnya, roda-roda andong bergerak melibas jalanan tanah berdebu. Surai kuda bergerak-gerak seiring langkah kakinya.
Lelaki berwajah sangar itu menoleh dan melihat Surtinah sekilas. “Jangan sampai Nyai memasang wajah kusut saat bertemu Tuan Willem nanti.”
Surtinah melengos.
“Tuan Willem orang yang baik. Dia tidak akan menyakiti Nyai. Hidup Nyai akan nyaman bersamanya.”
Surtinah meremas tas kain di tangan lalu meraba salah satu cundrik yang ia simpan di balik stagen. Ingin rasanya ia menikamkan cundrik itu ke dada Sukardi.
“Nyai harus berterima kasih pada Tjokro karena sudah mengirim pada orang yang tepat.”
Surtinah menggigit bibir. Sekuat tenaga ia menahan tangis. Ia tidak boleh terlihat kalah.
“Ada yang ingin Nyai lakukan sebelum kita ke pergi ke kota?” Sukardi menatap Surtinah.
Surtinah tergeragap. “Saya ingin bertemu Lanang dan Jaka,” sahutnya cepat.
Bab 7: Bunga Yang Terenggut Paksa (7)
Sukardi menatap Surtinah penuh rasa curiga. Kabar tentang kaburnya gadis itu tempo hari belum tanggal dari ingatan.
“Sa-saya hanya ingin memeluk Lanang dan Jaka untuk terakhir kalinya, Kang.” Surtinah memasang wajah memelas. Ia berusaha melibas amarah agar bisa bersikap baik pada Sukardi sehingga diizinkan untuk bertemu dengan Lanang dan Jaka walau sekejap.
Permintaan Surtinah bersambut sunyi. Alih-alih menjawab, jongos Willem itu justru kembali menatap lurus ke depan seolah kata-kata Surtinah hanya butiran debu yang diterbangkan angin.
Surtinah tertunduk lesu sembari diam-diam merapal doa semoga suatu hari Pemilik Kehidupan masih memberi kesempatan padanya untuk bertemu dengan Lanang dan Jaka. Keduanya dan simbok adalah penerang kala gelap dan pelepas dahaga di bawah tikaman sinar matahari yang terik. Hidupnya tanpa mereka seperti bunga yang tercerabut paksa dari tanah, perlahan layu, lalu mati.
“Kita ke kebun kopi dulu, Kang.” Suara Sukardi menyelip di antara bising tapak kaki kuda dan putaran roda melintasi jalan ketika mereka tiba di persimpangan jalan di ujung desa.
Suara Sukardi menarik Surtinah dari kubangan luka. Matanya menatap takpercaya tubuh tegap Sukardi yang tidak menoleh sedikit pun padanya. Buru-buru Surtinah mengusap wajah dengan selendang dan memasang mimik setenang mungkin. Ia tidak ingin terlihat kalah di depan Lanang dan Jaka.
Kusir menghentikan delman di tepi perkebunan. Surtinah menatap pilu deretan robusta dengan biji-biji berwarna merah cerah yang menyembul di antara dedaunan yang lebar dan sedikit kasar. Hanya berbilang jam, hidupnya akan berubah.
Salah satu mandor besar yang kebetulan berada di bibir kebun menghampiri Sukardi. Atas bantuan lelaki berkumis tebal itu, mandor besar mengizinkan Surtinah menemui Lanang dan Jaka.
“Titip simbok ya, Nang, Ka.” Surtinah memeluk kedua adiknya bergantian dengan mata berembun.
Lanang dan Jaka membisu.
“Doakan mbakyumu ini.” Surtinah tersekat di ujung kalimat. Kecewa, marah, sakit hati, berkelindan di dalam dada.
Lanang dan Jaka membeku.
“Aku pamit. Baik-baik di rumah, jaga simbok.” Surtinah mengusap pucuk kepala kedua adiknya penuh kasih.
Jaka menunduk. Mulutnya terkunci rapat. Ratusan kata ingin ia lontarkan, tetapi tenggorokannya seolah dipenuhi biji kopi sehingga sesak di dada takpernah terucap.
Lanang menatap lurus ke depan dengan tangan terkepal dan wajah kaku. Kepergian Surtinah seperti tusukan pedang yang tepat mengenai jantung. Ia menggelepar dalam genangan rasa sakit akibat tidak mampu menyelamatkan sang kakak dari perbudakan.
“Jangan lama-lama, Nyai. Waktu kita terbatas.”
Lanang menatap sengit Sukardi. Panggilan nyai pada Surtinah terdengar seperti suara benturan cangkul pada batu cadas. Kering, tajam, dan menyakitkan. Otot-otot kedua lengannya bertonjolan sementara dadanya naik turun.
“Sudah ya, Nang, Ka.” Surtinah membalikkan badan lalu berjalan cepat menuju delman. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Hatinya kini lumat tak bersisa.
Sedu sedan Surtinah mengiringi perjalanan mereka menuju bekas rumah yang ditempati Willem selama bertugas di Tretes.
“Tolong berhentilah menangis, Nyai. Tuan Willem tidak akan suka melihat wajah Nyai yang murung. Dia sangat perasa.” Sukardi memiringkan tubuh. Tatapannya memindai wajah layu tak bersemangat milik Surtinah.
Gadis berkebaya kunig gading itu mengusap kasar wajahnya. “Kalau memang Tuan Willem seorang yang baik, tidakkah ia jatuh iba padaku dan bersedia mengembalikanku pada bapak dan simbok?”
Sukardi menggeleng seraya menatap prihatin Surtinah. “Asal Anda tahu, Nyai, kalau tidak pada Tuan Willem, pasti Tjokro akan menawarkan Anda pada kepala pabrik, administratur perkebunan, dan tuan-tuan londo lainnya. Dia sangat menginginkan jabatan mandor besar dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya hanya dengan menjual Anda.”
Mulut Surtinah terbuka lalu tertutup kembali, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rasanya ia ingin masuk ke mesin penggiling kopi dan berputar di dalamnya hingga menjadi butiran sehalus debu.
“Anda beruntung, Tuan Willem yang dipilih pertama kali dan bersedia. Saya berani menjamin, dari semua tuan londo yang ada di perkebunan ini, Tuan Willemlah yang memiliki perangai paling santun.”
Surtinah terhempas. Hari ini, ia merasa hidupnya telah berakhir. Keterangan Sukardi mengakhiri segala kegaduhan di kepala dan hatinya. Sepertinya ia memang harus menerima dan menjalani takdir ini.
Delman berhenti taklama setelah Sukardi mengakhiri kalimat.
“Aku bisa turun sendiri, Kang.” Suara Surtinah terdengar dingin ketika Sukardi menyediakan tangannya untuk membantu turun dari delman.
Helaan napas berat Sukardi mengapung di udara. Ia menggeser tubuh agar Surtinah bisa turun.
Sukardi memberi perintah pada Surtinah untuk memasuki mobil yang telah menunggu di halaman.
Surtinah menghirup oksigen sebanyak mungkin, mengisi rongga dada dengan paru-paru lalu menyapukan pandangan ke halaman dan ke kebun kopi di kejauhan. Dalam hati, gadis berkebaya kuning itu mengucapkan selamat tinggal pada tanah kelahirannya.
“Mari, Nyai. Perjalanan kita masih cukup panjang.” Sukardi sengaja berdiri tidak jauh dari Surtinah karena dua kali panggilan sebelumnya hanya bersambut sunyi. Gadis pilihan Willem itu hanya bergeming meski suaranya cukup keras.
Perlahan, Surtinah melangkah mendekati mobil. Sejurus kemudian, sopir berkemeja putih yang duduk di balik kemudi menginjak pedal gas.
Benar kata Sukardi, perjalanan menuju kota Malang ternyata cukup panjang. Meski disergap lelah dan kantuk, Surtinah berusaha tetap membuka mata. Ia tidak terlalu percaya pada dua lelaki yang ada di kursi depan. Mata gadis itu menatap keluar jendela seraya sesekali melirik Sukardi dan sopir utusan Willem. Salah satu tangannya yang memegang cundrik ia selipkan ke dalam tas agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Lewat tengah hari, mobil melewati alun-alun kota Malang. Surtinah menatap takjub pemandangan yang tersaji di depan mata. Ia belum pernah melihat bangunan-bangunan sebagus itu. Selama ini, gedung terbesar yang pernah ia lihat adalah pabrik kopi. Bekas rumah Willem yang konon paling bagus di antara rumah-rumah tuan londo lainnya pun tidak sebagus yang ada di kota.
Bendera Kerajaan Belanda berkibar di halaman sebuah gedung megah dengan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Deretan huruf yang tidak dimengerti Surtinah tersusun rapi di dinding gedung bagian depan.
“Ini kantor Tuan Willem, Nyai.” Sukardi tersenyum bangga lalu menyebut istilah Belanda yang terdengar asing di telinga Surtinah.
“Sayang, Tuan Willem sedang ada urusan di Surabaya. Mungkin akhir pekan baru kembali. Kalau dia ada, saya kira Nyai bisa mampir sebentar untuk bertemu.”
Surtinah membiarkan kalimat Sukardi dipeluk angin. Membayangkan berada di antara meneer-meneer Belanda saja dia tidak pernah, apalagi nekad mendatangi tempat mereka berkumpul. Cari mati namanya.
Mobil memasuki jalanan yang lebar dan lengang dengan deretan pohon palem di kiri dan kanannya. Sebuah kanal selebar dua meter mengalirkan air yang jernih di bagian kiri sementara deretan rumah bergaya Eropa berdiri di sisi kanan.
Sesampainya di persimpangan, mobil berbelok ke kiri memasuki sebuah gang dengan plengkung di atasnya. Lagi-lagi Surtinah gagal memahami deretan huruf yang terpatri pada plengkung itu. Detik ini, ia menyesal tidak mengikuti ajakan Lanang untuk belajar pada Tuan Haji Ismail.
Akhirnya, sopir menghentikan mobil di halaman sebuah rumah berukuran sedang, tetapi terlihat anggun. Surtinah mengerjapkan mata, serasa mimpi ia akan tinggal di rumah seindah itu.
“Kita sudah sampai, Nyai.” Sukardi membuka pintu mobil dan memberi isyarat pada Surtinah untuk turun.
Bab 8: Selamat Datang Nyai
Kesiur angin menyambut tubuh Surtinah saat turun dari mobil. Sekian detik ia terpasak di bibir halaman dengan hamparan rumput serupa karpet berwarna hijau. Sebuah kolam ikan dengan jembatan di tengahnya berada di tengah halaman.Hati Surtinah sedikit terhibur melihat deretan bunga warna-warni di sisi tembok tinggi yang mengelilingi rumah ini.Sepertinya rumah Willem cukup nyaman.
Pintu rumah terbuka dan seorang perempuan seusia simbok keluar.Senyum secerah matahari pagi mekar sempurna di wajahnya.
Melihat perempuan yang terlihat rapi dan resik itu, refleks Surtinah membetulkan kebaya dan wiru jariknya yang sedikit kacau. Setelah itu, ia mengusap wajah dan merapikan anak-anak rambut yang keluar dari gelungan. Ia yakin, saat ini pasti penampilannya terlihat masai dan layu.
“Ini Narti yang akan mengurus segala keperluan Nyai di sini.”Sukardi memperkenalkan perempuan itu ketika mereka telah berhadapan.
“Selamat datang, Nyai.Silakan masuk.” Narti tersenyum hangat lalu meraih tas dari tangan Surtinah.
Surtinah tersenyum gugup.“Oh, saya bisa membawa sendiri.Tidak usah repot-repot,” tolak Surtinah halus.Ia merasa tidak sopan membiarkan perempuan seusia simbok membawakan barangnya yang tidak seberapa berat.
Narti tersenyum.“Tidak apa-apa, Nyai.Sudah menjadi tugas saya untuk melakukannya.”Ia menarik tas dari tangan Surtinah.
“Anda bukan lagi Surtinah putri Tjokro, Nyai.”Suara Sukardi seperti benang yang menarik kepala Surtinah sehingga tatapan keduanya bersirobok.“Mulai hari ini Anda nyai di rumah ini dan Tuan Willem sudah meminta kami untuk melayani Anda.Jadi jangan sungkan.”Sukardi melukis senyum.
“Betul, Nyai. Mari masuk.”Narti menggamit lengan Surtinah dan membimbingnya memasuki rumah.“Saya yakin Nyai betah di sini.Tuan Willem sudah menyiapkan semuanya dengan baik dan cermat.”
Diiringi degup jantung yang lebih cepat dari biasanya, Surtinah mengedarkan pandangan ketika kakinya menjejak bagian dalam rumah sementara otaknya merekam kalimat demi kalimat yang keluar dari lisan Narti.Matanya menangkap sebuah rak buku di salah satu sisi ruang tamu dan rak berisi guci dan aneka pajangan lainnya di dekat jendela sementara di setiap sudut ruang tamu terdapat lampu yang tertempel di dinding.
“Rumah ini dibeli Tuan William sebulan lalu dan baru selesai diperbaiki sesuai keinginan beliau sekitar dua minggu lalu, Nyai.”
Kaki Surtinah melangkah menuju bagian tengah rumah, tempat di mana meja makan berbentuk oval dengan empat kursi berada di tengah.Dua buah rak buku dengan ujung saling bersentuhan menempel di dua sisi dinding.
Surtinah berdiri di depanlemari buku setinggi dua meter yang dipenuhi buku. Gemetar tangannya membuka pintu kaca lalu meraba buku-buku yang tersusun rapi.Seketika ingatannya kembali pada Lanang dan Jaka.Mereka pasti senang kalau memiliki buku-buku ini. Mereka pasti akan lebih pintar dari bangsa kulit putih dan tidak perlu menjadi buruh petik kopi lagi.
Ingatan-ingatan tentang kedua adik dan nasib dirinya yang harus kalah karena kebodohan membuat mata Surtinah menghangat.
“Nyai ingin membaca buku-buku itu?”Narti berdiri di samping Surtinah.
Buru-buru gadis ayu itu mengusap ujung mata.“A-aku tidak bisa membaca, Mbok.”Ada yang berdenyut nyeri di sudut hatinya ketika kalimat itu terucap.
“Oh, maaf, Nyai, saya tidak tahu,” sesal Narti.
“Tidak apa-apa, Mbok.Makanya saya dijual ke Tuan Willem.Kalau saya pintar dan terpelajar seperti nona-nona Belanda itu, saya tidak akan jadi nyai.”Surtinah mencoba kembali bersikap biasa.Selarik senyum tersungging di bibir demi menyamarkan gemuruh di dada.
Sejak dulu bapak tidak pernah mengizinkan Surtinah untuk sekolah. Lelaki itu berpikir jika perempuan akan menghabiskan hidupnya di dapur, sumur, dan kasur, dan semua itu tidak membutuhkan sekolah. Cukup belajar dari orang-orang tua untuk bisa menjadi istri dan ibu yang baik.Sementara itu, Jaka dan Lanang hanya sebentar belajar di sekolah rakyat karena harus menjadi buruh di kebun kopi.Belakangan, Tjokro mengizinkan dua anak lelakinya belajar pada Tuan Haji Ismail. Surtinah tidak tahu alasan bapak berubah pikiran karena ia hampir tidak pernah terlibat pembicaraan penting dengan bapaknya.
“Semua sudah jadi takdir kita, Nyai.”Narti menatap lamat gadis di sampingnya. Perlahan ia mulai meraba jika Surtinah menyimpan beban berat di hati. “Siapa tahu Tuan Willem berbaik hati mengizinkan Nyai belajar.”
Surtinah menatap heran Narti.Ia bahkan tidak pernah berpikir Willem akan memperbolehkannya keluar rumah. Sebelum jadi nyai di rumahnya saja ia tidak diperbolehkan menghirup udara luar, apatah lagi setelah di sini. Benar-benar sangkar emas.
“Tuan Willem orang yang baik perangainya, halus tutur katanya.Ambil hati Tuan Willem dan minta padanya agar Nyai diizinkan belajar.”Narti meraih tangan Surtinah lalu menggenggamnya erat.
Ah, semua kemungkinan itu tidak pernah terlintas dalam benar Surtinah. Ia bisa melalu hidupnya di sini tanpa menjadi gila saja sudah bersyukur.
“Sepertinya Nyai sudah sangat lelah.Mari saya antar ke kamar.Nyai bisa beristirahat sambil menunggu makan malam siap.”
Narti menutup pintu lemari kemudian membimbing Surtinah menuju salah satu kamar yang terletak di sebelah selatan.
Kedua mata Surtinah membulat sempurna ketika tiba di kamarnya.
“Silakan istirahat dulu, Nyai.Nanti saat makan malam siap, saya akan panggil.” Narti tersenyum lalu meletakkan tas di atas meja di dekat ranjang. Jenak berikutnya, ia membuka pintu lemari baju dan memindah pakaian dari tas ke dalam lemari.
“Maaf, Nyai, baju-baju yang dibawa Nyai saya letakkan di rak paling bawah. Nyai tidak perlu memakai baju-baju itu lagi karena Tuan Willem sudah menyiapkan baju untuk Nyai.”Tangan Narti menyentuh deretan kebaya putih yang tergantung rapi di dalam lemari.
Surtinah memangkas jarak lalu menyentuhkan tangannya ke kebaya-kebaya itu dengan tatapan kagum.Kebaya dengan bordir di bagian bawah dan lengan itu terbuat dari kain yang halus, sangat berbeda dengan baju-bajunya selama ini.
“Ini semua buat saya, Mbok?”Surtinah meraih jarik dari tumpukan kain di rak kedua dari bawah.Jarik yang disediakan untuknya juga terbuat dari kain yang halus.
“Iya, Nyai. Semua untuk Nyai.”
“Ke-kenapa semua kebaya berwarna putih?”
“Sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis kalau seorang nyai berkebaya putih.”Narti tersenyum.
Embusan napas kasar keluar dari bibir Surtinah. Jadi, setelah ini, semua orang akan tahu kalau dirinya seorang nyai hanya dengan melihat pakaian yang dikenakannya saja. “Sungguh terlalu!” batinnya rusuh.Harga dirinya benar-benar telah runtuh.
“Baik, Nyai, saya tinggal dulu. Kalau ingin membersihkan diri, ini kamar mandinya dan handuk ada di dalam lemari.”Narti menunjuk sebuah ruang kecil.
Surtinah menelengkan kepala, “Kamar mandi?”
“Iya, kamar mandi, tempat bangsa kulit putih membersihkan diri.”Narti membuka pintu kayu sehingga terlihat bagian dalam kamar mandi dengan tendon air dan gayung serta perlengkapan mandi lainnya.
Surtinah mengangguk.Ia akan mempelajarinya nanti. Saat ini tubuhnya terlalu lelah untuk berpikir.
“Saya kira sudah cukup, Nyai.Saya pamit ke belakang dulu.”Narti beringsut lalu menutup pintu kamar.
Sepeninggal Narti, Surtinah duduk di bibir ranjang. Tangannya mengelus seprai yang halus dan menepuk-nepuk kasur, bantal, dan guling yang empuk dan nyaman.Kantuk dan penat yang sejak tadi telah menggelayuti tubuh menarik Surtinah untuk segera membaringkan badan dan taklama kemudian matanya telah terpejam sempurna.
Entah berapa lama Surtinah tertidur.Ia tergeragap ketika merasakan tepukan di paha sementara telinganya menangkap suara Narti memanggil namanya.
“Bangun, Nyai. Rupanya Tuan Willem tidak jadi pergi ke Surabaya dan akan pulang malam ini. Nyai harus bersiap menyambutnya.”
Bab 9: Engkau Milikku
Surtinah tergeragap. Sepertinya belum lama ia membaringkan tubuh di kasur empuk sudah harus bangun. “Siapa yang datang, Mbok?” tanyanya seraya menggelung rambut.
“Tuan Willem tidak jadi ke Surabaya. Jadi sekarang Nyai harus bersiap untuk menyambutnya.”
Seketika wajah Surtinah berselimut kabut. Tubuh tinggi tegap Willem dengan raut wajah yang tenang berwibawa, tetapi sedikit intimidatif terbayang di rongga mata.
“Nyai tidak perlu takut, semua akan baik-baik saja,” ujar Narti ketika melihat paras ayu Surtinah memucat. “Saya ambilkan air mandi dulu.” Narti bergegas keluar dan kembali dengan wadah berisi air panas. Aroma rempah dan wangi bunga meruah seiring kepulan asap yang keluar dari baskom. Perempuan cekatan itu kemudian menjelaskan pada Surtinah tata cara mandi bangsa kulit putih yang terasa asing.
Surtinah mandi dengan cepat meski sebenarnya ingin berlama-lama menggosok badan dengan sabun karena Narti telah mewanti-wanti agar saat Willem datang ia sudah harus siap. Surtinah mandi pakai sabun jika pemilik perkebunan membuka pasar dadakan setiap dua bulan sekali selama satu minggu dan membawa barang-barang dari kota. Selebihnya, ia dan simbok membuat lulur dari beras yang ditumbuk dan kunyit setiap seminggu dua kali atau cukup menggosok dengan batu apung jika sabun telah habis.
Narti menyiapkan semua keperluan Surtinah saat gadis itu mandi. Tangan babu di rumah Willem itu bergerak cepat mendandani Surtinah setelah gadis itu selesai mandi.
“Biar saya pakai sendiri jariknya, Mbok.” Lagi-lagi Surtinah merasa malu ketika Narti memakaikan jarik. Ia benar-benar merasa kurang ajar karena membiarkan orang yang lebih tua mengurus dirinya.
“Hasil wiru Nyai tidak terlalu halus. Biar saya yang melakukannya.” Narti menatap sekilas wajah Surtinah seraya melempar senyum lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya.
Surtinah melongo. Dari mana Narti tahu kalau ia tidak terlalu pintar mewiru jarik. “Ah, sudahlah. Aku turuti saja apa pun perintahnya,” batinnya kemudian.
Usai mendandani, Narti tersenyum puas melihat tampilan majikannya. Ia menyematkan bros putih bersusun dua dengan untaian manik-manik yang menjuntai tepat di tengah kebaya. Terakhir, ia menyematkan tusuk konde dengan untaian manik-manik berwarna emas pada gelungan rambut Surtinah.
Surtinah membekap mulut yang ternganga dengan tangannya ketika melihat pantulan dirinya di cermin. Seketika ingatannya terbang ke dongeng-dongeng tentang putri dari kayangan yang sering diceritakan simbok. “Apakah saat ini ia secantik mereka,” batinnya. Namun, buru-buru dihapusnya pikiran konyol itu. “Mana mungkin putri dari kayangan jadi gundik tuan londo.”
“Mari, Nyai, kita siapkan makan malam.” Narti menggamit lengan Surtinah dan membawanya ke dapur.
“Perkenalkan, ini Wilma, koki di rumah ini.” Narti menunjuk perempuan berkulit putih dengan rambut cokelat yang tersenyum ramah padanya.
Surtinah tersenyum canggung sembari mengangguk sopan.
“Silakan minum dulu, Nyai. Sepertinya sejak tiba Nyai belum menelan apa pun.” Wilma menyodorkan secangkir teh dan beberapa potong kue berwarna cokelat yang terlihat asing di mata Surtinah.
“Kalian berdua tidak minum?” tanya Surtinah gugup.
“Kami sudah makan, Nyai.” Narti tersenyum kemudian membantu Wilma memasak.
Lagi-lagi Surtinah merasa tidak enak karena menikmati teh sendirian. Di rumah, ia biasa minum teh bersama-sama sembari mengobrol. Hanya bapak yang jarang ikut masuk dalam pembicaraan karena lelaki itu sering minum teh cepat-cepat seolah ada hantu pemburu yang mengejarnya.
Surtinah tergerak melahap dua potong kue dan menandaskan isi cangkir setelah Narti kembali menegur dan mengingatkannya agar bergerak cepat karena khawatir Willem keburu tiba sebelum semua siap. Setelah itu, sepanjang senja hingga petang, Surtinah terus mendengar ocehan Narti tentang kebiasaan Willem dari soal makan hingga tempat meletakkan barang-barang dan ia harus bekerja keras merekam semuanya dan menyimpan dalam memori di kepala.
Deru mesin mobil menerobos telinga ketika Surtinah meletakkan semangkuk lodeh di atas meja. Ia menoleh ke arah ruang tamu dengan jantung berdegup kencang. Malam telah sempurna memeluk bumi dan ia harus bersiap menghadapi takdir paling buruk dalam hidupnya.
“Ayo kita sambut Tuan Willem, Nyai.” Narti menarik tangan Surtinah dan membawanya ke teras.
Surtinah terpasak di bawah bunga anggrek yang menempel di dinding sebelah selatan teras ketika Willem turun dari mobil. Ia mencekal lengan Narti ketika perempuan itu beringsut ingin meninggalkannya seorang diri menemui Willem.
“Tugas saya sudah selesai, Nyai. Kini Nyai yang harus melayani Tuan Besar.” Narti tersenyum penuh arti sembari melepas tangan Surtinah. Dalam hitungan detik, tubuh perempuan itu sudah lenyap di balik pintu ruang tamu.
Pandangan Surtinah terkunci pada tubuh Willem yang berajalan ke arahnya. Kedua tangannya meremas jarik. Ia lupa jika tindakannya akan merusak wiru yang sudah disusun sangat rapi oleh Narti.
“Selamat datang, Nyaiku.” Pemilik wajah tanpa kumis dan jambang itu tersenyum lalu meraih tangan Surtinah dan menciumnya.
Mata Surtinah membulat sempurna melihat sikap Willem. Hampir saja ia menarik tangannya jika tidak mengingat pesan Narti tentang kebiasaan bangsa kulit putih.
“Nyai cantik sekali malam ini.” Suara Willem terdengar tenang dan lembut. Sorot matanya teduh dan berwibawa.
“Te-terima kasih, Tuan. Biar saya bawakan barang-barang Anda.” Surtinah meraih tas dari tangan Willem kemudian bergegas masuk. Sungguh, ia ingin bisa terbang lalu bersembunyi di suatu tempat demi menghindari tatapan Willem yang memindai tubuhnya.
Sesuai arahan Narti, Surtinah menyiapkan semua keperluan Willem mulai dari air mandi hingga baju ganti. Merasa majikannya telah membersihkan diri, Surtinah memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Ia masuk ketika telinganya mendengar jawaban Willem.
“Ma-makan malam sudah siap, Tuan. A-Apa Anda ingin makan di kamar?” Surtinah berdiri kaku di ambang pintu. Susah payah ditahannya gemuruh di hati saat melihat Willem tengah meraih kaus lalu memakainya.
Willem menoleh. “Tidak, Nyai. Aku ingin makan denganmu di ruang tengah.” Ia mengurai senyum lalu berjalan mendekat.
Surtinah menggeser tubuh agar Willem bisa lewat. Gadis itu tersirap ketika Willem menggamit lengannya lalu membawanya ke ruang tengah. Sesampainya di dekat meja makan, Willem menarik kursi dan meminta Surtinah duduk.
Sepanjang makan malam, hati dan pikiran Surtinah begitu gaduh. Di satu sisi ia tidak mengira kalau Willem memperlakukannya dengan baik, tetapi di sisi lain ia tetap merasa terancam dan tidak rela dirinya jatuh ke pelukan lelaki itu.
Meski suasana hatinya tidak baik, Surtinah mencoba menanggapi setiap Willem mengajaknya bicara. Ia tidak ingin merusak suasana hati Willem yang tampaknya sedang bahagia. Siapa tahu ada kesempatan baginya untuk membujuk meneer Belanda itu agar melepaskannya.
“Duduk di sini, Nyai.” Willem menggeser kursi dengan lengan berbentuk lengkung yang berada di dekat meja bundar ketika Surtinah mengantar kopi dan setoples kue kering. “Temani saya minum kopi.”
Surtinah menurut. Kini ia duduk di samping Willem menghadap ke arah jendela sehingga ia bisa melihat halaman yang tampak indah di bawah temaram cahaya lampu taman.
“Ada yang ingin aku bicarakan.” Suara Willem terdengar berat. Ia memasang wajah serius. “Pernahkah Nyai membeli sesuatu di pasar?” tanyanya kemudian.
Surtinah mendongakkan wajah. “Pernah, Tuan.”
“Apa yang Nyai lakukan setelah membayar barang yang dibeli?”
“Pasti akan saya bawa pulang, Tuan.”
“Setelah itu?” Willem menaikkan salah satu alisnya.
Surtinah mengernyitkan dahi.
“Apa yang Nyai lakukan dengan barang itu di rumah? Disimpan atau dipakai?” Willem mengulang pertanyaan ketika melihat tatapan bingung Surtinah.
“Tentu saja saya pakai, Tuan. Apalah gunanya membeli barang jika tidak dipakai.”
Willem tersenyum. “Begitu juga yang terjadi padamu dan aku, Nyai. Aku adalah pembeli dan Tjokro penjualnya.”
Sekian detik Surtinah ternganga. “Ta-tapi saya bukan barang, Tuan.” Ia kini mengerti arah pembicaraan Willem.
“Itu anggapan Nyai. Tidak dengan Tjokro. Ia nyata-nyata telah memberikan Nyai padaku setelah aku memberi sejumlah uang dan jabatan mandor besar.”
Bab 10: Engkau Milikku (2)
Surtinah kembali tertunduk, sadar jika posisinya tersudut.
“Setelah aku bayar, tentu apa yang ditawarkan Tjokro kubawa pulang dan kugunakan sesuai keinginanku karena ia sudah jadi milikku.”
Surtinah menggigit bibir sementara jemarinya saling bertaut.
Willem menarik napas panjang. Hatinya jatuh iba pada gadis di hadapannya. Namun, ia terlanjur tertawan senyum dan mata bening Surtinah dan tidak ada niatan untuk membebaskannya. Sejak pertama kali bertemu, Willem melihat gejolak tersembunyi di mata Surtinah yang membuatnya terpikat.
“Aku tahu jalan ini berat buat Nyai. Tapi semua sudah terjadi. Aku berjanji akan memperlakukan Nyai dengan baik.”
Tangan Willem meraih dagu Surtinah dan mendongakkannya. Tatapan Willem menerobos rongga mata Surtinah, mencoba menyelami segala rasa yang taksempat terucap. Sejurus kemudian ia melipat jarak selama sekian detik. Sekian detik yang mampu menghentikan aliran darah di tubuh Surtinah dan membuat jantungnya seolah akan melompat keluar.
Hampir saja telapak tangan Surtinah jatuh ke pipi Willem ketika lelaki itu menjauhkan wajah seraya tersenyum. Namun, gerakannya terhenti di udara kala kesadarannya kembali. Posisinya berada di pihak yang kalah. Kesalahan bertindak hanya akan membuat nasibnya semakin suram. Surtinah memalingkan muka demi mengusir kesal seraya mengusap kasar bibirnya dengan punggung tangan.
Alih-alih marah saat Surtinah hendak menamparnya, Willem justur tersenyum. “Nyai perempuan terhormat, memiliki harga diri. Nyai tidak murahan. Itulah kenapa tawaran Tjokro aku terima.” Lelaki itu menjeda kalimat dengan satu tarikan napas panjang. “Pikirkan baik-baik kata-kataku tadi, Nyai. Aku harap kita bisa bekerja sama.” Willem menyugar rambut yang disisir rapi lalu meraih cangkir dan menyesap isinya. “Sekarang pergilah tidur. Nyai pasti lelah. ”
“Ba-baik, Tuan.”
Gegas Surtinah berjalan menuju kamar. Ia menarik napas lega karena Willem masih memberi waktu. Sesampainya di dalam kamar, berkali-kali ia menggosok bibir dan berkumur-kumur hingga merasa tidak ada lagi bekas bibir Willem yang tertinggal.
“Sungguh menyebalkan!” Surtinah mengomel. Sedih, kesal, kecewa berkelindan dalam hati menyadari lelaki yang menyentuhnya pertama kali bukan suaminya seperti yang selama ini ia idamkan.
Usai menggosok bibir, Surtinah berdiri di balik jendela. Gadis itu berjalan mondar-mandir di dalam kamar lalu berdiri di balik jendela. Saraf-saraf otaknya mulai memikirkan cara untuk kabur dari sangkar emas. Ia bisa saja kabur lewat jendela, tetapi tidak akan bisa keluar karena rumah Willem dijaga dua centeng di dekat gerbang. Selain itu, ia belum kenal daerah ini dan terlalu beresiko jika harus kabur malam hari. Bisa-bisa keluar dari rumah harimau, ia akan disambut macan.
Surtinah mundur selangkah dengan wajah memucat ketika melihat Sukardi melihat ke arah jendela kamarnya. Sejak awal bertemu, Surtinah merasa jika jongos Willem itu seolah mempunya mata lebih dari dua yang digunakan untuk mengunci dirinya. Taklama kemudian seorang lelaki muda muncul dari halaman belakang dan berjalan menuju pintu gerbang. Surtinah melihat Sukardi menepuk bahu lelaki muda itu kemudian berjalan ke arah belakang. Jongos Willem itu sempat berhenti di tengah jalan lalu mendongak dan memandang ke arah jendela.
Lelah dengan semua kecamuk pikiran, Surtinah memutuskan untuk tidur. Selama matahari masih terbit, ia yakin kesempatan lari akan selalu ada. Ia memutuskan bersikap baik di depan Willem agar lelaki itu percaya dan tidak menaruh curiga padanya. Ia juga akan bersikap baik pada semua penghuni rumah, terkecuali Sukardi. Siapa tahu mereka bersedia membantunya kabur.
Surtinah mengawali hari lebih pagi dari semua penghuni rumah. Wilma datang tepat ketika ia menyeduh teh. Ia sudah diberitahu bagaimana menggunakan peralatan di dapur termasuk cara menyeduh teh dan kopi yang disukai Willem.
“Pagi sekali Nyai bangun hari ini.” Wilma menyapa hangat. Perempuan itu selalu terlihat riang sehingga membuat Surtinah nyaman. “Apa kamar Nyai tidak nyaman sehingga lekas bangun?”
“Tidak, Wilma. Semua menyenangkan. Saya belum pernah tidur di kasur seempuk itu.” Surtinah menyodorkan secangkir teh pada Wilma. “Minumlah dulu sebelum memasak.”
“Terima kasih, Nyai. Anda sungguh baik.” Wilma duduk lalu menyesap teh perlahan. “Nyai pintar menyeduh teh. Rasanya pas. Sepertinya Tuan Willem memilih orang yang tepat untuk menjadi nyainya.”
“Anda berlebihan. Saya tidak seterampil itu. Teh buatan simbok di desa masih lebih nikmat.” Surtinah meraih cangkir dan buru-buru menyeruput isinya demi menyembunyikan rasa malu. “Hari ini masak apa, Wilma?” ujarnya mengalihkan topik pembicaraan.
Wilma menyebut beberapa jenis makanan yang asing di telinga Surtinah. Perempuan bermata cokelat itu dengan senang hati mengajari Surtinah resep menu bangsa kulit putih. Meski tidak semua yang dikatakan Wilma bisa terekam memori di kepalanya, ia sangat berterima kasih karena bisa belajar banyak hal.
Matahari mulai mengintip di ufuk timur ketika Narti datang dan segera menyiapkan air mandi untuk Surtinah dan Willem yang ketika sudah siap segera dibawa Surtinah ke kamar Willem sementara Narti membawakan air mandinya.
Surtinah tidak kesulitan mengikuti rutinitas pagi yang padat karena sudah terbiasa. Willem tersenyum bungah melihat Surtinah begitu terampil dan telaten mengurus semua keperluannya. Meskipun masih terlihat sedikit muram dan menjaga jarak dengannya, ia yakin lambat laun gadis itu akan menerima takdirnya.
“Bagaimana tidur Nyai semalam?” Willem menatap Surtinah lamat-lamat. Mereka tengah sarapan di tempat minum kopi semalam. Bagian tengah rumah Willem menjorok ke depan dengan dinding kaca cukup lebar sehingga dari dalam akan terlihat keindahan halaman.
Willem memutar musik dari sebuah benda berbentuk bulat. Musik yang belum pernah mampir ke telinga Surtinah.
“Saya bisa tidur nyenyak, Tuan.”
“Syukurlah.” Willem tersenyum lalu mulai mengosongkan isi piringnya. Setelahnya, ia tidak banyak bicara.
“Nanti siang, Nyonya Anna akan datang mengantar gaun dan mengajari Nyai berdansa,” ujar William setelah menghabiskan sarapan.
“Saya kira baju-baju di lemari sudah cukup, Tuan. Anda terlalu berlebihan.”
Willem menggeleng. “Sesekali Nyai juga perlu memakai gaun. Apa Nyai tidak bosan memakai baju dengan model yang sama setiap hari?”
“Baik, Tuan. Terserah bagaimana baiknya saja.” Surtinah tidak bisa membayangkan dirinya memakai pakaian nona-nona Belanda. Entah bagaimana rupanya nanti. “Oh iya, apa itu dansa, Tuan?”
“Semacam menari bersama.”
Mulut Surtinah mengeluarkan bunyi huruf “O”. Ia tidak ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Toh nanti orang suruhan Willem akan menjelaskan dan mengajarinya.
“Apa berdansa menjadi salah satu tugas seorang nyai?”
Willem memperlihatkan deretan gigi seputih kapas miliknya. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Surtinah melihat Willem tertawa. Kesan serius dan sedikit intimidatif seketika hilang dari pemilik kulit sewarna susu itu.
Surtinah tersenyum malu, menyadari betapa konyol pertanyaannya.
“Tidak, Nyai. Dansa tidak menjadi kewajiban seorang nyai. Tapi sesekali kita harus menghadiri undangan dari teman dan sahabatku dan ada kalanya kita akan berdansa di sana. Karena sekarang aku sudah punya Nyai, aku tidak ingin berdansa dengan perempuan lain selain Nyai.”
Mata Surtinah membulat sempurna. Tangannya menyambar cangkir dan meneguk isinya cepat-cepat seolah ada tulang ayam yang tersangkut di tenggorokan dan harus digelontor dengan sebanyak mungkin cairan.
Bersambung
Kelanjutan cerita ini bisa dibaca dengan membeli buku cetak atau ebook.
Info dan pemesanan buku hubungi: 0882-2116-0714 atau klik link di awal postingan
Bab 11-15
https://karyakarsa.com/AnifahSetyawati/gadis-kawisari
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰