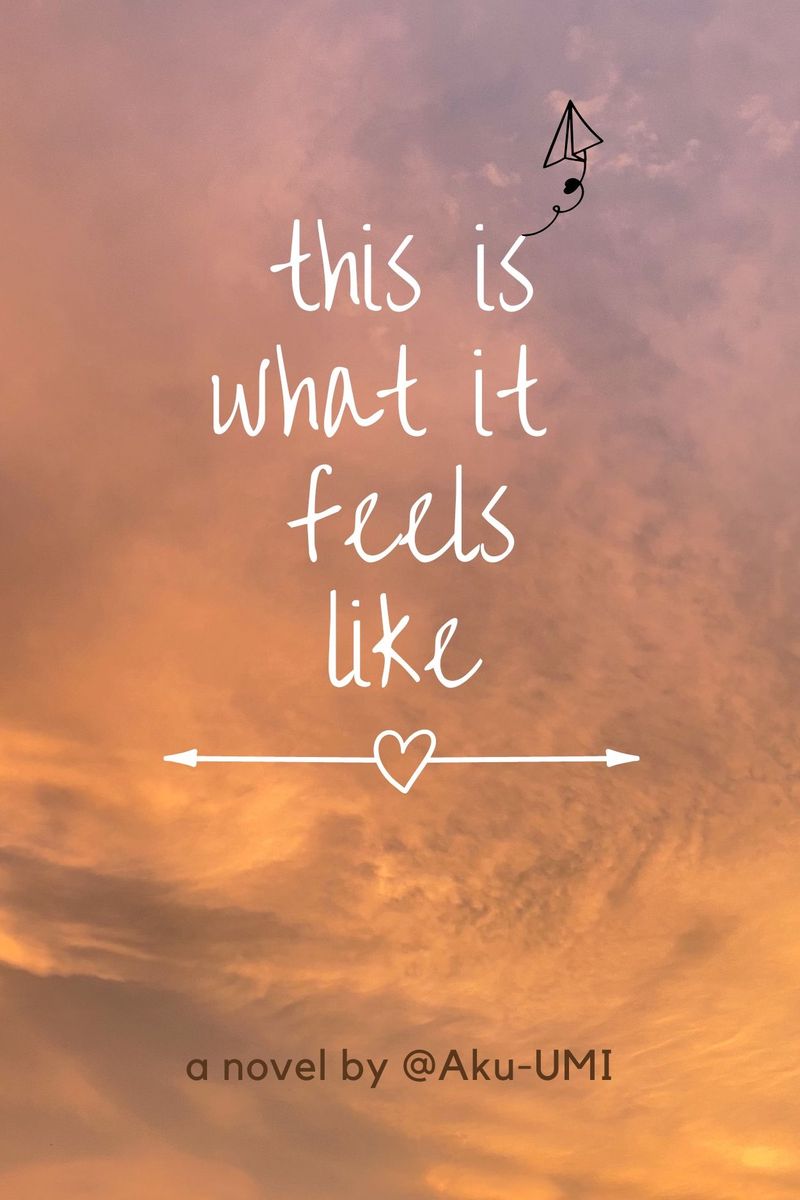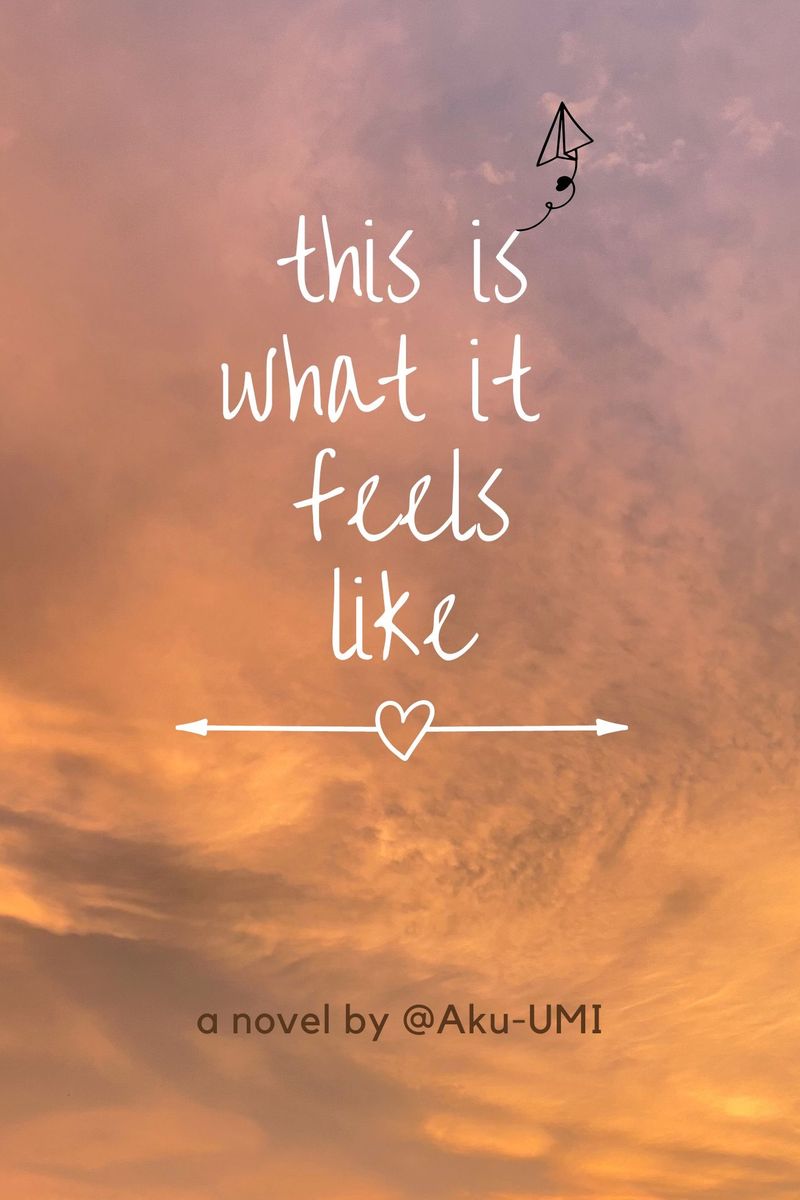
“Complicated seolah kasih kesan buruk. Sebuah masalah mungkin oke kalau disebut complicated. Atau konflik. Sementara hidupmu bukan sebuah masalah. Hidupmu nggak buruk. Aku punya waktu seumur hidup buat kamu ajak jalan-jalan ke tiap sudut hidupmu yang kompleks itu.”
Tiga, katanya
Hal pertama yang aku lakukan ketika harus pindah ke rumah ‘sebut saja’ suamiku adalah berpamitan dengan Papa Aji. Aku sudah menyiapkan banyak sekali kata-kata; termasuk permintaan maaf, penjelasan, juga penawaran untuk mengobati luka dan kecewanya nanti. Aku sudah sepenuhnya berubah menjadi manusia, menjadi anak yang mungkin tidak akan bisa disebut berbakti lagi.
Bahkan tujuanku menerima pernikahan ini pun bukan untuk menyenangkan hati orang tua, tetapi justru sebaliknya. Aku ingin memperlihatkan pada mereka, terutama Mama, bahwa dia juga bukan siapa-siapa dalam menerawang masa depan. Bahwa pengalamannya yang berjuta-juta tidak lantas bisa merendahkan kemampuanku dalam memilih jalan sendiri.
Dia bisa saja pernah keliru, masih keliru, dan akan keliru di masa depan. Seharusnya itu tak perlu terlalu mengganggunya, karena pada dasarnya, kita hanya manusia biasa, tak perlu memaksa untuk bisa belajar dari pengalaman dan seketika berubah menjadi yang terbaik.
Nasi sudah menjadi bubur, aku yang membuatnya kali ini, jadi aku juga yang akan memastikan tidak ada yang terbuang sia-sia. Ketika melambaikan tangan terakhir dari dalam mobil, aku melihat senyum yang begitu penuh bahagia di wajah Mama dan Papa Amar. Senyumku tak kalah hebat, aku benar-benar berterima kasih atas yang satu ini—kemampuanku dalam beradaptasi, berakting, dan apa pun namanya untuk menyesuaikan diri di setiap kondisi kehidupan. Karena detik setelah kaca mobil kembali naik, bibirku terkatup rapat.
Hening seketika menguasai kabin mobil, bahkan suara mesin tak pernah terdengar sebising ini.
“Mas Hans, tolong anter aku ke Tebet dulu.”
Dia menoleh, tak lama, tapi mata kami sudah sempat bertemu. Ketika dia bertanya pun, dia masih sesekali melirikku. “Mau ngapain ke Tebet? Arah kita bukan ke sana.”
Aku mengangguk. “Mau pamitan sama seseorang.”
“Pacarmu?”
Aku mengedikkan bahu.
Dia diam, tidak membalas atau mungkin tidak tertarik untuk mengulik kisah ini. Tidak, aku tidak kecewa atau sakit hati, karena sadar betul, siapa yang mendadak tertarik di pertemuan super singkat begini? Manusia perlu waktu untuk menyayangi orang lain, kecuali memberi rasa iba atas dasar kemanusiaan. Maka kamu tidak perlu mencari tahu siapa dia, layakkah dia sungguh-sungguh dibela, kamu bisa saja merasa terluka sebagai manusia ketika melihat manusia lain terluka.
Jadi yang aku lakukan sekarang, membantu perjalanannya dengan menyalakan maps dari handphone-ku. Dia hanya perlu mempercayai kehebatan teknologi saat ini, maka kita sudah sampai di tempat tujuan. Sebuah rumah yang aku sendiri bahkan baru beberapa kali menginjakkan kaki di sini, padahal seharusnya, mungkin seharusnya, aku bisa saja menghabiskan separuh hidupku di sini juga. Sebagai anak dari pemilik rumah ini. Anak yang tak resmi.
Hadir di luar pernikahan hanya akan merugikan si anak, betul?
Aku membasahi bibir, membenarkan rambut, memastikan pakaianku rapi, pada intinya aku sedang mempersiapkan diri sebelum penjelasan yang sebetulnya sudah aku duga tidak akan mudah. Tapi ada yang aneh, ketika aku menoleh ke kanan, aku terheran-heran melihat Hans ikut melepas seat belt dan siap membuka pintu, sebelum akhirnya aku interupsi. “Kamu mau ke mana, Mas?”
Keningnya berkerut, kepalanya menggeleng pelan dan menoleh ke rumah Papa Aji, lalu menatapku kembali. “Ikut kamu turun?”
“Mau ngapain?”
Dia tak menjawab, tapi tatapannya tak beralih dari mataku.
“Kamu mau liat aku pamitan sama pacarku?”
“Why not?”
Aku kembali mengedikkan bahu. “Okay.” Kali ini benar-benar turun dari mobil dan berjalan lebih dulu, rasanya tidak perlu juga aku menunggu Hans harus di sebelahku. “Hai, Mbak!” sapaku pada ART Papa Aji, disambut dan dibawa ke dalam rumah. “Papa Aji ada, kan?”
“Ada, ada, Kak. Tadi lagi di belakang, main bola sama Kakak Zydan. Silakan duduk, Kak, Pak.” Dia menatapku dan Hans bergantian, lalu menggelengkan kepala ketika menataku lagi. “Maaf, Mas maksudnya—”
“Dia suami saya,” ralatku agar suasana tidak meledak karena canggung. Tentu saja aku memberi senyuman paling manis dan tulus ketika mengatakannya. “Makasih, ya, Mbak,” ucapku saat dia pamit untuk memanggil Papa Aji. Tentu saja tadi ekspresi terkejutnya tak bisa ditutupi.
Siapa yang tidak terkejut ketika orang yang baru kamu temui beberapa minggu lalu dalam status single, lalu hari ini sudah memiliki suami? Suami, ya? Aku mengangkat tangan kanan dan memperhatikan cincin di jari manis itu, dalam-dalam. Apa makna sebenarnya dari cincin ini? Apa makna sebenarnya dari pernikahan kalau bahkan bukan kita yang memilih sementara kita yang menjalaninya? Aku menoleh ke kanan, Hans duduk tanpa suara, tapi sekarang dia juga menoleh dan menatapku. Merespons reaksinya, aku mengangkat tangan kananku yang terdapat cincin di sana, lalu tersenyum padanya. “Beautiful ring. Aku udah bilang belum?”
Kepalanya mengangguk.
“Udah?”
Lagi, dia mengangguk. “Terima kasih.”
Aku tersenyum lebar. “Anytime.”
Dia kembali diam.
Aku tidak tahu, tidak berani mendeskripsikan laki-laki ini terlalu dini. Karena jujur saja, aku dan dia belum punya obrolan yang berarti. Hanya sepotong-potong kata, basa-basi semata, jadi dengan semua itu, rasanya sah-sah saja menyebutnya tak banyak bicara. Namun di satu sisi, aku sudah melihatnya berbincang dengan Mama, Papa Amar, beberapa orang lain, dia tak terlihat sependiam itu. Dia tak terlihat kesulitan menemukan kata-kata. Tidak juga terlihat tertekan harus bertemu orang.
Oh, aku ingat satu hal!
Aku dan Hans pernah ngobrol lumayan panjang di pertemuan pertama. Hari itu, setelah semalaman aku tidak tidur demi menyusun semua rencana sedetail-detailnya, untung dan rugi, konsekuensi yang mungkin saja aku terima atau pasti aku terima (maksudku di sini adalah dosa, mungkin saja Tuhan benar-benar marah padaku, tapi aku berusaha menyakinkan-Nya bahwa seharusnya yang Dia marahi adalah Mama dan Papa Amar), aku bertemu dengannya tanpa ekspektasi apa pun. Aku bahkan sudah pasrah bagaimana fisiknya, sesuai dengan di foto atau tidak, bagaimana baunya, wanginya, suaranya, sudut pandangnya, kata-kata pilihannya, semuanya. I had no expectations.
Turned out, he’s so damn fine.
Percakapan kami saat itu tak banyak, tapi ternyata kalau harus dibandingkan dan ditentukan mana yang paling banyak, maka momen itu pemenangnya.
“Secara fisik, apa aku tipemu, Mas?”
“Aku nggak punya kriteria khusus soal fisik.”
“Kalau gitu kenapa nggak cari yang lain?”
“Justru karena nggak punya kriteria khusus, kamu pun nggak masalah.”
“Kamu pun? It sounds like I’m not that pretty for you.”
“You’re pretty. Kamu gimana? Secara fisik, aku tipemu?”
“Bukan. Kamu bukan pilihanku, jadi semua tentangmu, semua yang ada di kamu, bukan tipeku.”
Kala itu, dia diam, tak terlihat kesal, marah, apa pun yang seharusnya dia rasakan dan aku menerima itu.
Jadi aku bertanya lagi. “Apa ekspektasimu dalam pernikahan ini? Visi-misi, nilai-nilai kehidupan, ekonomi, tempat tinggal, jumlah anak, and so on.”
“Nggak ada,” jawabnya tenang, terdengar yakin. “No expectations, no disappointments.” Aku suka prinsipnya yang satu itu. “Pernikahan buatku bukan program bikinan yang bisa auto pilot, jadi aku akan jalani menyesuaikan partner. Itu termasuk jumlah anak, cara didik, budaya di dalam rumah. They’re negotiable. Soal ekonomi, aku akan kasih kamu akses buat lihat semua. Gaji, tabungan, dan lain-lain. Tempat tinggal, I have my own house. Kalau kamu bersedia tinggal di sana, let’s build our home together, kalau kamu punya alternatif lain, kita bisa diskusi lebih jauh.” Tahu apa yang terjadi ketika kamu tidak berekspektasi dalam hidup? Maka kamu akan kebingungan, tidak tahu harus bagaimana. Seperti aku saat itu. Terdiam, kehilangan kata-kata, dan tidak tahu harus menjawab apa. “Aku paham, perempuan masa kini menjunjung tinggi value diri dan aku bangga akan hal itu. Jadi, kalau kamu merasa pekerjaan domestik nggak seharusnya cuma dikerjain sama perempuan, let's be a great team. Aku nggak buta masak, bersih-bersih rumah, cuci baju, dan nama-nama pekerjaan di dalam rumah lainnya.”
Terdengar menjanjikan, semua yang disebutkan tidak memiliki kekurangan. Hanya jika diucapkan oleh seseorang yang aku inginkan. Nyatanya, dia datang entah dari mana di sudut kehidupanku yang aku tidak tahu, membuat semua penawarannya tadi terdengar sangat normatif.
Bare minimum.
“Rey?”
Lamunanku buyar, aku meletakkan tangan di atas pangkuan, tersenyum lebar menatap Papa Aji. Ketika dia mendekat dan aku tahu dia akan memelukku, aku segera berdiri, melebarkan tangan untuk memeluknya, menerima kecupannya di kening. Papa Aji melirik Hans dengan sorot mata penuh tanya, pun sama halnya dengan Hans, tapi entah apa yang ada di pikirannya.
“Jadi, siapa dia?” tanya Papa ketika sudah duduk tenang di sofa miliknya ini.
Aku masih dengan senyum lebar, mengangkat tangan kanan dan menunjukkan padanya. “I’m married.”
Reaksinya sudah bisa diprediksi. Gelak tawan. Tapi karena aku tak ikut tertawa, Papa Aji sepertinya menyadari apa yang aku katakan bukan lelucon di hari ini. Tatapannya berubah, terlihat penuh macam-macam perasaan, aku hanya menebak-nebak tetapi mungkin saja tebakanku benar. “Kamu serius, Rey?”
“Yup!”
“Jadi waktu kamu bilang mau kasih cucu, itu beneran? Ini? Kamu lagi hamil?”
Ouch.
Aku meringis di dalam hati. Ini yang aku ucapkan waktu itu. Ucapanku diwujudkan detik itu juga oleh Tuhan. Padahal, saat bercanda akan memberinya cucu, aku bahkan tidak terbayang akan pernikahan. Sama sekali. Tapi Papa Aji tidak perlu tahu detail rencanaku, jadi aku mengangguk. “Aku tahu Papa akan marah, kecewa dan nggak merasa aku hargai. Apa pun perasaan Papa, boleh. Aku terima.” Tunggu dulu, aku melupakan Hans! Dia pasti sedang kebingungan mencerna semua ini. Pacarku atau Papaku?
“Kamu dipaksa Papa Amar dan Mama?”
“Nope.” Aku menggeleng kuat. “Awal pertemuan kami, emang dikenalin sama mereka, tapi selebihnya, itu keputusan kami sendiri.”
“Kamu tau kamu bisa minta bantuan Papa, kan, Rey?”
“Aku tahu dan akan minta kalau aku butuh, Papa. Tapi serius, Pa, ini bukan kayak yang Papa pikirin. Justru Papa harus seneng, karena dengan aku udah nikah, aku tinggal sama suamiku, waktu ketemu kita bisa lebih banyak. Nggak perlu khawatir akan ketahuan Mama. Suamiku baik.”
Papa Aji menoleh pada Hans, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sementara Hans, aku lihat dia tersenyum dan mengangguk. Lalu Papa Aji kembali menatapku, dia mungkin saja masih kesulitan menerima ini. Terbukti karena sekarang dia sedang menyeka matanya, kemudian tersenyum paksa, lalu tertawa pelan ketika melihat Hans. “Hidup dia beneran complicated, saya yang bikin. Jadi kalau sekarang saya masih dikasih keajaiban buat kasih wejangan sebagai Papanya, saya cuma mau … saya mohon, jangan buat hidup dia lebih sulit dari sebelum ada kamu.” There you go! Hantaman lain dari ‘I had no expectation’ kembali aku terima. “Cita-cita saya setelah lihat Rey pertama kali adalah jadi wali di pernikahan impiannya.” Papa Aji tersenyum dengan mata yang memerah, aku mengeratkan rahang berharap tidak ikut menangis. “Tapi saya bukan siapa-siapa. Dia bahkan nggak perlu saya di hari pernikahannya. Saya nggak nyalahin dia, kamu. Karena memang begini resikonya. Tapi yang pasti, saya titip Rey, dan tolong tetap izinkan saya ketemu dia.”
“Pasti, Pa.” Hans menganggukkan kepala. “Pernikahan artinya bukan ambil anak perempuan dari orang tuanya.” Hans melirikku, menatap sekitar empat detik dalam diam, lalu berbicara pada Papa Aji lagi. “Reva—Rey, akan selalu jadi anak perempuan kesayangan Papa.”
Kalau kamu tidak lupa, aku belum lama menyebut kalau Hans tidak terlihat kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Dia buktikan lagi kali ini. Obrolannya dengan Papa Aji selanjutnya membuatku lumayan kagum karena dia tak terlihat seperti orang yang tidak mengenal Papa Aji. Padahal ini adalah kali pertama dia bertemu Papa, bahkan mengetahui keberadaannya.
Dia baru menunjukkan kebingungannya setelah kami sudah kembali duduk di dalam mobilnya. Selesai menyalakan mesin, memasang seat belt, dia tak langsung menjalankan mobil, tetapi—dia melepas seat belt-nya, dan menyerongkan tubuh menatapku. “Kamu mau duduk di sebelahku waktu aku ucapin akad nikah, artinya kamu terima semua penawaran waktu itu. Di dalamnya ada; let’s build our home. Rumah yang bukan bangunan ini, nggak akan terbentuk tanpa adanya keterbukaan.” Pembukaan yang jenius dan membuatku dengan mudah memahami tujuannya. Sedikit menakutkan, tidak banyak memang. Sedikit. “Ngutip kalimat Papamu, hidupmu complicated. Aku lebih suka nyebutnya kompleks, jadi aku minta tolong kamu bantu aku pahami hidupmu.”
“Kenapa kompleks?”
“Complicated seolah kasih kesan buruk. Sebuah masalah mungkin oke kalau disebut complicated. Atau konflik. Sementara hidupmu bukan sebuah masalah. Hidupmu nggak buruk. Aku punya waktu seumur hidup buat kamu ajak jalan-jalan ke tiap sudut hidupmu yang kompleks itu.”
“Soal Papa Aji?”
“Salah satunya, kan?”
Aku tertawa.
Sudut hidup mana lagi yang dia maksud selain aku ada di saat Papa Aji dan Mama baru menerima surat kelulusan SMA? Papa Aji yang tak siap, mereka berdua tak pernah siap memiliku. Karena hadirnya aku sama dengan mengubah jalan hidup yang sudah mereka rencanakan. Jadi keputusan sebelah pihak, orang tua Papa Aji mengirimnya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, berharap Mama juga mengambil keputusan yang sama; menyingkirkanku. Tapi Mama adalah orang yang berani, aku menyukainya meski sekarang kecewa. Dia dan orang tuanya memutuskan untuk membiarkanku melihat indah dan kacaunya dunia. Kesabaran dan perubahan ke arah lebih baik yang membuat Mama akhirnya bertemu Papa Amar, dan aku bahagia sekali karena Mama bisa merasakan hal-hal yang hilang atau yang belum sempat dia dapatkan sebagai seorang perempuan.
Lalu ketika aku wisuda SMA, aku bertemu Papa Aji. Dia yang mencari dan menemuiku. Aku tidak sulit mengenalinya, karena aku memang tahu tentangnya. Maksudku, Mama dan Papa Amar sangat terbuka tentang siapa aku, papa kandungku, meski yang dia berulang-ulang katakan adalah Papa Aji tak menginginkanku, dia hidup di negara yang berbeda, kami tidak akan pernah bertemu.
Nyatanya, pertemuan dan Papa Aji sudah berlangsung lama, dan aku bersyukur karena baik Mama dan Papa Amar tidak mengetahui ini.
Bagian lucunya dari kisah dua Papa dan Mamaku ini adalah … sedikit sama terulang di kehidupanku. Aku dan Danar. Lalu aku dan Hans. Apakah Hans akan menjadi seperti Papa Amar?
Sepertinya tidak.
Karena aku berangkat dalam perjalanan pernikahan ini dengan niat yang sangat tidak mulia.
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰