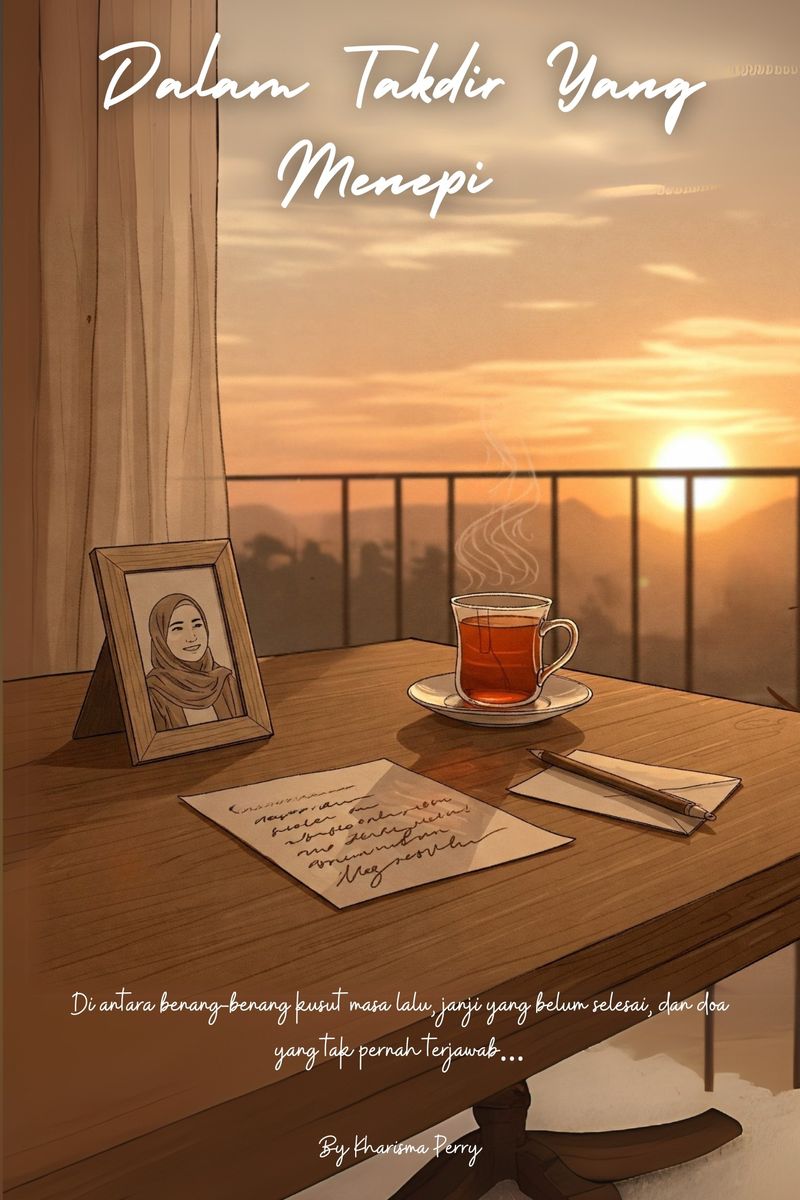Langit mendung menggantung di atas mereka. Angin basah menyapu pelan wajah Naina yang tak kuasa menahan air mata.
"Farah tahu?" tanyanya.
Ishaq mengangguk. “Ia tahu aku mencintaimu lebih dulu. Tapi ia juga tahu bahwa rasa tidak selalu tumbuh pada waktunya yang tepat.”
Malam turun dengan angin yang membawa aroma basah daun dan tanah. Di dalam kamar yang disediakan Bu Sri, Naina kembali duduk dalam gelap. Lampu minyak menyala redup, menebar cahaya kekuningan ke dinding yang diam.
Ia tidak bisa tidur.
Tatapan mata Ishaq tadi sore masih membekas. Bukan tatapan yang ia harapkan. Bukan juga tatapan yang ia benci. Tapi cukup untuk membuka pintu-pintu kenangan yang sudah lama ia segel.
Naina menarik napas panjang, lalu membuka buku harian tua dari tasnya. Buku itu ia bawa kemana pun ia pergi, meski tak selalu ia tulisi. Tapi malam ini, tangan dan hatinya sama-sama ingin bicara.
“Hari ini, aku melihat Farah dan anak itu. Aku melihat Ishaq. Dan semua rasa yang kusimpan, ternyata tidak mati. Hanya terkubur terlalu dalam—hingga aku lupa caranya bernapas tanpa memikirkan mereka.”
Ia berhenti menulis. Lalu berdiri. Jendela kamarnya langsung menghadap jalan kecil tempat Ishaq sempat berjalan menjauh. Jalan itu juga jalan yang dulu ia tinggalkan, dengan satu koper dan hati yang remuk.
**
Keesokan paginya, Naina membantu Bu Sri membersihkan halaman belakang. Ia menyapu daun-daun jati yang gugur, dan sesekali memandangi arah jalan dari sela pagar kayu. Dalam hati ia berharap, mungkin Farah akan datang. Atau Qiana. Atau bahkan Ishaq lagi.
Tapi yang datang bukan mereka.
Seorang laki-laki sepuh, berkopiah dan mengenakan sarung, berjalan pelan menuju halaman. Bu Sri langsung menghampiri.
“Pak Ustad Hamid! Sudah lama tidak kemari.”
Ustad Hamid tertawa ringan. “Saya dengar ada tamu lama kembali. Saya cuma ingin menyapa.”
Naina menunduk sopan. “Assalamu’alaikum, Pak Ustad.”
"Wa’alaikumussalam, Naina. Astaghfirullah… sudah sebesar ini sekarang. Eh, maksud saya, sudah sebijak ini sekarang." Candanya ringan, namun menyiratkan pengertian dalam.
"Belum sebijak itu, Pak Ustad," balas Naina pelan.
Ustad Hamid menatap Naina beberapa saat, lalu duduk di kursi bambu tua. “Orang-orang bilang kau pergi karena patah hati. Tapi saya percaya, setiap orang pergi karena sedang mencari dirinya yang hilang.”
Naina terdiam.
"Kau sudah menemukannya?" tanya Ustad Hamid, lembut.
Ia menggeleng pelan. “Mungkin… aku masih berjalan ke arahnya.”
**
Siang itu, hujan turun lagi. Naina memutuskan untuk menyusuri jalan kecil menuju taman tua yang dulu sering ia kunjungi. Tempat itu tak banyak berubah. Ayunan berderit pelan, rumput liar tumbuh di sela batu pijakan. Tapi ada satu hal yang membuatnya terhenti.
Di bangku kayu di sudut taman, Ishaq duduk sendiri. Memegang sebuah buku kecil dan pena.
Ia tidak melihat Naina. Tapi entah mengapa, Naina merasa Ishaq tahu dia ada di sana.
Dan benar saja.
"Kau masih suka tempat ini, ya?" suara Ishaq pecah pelan, tanpa menoleh.
Naina melangkah pelan, lalu duduk di ujung bangku yang sama.
"Aku tidak tahu kenapa aku kembali ke sini," ucapnya jujur. “Tapi tempat ini… seperti menunggu.”
“Aku menunggumu.”
Naina memalingkan wajah. Kata-kata itu terlalu jujur untuk dibiarkan lewat begitu saja.
"Kenapa kau menikah dengan Farah?" tanyanya, tak sanggup lagi menyimpannya.
Ishaq menutup bukunya. Hening. Lalu menjawab, “Karena kau pergi.”
Jawaban itu seperti pisau. Tapi bukan karena menyakitkan—melainkan karena kebenaran di dalamnya.
“Aku pergi… karena aku tahu kalian saling mencintai. Aku tidak mau ada yang tersakiti.”
“Bahkan dugaanmu sama sekali tak benar, Naina.”
**
Langit mendung menggantung di atas mereka. Angin basah menyapu pelan wajah Naina yang tak kuasa menahan air mata.
"Farah tahu?" tanyanya.
Ishaq mengangguk. “Ia tahu aku mencintaimu lebih dulu. Tapi ia juga tahu bahwa rasa tidak selalu tumbuh pada waktunya yang tepat.”
Naina menatap tanah.
“Qiana… anakmu?”
Ishaq menatap lurus ke depan. “Farah adalah ibu yang hebat. Ia melahirkan Qiana dengan seluruh perjuangan hidupnya. Tapi siapa ayahnya… bukan pertanyaan yang bisa dijawab hanya dengan satu kata.”
Naina menoleh dengan kening berkerut.
“Apa maksudmu?”
Ishaq berdiri. “Kau harus bicara langsung dengan Farah. Aku hanya bagian dari kisah ini, tapi tidak berhak menceritakan semuanya.”
**
Bab ini ditutup dengan Naina yang kembali ke rumah dalam hujan. Pikirannya penuh, hatinya gelisah, dan langkahnya berat. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin melarikan diri.
Karena kali ini, yang harus ia hadapi bukan hanya masa lalu—tapi juga kebenaran yang selama ini ia hindari.
"Lalu kenapa kau menikahi sahabatku jika tak ada rasa padanya? Dasar lelaki bodoh!" Umpat Naina diisakan tangisnya dalam heningnya malam di Kota kecil itu.
---
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰