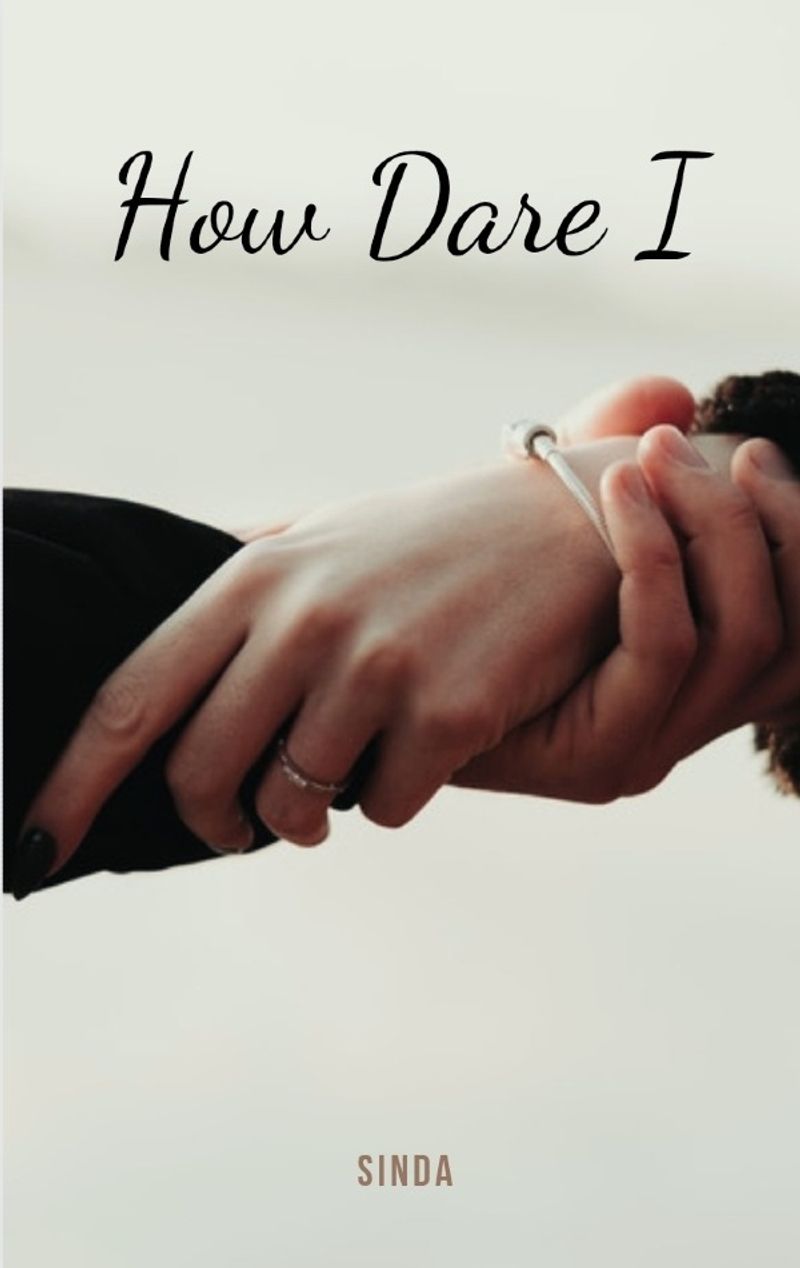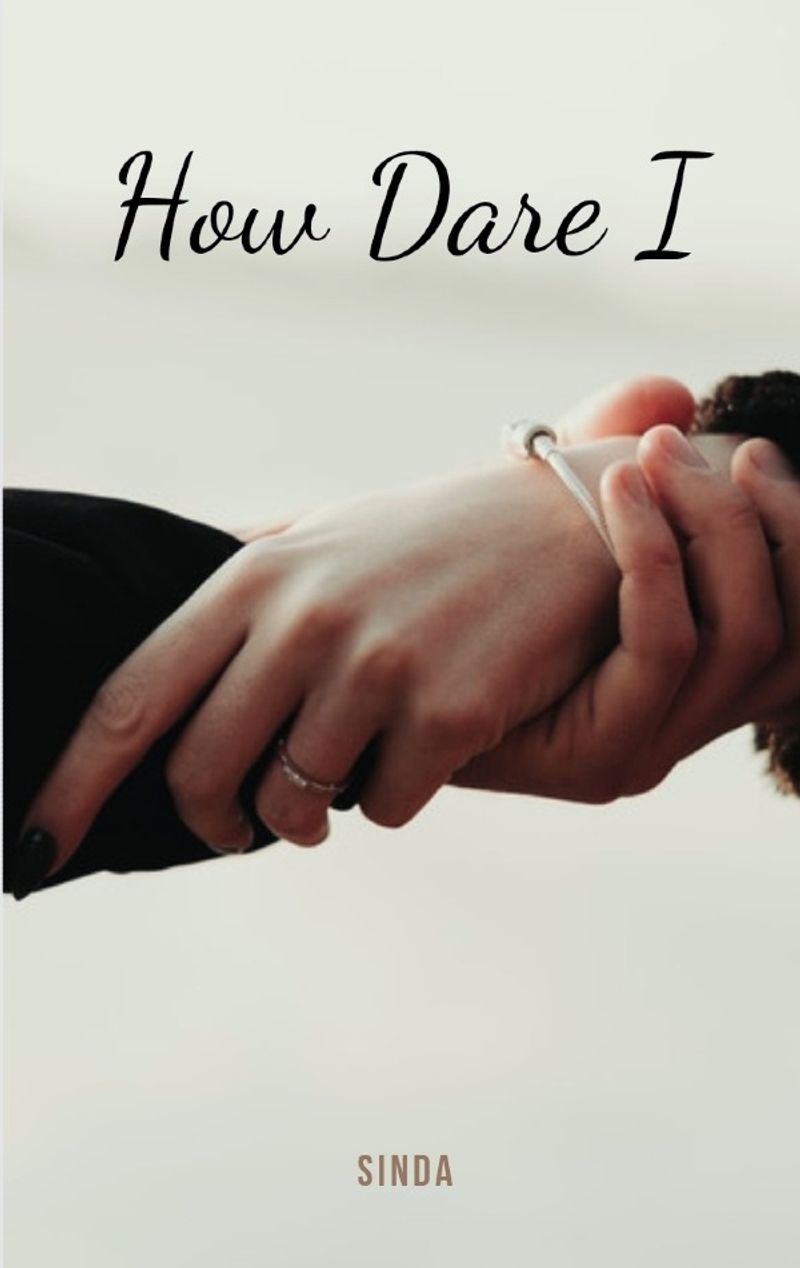
Tadinya berniat melajang seumur hidup, di usia 28 tahun, aku putuskan untuk berumahtangga. Dua hal yang menjadi pertimbangan. Satu, upah yang akan kudapat. Kedua, aku memang harus punya suami, agar adikku bisa segera menikah.
Awalnya, kukira semua mudah. Hanya tinggal berlakon seperti seorang istri selama setahun, dapat gaji dan sudah. Namun, semua menjadi sulit karena mantan istri Pak De muncul. Tadinya bisa mengesampingkan perasaan, Eveline malah membuatku lupa cara mengendalikan diri.
Kalau sudah...
Bab 6
Para kerabat dan beberapa teman keluaga Pak Denish sedang menikmati jamuan di rumah besar Buk Fera, aku tengah berkeliling tak tentu arah mencari seseorang.
Aisi.
Anak itu tak kelihatan sejak acara pernikahan selesai.
Satu fakta yang sampai saat ini masih tak bisa kupercaya, aku sudah menikah. Menikah. Sungguh berani aku ini. Berani mati.
Kembali soal Aisi. Tadi, aku sempat melihatnya saat akan meninggalkan gedung acara. Namun, anak itu memalingkan wajah dariku. Sampai sekarang belum bertemu dia lagi, jadi aku mencari.
Aku putuskan mencarinya sendiri, sebab sadar bahwa bertanya pada Pak De hanya akan menghasilkan sia-sia.
"Kak Sanra?"
Aku bertemu Sania di sebuah ruangan. Selain wanita itu, ada beberapa perempuan lain yang tadi diperkenalkan Buk Fera sebagai sepupu-sepupu Denish.
"Mau ke mana, Kak?" tanya wanita itu ramah.
"Aisi," jawabku cepat. "Saya cari Aisi."
"Oh, Aisi di lantai dua. Di kamar Omanya. Katanya tadi, ngantuk."
Mengangguk dan mengucapkan terima kasih, aku segera berbalik pergi. Sebelum pergi, aku sempat mendapati salah satu sepupu Denish melempar senyum sinis.
Ish. Belum apa-apa, aku sudah punya seseorang yang tak suka padaku.
Ruangan tempat Sania tadi ruang tamu, saat melewati ruangan yang lebih besar, langkahku menuju tangga dihentikan sebuah panggilan.
Aku menoleh, langsung menaikkan satu alis saat tahu siapa yang memanggil.
"Mau ke mana kamu?" Pak Denish bertanya.
Dia berdiri di depanku dengan satu tangan di saku celana. Sudah menanggalkan jas dan hanya menggunakan kemeja putih, dia lebih mirip bos daripada pria yang beberapa saat lalu resmi menjadi suamiku.
"Bapak ada lihat Aisi?" tanyaku sengaja.
Lelaki itu menggeleng tak peduli. "Memang saya pengasuhnya Aisi?"
Aku memicing. Jawabannya seolah dia bukan ayah dari anak yang sedang kucari. Apa pria itu bahkan sadar jika putrinya belum makan sampai sekarang? Aisi hanya mengambil dua potong roti saat sarapan tadi pagi.
Mungkin karena dilanda kesal, aku merasakan debar jantung mulai tak beraturan. Keringat dingin juga mulai muncul di dahi.
"Kamu mau ke mana?" tanya lelaki itu sekali lagi.
Sudah membuka mulut, aku tak bisa mengeluarkan suara. Mendadak pijakanku bergoyang, pandanganku seketika menggelap.
Aku limbung, tetapi tak sampai terjatuh.
"Kamu kenapa?"
Memejam erat beberapa saat, aku membuka mata dan mendapati diri sudah bertopang pada dada Pak Denish. Beberapa orang mulai mengerumuni kami.
"Kamu mau pingsan?"
Pertanyaan sia-sia. Malas menjawab, aku berusaha berdiri tegak. Namun, mendadak tubuh seolah tak punya tenaga. Aku bersikeras, menolak saat Pak Denish ingin memegangi bahu. Namun, di saat yang sama, pandanganku kembali gelap. Kali ini, aku benar-benar tumbang.
***
"Sepertinya kurang tidur, Pak. Perbanyak istirahat, ya."
Pada dokter yang menoleh dan tersenyum sopan, aku mengangguk singkat. Memijat pangkal hidung, aku merutuki diri. Kenapa harus benar-benar pingsan tadi?
"Kamu kenapa kurang tidur?" Itu hal pertama yang Pak De katakan saat dokter sudah pergi dan dia menghampiriku di ranjang.
Tidak menjawab, aku merasa ada yang janggal dengan gaun yang melekat di tubuh. Kenapa longgar?
"Karena kamu pingsan, saya berinisiatif untuk membuka ritsleting gaun kamu," jelas Pak Denish tanpa kuminta.
"Aisi," kataku pada akhirnya. "Dia di mana?"
"Untuk apa kamu cari Aisi?"
Tidak berbobot! Aku menahan diri untuk tak meneriaki dia.
"Sejak pagi dia enggak ada makan nasi. Aku lagi mau susul dia ke kamar Buk Fera tadi. Kata Sania dia di sana, tidur."
Aku bangkit dari posisi berbaring. Perut langsung diserang mual, karena semua tampak berputar-putar. Kupegangi kepala, sambil memejamkan mata.
"Tidur saja dulu. Aisi biar saya yang kasih makan."
Pak Denish membantuku berbaring lagi. Dia ikut membungkuk, sampai wajah kami jadinya sangat dekat.
Tidak sedang berhalusinasi, aku mendapati Pak Denish tersenyum miring sekarang.
"Saya benar, 'kan? Hitam memang cocok untuk kamu." Sambil bicara, tangannya bergerak menurunkan gaunku hingga bahu terlihat.
Mataku melirik ke arah matanya tertuju. Jemari telunjuknya sedang menurunkan tali braku yang memang berwarna hitam.
Kurasa dia memang sengaja. Pengakuannya yang bilang bahwa sengaja menurunkan ritsleting gaun demi melancarkan jalan napasku saat pingsan tadi, agaknya cuma mengada-ada.
Lihat yang dia lakukan sekarang. Karena ritsleting itu terbuka, dia jadi lebih leluasa menurunkan gaunku. Nyaris seluruh dadaku terpampang di depan matanya yang menggelap sekarang.
Dahiku mengkerut. Sengaja aku diam saja, menunggu apa yang sebenarnya ingin lelaki itu lakukan.
Detik bergulir, gaun putih itu sudah turun melewati dada. Sambil terus menatapi, Pak Denish terus menariknya hingga pinggang.
Pria itu menatap lebih tajam, aku menaikkan pinggul agar gaun itu bisa lolos. Dan benar saja, Pak Denish menariknya lepas dari kakiku.
Kutunggu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mata kami berpandangan, perlahan aku berkeringat lagi.
Pak Denish sedikit bangkit, untuk kemudian mengambil sehelai kain dari sisi kanan ranjang. Pria itu kembali duduk di sampingku, lalu membantuku mengenakan kain yang ternyata adalah sebuah dress tidur.
"Kamu tidur saja dulu. Aisi, biar saya yang kasih makan."
Wih!
Ternyata dia tak berniat jahat. Pikiranku sudah ke mana-mana melihatnya menanggalkan gaun tadi. Rupanya hanya ingin membantu bertukar pakaian.
"Kita enggak pulang?" tanyaku saat dia memakaikan selimut.
Pak Denish menggeleng. Dia masih duduk di tepian ranjang. Masih memandangiku pula.
"Apa?" tanyaku karena tak suka bingung.
"Cuma penasaran. Kamu kurang tidur karena apa? Mikirin malam pertama sama saya?"
Menganga sebentar, aku tarik selimut sampai menutupi wajah. Memejam, aku mencoba tidur.
"Tenang saja. Saya pastikan kamu tidak kecewa. Kan saya kasih garansi uang kembali." Di ujung kalimat, pria itu tertawa.
Dan tawanya itu adalah hal terakhir yang aku ingat sebelum benar-benar lelap.
***
Pernikahan dilaksanakan hari Sabtu, hari Minggu pagi kami masih ada di rumah Buk Fera. Bangun pukul enam, aku segera pergi ke dapur. Membantu asisten rumah tangga untuk membuat sarapan.
"Ndak perlu ikut bantu, Mbak Sanra. Biar kami saja." Wanita paruh baya bernama Reni itu melarang aku ikut turun tangan. Wajahnya dihiasi ekspresi tak nyaman.
"Saya enggak akan ikut masak, kok, Buk. Cuma bantu-bantu saja. Potong-potong sayur." Aku mendekat ke arah meja dan mulai memotong apa pun yang ada di sana.
"Menantu-menantunya Buk Fera memang baik-baik, ya?" komentar wanita itu.
Aku hanya menanggapi dengan senyum kecil. Sebenarnya ada hal yang sejak tadi aku pikirkan. Di mana Aisi dan ayahnya? Saat bangun tadi, aku sendirian di kamar itu.
Tidak berharap ditemani Pak Denish, hanya saja aku sedikit khawatir. Apa kata orang-orang di sini kalau tahu kami yang baru menikah ini tidak tidur seranjang?
"Siapa yang suruh kamu turun ke dapur?"
Suara itu membuat aku menoleh. Pak Denish muncul dengan penampilan anehnya lagi. Tanpa baju.
Apa yang ada di pikiran pria itu, ya? Kenapa hobi sekali berkeliaran tanpa baju?
"Pagi, Pak Denish," sapa Buk Reni. "Saya sudah kasih tahu kalau Buk Sanra ndak perlu bantu. Tapi, bersikeras mau ikut katanya."
Mengalihkan wajah dari Pak Denish, aku yang sudah akan menggerakkan pisau seketika mematung. Lengan pria itu sudah melingkari leher.
Punggungku merinding karena bersentuhan langsung dengan dada bidang milik ayahnya Aisi. Gesekan kulit lengannya yang mengenai leher dan daguku menghantar sensasi yang tak pernah kurasa sebelumnya.
"Coba saya lihat kamu?" Pak Denish menarik daguku agar menoleh padanya.
Pria itu menaruh telapak tangan di kening. Kemudian menjepit pipiku dengan ibu jari dan telunjuk, hingga mulut sedikit terbuka. Dia memeriksa ke sana.
Kemudian ibu jarinya mengusap lembut bawah mataku.
"Lumayan," komentarnya di akhir.
Aku yang kebingungan dengan tingkahnya itu tak bisa berkedip. Memalingkan wajah pun kurasa aku enggan, kalau saja tak mendengar seseorang memekik.
"Waow! Saudara-saudara! Lihat ini!"
Daren berdiri di ambang pintu menuju dapur. Lelaki tersebut memasang air muka takjub. Telunjuknya mengarah pada kami.
"Astaga!" Dimas yang baru datang bertingkah tak kalah menyebalkan. Lelaki itu menutup wajahnya dengan tangan, tetapi mengintip dari celah jemari.
Aku sudah ingin menjauh dari Pak Denish, tetapi pria itu malah sengaja melingkarkan satu lengan lagi di perut. Aku tak bisa berkutik dibuatnya.
Suara tawa bahagia terdengar di dapur itu. Wajahku makin tebal dan hanya bisa menunduk saat Buk Fera ikut bergabung.
"Jangan marah sama Aisi, ya, San. Namanya juga, kamu menikah sama laki-laki yang udah punya anak."
Siapa yang marah pada Aisi?
"Lepas dulu. Ini Bapak mau apa begini?" Aku berusaha menjauhkan lengannya dari leher.
Menyentuh di sana, aku baru sadar kalau lengan itu tak kecil. Padat, dengan kulit putih dan beberapa urat yang mencuat di kulitnya.
Aku membayangkan. Jika Pak De ingin, ia bisa meremukkan leherku dengan mudah. Lalu, jantungku berdebar makin kencang saat menyadari jika rangkulannya ini malah terasa lembut dan hati-hati.
Ish. Aku benci diriku yang menye-menye begini. Kenapa harus sejauh itu berpikirnya? Apa aku ingin membiarkan diri terpesona pada Papanya Aisi?
Menengok padanya, lelaki itu menyipitkan mata.
"Saya mau periksa. Apa kamu sudah baik-baik saja atau belum," sahutnya tenang.
"Bapak udah periksa, 'kan? Kalau begitu, tolong, singkirkan ini." Kucoba mengangkat lengannya yang merangkul dada, tetapi lengan itu tak bergerak sedikit pun. Tak menyerah, aku berusaha lagi. Namun, hasilnya tetap sama.
Pak Denish sedikit menunduk. Aku merasakan embusan napasnya di dekat telinga.
"Yakin kamu bisa lawan saya duel? Angkat satu lengan saya saja, kamu tidak bisa."
Kugigit bibir kuat saat Buk Fera, Daren dan Dimas yang sejak tadi menontoni memilih membubarkan diri. Begitu juga Buk Reni.
Merasa mendapat kesempatan, aku pun mendorong tubuh ke belakang. Berharap dengan begitu Pak Denish bisa melepaskan kungkungan lengannya.
Berhasil.
Pria itu membuat jarak, berkacak pinggang padaku dengan wajah ditekuk.
"Enggak malu apa dilihatin Ibu sama adik-adik Bapak? Aneh-aneh aja!"
"Kamu memang hanya punya tulang dan kulit, ya? Sama sekali tidak ada daging?"
Aku melongo mendengar itu. Dia mengataiku. Lagi.
"Bukannya enak, kebentur bokong kamu malah bikin sakit. Tidak ada empuk-empuknya sama sekali."
Selesai mengatai, pria itu melenggang pergi dari dapur. Aku berusaha meredakan emosi yang sudah mulai naik dan membuat ubun-ubun hangat.
Biarkan saja. Tidak baik jika melampiaskan kemarahan di sini. Ini rumah ibunya Pak De.
Menarik napas, membuangnya pelan, aku kembali memotong wortel. Buk Reni sudah datang lagi. Perempuan itu sengaja melempar senyum padaku. Aku tahu, dia tengah mengejek.
"Saya jadi penasaran."
Aku memejam kala suara itu muncul lagi di dapur. Berusaha mengabaikan, aku waspada kala mendapati derap langkah Pak Denish malah mendekat ke arahku.
Seketika mata ini membola. Mungkin nyaris menggelinding keluar, karena terlampau terkejut. Pak Denish baru saja menyentuh bokongku. Tak hanya menyentuh, pria itu juga meremasnya.
Pelan-pelan menengok pada dia, aku langsung disuguhi ekspresi malas.
"Benar. Sama sekali tidak empuk. Kecil semua kamu ini?"
Melempar pisau ke atas meja, aku berjalan pergi melewati dia. Masuk ke kamar, lalu membungkus diri dalam selimut.
"Kenapa kamu?" tanyanya dari ambang pintu. Ternyata dia mengekori.
Tidak kujawab. Dalam selimut, aku yang hampir menangis sedang merencanakan balas dendam. Lihat saja. Lelaki itu akan kubuat malu seperti ini juga.
Bab 7
Sarapan siap. Satu per satu keluarga Pak Denish menghuni meja makan. Hal pertama yang aku cari adalah Aisi.
Dan benar saja. Saat anak itu muncul, aku melihat rambutnya tidak diikat. Dibiarkan tergerai, tetapi tidak rapi. Seperti kebiasaannya.
Aku menghampiri dia yang baru memasuki ruang makan. Gadis itu berhenti berjalan, kemudian menatap ke arah lain.
"Aisi bobok di mana?" tanyaku pelan.
"Di kamar Oma."
Dahiku berkerut. "Loh, bukannya sama Papa?"
Dia menggeleng. Melirik ke arah meja makan di mana ayahnya sudah di sana, gadis itu mencebikkan bibir.
"Aisi dimarah. Papa nggak bisa bantu Aisi makan, Aisi dimarah. Jadinya, bobok sama Oma."
Mengangguk saja, aku berkata, "Lain kali, cari Kakak. Kalau ada apa-apa, cari Kakak."
Aisi mengangguk. Dia menatapku takut-takut. Aku tahu dia sedang menyimpan sesuatu untuk ditanya atau dikatakan.
Untuk membuatnya sedikit nyaman, aku mendekat, lalu merapikan rambut gadis itu. Kusatukan ke belakang, lalu meminta dia memberikan ikat rambut yang selalu dipakai sebagai gelang di tangan.
"Kalau rambutnya enggak mau diikat, disisir, Aisi. Aisi kayak singa tadi. Cantiknya hilang."
"Aisi mana bisa ikat rambut," bantahnya.
"Aisi itu bukan anak kecil lagi, loh. Udah kelas enam, sebentar lagi SMP. Masak ikat rambut aja enggak bisa?"
Anak itu mendongak. Matanya menatapku penuh maksud.
"Apa? Aisi mau bilang apa?"
Aisi menggeleng. Jadi, aku yang mengambil inisiatif untuk memulai. Kupegangi dua bahu gadis itu. Menatap kedua matanya bergantian, lalu sedikit tersenyum.
"Enggak ada yang berubah. Aisi boleh anggap Kakak kayak biasa aja. Kakak juga enggak berniat menggantikan posisi Mamanya Aisi. Kakak juga enggak akan cubit atau pukul Aisi. Kayak biasa aja. Bisa?"
Anak itu memang masih SD. Namun, aku yakin ia sudah paham apa yang terjadi. Punya ibu tiri, Aisi pasti punya ketakutan tersendiri. Dan aku tak mau dia membuat jarak karena ketakutannya itu. Bisa tambah susah mengurusnya nanti.
"Bener?" tanyanya memastikan.
Aku mengangguk. Mengusap pipinya, aku berdecak. "Aisi juga belum cuci muka, ya?"
Anak itu memamerkan giginya.
"Malas banget, sih? Cantikmu hilang, baru tahu."
Aisi menempelkan telapak tangannya di lenganku. "Kata Papa, Kakak demam. Udah sembuh?"
"Udah," sahutku cepat. "Sekarang pergi ke kamar mandi. Cuci muka dulu."
Kakinya langsung menghentak tak senang. Aisi bersungut. Namun, dia tetap berbalik dan menuju kamar mandi di dekat ruang makan.
Beres mengurusnya, aku kembali ke meja. Membalik piring Pak Denish, kemudian menyendok nasi untuknya.
Aisi datang tak lama kemudian. Anak itu mengambil tempat di samping kursiku. Kulakukan hal sama pada piringnya.
Sarapan pun dimulai. Sama seperti saat di resto kemarin, keluarga itu tak banyak bicara saat makan. Lain dengan Pak Denish dan Aisi.
"Kak San, air Aisi tambah."
Kutuang air ke gelas gadis itu.
"San, tolong sayurnya."
Aku setengah bangkit untuk mengambil yang Pak Denish minta.
"Kak San, nanti di rumah buat ayam kuah kayak gini, ya?"
Sambil mengunyah, aku menggeleng pada Aisi. "Kamu tahu Kakak enggak bisa masak yang banyak bumbunya."
Kulihat Buk Fera melirik. "Kalau mau, Ibuk bisa ajarin kamu. Nanti Ibuk kasih resepnya. Mau?"
Aku mengangguk kaku. Gawat. PR baru.
"Kak Sanra, kalau butuh bantuan soal masak, apalagi bikin kue, bisa kasih tahu aku, ya." Sania menawarkan bantuan. "Aku punya teman yang guru les masak gitu. Tapi, khusus kue."
"Kursus gitu?" tanyaku penuh atensi.
Sania mengangguk.
"Kira-kira, kalau kursus begitu, jadwalnya berapa kali seminggu?"
"Kalau teman aku, tiga kali seminggu, Kak. Tapi, kalau Kakak mau, aku bisa minta yang privat aja, biar bisa disesuaikan sama jadwalnya Kakak."
Bibirku langsung tersenyum. Sepertinya seru.
"Suka buat kue?" Buk Fera ikut bergabung.
"Lihat di tivi, kayaknya seru gitu. Nanti kalau udah jago, bisa jadi peluang," jelasku.
"Bisnis?" Itu tanya dari Dimas.
Aku mengangguk. "Pakaian sama makanan, kayaknya itu selalu jadi bisnis yang menjanjikan."
"Kamu punya keinginan buka bisnis?" Bu Fera menaruh sendoknya.
Belum sempat aku menjawab, Pak Denish menyela.
"San, tolong ayamnya."
Aku mengambil ayam untuk pria itu. Setelahnya, dia memberi perintah lagi.
"Tolong air saya ditambah."
Perintah kedua, aku menyipit pada lelaki itu. Dia ini sengaja atau apa? Teko persis di depannya. Kenapa tak ambil sendiri?
"San, tolong."
Aku menengok pada dia. "Apa lagi?" tanyaku tanpa menutupi rasa kesal.
Pria itu memajukan wajah. Jarinya menunjuk sudut mulut. "Tolong, bersihkan."
Wah! Dia keterlaluan. Tentu saja aku menolak. Kugelengkan kepala, lalu kembali melanjutkan makan.
Saat acara sarapan itu selesai, aku memberanikan diri menemui Pak Denish untuk bertanya mengapa dia bertingkah seperti tadi di depan keluarganya.
"Apa Bapak juga perlu membuktikan sama keluarga Bapak kalau sudah move on dari Mamanya Aisi?"
Dia yang bersandar di lemari pakaian, menggeleng.
"Lalu? Kenapa kayak tadi?"
"Saya tidak suka."
"Soal?"
"Saya tidak suka melihat kamu bicara dengan keluarga saya seperti tadi."
Meski bingung, aku tak protes. Namun, aku menyuarakan rasa ingin tahu. "Kenapa, kalau boleh saya tahu?"
"Karena kamu tidak pernah bicara seperti tadi pada saya."
"Hah?"
"Kamu serius mau kursus masak? Mulai sekarang, ceritakan apa pun yang kamu mau, hanya pada saya. Jangan pada orang lain, kalau pun pada keluarga saya, mereka harus jadi yang kedua tahu."
"Oh, oke," putusku bingung.
Pak Denish melangkah, mendekat ke ranjang yang aku duduki. Pria itu membungkuk, memegangi dua bahuku.
"Jadi, kita ...."
Mataku mengerjap. Spontan memundurkan kepala saat Pak Denish sengaja memajukan wajah.
"Senin malam nanti, siap-siap. Saya akan buktikan perkataan saya tempo hari."
Dia menegakkan tubuh, aku menelan ludah. Mampus aku. Bagaimana ini?
***
Sesuai dengan namaku yang pendek, Sanra, cara pikirku juga sama. Sederhana. Simpel. Menjurus ke menggebu-gebu tanpa pikir panjang. Karena itu, Senin sore saat Aisi pulang sekolah dan menunjukkan raut sedih, aku langsung mengintrograsi.
Awalnya, anak itu menolak bercerita. Katanya tak habis menangis, meski matanya yang bengkak bisa kelihatan jelas. Tak menyerah, aku terus mencerca dengan pertanyaan dan sesekali membujuk. Hingga akhirnya, bocah perempuan itu mengaku.
Dia diganggu teman sekelas. Dan memang menangis. Ikat rambutnya yang baru kubelikan kemarin, diambil temannya secara paksa.
Pencurian. Perampasan.
Fakta itu langung membuat aku jadi orang sumbu pendek. Aku berapi-api. Kutanya siapa yang melakukan hal itu, dan di mana rumahnya.
"Ribka. Yang rumahnya di perumahan sebelah."
Sambil menangis, Aisi mengatakan itu. Tak puas, aku menanyai sekali lagi, soal mengapa anak bernama Ribka itu mengambil ikat rambut miliknya.
"Kata dia, ikat rambutnya Aisi jelek. Enggak cocok Aisi pakai."
Mulutku menganga, sudah pasti wajahku merah. Aku berang. Rasanya tak rela. Enak sekali anak itu mengambil milik Aisi?
"Kakak marah. Kamu, kok, enggak nolak pas dia mau ambil ikat rambutmu?" tanyaku pada Aisi sembari mengusapi air matanya.
"Aisi larang. Tapi, dia bawa gengnya," adu Aisi dengan wajah sedih.
Aku menggigit bibir. Makin murka. Bukan semata karena ikat rambut itu harganya lumayan mahal dan memang cantik. Namun, lebih ke tak suka ada sesuatu yang diambil dari Aisi. Secara paksa pula.
Berani sekali anak itu? Dia kira dia siapa?
Menekuk lutut di depan Aisi, aku memegangi dua bahu anak itu. Menatapnya yakin. "Di mana rumahnya? Kasih tahu Kakak. Kakak mau ambil ikat rambut Aisi."
Sepuluh menit kemudian, aku dan Aisi sampai di rumah anak bernama Ribka itu. Aku langsung gedor pintu rumah tersebut. Seorang ibu-ibu muncul dan langsung memberikan tatapan tak suka dan sinis padaku.
"Cari siapa, ya?" Ia melirik pada Aisi. "Aisi?"
"Mana Ribka?" tanyaku langsung.
"Mau apa cari anak saya?" Dia berkacak pinggang.
"Ikat rambut Aisi dicuri Ribka. Saya mau bertemu Ribka untuk minta ikat rambut itu dikembalikan."
Wajah Ibu itu merah padam. Kurasa dia tersinggung karena anaknya kutuduh pencuri.
"Kenapa berani sekali kamu tuduh anak saya pencuri? Kamu ini siapa?" teriaknya.
Aku mengerutkan dahi. "Enggak usah teriak-teriak, Buk. Kalau Ibu engggak percaya, panggil aja anak Ibu. Tanya, apa dia ambil ikat rambut Aisi atau enggak."
Kutantang begitu, ia bereaksi seperti yang kuduga. Ibu itu panggil Ribka. Anak yang seumuran Aisi itu datang, sedikit terkejut, tetapi langsung terlihat tak suka atas kehadiran kami.
"Kamu ambil ikat rambut Aisi?" tanya si Ibu.
Ribka langsung terlihat gelagapan. Matanya berkedip cepat.
"Kamu ambil ikat rambut Aisi?" ulang Ibu tadi.
Ribka menggeleng. "Ikat rambutnya jelek dipakai Aisi. Jadi, aku bantu buang."
Aku tersenyum miring mendengar pengakuannya. Sesaat setelah dia datang tadi, aku sudah menemukan di mana ikat rambutnya Aisi. Di pergelangan tangan Ribka.
"Buang?" tanyaku dengan suara datar. "Itu apa yang di tangan kamu?"
Ibunya ikut memeriksa, kemudian langsung tampak kecewa dan marah. Sedangkan Ribka, anak itu seperti sudah akan menangis.
Ibunya Ribka mengambil ikat rambut itu dari anaknya. Ia berikan padaku dengan kasar.
"Itu cuma ikat rambut. Harusnya kamu enggak perlu datang, seolah melabrak saya, padahal ini cuma masalah anak-anak." Dia menyuarakan pembelaan diri.
"Saya memang melabrak Ibu," sahutku yakin. "Masalah anak-anak? Ini pencurian. Barang Aisi, diambil paksa oleh anak Ibu. Ini perampasan, kriminal. Harusnya ibu bersyukur saya enggak adukan ini ke polisi."
Dia makin marah. "Polisi? Sombong sekali kamu membawa masalah ikat rambut sampai ke pihak polisi? Mereka hanya bermain, bercanda. Toh, siapa yang tahu kalau besok Ribka akan mengembalikan ikat rambut itu?"
Aku menggeleng dengan ekspresi sinis. "Bercanda? Aisi menangis. Ia tidak terhibur dengan candaan anak Ibu, artinya ini bukan candaan. Heran, bukankah harusnya ada yang meminta maaf sekarang?"
Ibu itu mendorong bahuku, hingga aku sedikit terhuyung ke belakang.
"Kamu siapa, sih? Saya baru lihat kamu. Kenapa harus ikut campur urusan orang? Orangtua Aisi saja tidak repot, kenapa kamu yang repot?"
Satu kali itu, aku bungkam. Tak bisa memberikan jawaban. Kalau aku menyebut diri sebagai ibu tiri Aisi, apa boleh? Apa Aisi setuju hal ini dibeberkan pada orang lain, mengingat pernikahankubdan Pak De hanya diketahui pihak keluarga.
Memberitahu bahwa aku adalah istri baru Pak Denish, kuyakin Aisi belum tentu setuju. Bagaimana kalau dia malah jadi bahan omongan Ribka dan kawan-kawannya nanti. Lagipula, Ibunya Ribka belum tentu mau percaya pada pengakuanku.
Maka itu, aku tak memberi penjelasan apa-apa.
"Sudahlah. Manusia zaman sekarang memang aneh-aneh. Sudah salah, malah yang paling garang dan ogah meminta maaf. Kami permisi, Buk. Tolong diingatkan anaknya agar tak ambil ikat rambut Aisi lagi. Kalau dia mau, saya bisa belikan untuk dia."
Menggandeng tangan Aisi, aku langsung pergi dari sana. Kami pulang.
Bab 8
Aku masuk ke kamar dan menemukan Pak Denish sedang duduk di atas ranjang. Pria itu bersandar, menatap datar ke arahku yang sudah duduk di tepian kasur.
Melihatnya di kamar ini, malam ini, aku jadi teringat pembicaraan kami di rumah Buk Fera. Soal rencana Senin malam.
Teringat itu, aku langsung tersenyum kikuk. Rasanya otak jadi kosong. Inginnya lari saja, tetapi sudah tak mungkin. Malam ini, untuk pertama kalinya, mau tak mau aku harus tidur satu ranjang dengan Pak Denish.
Mending kalau hanya sekadar tidur. Bagaimana kalau dia minta yang macam-macam?
"Enggak perlu pasang senyum di depan saya. Saya cuma butuh kamu untuk urus Aisi. Enggak perlulah pamer senyum, apalagi yang palsu begitu."
Mukaku langsung kaku. Kuhapus senyum kikuk tadi. Berikutnya, aku melempar tatap dingin padanya.
"Kamu sudah tak sabar mau membuktikan omongan saya?"
Aku menggeleng. Kubuat ekspresi semakin gelap. Berharap dia paham jika sekarang aku bukan sedang antusias, tak sabar, atau semacamnya.
"Saya senyum karena enggak tahu harus apa," terangku kemudian. Duduk membelakangi Pak De, aku menimbang.
Masalah Aisi dengan Ribka. Haruskah aku mengatakannya? Sebenarnya aku ingin sekali. Agar Pak Denish bisa pergi ke sekolah besok, dan memberitahu pada pihak guru. Bukan bermaksud membesar-besarkan masalah. Aku hanya ingin membuat Ribka jera.
"Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, San."
Aku berjengit. Terkesiap karena mendadak merasakan embusan napas Pak De di tengkuk. Menoleh, bulu kuduk malah meremang karena tak sengaja ujung hidung menyenggol rahangnya.
"Kamu cuma perlu menikmati," tambahnya. Matanya menatapku penuh maksud. Yang sialnya, aku paham apa maksudnya.
Pak Denish berpindah. Ia duduk di depanku, di atas kedua pahaku. Pria itu memegangi wajahku, memberikan tatapan yang kembali membuat aku meremang.
"Kalau tidak puas, boleh tuntut saya," ucapnya sebelum mendekat dan mengecup bibirku.
Seketika masalah Aisi kusisihkan. Ada hal yang harus ditangani duluan. Yakni, menilai Pak Denish, untuk nantinya membuat keputusan harus menuntutnya atau tidak.
***
"Aisi!"
Tidak memanggil seperti biasa, aku berteriak.
"Aisi!"
Tidak berjalan tenang menuju kamar anak itu, aku berlari tergesa.
Membuka kamar Aisi, aku langsung menyambar handuk di belakang pintu. Hendak mendekat pada Aisi yang masih lelap di atas kasur, kakiku tak sengaja menginjak ujung handuk yang menjuntai.
Bunyi debuman kencang terdengar di ruangan itu. Tak ada waktu untuk meringis dan meratapi lutut yang barusan menghantam lantai, aku tertatih menuju ranjang Aisi.
Kubangunkan anak itu dengan sedikit kasar. Kuguncang bahunya kuat.
"Aisi! Udah jam tujuh. Kamu bisa terlambat. Aisi!"
Aisi bangun. Anak itu menggeliat, bukannya langsung duduk, malah menatapku kesal.
"Kalau udah kesiangan, ya, udah, Kak. Sekolahnya besok aja."
Aku yang sedang mengambil seragam barunya dari lemari langsung menoleh dengan mata melotot.
"Mandi sana! Terlambat atau enggak, kamu enggak boleh bolos hari ini. Cepat!"
Aisi turun dari ranjang malas-malasan. "Bantuin Aisi mandi," rengeknya.
Aku menggeleng. Kuletakkan seragamnya di kasur. "Mandi sendiri. Kakak mau buatkan sarapan." Aku berjalan terseok menuju pintu.
Saat itu Pak Denish muncul. Pria itu sudah mengenakan kaus putih, rambutnya sedikit basah. Mungkin habis mandi. Dia menatapku bingung.
"Kamu kenapa?" tanyanya.
"Jatuh," jawabku singkat, kemudian terus melangkah.
"Biar saya yang bantu Aisi mandi."
Langkahku yang sudah akan mencapai pintu berhenti. Langsung aku menggeleng kuat, berbalik.
"Enggak. Aisi biar mandi sendiri. Memang dia umur berapa, masih boleh Bapak mandikan?" Aku menatapnya tajam.
"Aisi enggak bisa mandi sendiri," sambar anak Pa Denish yang keras kepala itu.
"Biar saya yang bantu mandikan," ulang Pak De.
"Enggak!" Nada suaraku meninggi.
"Kamu ini kenapa?" Pak Denish terlihat tak suka. "Kamu seolah menuduh saya akan melakukan sesuatu."
Aku mengangguk. Menggosok lutut sesaat, aku menghampiri Aisi. "Ayo, mandi. Kamu, tuh, makanya nurut kalau Kakak bilangin. Kamu udah besar, harusnya udah bisa mandi sendiri. Kan kalau kayak gini repot."
Mengantar Aisi ke kamar mandi, aku baru sadar kalau Pak Denish mengekori kami.
"Bapak mau apa di sini?" sergahku tak ramah. "Tolong jangan bikin saya makin ribet, ya? Bisa urus diri sendiri, 'kan?"
Aisi masuk ke kamar mandi.
"Saya menawarkan bantuan, kalau kamu lupa. Kenapa kamu malah terus mengomel? Kamu sudah begitu sejak saya bangunkan tadi."
Tak jadi masuk ke kamar mandi, aku menatapnya geram. "Lebih bagus Bapak enggak bangunkan saya sekalian. Ini udah jam berapa? Kalau Bapak memang udah bangun dari tadi, harusnya bangunkan lebih awal! Kalau udah begini, gimana? Aisi bisa terlambat ke sekolah!"
"Memangnya Aisi masuk sekolah jam berapa?"
Pertanyaan mengandung bara api. Apinya sudah menyala di atas ubun-ubunku. Sebenarnya siapa orangtuanya Aisi di sini?
Tak sudi aku menjawab pertanyaan itu. Kutinggal dia untuk masuk ke kamar mandi. Lebih baik bergegas membantu Aisi.
Aku bersyukur karena selalu membuat telur rebus. Di saat begini, makanan itu sangat berguna. Meski Aisi sempat menolak, tetapi gadis itu akhirnya setuju sarapan dengan telur rebus.
Aku menyuapi Aisi makan, sembari mengikat rambutnya. Kuminta anak itu memakai sepatu. Sedangkan Pak Denish, pria itu hanya bersedekap dan menontoni kami. Tak punya inisiatif membantu.
Suara klakson ojeknya Aisi terdengar. Aku makin gelagapan. Kusuapi Aisi untuk terakhir.
"Minumnya di jalan, ya."
Anak itu mengangguk, sudah selesai dengan sepatunya. Kami berlari menuju teras.
"Hati-hati, ya. Jangan lari-larian di sekolah. Pensilnya jangan hilang lagi."
"Iya. Uang jajan Aisi, Kak."
Aku menepuk dahi. Berbalik, aku yang hendak berlari malah salah menginjak, hingga tergelincir di undakan menuju teras. Aku terjatuh. Untuk yang kedua di pagi ini.
Kali ini yang sakit bukan cuma lutut. Pergelangan kakiku rasanya seperti patah.
"Kamu ini kenapa, sih?" Pak Denish datang dan membantuku berdiri. "Heboh tanpa sebab," cemoohnya.
Ingin sekali menimpali, tetapi uang jajan Aisi lebih penting. Saat melangkah, aku langsung meringis. Pergelangan kaki kananku sakit sekali. Sakitnya sampai ke otak.
"Terkilir kayaknya," komentar Buk Yanti dengan raut prihatin. "Ya, sudah, San. Uang jajan Aisi saya duluankan saja. Kamu langsung urut kakimu. Takutnya makin sakit."
Mengangguk setuju, aku mengucapkan terima kasih.
"Aisi berangkat, ya. Dadah!"
"Pergi dulu, San. Mari, Pak Denish."
Sepeda motor Buk Yanti berangkat, aku duduk di kursi teras. Kucoba menggerakkan kaki, kemudian memijatnya. Sakit di sana makin menjadi.
"Kamu ini sebenarnya kenapa?"
Pak Denish bertanya sembari membawa satu kursi mendekat. Laki-laki itu menarik kakiku, untuk ditaruh di atas pahanya.
Alisku mengait ke arahnya.
"Saya kira kamu tak bisa mengomel. Sejak bangun tadi, kamu terus saja bicara. Jatuh pula. Kamu masih tidur atau bagaimana?"
Hanya menatapinya dengan mulut bungkam, aku meracau dalam hati.
Memang, siapa yang membuat aku sampai bangun kesiangan? Siapa yang bangun pukul tiga pagi, hanya untuk minta main kuda-kudaan lagi? Siapa?
Oh, sial. Main kuda-kudaan! Sejak kapan mengenal istilah itu?
"Ini terkilir. Mau ke dokter atau ke tukang pijat?" Pak Denish berhneti memijat kaki. Ia menoleh, menunggu aku menjawab.
"Enggak usah diapa-apain," jawabku setelah beberapa saat. Kuturunkan kaki, sakit kembali terasa.
"Gimana bisa kamu kerjain hal-hal kalau kakimu sakit begitu?" tanyanya balik.
Gagal berdiri, aku kembali duduk. Pak Denish ada benarnya. "Tukang pijat aja," putusku akhirnya.
Pak Denish mengangguk. Ia berdiri, kemudian masuk ke rumah. Pria itu kembali beberap saat kemudian, lalu membantuku berdiri.
"Tunggu di dalam. Tukang pijatnya datang setengah jam lagi." Dia mengantar dan membuatku duduk di sofa ruang tamu.
Aku mendongak, menanti apa yang mau dia katakan lagi. Namun, pria itu malah bergeming. Tak buka suara dan hanya memandangi.
"Apa?" tanyaku tak sabar, setengah gugup.
Eh? Kenapa aku gugup? Untuk apa aku gugup?
Tangan Pak Denish bergerak. Menyasar pipiku dan mencubitnya pelan. Tak hanya sekali, tetapi terus-terusan.
"Jadi, sudah memutuskan?" Alisnya naik satu. Ekspresi paling mengesalkan, karena lelaki itu terlihat sinis, tetapi juga luar biasa tampan.
"Memutuskan apa?" Aku menjauhkan tangannya. "Sakit, Pak De!"
"Apa iya?" Dia malah beranda dan terus menoel pipiku. "Gimana? Sudah putuskan mau menuntut saya atau tidak?"
Tanganku berhenti menepi tangannya. Seluruh tubuh rasanya membeku. Ada hangat yang menjalar di pipi. Kupalingkan wajah dari Pak Denish.
"Sejauh yang saya ingat, kamu cukup menikmati tadi malam itu."
"Tadi malam?" Aku menyela. "Bapak juga minta pas tadi pagi."
Ekspresi Pak Denish sama sekali tak menunjukkan rasa terganggu. Pria hanya mengangguk.
"Saya salah terka. Saya kira kamu sudah pernah melakukan itu. Jadi ...."
"Jadi apa?" kejarku dengan perasaan malu dan penasaran.
Pak Denish menoleh tajam. "Saya yang tanya duluan. Kamu yang harus menjawab."
Melipat bibir, aku memainkan jemari. "Enggak," jawabku pelan.
"Enggak apa?"
Memegangi wajah, menunduk, aku menerangkan, "Enggak dituntut. Astaga, Bapak serius dengan ini?"
Tawa Pak Denish berderai. Dari yang kudengar, pria itu sepertinya sangat senang.
Aku merasakan ada sapuan telapak tangan di kepala. Mengintip dari sela jemari, aku menemukan itu ulah Pak Denish.
Beberapa saat kemudian, aku terperanjat sebab Pak Denish membungkuk dan mengecup pipi.
"Saya lapar. Kamu mau nasi goreng? Kamu pasti lapar karena terus-terusan mengomel." Dia bicara sembari berlalu ke dapur.
Sedangkan aku, masih duduk di sofa. Memegangi dada yang bertalu-talu.
Ish. Belum tiga hari menjadi istri Pak Denish, apa aku sudah menyukai dia sebegitu banyak, hingga hanya karena perlakukan seperti tadi, aku berdebar dan merona?
Karya ini GRATIS! Tapi kamu boleh kok kasih tip biar kreator hepi 🥰